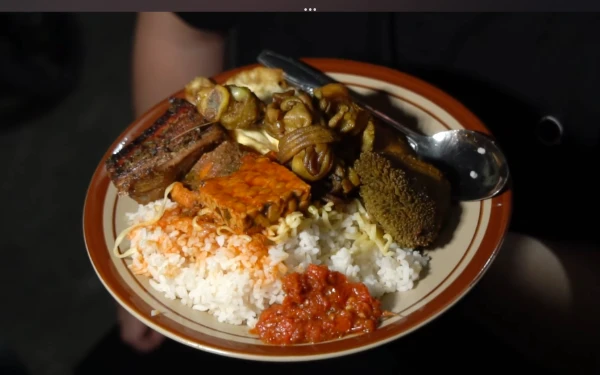KETIK, YOGYAKARTA – Di tengah berbagai klaim pemerintah pusat atas perkembangan penanganan bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, khususnya Aceh, fakta miris kembali terungkap.
Puluhan kampung di Aceh hingga pekan ini ternyata masih terisolasi akibat putusnya akses jalur darat, dampak dari banjir dan longsor hebat beberapa pekan lalu. Setidaknya di Kabupaten Aceh Tengah, sebanyak 26 kampung masih mengalami isolasi. Fakta itu diumumkan sendiri oleh Pemkab Aceh Tengah sebagai dasar perpanjangan masa tanggap darurat hingga 22 Januari 2026 mendatang.
Jumlah 26 kampung di Aceh Tengah tentu saja masih belum termasuk kabupaten/kota lain di Provinsi Aceh yang tidak menutup kemungkinan masih mengalami hal yang sama.
Hal ini seolah kembali menyingkap lemahnya kesiapsiagaan pemerintahan Presiden Prabowo dalam menghadapi bencana. Pemkab Aceh Tengah dalam pernyataan resminya menyebut, 26 kampung tersebut masih terisolasi karena kerusakan infrastruktur yang belum tertangani. Putusnya akses darat membuat distribusi bantuan tersendat dan memaksa sebagian warga bertahan tanpa pasokan logistik yang memadai.
"Seluruh pembiayaan akibat penetapan status tanggap darurat ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tengah Tahun Anggaran 2026, serta sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Bupati Aceh, Haili Yoga dalam pernyataan resminya tentang perpanjangan status tanggap darurat, seperti dikutip dari laman resmi Pemkab Aceh Tengah pada 9 Januari 2026 lalu.
Namun, perpanjangan status dinilai belum cukup menjawab persoalan mendasar terkait kesiapan sistem penanganan bencana, khususnya dalam menjamin akses cepat ke wilayah terdampak.
Pakar geomorfologi lingkungan, Prof. Djati Mardiatno, menilai keterisolasian wilayah seharusnya bisa diantisipasi sejak awal melalui skema akses alternatif dalam kondisi darurat. Menurutnya, keterbatasan akses darat bukan alasan untuk membiarkan wilayah terdampak terputus dari bantuan.
“Ya, sebenarnya kalau kondisinya seperti itu, itu kan berarti kan faktor aksesibilitas ya. Sehingga kalau kondisinya masih seperti itu, mau nggak mungkin memang harus mencari sarana penghubung lain untuk bisa masuk ke daerah-daerah yang terisolasi tadi. Terpaksa harus melalui jalur udara, nggak ada pilihan lain lagi atau misal melalui jalur sungai,” ujar Djati, dalam pernyataan tertulisnya, Rabu, 14 Januari 2026.
Djati menegaskan, pemerintah semestinya telah menyiapkan rencana kontinjensi yang jelas sebelum bencana terjadi, termasuk skenario penanganan wilayah terisolasi. Tanpa perencanaan tersebut, distribusi bantuan kerap terlambat dan tidak merata.
“Jadi, sebelum kejadian bencana, di dalam rencana contingency itu sudah ada skenario itu. Nah, misalnya jika ada rencana contingency dan ada kejadian bencana maka daerah-daerah yang terisolasi tentunya juga menjadi prioritas untuk mendapatkan pasokan logistik agar mereka sementara bisa bertahan hidup ya, terutama kebutuhan-kebutuhan dasar,” jelasnya.
Menurut Djati, besarnya dampak banjir dan longsor di Sumatera menunjukkan bahwa rencana kontinjensi pemerintah pusat dan daerah belum berjalan efektif. Kondisi ini sekaligus mencerminkan lemahnya perencanaan konektivitas wilayah di daerah rawan bencana.
Ia juga mengingatkan bahwa kerusakan infrastruktur tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan kerusakan lingkungan. Pembukaan hutan yang masif mengurangi daya serap tanah terhadap air hujan dan memperbesar risiko bencana lanjutan.
“Jika terjadi hujan ekstrim, air hujan lebih banyak mengalir menjadi aliran pembukaan yang dapat memicu terjadinya erosi, longsor, banjir, dan banjir bandang. Termasuk juga bertambahnya kerusakan infrastruktur,” pungkas