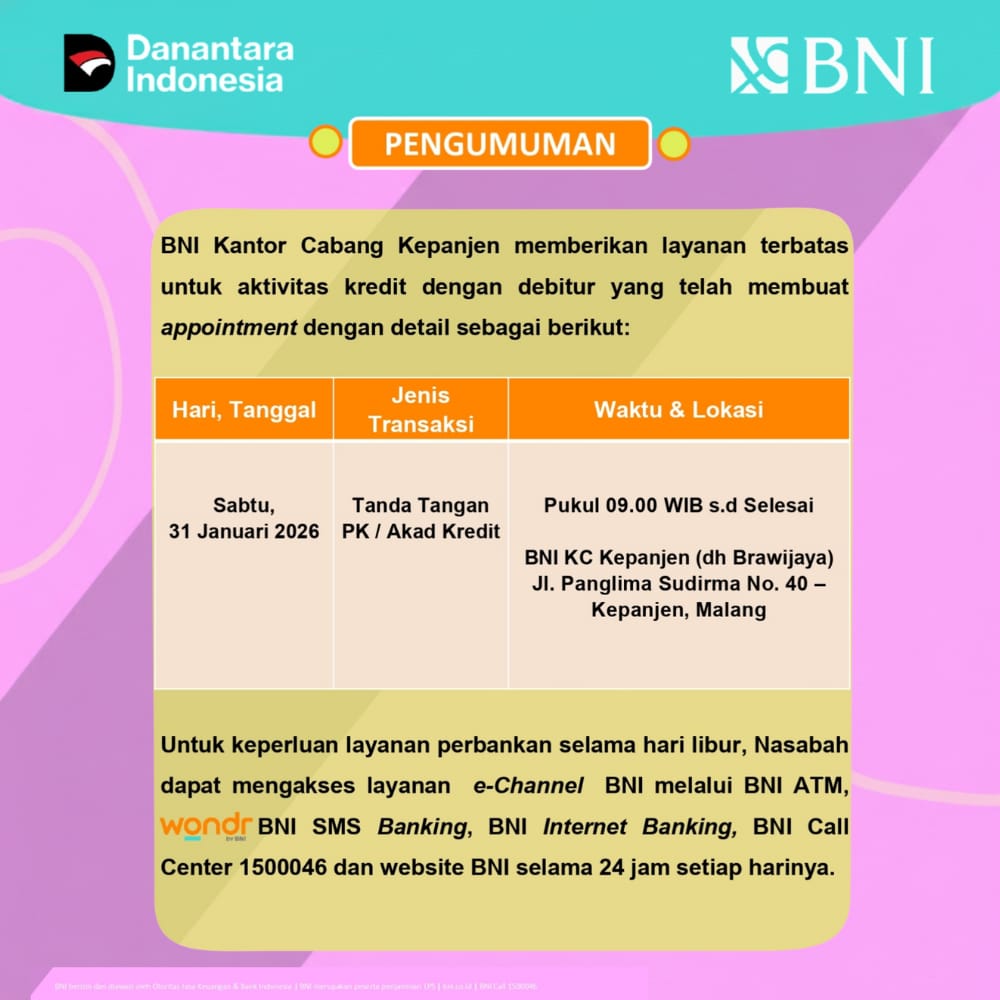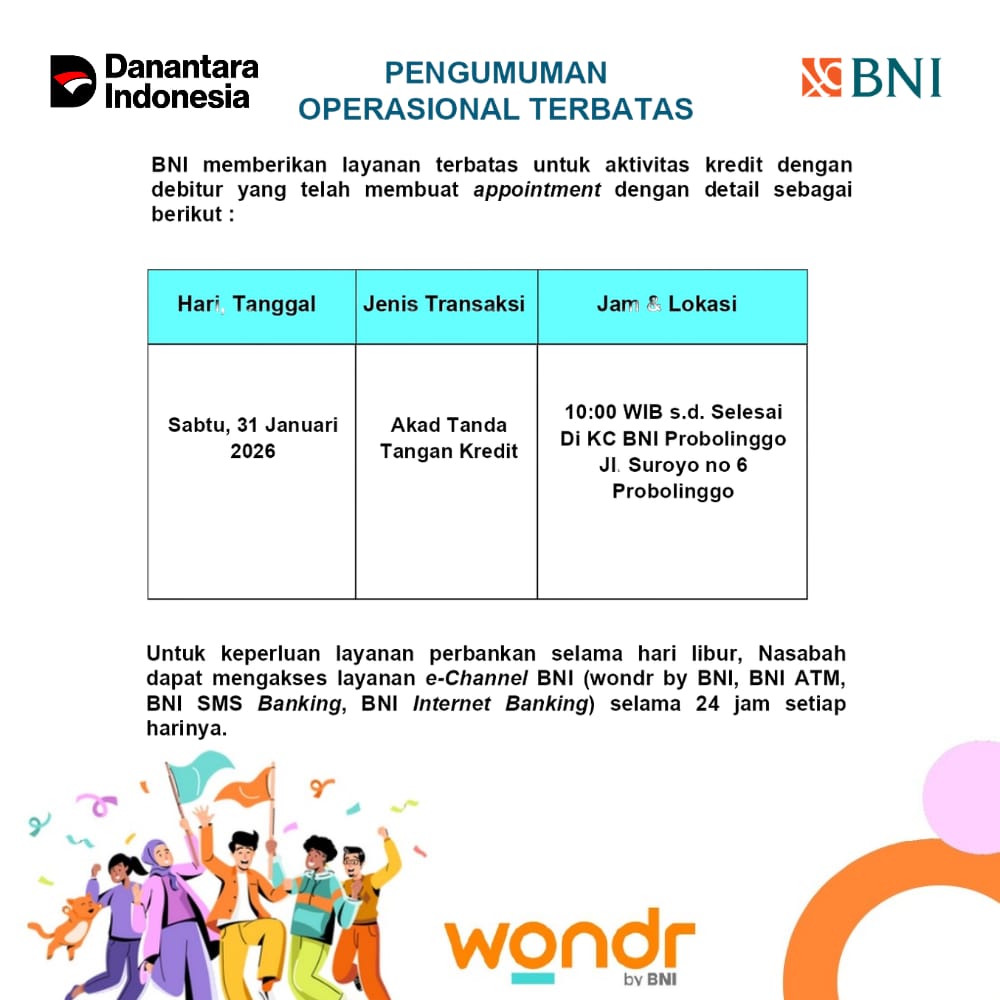Adanya Dana Desa merupakan mandatori dari keberadaan UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang kini sudah diamandemen menjadi UU Nomor 3 Tahun 2024. Undang-undang tersebut memberikan kewenangan luas kepada desa tak hanya dalam hal mengurus kepentingan warga tapi juga mengatur pengelolaan keuangan melalui Dana Desa.
Tentu kebijakan ini menandai perubahan paradigma pembangunan yang semula top down ke bottom up, dimana desa tak lagi menjadi objek tapi subjek dari pembangunan itu sendiri (Kemendesa, 2021)
Setiap tahun miliaran rupiah mengalir ke Rekening Kas Desa (RKD), dana transfer fiskal ini dipergunakan untuk memperbaiki jalan, jembatan bahkan fasilitas publik. Namun seiring laju perkembangan pembangunan yang ada di desa, muncul persoalan baru yang kian menumpuk dan sering kali diabaikan, yakni pengelolaan sampah.
Jika dulu masyarakat desa bisa hidup selaras dengan alam, sebab banyak bahan baku yang bersumber dari alam dan mudah diurai. Namun kini plastik, kemasan instan dan produk-produk lain yang sulit terurai sudah menjadi bagian dari gaya hidup sehari-hari. Tentu hal ini berdampak pada volume sampah yang kian menggunung dan ironisnya tanpa adanya sistem pengelolaan sampah yang memadai.
Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup di tahun 2023 kawasan perdesaan menyumbang 40 persen sampah nasional, dimana sungai-sungai kecil menjadi tempat pembuangan sampah yang menyebabkan parit tersumbat, belum lagi pencemaran udara akibat dari pembakaran sampah.
Data tersebut menunjukkan problem sampah tidak lagi monopoli kawasan perkotaan, ditambah lagi sebagian besar desa belum memiliki tempat pengolahan sampah terpadu atau sistem pemilahan.
Beberapa waktu yang lalu penulis berdiskusi panjang dengan para pegiat lingkungan, mereka berkeluh kesah pemerintah daerah dinilai lamban dalam mengatasi persoalan pengelolaan sampah, belum lagi dihadapkan dengan masalah pengelolaan sampah dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Makan Bergizi Gratis (MBG) dimana didalamnya terdapat sampah residu dan perlu ditangani secara khusus.
Para pegiat lingkungan juga membeberkan fakta bahwa satu Dapur MBG bisa menghasilkan sampah hingga 1 kwintal perhari, sementara untuk pemenuhan MBG dilakukan selama 5 hingga 6 hari kerja.
Keluarnya Surat Edaran Bupati Nomor 270 Tahun 2025 tentang pengelolaan sampah secara mandiri, menjadi angin segar bagi para pegiat lingkungan, meski masih dinilai lamban tapi ini membuktikan keseriusan pemerintah daerah dalam penanganan masalah sampah yang ada di Bondowoso.
Mereka juga berharap ini tidak hanya diatas kertas semata, namun ada ditindaklanjuti secara serius, mengingat lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) akan ditutup pada bulan Desember tahun ini.
Dalam konteks ini adanya Dana Desa memiliki peran strategis untuk mendukung dalam upaya pengelolaan sampah berbasis masyarakat tentunya berorientasi pada keberlanjutan. Selama ini orientasi pembangunan di desa masih fokus pada infrastruktur fisik saja, hal ini disebabkan banyak dari pemerintah desa masih menilai kemajuan itu dari berapa kilometer jalan dibangun, bukan dari seberapa jauh kesadaran warga tumbuh.
Sehingga perlu untuk mendorong pemerintah desa agar menggeser paradigma pembangunan menuju pembangunan hijau, kombinasi antara kesejahteraan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Pertanyaan besarnya adalah apakah Dana Desa bisa untuk melakukan itu?
Tentu saja boleh, dasar hukumnya pada Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2021 secara gamblang memperbolehkan penggunaan Dana Desa untuk kegiatan berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dengan demikian penggunaan Dana Desa untuk pengelolaan sampah dan pelestarian lingkungan tak hanya relevan tapi juga sejalan dengan mandat regulasi.
Alokasi dana tersebut bisa digunakan untuk kegiatan semisal bank sampah desa, program edukasi lingkungan serta ekonomi sirkular. Bahkan menurut Nurhadi (2020), penggunaan Dana Desa untuk lingkungan hidup dapat menciptakan efek berganda (multiplier effect) yakni mampu meningkatkan kesadaran masyarakat, mencetak lapangan kerja hijau serta penguatan ekonomi lokal.
Dapat disimpulkan secara garis besar masalah pengelolaan sampah bukan terletak pada persoalan dana, melainkan dari perilaku. Di mana masih banyak warga masyarakat memandang sampah sebagai urusan dari pemerintah, di sinilah pentingnya desa menjadi motor penggerak perubahan sosial, semisal gerakan jumat bersih, pelatihan daur ulang untuk kelompok PKK dan Karang Taruna atau lebih jauh pemerintah desa bisa memperkuat dengan membuat Peraturan Desa (Perdes) tentang pengelolaan sampah.
Dengan mendorong desa mengelola sumber daya dan limbah secara mandiri diharapkan mampu memperkuat daya tahan sosial-ekologis desa terhadap ancaman degadrasi lingkungan.
Pengelolaan sampah ini tak bisa berjalan tanpa koordinasi antar pihak, pemerintah desa memiliki peran sebagai fasilitator dan regulator, sementara lembaga sosial macam PKK, Karang Taruna serta kelompok tani di desa menjadi pelaksana program. Disamping itu tak kalah penting adalah peran BUM Desa sebagai lembaga ekonomi desa yang bisa mengelola rantai bisnis daur ulang dan pemanfaatan sampah.
Pengelolaan sampah secara integral oleh BUM Desa dapat membuka peluang ekonomi baru, disamping itu konsep ekonomi sirkular juga membuka peluang bagi desa untuk mengelola sampah secara produktif. Tentu dalam hal ini yang paling penting adalah peran aktif masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan program ini.
Meski memiliki potensi yang besar, pengelolaan sampah berbasis masyarakat memiliki berbagai tantangan, sebagaimana dijelaskan di atas, mulai dari orientasi pembangunan, di mana isu lingkungan masih dianggap sebagai kegiatan sekunder, belum lagi aparatur desa belum memahami manajemen sampah modern termasuk minimnya data lingkungan, seperti volume dan komposisi sampah sehingga perencanaan tak lagi berbasis bukti.
Dengan pendekatan partisipatif dan kolaboratif, pengelolaan sampah berbasis masyarakat tak hanya mampu atasi persoalan lingkungan tapi juga bisa memberikan nilai lebih dan memperkuat nilai sosial.
Dengan kata lain Dana Desa tak sekedar alat distribusi keuangan semata, namun menjadi instrumen menuju desa hijau, mandiri dan berdaya tahan lingkungan sebagaimana visi Indonesia menuju pembangunan berkelanjutan (SDGs).
Sejatinya pembangunan di desa tak hanya berhenti pada betonisasi saja, didalamnya harus ada ekologi yakni membangun manusia dengan alamnya. Desa yang mandiri secara ekonomi, berdaulat secara sosial dan lestari secara ekologis merupakan cita-cita bersama sekaligus Asta Cita ke-8 Presiden Prabowo Subianto
*) Moch. Efril Kasiono merupakan Pendamping Desa di Kabupaten Bondowoso
**) Isi tulisan di atas menjadi tanggung jawab penulis
***) Ketentuan pengiriman naskah opini:
Naskah dikirim ke alamat email redaksi@ketik.com
- Berikan keterangan OPINI di kolom subjek
- Panjang naskah maksimal 800 kata
- Sertakan identitas diri, foto, dan nomor HP
- Hak muat redaksi.(*)