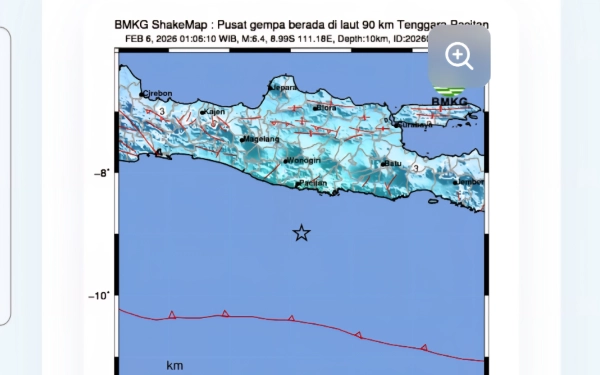KETIK, SURABAYA – Di tengah terus menguatnya kekuatan diplomatik untuk pengakuan kemerdekaan Palestina di berbagai negara, dunia mengenang hari ini sebagai salah satu momen sejarah terburuk bagi bangsa tersebut.
Hari ini, 43 tahun lalu atau 16 September 1982, puluhan ribu rakyat sipil Palestina yang tidak berdosa, dibantai secara sadis oleh milisi sayap kanan dari Partai Kataeb atau Falang Lebanon, yang didukung oleh Zionis Israel. Pembantaian tersebut berlangsung selama tiga hari, yakni hingga 18 September 1982.
Puluhan ribu sipil tak berdosa itu merupakan rakyat sipil Palestina yang mengungsi di kamp pengungsi di Sabra dan Shatila, Beirut Barat, Lebanon. Mereka mengungsi karena negerinya sedang dicaplok oleh Israel.
Peristiwa Sabra Shatila juga terkait dengan perang saudara di Lebanon antara tiga faksi, dengan keterlibatan Israel secara langsung di dalamnya.
Peristiwa bermula saat Bashir Gemayel dari kelompok Maronit dan pemimpin Partai Kataeb (dikenal juga sebagai Partai Phalange) terpilih sebagai Presiden Lebanon pada 23 Agustus 1982. Bashir atau Bachir Gemayel merupakann salah satu tokoh politik Lebanon yang pro Israel.
Tetapi ia terbunuh pada 14 September 1982 dalam sebuah serangan bom. Partai Phalange yang memang bermusuhan dengan PLO langsung menuduh milisi Palestina sebagai pelakunya. PLO atau Palestine Liberation Organization.
Tuduhan orang Palestina sebagai pihak yang bertanggungjawab atas kematian Bashir Gemayel memang tidak pernah dibuktikan secara konkrit. Beredar kabar pula, bahwa pelaku pembunuhan adalah seorang Lebanon yang bekerja sebagai agen intelejen bagi Suriah.
Namun, pembunuhan itu sukses memantik amarah milisi Lebanon yang juga dimanfaatkan oleh Israel untuk membasmi PLO, salah satu kekuatan politik Palestina yang ditakuti Israel kala itu.
 Kamp pengungsian Shatila yang berdiri sejak 1949 di Beirut, yang menjadi sasaran pembantaian milisi sayap kanan Lebanon atas dukungan Israel pada 16 - 18 September 1982. (UNRWA)
Kamp pengungsian Shatila yang berdiri sejak 1949 di Beirut, yang menjadi sasaran pembantaian milisi sayap kanan Lebanon atas dukungan Israel pada 16 - 18 September 1982. (UNRWA)
Israel, yang saat itu sedang menduduki Beirut Barat setelah invasi besar-besaran ke Lebanon, kemudian mengepung kamp Sabra dan Shatila. Tidak ada warga yang boleh keluar.
Hari Pertama: Pasukan Masuk, Lampu Dinyalakan
Pada sore 16 September 1982, pasukan Israel membuka jalan bagi milisi Phalange masuk ke kamp. Pasukan Israel berkontribusi dalam peristiwa yang disebut PBB sebagai genosida (pembantaian etnis) itu dengan mengepung kamp pengungsi sipil dari empat penjuru: barat, timu, utara dan selatan.
Dalam kondisi terkepung itulah, milisi Lebanon yang didukung oleh Israel membantai rakyat sipil Palestina di kamp pengungsian Sabra dan Shatila.
Dengan dalih mencari “sisa-sisa pejuang PLO”, milisi itu mulai menyisir rumah demi rumah. Malam tiba, tentara Israel menyalakan lampu sorot dari tank dan pos penjagaan, menerangi setiap sudut kamp. Yang terjadi setelah itu bukan operasi militer, melainkan pembantaian massal.
Hari Kedua: Jeritan yang Dibiarkan
17 September 1982 menjadi hari paling mencekam. Sepanjang siang dan malam, teriakan warga terdengar dari dalam kamp. Namun pasukan Israel yang berjaga di luar tidak menghentikan aksi pembunuhan.
Pria ditembak, wanita diperkosa, anak-anak dan orang tua dibantai tanpa ampun. Jalanan kamp dipenuhi mayat yang tergeletak di antara puing-puing rumah.
Hari Ketiga: Dunia Mengetahui
Pada 18 September 1982, kabar tentang pembantaian bocor ke media internasional. Tekanan dunia mulai datang. Milisi Phalange akhirnya ditarik keluar, meninggalkan pemandangan mengerikan: ratusan hingga ribuan jenazah bergelimpangan, sebagian besar perempuan, anak-anak, dan lansia.
Jumlah Korban dan Pertanggungjawaban
Hingga kini, jumlah korban masih diperdebatkan, berkisar antara 800 hingga lebih dari 3.000 jiwa.
Secara resmi, pelaku langsung adalah milisi Phalange Lebanon. Namun, Israel dianggap bertanggung jawab secara tidak langsung karena membiarkan pembantaian itu terjadi, bahkan mendukung secara logistik.
Di dalam negeri, masyarakat Israel sendiri geger. Demonstrasi besar-besaran meledak. Sebuah penyelidikan yang dikenal sebagai Komisi Kahan menyatakan Israel bersalah karena gagal mencegah tragedi tersebut. Ariel Sharon, Menteri Pertahanan saat itu, dipaksa mundur dari jabatannya.
Bagi bangsa Palestina, Sabra dan Shatila bukan sekadar catatan sejarah, melainkan luka abadi. Peristiwa ini menjadi simbol penderitaan panjang sebuah bangsa yang kehilangan tanah, rumah, dan bahkan nyawa di tanah pengasingan.
Sabra dan Shatila adalah pengingat pahit bahwa di tengah konflik politik dan militer, yang paling menderita adalah mereka yang tak bersenjata: para pengungsi, wanita, dan anak-anak yang tak bisa melawan. (*)