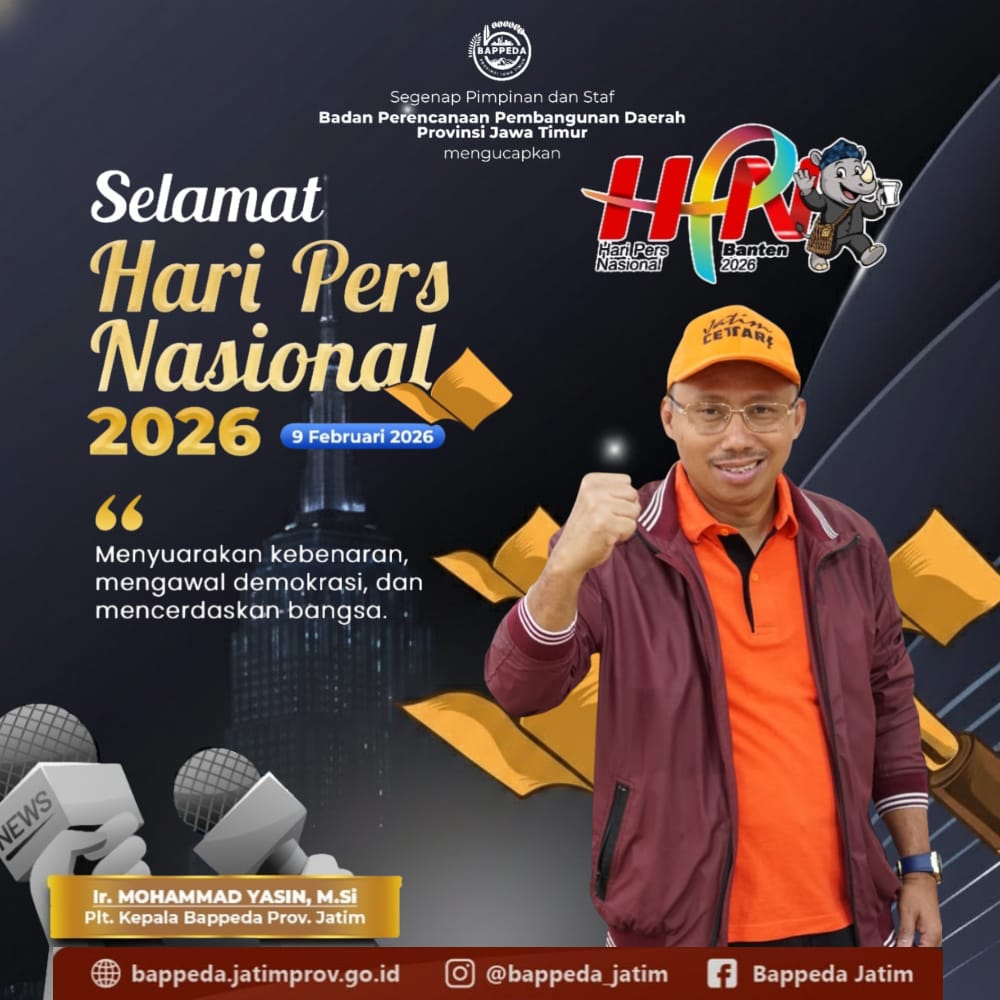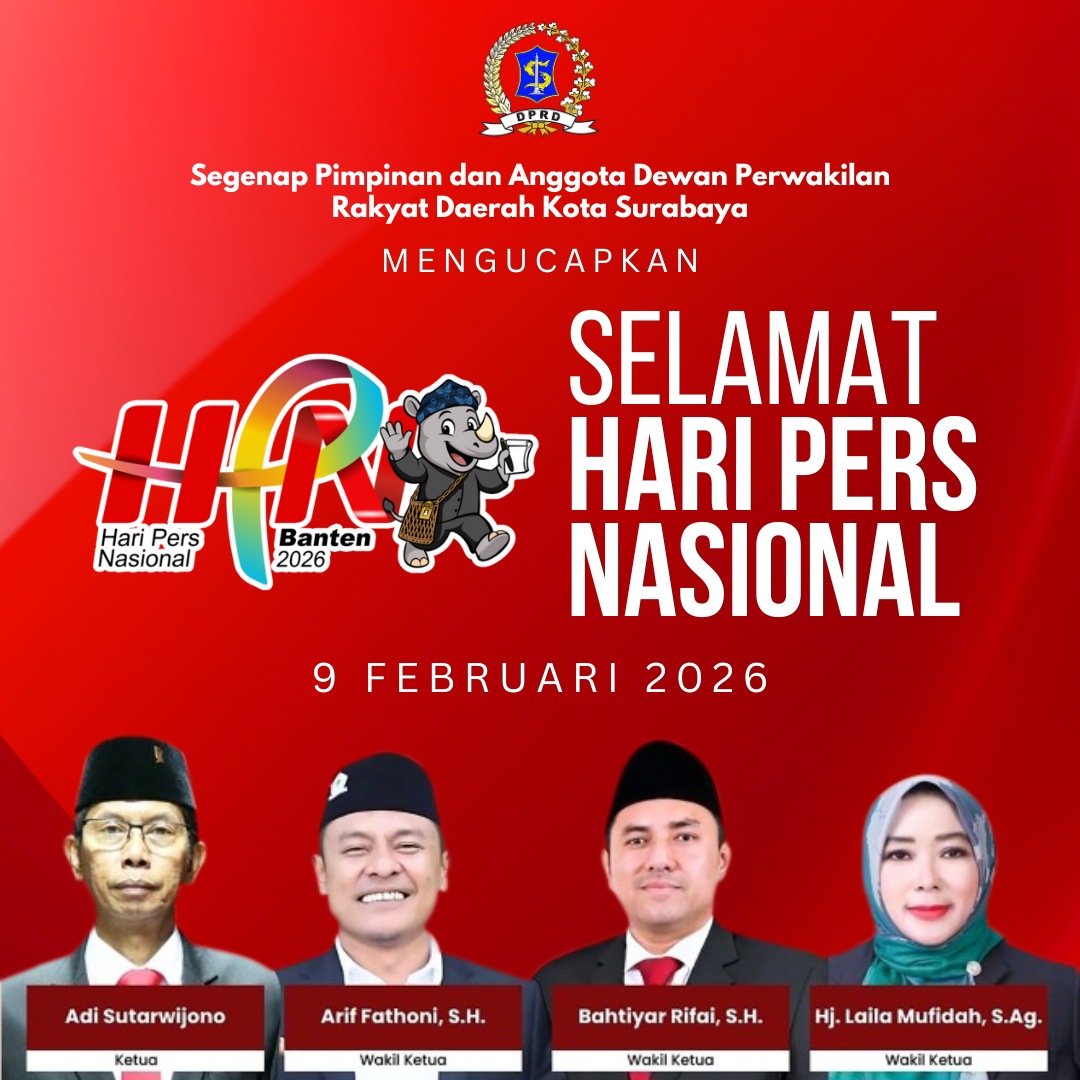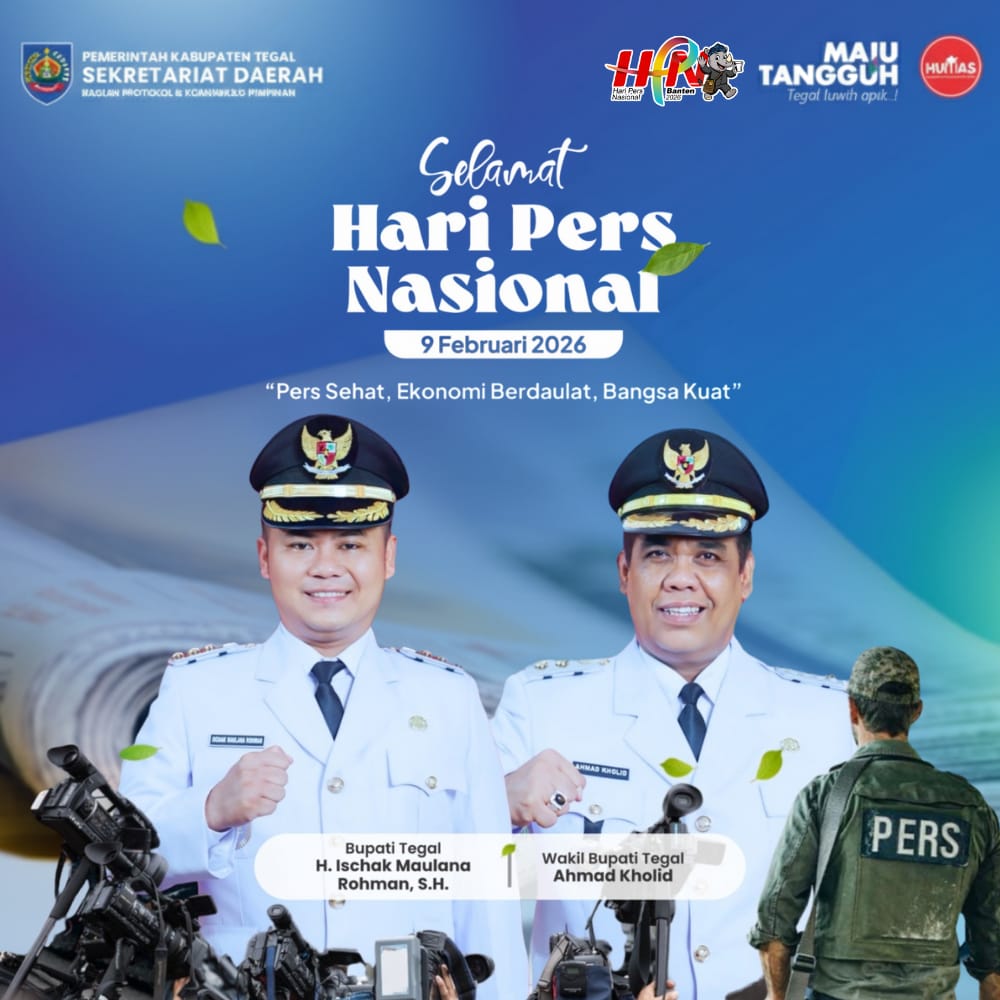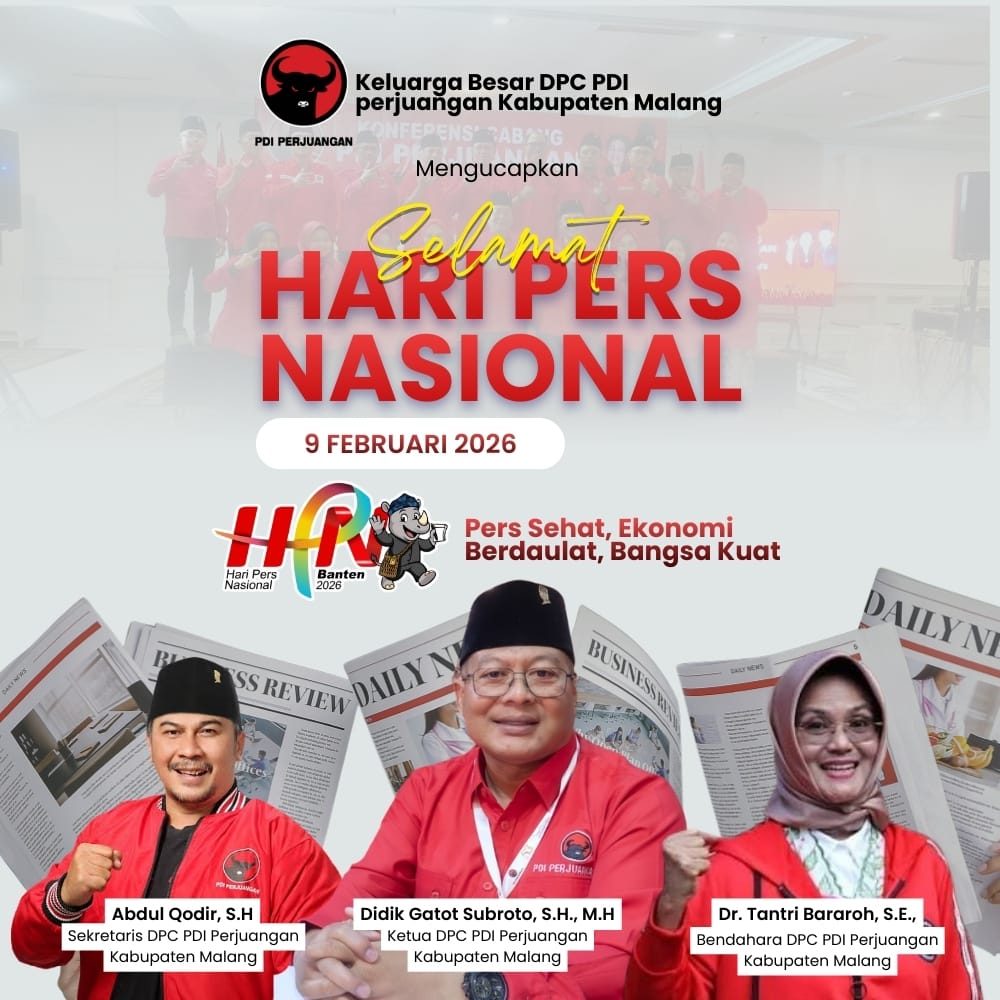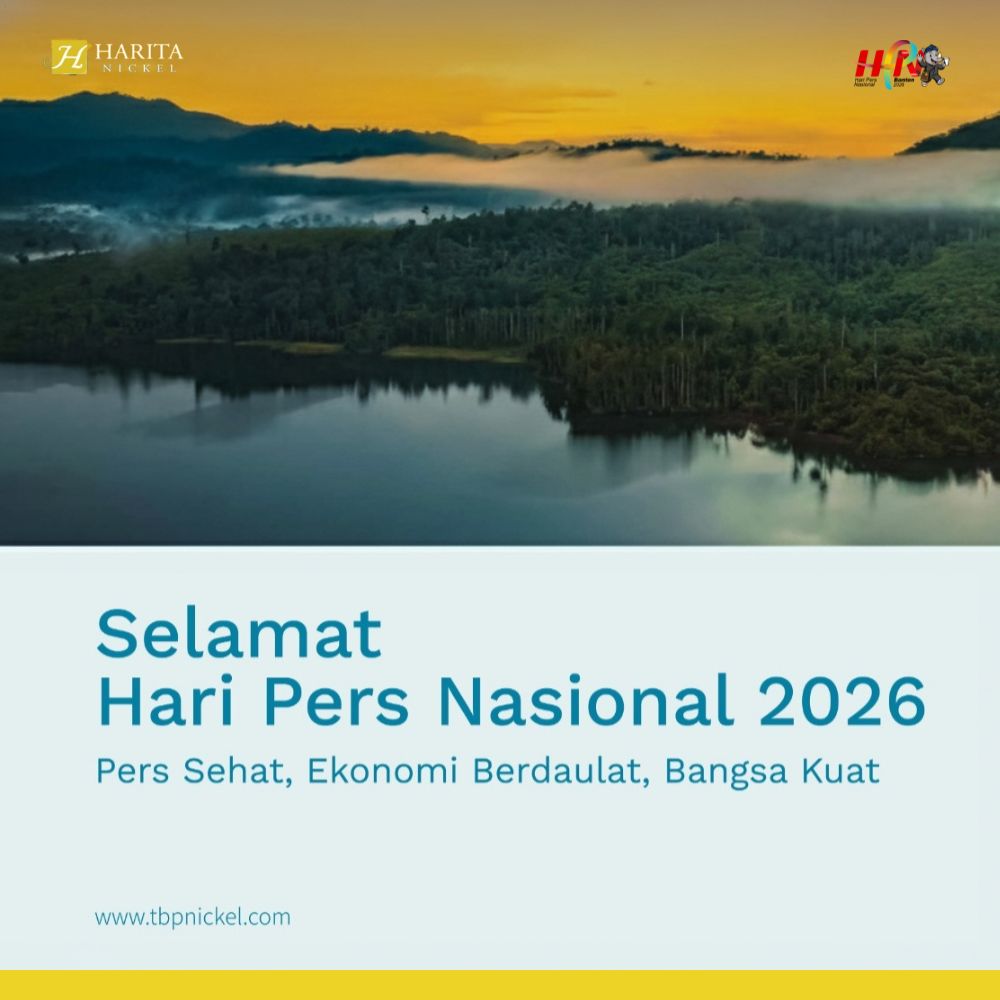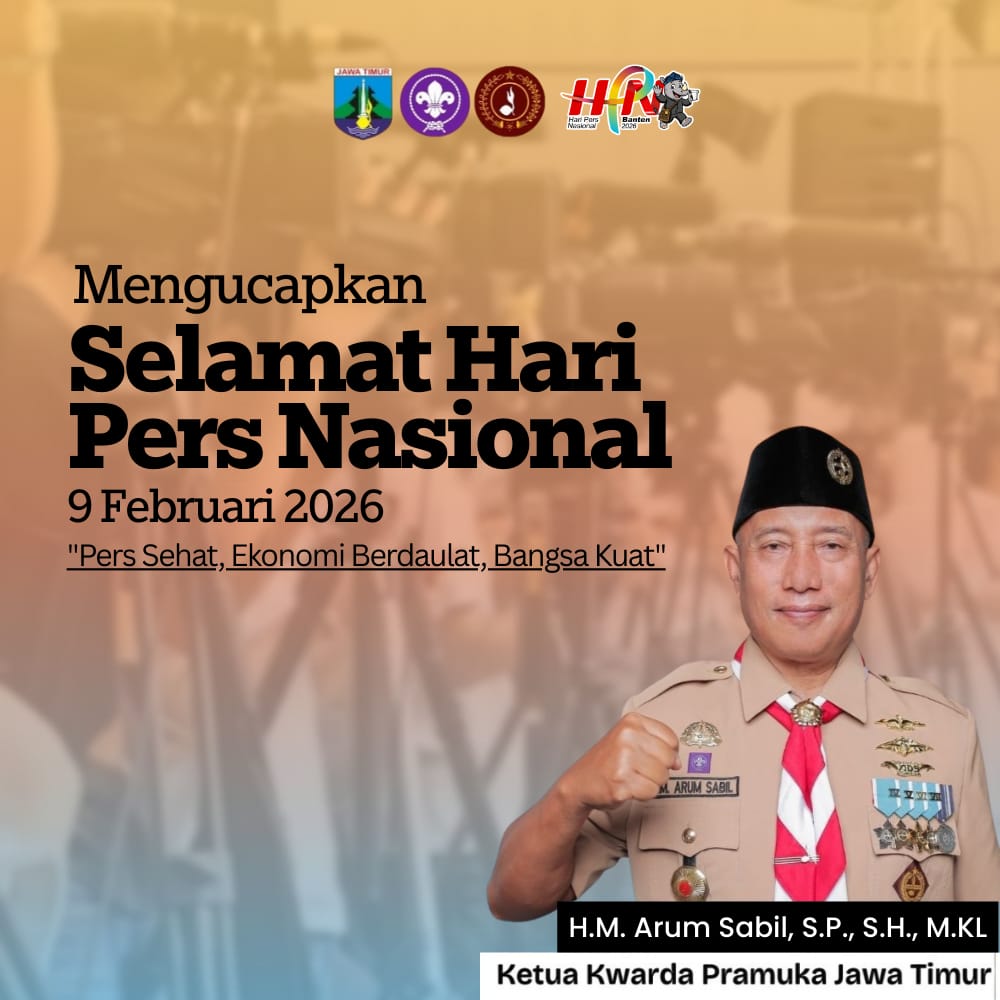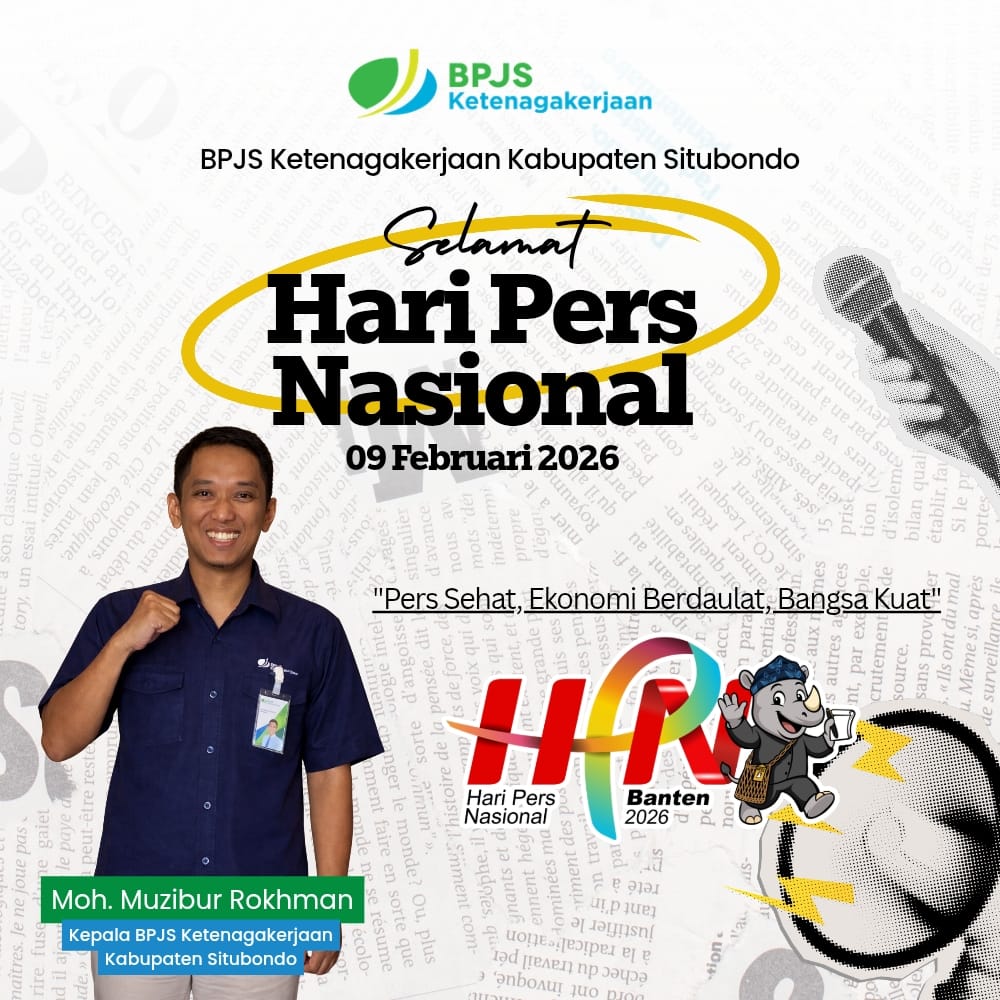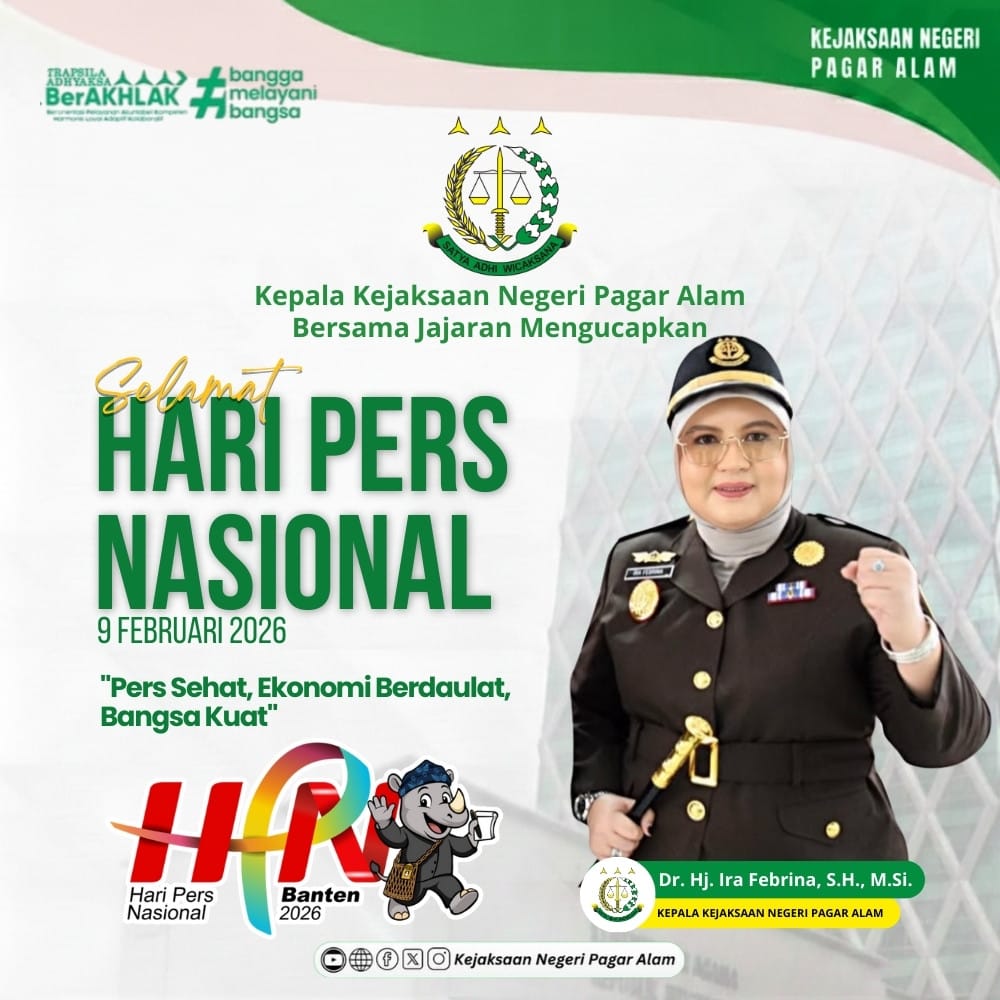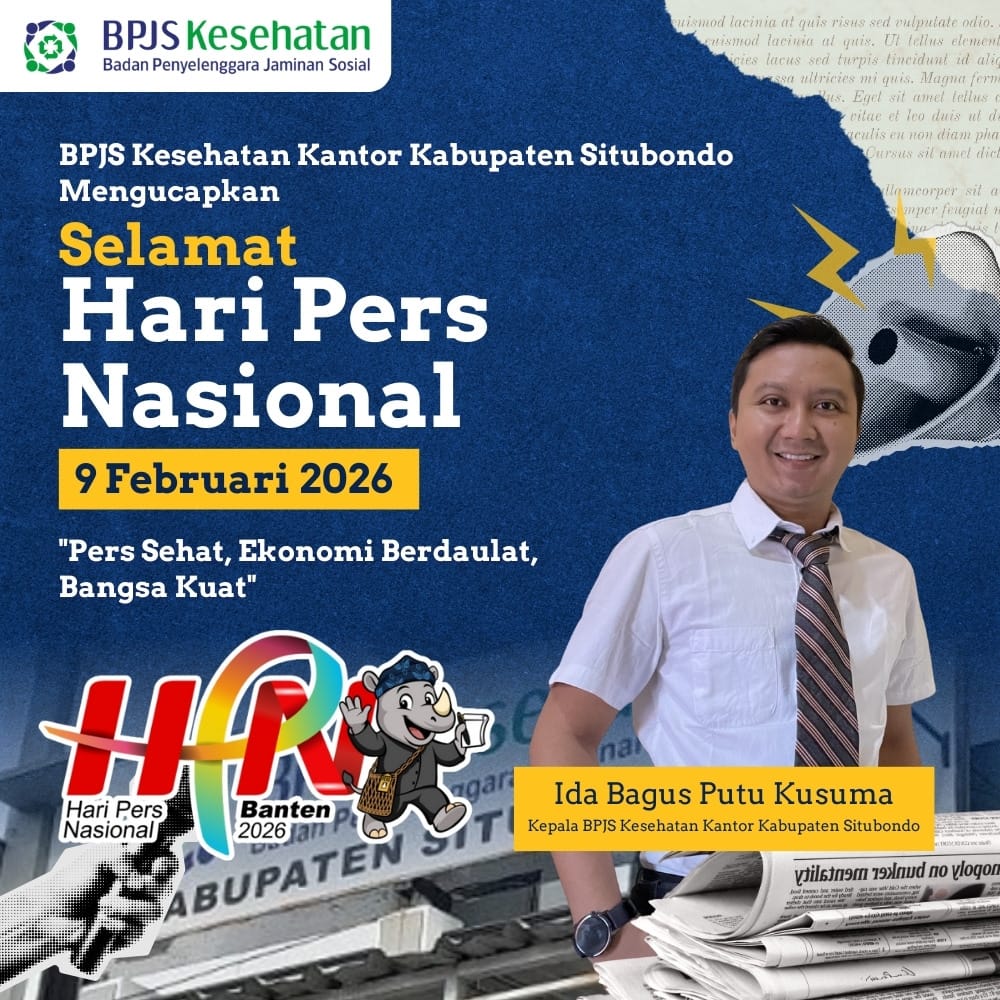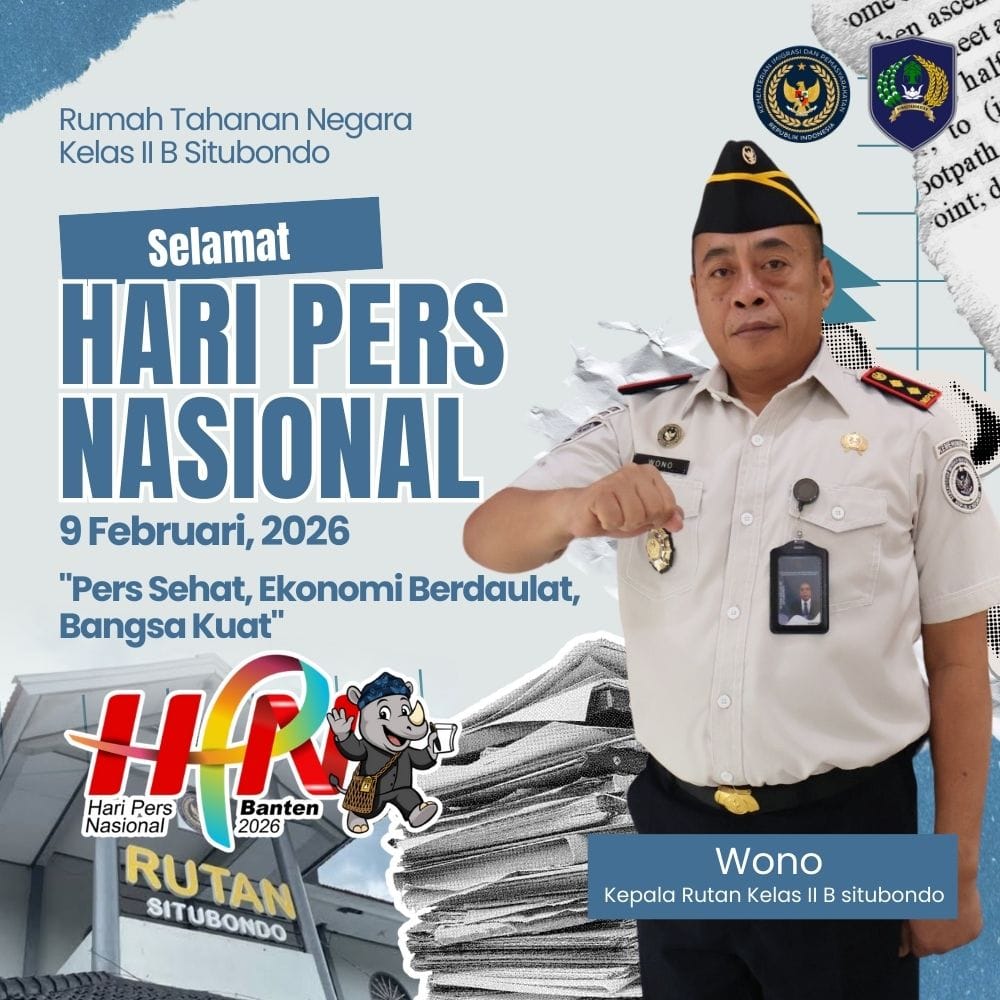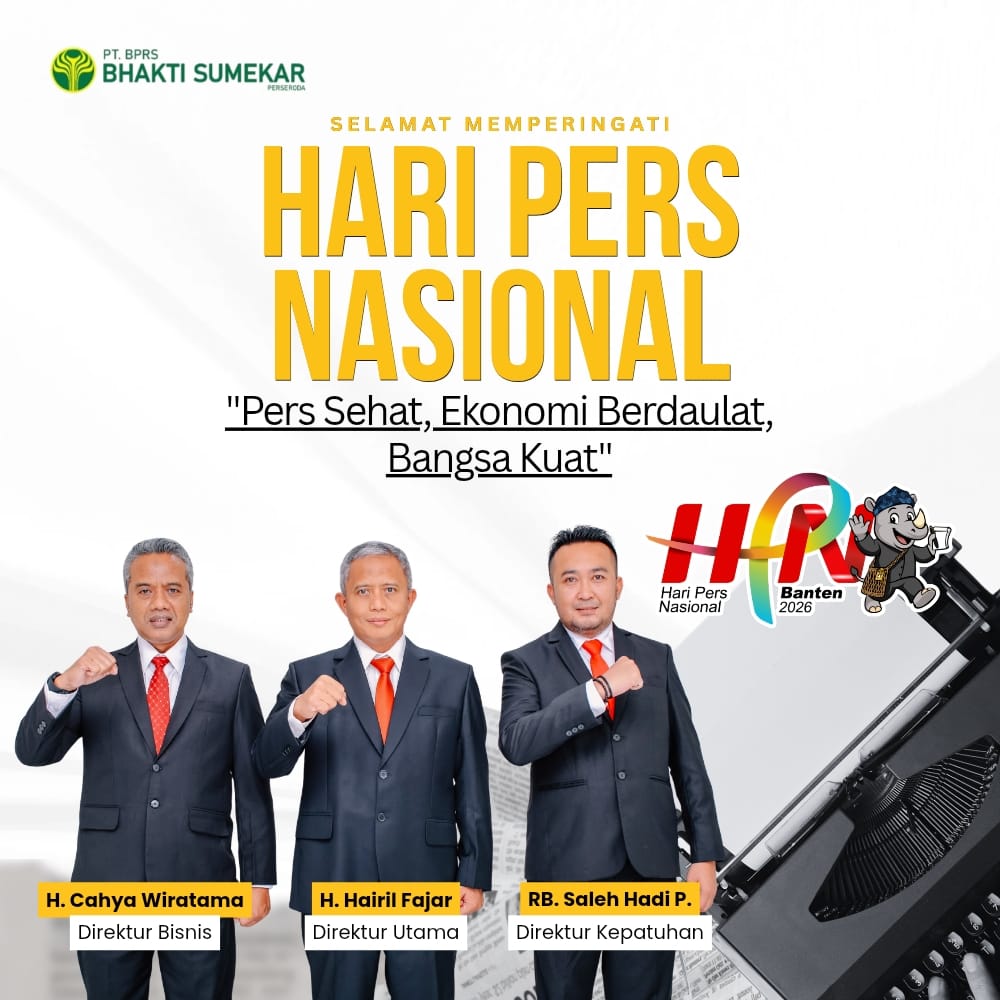Belasan tahun lalu, jauh-jauh hari sebelum beberapa hari ini saya membaca berita tentang Bupati Sugiri Sancoko yang ditangkap KPK terkait budaya minta upeti, sebenarnya saya sudah mulai melupakan fenomena penyimpangan kekuasaan itu. Belakangan ini, sorotan terhadap birokrasi (terutama eksekutif di daerah) mungkin agak berkrang, kalah dengan isu lain seperti perilaku DPR yang menaikkan kesejahteraannya hingga memunculkan demo anarkis yang menyita energi. Atau isu “feodalisme” di pondok pesantren atau isu-isu lainnya.
Dan sepertinya, sejak kita punya presiden baru hasil Pemilu 2024, perhatian publik dan media lebih banyak mengarah pada kebijakan pusat, tertutama program andalan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Birokrasi di daerah hampir luput dari sorotan. Tapi belakangan ini, tampaknya kita harus menoleh lagi dinamika kekuasaan yang paling dekat dengan kita, yaitu birokrasi pemerintah daerah.
Sebenarnya birokrasi atau pemerintahan yang paling dekat dengan warga adalah pemerintah desa. Tampaknya, sorotan terhadapnya juga sudah mulai kuat. Terbukti dengan seringnya kita melihat postingan tentang penyimpangan di desa, yang sebagian juga sudah berhadapan dengan hukum. Nah, saya kira kasus yang terjadi pada Bupati Sugiri Sancoko di Ponorogo ini harus membuat kita juga menyadari bahwa kekuasaan daerah juga butuh disorot agar penyimpangan-penyimpangan kekuasaan (‘abuse of power’) kekuasaan di daerah juga berkurang.
Kesadaran saya tentang korupsi di kabupaten sendiri sudah agak lama. Belakangan ini mungkin sudah mulai ada perubahan, tidak seperti kekuasaan-kekuasaan sebelum-sebelumnya. Pada waktu itu, birokrasi sangat parah. Semakin kita mendekat ke pemerintah dan mengenal “jeroan”-nya, ternyata waktu itu saya melihat fakta yang mencengangkan.
Alkisah, perkenalan saya yang kian dekat waktu itu dengan beberapa kepala dinas, terutama dua orang yang akhirnya dekat karena pnua hobi yang sama, akhirnya membawa saya pada cerita tentang perilaku dan relasi di birokrasi—terutama dinamika hubungan yang bernansa relasi kuasa yang jarang kita lihat kalau kita hanya melihatnya dari jauh. Anda tentu akan terkesima dengan sosok Bupati Sugiri yang tampak merakyat, supel, komunikatif, dan dalam hal tertentu merepresentasikan model kepemimpinan yang terbuka. Tapi mungkin, seperti saya, anda juga ada yang kaget ketika ia di-OTT KPK karena praktik “budaya upeti” yang ia jalankan.
Apa yang terjadi di dalam pemerintahan, posisi penguasa dengan para bawahannya, ternyata tak selalu semanis seperti apa yang tampak di luar. Mungkin anda punya bupati yang tampak gampang bergaul dengan rakyatnya, aktivis ormas atau komuntas—yang membuat kita mengatakan bahwa ia “orangnya enakan” dan “tidak terlalu kaku”, “tidak sok kuasa”. Tapi ternyata belum tentu ia manis dan enakan terhadap para pejabat di bawahnya. Dan ternyata, seperti yang terjadi pada Sugiri dan mungkin para pimpinan lainnya: Menjadikan anak buah dan pejabat bawahan sebagai mesin pengumpul uang, Otoritas yang dimiliki untuk menata posisi pejabat, apakah sekedar mempertahankan, memutasi atau mempromosikan jabatan, bisa dimainkan untuk mendapat keuntungan.
Kembali ke pengakuan dua mantan kepala dinas yang saya kenal tadi. Praktik yang dilakukan tentu lebih parah. Mungkin karena semakin ke sana, birokrasi kita memang tak sebaik sekarang. Diceritakan bahwa waktu itu kedua orang yang sudah lama pensiun itu crhat bagaimana diri mereka selaku kepala dinas tidak bisa merdeka karena harus menuruti perintah “kanjenge”. Bahkan ada atasan yang secara vulgar mendikte tentang kegiatan-kegiatan, terutama yang potensi mendapatkan rented an upeti besar. Bukan hanya proyek pengadaan dan pembangunan fisik, tapi juga soal tana-menata posisi dan jabatan.
Memang, pegawai negeri itu yang tidak enak adalah bahwa mereka harus selalu ikut alur keekuasaan yang ada. Kalau pimpinannya yang dipilih dari hasil Pilkada pas baik, mereka nyaan, tenang, dan senang. Ada kalanya mereka mendapatkan pemimpin atau atasan yang rakus, yang mendikte pebijakan dan keputusan. Bahkan yang meminta jatah upeti secara terang-terangan lewat jaringan yang kadang terstruktur.
Yang membuat saya menebah dada karena waktu itu saya baru tahu adalah bagaimana orang dalam birokrasi itu menceritakan ketika tiap-tiap kepala SKPD/dinas, termasuk mereka berdua yang blak-blakan ke saya, meminta jatah tahunan. Tiap tahun, kepala dinas—termasuk dua orang yang cerita itu—harus menyetor upeti, rata-rata 100 juta hingga 200an juta. Hal itu sudah sama-sama diketahui oleh mereka yang jadi kepala dinas. Itu adalah upeti yang rutin. Penyetorannya diberikan menjelang hari raya. Bisa ditebak, kebutuhan akan biaya menyambut hari raya bagi tiap orang selalu besar. Itulah kenapa setoran dikakukan saat itu.
Dampak Sistem Upeti
Kira-kira kalau upeti terstruktur seperti itu apa dampaknya? Dampaknya yang paling jelas pada kinerja dan kualitas birokrasi itu sendiri. Para kepala dinas atau kepala bidang, yang secara strategis punya kewenangan menggunakan anggaran (kuasa pengguna anggaran), kadang merasa bahwa posisi mereka di birokrasi hanya sebagai mesin atm yang harus menyisihkan duit dari anggaran yang sudah direncanakan, hanya demi mengumpulkan uang untuk disetor pada tuannya.
Si tuan yang menghendaki upetinya lancar kemudian harus menata birokrasinya agar sistem upeti yang dipraktikannya berjalan mulus. Maka ketika memilih orang untkuk jabatan yang strategis dan “basah” atau yang anggarannya besar, ia harus memastikan bahwa orang yang akan menempati jabatan itu adalah orang yang loyal dan setia. Bahkan bukti kesetiaan harus ditunjukkan di muka, yait berani membayar untuk mendapatkan jabatan.
Sekali lagi, posisi kepala dinas/SKPD dan Kabid, selaku pimpinan di satuan kerja yang menggunakan dan mengelola anggaran kegiatan, adalah posisi yang harus ditata. Menata orang-orang dengan dasar kesetiaan, loyalitas, dan ketertundukan ini jelas akan mengabaikan prinsip manajemen sumber daya manusia yang rasional—misalnya prinsip “right man on the right place”. Yang dijalankan adalah berdasarkan prinsip “mana orang yang harus dipertahankan di posisi tertentu, dan mana yang harus dibuang”, “mana orang yang loyal dan mana yang tidak loyal”. Bukan berdasarkan profesionalitas dan integritas, tapi berdasarkan pertimbangan isi tas (duit).
Situasi ini kemudian membuat birokrasi rusak, tidak sehat, dan patologis. Sebab organ dan jaringan birokrasi mengalirkan sesuatu yang tidak mengalir sesuai tempatnya. Yang seharusnya mengalir tersumbat. Keinginan dan kehendak tuan dipaksakan, sedangkan organ tubuh birokrasi tidak siap dengan itu. Menata orang-orang tidak sesuai kompetensi dan kebutuhan untuk kebutuhan memaksimalkan fungsi birokrasi yang sehat dan melayani.
Budaya upeti juga mempersulit pengadministrasian kegiatan pelayanan dan kegiatan memaksimalkan uang yang ada untuk benar-benat fungsional dalam pelaksanaannya. Satuan-satuan kerja, dinas dan bidang, kadang merencanakan kegiatan yang tak penting dan mengada-ngada, yang tak fungsional bagi kemajuan. Asal kegiatan bisa berpotensi gampang dimanipulasi untuk keuntungan, itulah yang diperbanyak. Bahkan kegiatan yang penting dan strategis, akhirnya justru tidak terlaksanakan meskipun sudah dirrencanakan. Inilah yang menyebabkan realisasi anggaran kadang minim, banyak kegiatan yang tidak terlaksana karena orang-orang di bidang-bidang dan dinas-dinas hanya sibuk mendahulukan kegiatan yang menguntungkan bagi upaya menyisihkan duit, yang dikumpulkan untuk disetor sebagai upeti pada atasan.
Selain itu, dari sisi manajemen SDM, sistem seperti itu juga merusak. Orang-orang yang berpotensi memaksimalkan dirinya sesuai kemampuan, justru potensinya tidak keluar. Pegawai yang cerdas dan berkualitas bisa jadi malah tersingkirkan karena ia tak mendukung skenario pengumpulan upeti. Akhirnya semangat kerja hilang karena orang yang punya potensi dan kualitas yang punya harapan untuk bisa memerankan diri secara maksimal justru tidak mendapat tempat.
Lalu dampak besarnya adalah apatisme para pegawai yang merasa bahwa posisi dan perannya hanya tergantung pada politik si tuan. Inilah yang menyebabkan tak sedikit orang-orang di birokrasi beranggapan: Untuk apa kerja giat-giat dan serius mengabdi pada rakyat dan Negara, toh Negara telah dikuasai atasan-atasan yang rakus, Dalam situasi ini, apatisme dan ketidakpercayaan telah menggejala dalam tubuh birokrasi. Yang menyebabkan birokrasi di Negara kita malas, apatis, kurang semangat, bahkan penyakit menyimpang oleh oknum-oknumnya juga menjadi virus yang menular.
Awalnya saya menduga bahwa apa yang diceritakan oleh dua orang kepala dinas pada masanya itu sudah tidak mungkin terjadi di berbagai kabupaten atau kota. Sebab saya amati kian ke sini, Negara—dalam hal ini kementerian yang menangani aparat Negara dan reformasi birokrasi—terus menjalankan tugasnya dengan terobosan-terobosan kebijakan untuk membangun birokrasi yang semakin bersih dan berintegritas. Saya sendiri ketika kemudian selama 10 tahun menjadi pimpinan lembaga Negara tingkat kabupaten, upaya melakukan meritokrasi, peningkatan kinerja dan integritas itu sedemikian massif.
Makanya, saya kaget ketika berbagai platform media menyuguhkan berita tentang budaya setor-menyetor upeti seperti terjadi di Ponorogo. Tentu ini harus menjadi perhatian kita semua. Ini bukan hanya soal tugas pemerintah pusat untuk mempercepat reformasi birokrasi saja. Ini terkait dengan ekosistem politik yang melingkupinya. Sebab itu adalah korupsi politik. Pelakunya adalah pimpinan daerah yang terpilih dari Pemilihan (pilkada) di mana budaya transaksional dan penuh “politik uang” masih banyak terjadi. (*)
*) Nurani Soyomukti adalah penulis dan pegiat literasi, pendiri INDEK (Institute Demokrasi dan Keberdesaan), dan saat ini sedang ‘nyantri’ di Pasca-Sarjana Akidah dan Filsafat Islam Universitas Negeri Tulungagung. Fb Nurani Soyomukti dan IG @soyomuktinurani.
**) Isi tulisan di atas menjadi tanggung jawab penulis
***) Ketentuan pengiriman naskah opini:
- Naskah dikirim ke alamat email redaksi@ketik.com
- Berikan keterangan OPINI di kolom subjek
- Panjang naskah maksimal 800 kata
- Sertakan identitas diri, foto, dan nomor HP
- Hak muat redaksi.(*)


















![Thumbnail Berita - [FOTO] Hangat dan Penuh Keakraban, Ah Pek Kopitiam Malang Jadi Tempat Favorit Kumpul Keluarga dan Sahabat](https://ketik.com/assets/upload/57072026021417515410001454080.webp)