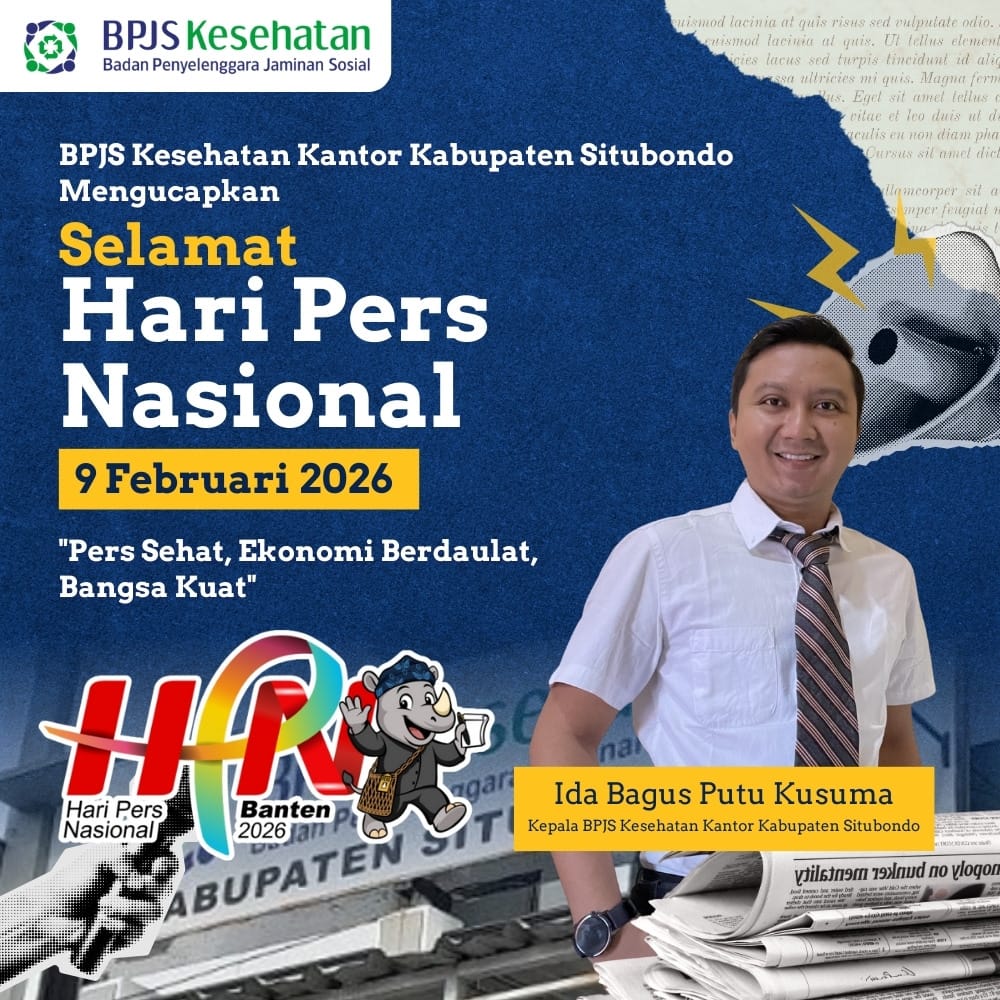Setiap tahun perguruan tinggi di Indonesia meluluskan ribuan sarjana, yang diharapkan mereka siap memasuki dunia kerja dan berkontribusi bagi pembangunan. Sementra itu ijazah dianggap sebagai simbol keberhasilan pendidikan sekaligus modal awal untuk memperoleh kemandirian ekonomi.
Namun, realitanya menunjukkan bahwa transisi dari dunia akademik ke dunia usaha dan industri tidak selalu berlangsung mulus. Banyak lulusan baru menghadapi masa tunggu kerja yang cukup lama dan ketidakpastian.
Di tengah ekspansi pendidikan tinggi dan meningkatnya tuntutan kualitas dan kualifikasi akademik, peluang kerja bagi pencari kerja pemula justru semakin kompetitif. Fenomena pengangguran terdidik yang kerap muncul dalam laporan media mengidentifikasikan adanya ketidakseimbangan antara output pendidikan dan kebutuhan pasar kerja.
Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan ketenagakerjaan bagi lulusan baru tidak dapat dipahami semata sebagai kegagalan individu, melainkan sebagai persoalan struktural yang melibatkan sistem pendidikan, dinamika pasar tenaga kerja, serta kebijakan pembangunan sumber daya manusia.
Transisi dari dunia pendidikan ke dunia kerja kerap tidak mulus tersebut mencerminkan persoalan struktural ketenagakerjaan di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) lulusan perguruan tinggi masih relatif tinggi.
Pada Agustus 2023, TPT lulusan universitas tercatat sebesar 5,18 persen, sementara lulusan diploma mencapai 6,35 persen (BPS, 2023). Temuan ini memperlihatkan bahwa pendidikan tinggi belum sepenuhnya berfungsi sebagai jembatan efektif menuju dunia kerja, sebagaimana diidealkan dalam teori human capital yang menempatkan pendidikan sebagai investasi produktif bagi tenaga kerja.
Salah satu penjelasan atas kondisi tersebut adalah terjadinya mismatch antara dunia pendidikan dan kebutuhan dunia usaha dan industri. Dalam perspektif ekonomi ketenagakerjaan, skill mismatch terjadi ketika kompetensi yang dimiliki lulusan tidak sejalan dengan keterampilan yang dibutuhkan banyak pasar kerja.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mencatat bahwa banyak lulusan belum memiliki keterampilan aplikatif yang relevan, terutama dalam bidang teknologi digital, analisis data, dan problem solving (Kemendikbud Ristek, 2022). Kurikulum pendidikan tinggi kerap bergerak lebih lambat dibandingkan dinamika industri, sehingga menghasilkan lulusan yang kuat secara teoritis tetapi lemah dalam kesiapan profesional.
Kesenjangan tersebut diperkuat oleh perbedaan orientasi antara dunia akademik dan dunia kerja. Pendidikan tinggi cenderung menekankan pencapaian kognitif dan akademik, sementara dunia kerja menuntut kemampuan adaptif, kolaboratif, dan skill.
Survei Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menunjukkan bahwa pelaku industri menilai kesiapan kerja lulusan baru masih rendah, terutama dalam hal pengalaman praktik dan pemahaman budaya kerja (Kadin, 2021). Dalam kerangka teori employability, kesiapan kerja tidak hanya ditentukan oleh pengetahuan, tetapi juga oleh pengalaman dan sikap profesional.
Kurangnya pengalaman kerja menjadi hambatan klasik yang terus berulang. Banyak perusahaan mensyaratkan pengalaman kerja satu hingga dua tahun bahkan untuk posisi pemula.
Situasi ini menciptakan apa yang disebut para sosiolog sebagai experience trap, yakni kondisi ketika lulusan tidak dapat memperoleh pekerjaan karena tidak berpengalaman, tetapi tidak dapat berpengalaman karena tidak memperoleh pekerjaan. Program magang memang hadir sebagai solusi, namun masih bersifat terbatas dan belum sepenuhnya terintegrasi secara sistemik dalam kurikulum pendidikan tinggi.
Sementara itu persyaratan kerja yang tidak realistis semakin mempersulit ruang masuk lulusan baru. Batas usia yang ketat, tuntutan penguasaan berbagai keterampilan sekaligus, serta ekspektasi produktivitas instan mencerminkan logika pasar kerja yang semakin kompetitif.
Dalam perspektif sosiologi kerja, kondisi ini menunjukkan pergeseran resiko dari institusi ke individu, di mana pencari kerja pemula dituntut menanggung beban adaptasi tanpa dukungan transisi yang memadai. Dunia kerja tidak lagi diposisikan sebagai ruang pembelajaran, melainkan arena seleksi yang keras sejak tahap awal.
Tantangan Era Digital
Perubahan dunia kerja akibat digitalisasi dan otomatisasi turut memperumit situasi. World Economic Forum melaporkan, bahwa banyak pekerjaan konvensional berpotensi tergantikan teknologi, sementara pekerjaan baru menuntut keterampilan digital tingkat lanjut (Kemenaker, 2023).
Teori creative destruction menjelaskan bahwa inovasi memang menciptakan peluang baru, tetapi sekaligus menyingkirkan kelompok yang tidak siap beradaptasi. Lulusan baru sering kali berada di posisi rentan dalam proses transisi ini.
Dampak dari persoalan tersebut tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial dan psikologis. Masa tunggu kerja yang lama memicu kecemasan, penurunan kepercayaan diri, bahkan krisis makna hidup di kalangan generasi muda.
Sejumlah laporan nasional tentang kesehatan mental menunjukkan meningkatnya tekanan psikologis pada anak muda akibat ketidakpastian kerja dan eksploitasi sosial yang tinggi (KemenPPPA, 2023). Dalam perspektif psikologi sosial, kerja tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai sumber identitas dan martabat sosial.
Sulitnya lapangan kerja bagi lulusan baru perlu dibaca sebagai persoalan sistemik, bukan kegagalan individu. Pendidikan tinggi, dunia industri, dan negara perlu membangun ekosistem transisi kerja yang lebih inklusif dan adaptif.
Tanpa pembenahan struktural—mulai dari kurikulum berbasis pengalaman hingga kebijakan ketenagakerjaan yang ramah pemula—jurang antara harapan lulusan dan kenyataan dunia kerja akan terus melebar, meninggalkan generasi muda dalam ketidakpastian yang berkepanjangan.
Disisi lain, keterbatasan akses kerja membawa konsekuensi sosial dan psikologis yang signifikan. Kerja tidak hanya berfungsi sebagai sumber penghasilan, tetapi juga sebagai ruang pembentukan identitas dan makna hidup.
Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pendidikan tinggi, dunia industri, dan negara untuk membangun ekosistem kerja yang lebih ramah bagi lulusan baru. Tanpa pembenahan struktural yang berkelanjutan, kesenjangan antara harapan generasi muda dan kenyataan dunia kerja akan terus melebar.
*) Ahmad Ghozi merupakan Kepala Pusat Career Development Center UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
**) Isi tulisan di atas menjadi tanggung jawab penulis
***) Ketentuan pengiriman naskah opini:
- Naskah dikirim ke alamat email redaksi@ketik.com
- Berikan keterangan OPINI di kolom subjek
- Panjang naskah maksimal 800 kata
- Sertakan identitas diri, foto, dan nomor HP
- Hak muat redaksi.(*)



















![Thumbnail Berita - [FOTO] Hangat dan Penuh Keakraban, Ah Pek Kopitiam Malang Jadi Tempat Favorit Kumpul Keluarga dan Sahabat](https://ketik.com/assets/upload/57072026021417515410001454080.webp)