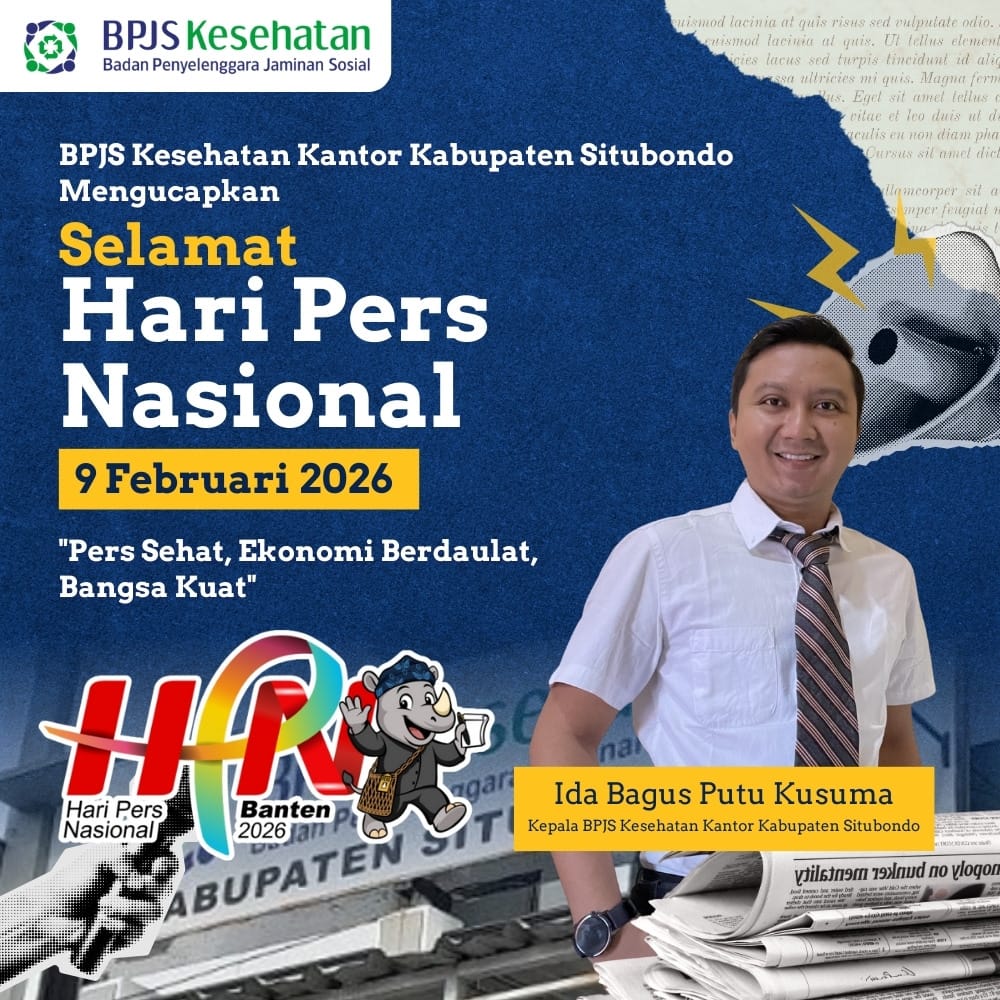Aceh kembali terendam. Banjir besar yang melanda Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Tengah, Aceh Timur, Gayo Lues, dan sejumlah kabupaten lainnya dalam beberapa pekan terakhir bukan sekadar peristiwa alam, melainkan cermin telanjang dari krisis struktural yang telah lama dibiarkan.
Ribuan rumah tenggelam, puluhan ribu warga mengungsi, sawah dan ladang rusak, rantai pangan terganggu, dan ruang hidup rakyat semakin menyempit. Infrastruktur vital lumpuh, sementara kehadiran negara sering terasa lamban, reaktif, dan tidak menyentuh akar persoalan.
Bencana ini menegaskan bahwa persoalan Aceh tidak berdiri sendiri sebagai problem daerah, melainkan berkaitan erat dengan model pembangunan nasional yang sentralistik, eksploitatif, dan kurang memberi ruang bagi kekhususan Aceh. Ketika lingkungan rusak, tata ruang diabaikan, dan kearifan lokal dikesampingkan, maka bencana hanya tinggal menunggu waktu.
Aceh bukan wilayah taklukan yang lahir dari penaklukan Republik. Aceh bergabung dengan Indonesia melalui pilihan politik dan moral. Membantu Republik yang baru lahir demi cita-cita kemerdekaan bersama. Dalam perspektif Aceh, bergabung dengan Indonesia bukan berarti menanggalkan jati diri, kedaulatan historis, dan sistem nilai yang telah hidup berabad-abad, melainkan membangun persekutuan yang adil dan setara.
Dalam konteks inilah makna “merdeka” bagi Aceh harus dipahami. Merdeka bukan semata lepas dari penjajahan asing, melainkan terjaminnya hak Aceh untuk mengatur dirinya sesuai identitas, sejarah, dan keyakinannya sebagaimana kemudian diakui dalam Undang - Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Namun ketika pengakuan itu berhenti di atas kertas dan tidak menjelma dalam praktik kebijakan, maka kemerdekaan Aceh menjadi formalistik dan rapuh.
Jika kemerdekaan Aceh hanya diukur melalui status otonomi khusus atau kewenangan administratif, maka banjir yang terus berulang ini menunjukkan bahwa kemerdekaan tersebut belum hadir secara substantif. Rakyat Aceh masih terjajah, kali ini bukan oleh kolonial asing, tetapi oleh ketimpangan pembangunan, kelalaian negara, dan sistem ekonomi-politik yang menjauhkan rakyat dari kedaulatan atas tanah dan hidupnya sendiri.
Para Indatu Aceh berjuang bukan hanya untuk mengusir penjajah, tetapi untuk memastikan Aceh berdiri sebagai negeri yang berdaulat atas tanah, sumber daya, hukum, dan masa depannya. Perlawanan Aceh terhadap kolonialisme adalah perlawanan terhadap perampasan martabat dan cara hidup. Spirit inilah yang semestinya menjadi jiwa dalam setiap kebijakan yang menyentuh Aceh hari ini.
Namun sejarah pascakemerdekaan Indonesia justru memperlihatkan fase panjang pengingkaran terhadap semangat tersebut. Kontribusi Aceh dalam mempertahankan Republik dipinggirkan, ruang politik dipersempit, dan sumber daya alam dieksploitasi tanpa keadilan distribusi.
Gas, hutan, dan laut Aceh menjadi bagian dari akumulasi kekayaan nasional, sementara rakyat Aceh terus berhadapan dengan kemiskinan struktural. Inilah dosa-dosa Republik terhadap Aceh yang tidak dapat ditebus hanya dengan retorika persatuan.
Kemerdekaan tidak cukup dimaknai sebagai bebas dari penjajahan fisik. Kemerdekaan sejati adalah kemerdekaan sumber daya manusia. Dalam konteks Aceh hari ini, kemerdekaan itu masih jauh dari kata tuntas.
Di bidang pendidikan, UUPA secara tegas mengakui kekhususan Aceh dalam mengembangkan pendidikan berbasis nilai-nilai Islam. Namun dalam praktiknya, kebijakan pendidikan nasional sering kali berjalan tanpa sinkronisasi substansial dengan kebutuhan Aceh.
Pendidikan Islam masih kerap diposisikan sebagai pelengkap, bukan fondasi pembangunan manusia Aceh. Sejarah, pemikiran, dan tradisi keilmuan Aceh belum sepenuhnya menjadi arus utama dalam sistem pendidikan, sehingga generasi muda tumbuh tercerabut dari akar identitasnya sendiri.
Dalam sektor ekonomi, ironi serupa terjadi. Hadirnya Bank Syariah Indonesia (BSI) yang diposisikan sebagai simbol ekonomi syariah di Aceh belum sepenuhnya menjawab persoalan kemandirian ekonomi rakyat.
Akses pembiayaan bagi petani, nelayan, dan UMKM masih terbatas, sementara orientasi ekonomi cenderung melayani kepentingan elite dan proyek-proyek besar. Ekonomi syariah direduksi menjadi institusi keuangan, bukan sistem yang membebaskan dan menyejahterakan.
Kondisi di lapangan memperlihatkan kerentanan serius. Beberapa waktu sebelum bencana banjir, Aceh bahkan mendapat teguran dari kementerian terkait dalam persoalan pembelian beras impor. Terlepas dari ada atau tidaknya mafia pangan, fakta ini menunjukkan lemahnya kedaulatan pangan Aceh.
Padahal Aceh memiliki lahan, petani, dan potensi produksi yang besar. Ketika pangan lokal dikalahkan oleh sistem distribusi nasional dan impor, maka negara sedang mencabut kedaulatan rakyat Aceh atas perutnya sendiri.
Ironisnya, kekhususan Aceh sebagaimana diamanatkan UUPA, termasuk hak untuk menjalin kerja sama luar negeri dalam bidang perdagangan dan ekonomi belum dimaksimalkan secara serius. Aceh diperlakukan seolah hanya objek kebijakan pusat, bukan subjek yang berhak menentukan arah ekonominya sendiri. Inilah wajah kolonialisme gaya baru: sah secara hukum, timpang secara keadilan.
Namun kritik terhadap kemerdekaan Aceh tidak boleh berhenti pada Republik Indonesia semata. Bangsa Aceh juga harus berani bercermin. Penjajahan gaya baru memang hadir melalui sistem dan kebijakan negara, tetapi kemerdekaan Aceh juga terkikis dari dalam oleh kelalaian kolektif dan pengkhianatan elite.
Sebagian generasi hari ini mulai kehilangan kesadaran tentang makna dan tujuan kemerdekaan. Merdeka direduksi menjadi slogan, bukan cita-cita untuk mewujudkan Nanggroe yang bersyariat, berdaulat, dan masyarakat yang sejahtera serta maju.
Kekuasaan diperebutkan bukan sebagai amanah, tetapi sebagai alat akumulasi. Elit-elit Aceh sibuk memperjuangkan kepentingan individual, memperkaya diri dan membangun koloni kekuasaan, sementara rakyat dibiarkan menanggung dampak kebijakan yang tidak adil.
Karena itu, memperjuangkan kemerdekaan Aceh hari ini menuntut keberanian orang Aceh untuk membebaskan dirinya sendiri. Membebaskan pikiran dari mental terjajah, membebaskan politik dari praktik transaksional, dan membebaskan ekonomi dari ketergantungan serta budaya rente. Kemerdekaan tidak akan hidup jika orang Aceh menyerahkan nasibnya kepada elite yang lupa amanah, atau jika generasi mudanya tercerabut dari sejarah dan nilai perjuangan Indatu.
Memperjuangkan kemerdekaan bagi orang Aceh berarti mengembalikan politik sebagai jalan pengabdian, pendidikan sebagai proses pembebasan, dan ekonomi sebagai sarana keadilan sosial. Inilah jihad zaman ini: melawan lupa, melawan ketidakadilan yang dinormalisasi, dan melawan pengkhianatan yang dibungkus retorika.
*) Dasrol Habibi merupakan Kader HMI Cabang Blangpidie sekaligus Ketua BEM STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya
**) Isi tulisan di atas menjadi tanggung jawab penulis
***) Ketentuan pengiriman naskah opini:
- Naskah dikirim ke alamat email redaksi@ketik.com
- Berikan keterangan OPINI di kolom subjek
- Panjang naskah maksimal 800 kata
- Sertakan identitas diri, foto, dan nomor HP
- Hak muat redaksi.(*)