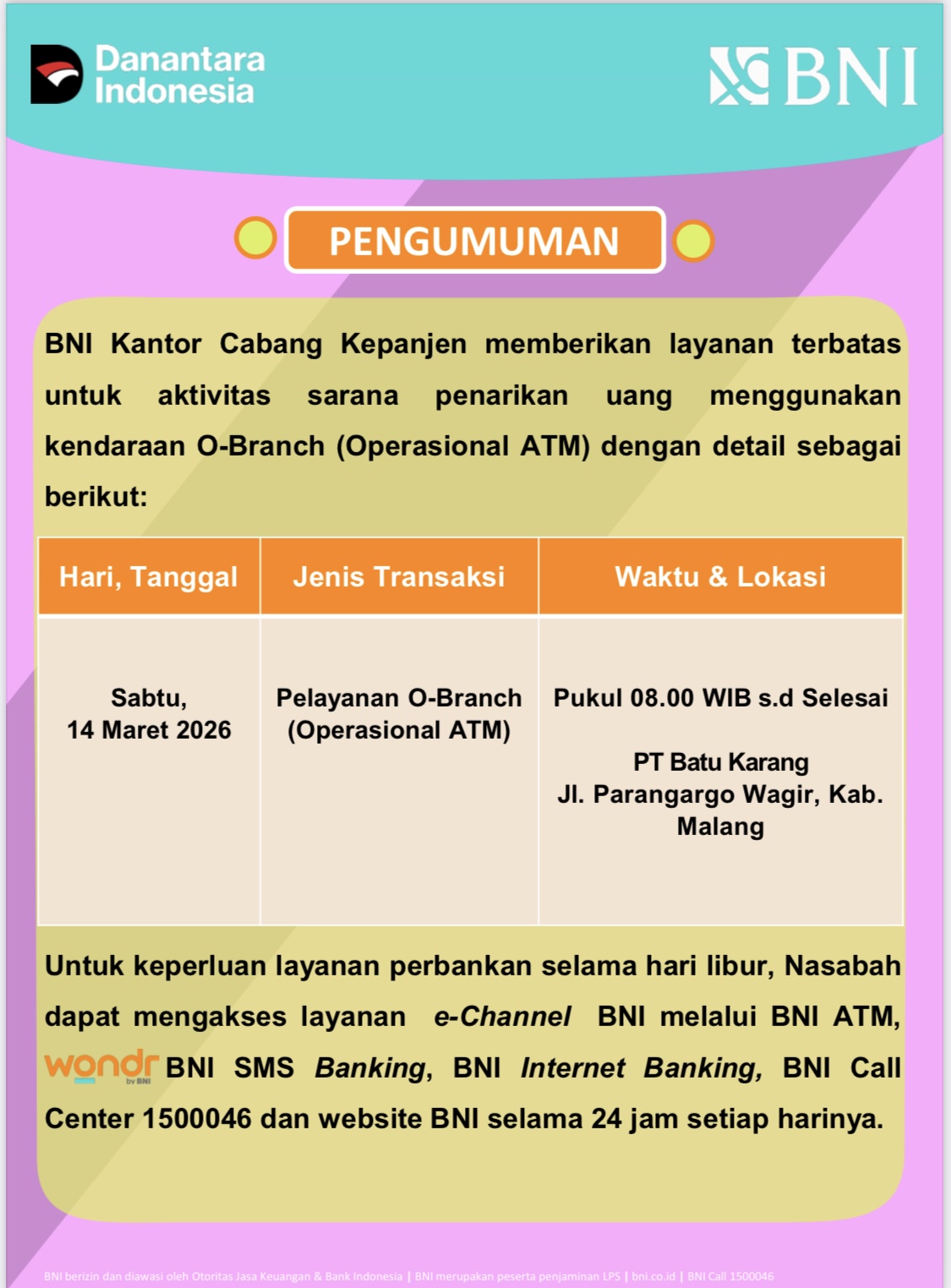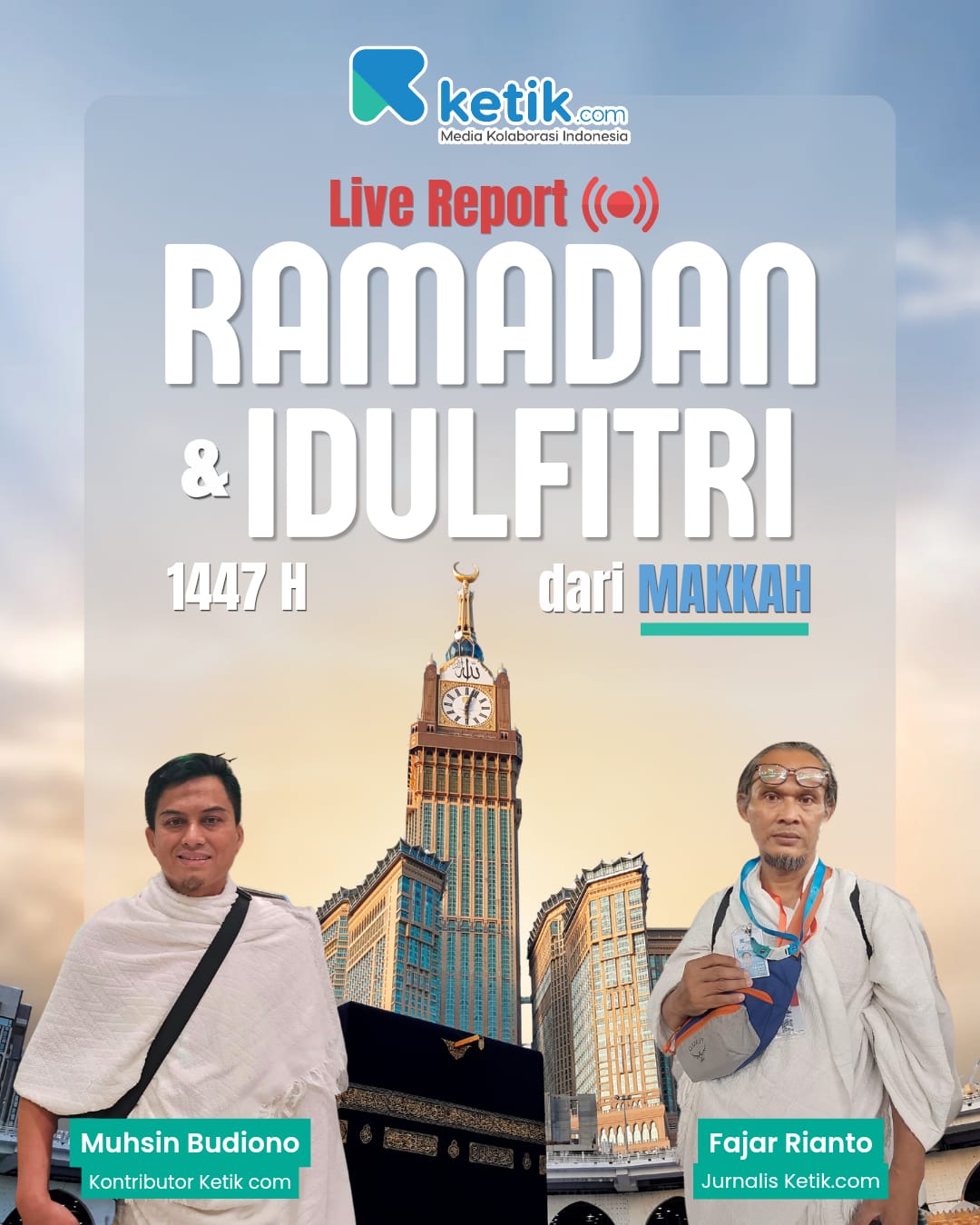Opini kali ini tak lain sebagai bentuk kegelisahan penulis, ketika membaca produk hukum daerah. Yakni Peraturan Walikota (Perwali) Probolinggo Nomor 44 Tahun 2021 beserta perubahannya melalui Perwali Nomor 37 Tahun 2023.
Di dalam regulasi pada intinya mengatur pengendalian, pengawasan, dan evaluasi terhadap kegiatan usaha tertentu yang dinilai berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kota Probolinggo, itu, isinya justru memaparkan ruang abu-abu.
Namun perlu digarisbawahi, kegelisahan ini bukan lahir dari sikap menolak aturan. Melainkan bentuk kekhawatiran terhadap hukum yang seharusnya memberi kepastian, justru berubah menjadi sumber ketidakpastian. Dari kegelisahan inilah tulisan ini bermula.
Tulisan ini juga bukan bertujuan menghakimi niat pemerintah. Tetapi mengurai keganjilan regulasi yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Sebab ketidak pastian, justru akan berubah menjadi konflik terbuka antara warga dan kekuasaan. Minimnya perlindungan terhadap pelaku usaha seperti (izin usaha), juga membuka ruang lebar bagi tindakan administratif yang rawan dipersoalkan.
Masalah paling mendasar terlihat dari penggunaan frasa kunci “berpotensi menimbulkan kerawanan ketentraman dan ketertiban masyarakat”. Istilah ini menjadi pondasi utama kebijakan. Tapi ironisnya tidak pernah didefinisikan secara operasional. Tidak ada indikator objektif, tidak ada ukuran kuantitatif, dan tidak ada batasan konkret. Akibatnya, tafsir sangat bergantung pada subjektivitas pejabat atau tim evaluasi.
Dalam kondisi seperti ini, pelaku usaha tidak memiliki alat ukur untuk menilai apakah kegiatan mereka melanggar atau tidak. Lebih jauh, tindakan penutupan usaha berpotensi dipersepsikan sebagai tindakan sewenang-wenang karena tidak berbasis kriteria yang jelas. Sebuah kondisi yang bertentangan dengan asas kepastian hukum (rechtszekerheid).
Persoalan lain yang tidak kalah krusial adalah pelibatan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam proses evaluasi perizinan. Perwali memang menyebutkan bahwa tim dapat melibatkan unsur MUI, namun tidak memberikan batasan kewenangan yang tegas. Apakah MUI berperan memberi pertimbangan etika, moral, atau justru penilaian substantif terhadap kelayakan usaha?
Ketiadaan kejelasan ini menimbulkan konflik norma, terutama ketika proses administratif negara bersinggungan dengan lembaga non-pemerintah berbasis keagamaan. Dalam konteks pelayanan publik, negara dituntut bersikap netral. Tanpa dasar undang-undang yang jelas, pelibatan MUI berpotensi digugat sebagai pelanggaran asas non-delegation of authority.
Kelemahan serius berikutnya tampak pada pasal yang mengatur tindakan penutupan atau penyegelan usaha. Norma tersebut bersifat sangat umum dan tidak disertai tahapan prosedural yang lazim dalam hukum administrasi. Tidak dijelaskan apakah harus ada teguran bertahap, peringatan tertulis, berita acara pemeriksaan, atau kesempatan klarifikasi bagi pelaku usaha.
Tidak ada pula mekanisme keberatan atau banding administratif, serta tidak diatur batas waktu penutupan dan syarat pembukaan kembali. Dalam perspektif AUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik), kondisi ini berpotensi melahirkan keputusan diskresi yang cacat prosedur dan rentan dibatalkan di PTUN.
Masalah multitafsir juga muncul dalam lampiran perwali yang memasukkan kategori “usaha lainnya”. Frasa ini seolah menjadi pintu darurat bagi perluasan kewenangan tanpa batas. Tanpa parameter yang jelas, hampir semua jenis usaha dapat sewaktu-waktu dikategorikan “berpotensi rawan”.
Dari kafe kecil, angkringan dengan musik akustik, hingga barbershop yang buka malam hari, semuanya bisa masuk dalam kategori ini jika penguasa menghendaki. Norma semacam ini jelas bertentangan dengan asas lex certa yang mensyaratkan kejelasan dan ketegasan norma hukum.
Lebih ironis lagi, perwali ini tidak menyediakan indikator evaluasi yang terukur. Tidak ada parameter kebisingan, jam operasional, kepadatan pengunjung, atau data empiris terkait potensi kriminalitas. Tidak dijelaskan pula metode audit, verifikasi lapangan, atau mekanisme pembuktian. Tanpa instrumen penilaian objektif, keputusan tim evaluasi rawan dianggap cacat wewenang dan tidak sah secara hukum.
Pengelompokan usaha hiburan seperti karaoke, pub, diskotek, dan kelab malam sebagai sumber potensi kerawanan juga patut dikritisi. Perwali tidak menjelaskan apakah seluruh usaha tersebut otomatis dianggap rawan atau hanya berpotensi dalam kondisi tertentu. Tidak ada dasar empiris atau argumentasi rasional yang dituangkan dalam norma. Dalam konteks ini, regulasi berisiko dinilai diskriminatif terhadap sektor usaha tertentu.
Yang paling mengkhawatirkan, perwali ini telah melangkah terlalu jauh dengan mengatur pembatasan hak usaha secara substansial. Penutupan usaha, pelibatan lembaga luar, hingga pengelompokan usaha yang dapat dicabut izinnya seharusnya diatur dalam Peraturan Daerah, bukan peraturan wali kota. Tanpa dasar Perda yang kuat, perwali ini rawan dinilai melampaui kewenangan (ultra vires) dan berpotensi batal demi hukum.
Ketiadaan mekanisme perlindungan hukum bagi pelaku usaha semakin mempertegas lemahnya tata kelola regulasi ini. Tidak ada prosedur banding, tidak ada hak klarifikasi yang dijamin, dan tidak ada kepastian siapa pengambil keputusan final. Dalam negara hukum, kondisi seperti ini jelas bertentangan dengan prinsip fair procedure.
Pada akhirnya, Perwali Nomor 44 Tahun 2021 dan perubahannya menyisakan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Regulasi yang kabur, prosedur yang tidak jelas, dan kewenangan yang melampaui batas justru berpotensi menciptakan konflik hukum baru. Jika tidak segera diperbaiki, perwali ini bukan hanya merugikan pelaku usaha, tetapi juga melemahkan wibawa hukum pemerintah daerah itu sendiri. (*)
*) Eko Hardianto adalah Wakil ketua PWI Probolinggo Raya dan wartawan Ketik.com
**) Isi tulisan di atas menjadi tanggung jawab penulis
***) Karikatur by Rihad Humala/Ketik.com
****) Ketentuan pengiriman naskah opini:
- Naskah dikirim ke alamat email redaksi@ketik.co.id.
- Berikan keterangan OPINI di kolom subjek
- Panjang naskah maksimal 800 kata
- Sertakan identitas diri, foto, dan nomor HP
- Hak muat redaksi. (*)