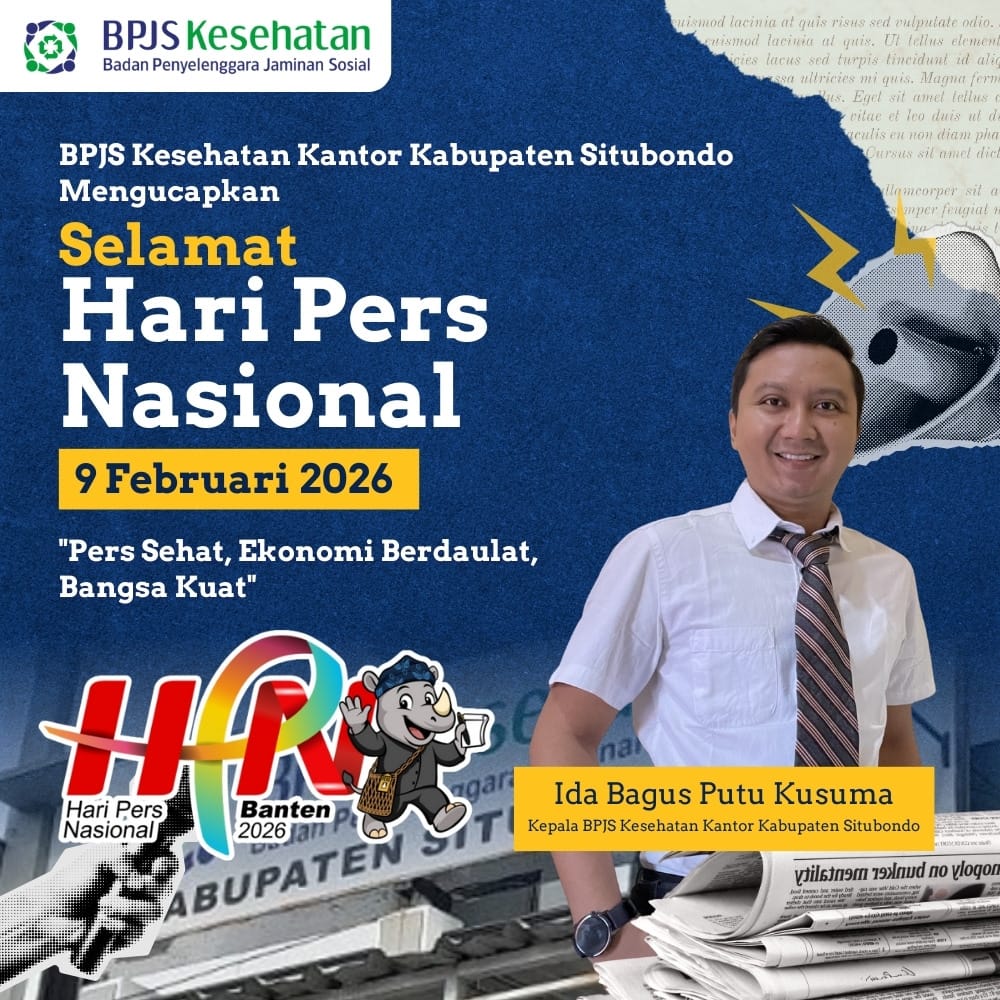Setiap tanggal 9 Februari, kita berkumpul untuk merayakan kedaulatan informasi dan kemerdekaan berpendapat. Namun, di tahun 2026 ini, ada sebuah kenyataan yang bertolak belakang sekaligus menyesakkan dada bagi siapa saja yang masih percaya pada kekuatan pena.
Saat teknologi informasi mencapai titik puncaknya dan akses terhadap data begitu melimpah, kaki-kaki jurnalis justru semakin jarang menginjak bumi secara langsung. Budaya hunting yang selama ini dianggap sebagai kegiatan sakral mencari berita dengan keringat di lapangan kini mulai memudar secara perlahan.
Keberanian menyusuri gang sempit atau ketekunan menunggu narasumber di depan pintu kantor kini telah digantikan oleh kenyamanan di balik meja sembari menunggu notifikasi siaran pers masuk ke dalam grup percakapan digital.
Kalah dari Media Sosial
Kenyataan pahit ini membawa dampak sistemik pada relevansi pers di mata publik. Kita harus mengakui sebuah realitas yang ironis bahwa kabar di media massa kini seringkali keduluan oleh unggahan di media sosial.
Ketika sebuah peristiwa besar terjadi, masyarakat lebih dulu mendapatkan informasi dari saksi mata lewat video pendek atau utas di platform digital sebelum media resmi sempat memverifikasinya. Hal ini adalah tamparan keras bagi industri pers yang seharusnya menjadi garda terdepan informasi.
Namun, bukannya merespons ketertinggalan itu dengan verifikasi lapangan yang mendalam untuk memberikan nilai tambah dan akurasi, banyak media justru sekadar mengambil rilis resmi untuk mengejar ketertinggalan tersebut secara instan.
Fenomena ini menciptakan sebuah lingkaran setan di mana media massa kehilangan fungsinya sebagai penyedia informasi pertama sekaligus kehilangan kedalamannya sebagai pemberi makna atas sebuah peristiwa. Jika media sosial menang di kecepatan karena faktor jurnalisme warga, maka media massa seharusnya mengambil ceruk kebenaran yang lebih utuh.
Namun, yang terjadi justru sebaliknya; banyak ruang redaksi yang memilih jalan pintas dengan mengandalkan narasi satu pihak yang sudah disiapkan oleh humas.
Akibatnya, publik tidak lagi melihat perbedaan signifikan antara membaca berita di portal resmi dengan membaca status di media sosial, kecuali bahwa media sosial seringkali terasa lebih jujur dan apa adanya karena tidak melalui proses penyaringan kepentingan yang terlalu tebal.
Jurnalisme Salin Tempel
Data menunjukkan kecenderungan yang sangat mengkhawatirkan bagi masa depan literasi kita semua. Kini, mayoritas produk jurnalistik yang kita konsumsi setiap hari memiliki struktur, kutipan, bahkan tanda baca yang nyaris seragam antara satu media dengan media lainnya.
Kita sedang menyaksikan lahirnya era jurnalisme salin-tempel yang masif karena banyak redaksi yang terjebak dalam zona nyaman jurnalisme rilis yang serba praktis. Ketika seorang jurnalis hanya duduk manis menunggu kiriman rilis, ia secara sukarela melepaskan fungsinya sebagai penyaring informasi atau gatekeeper.
Peran mulia itu kini bergeser menjadi sekadar penyalur atau megaphone bagi kepentingan pihak tertentu yang memiliki sumber daya untuk mengemas narasi secara rapi dan menguntungkan pihak mereka sendiri.
Kondisi ini membuat kita tidak lagi menguji kebenaran di lapangan secara empiris. Kita hanya memoles bahasa humas agar terlihat layak tayang di mata publik tanpa pernah mempertanyakan apa yang tersembunyi di balik kata-kata indah tersebut.
Dampaknya sangat fatal karena berita kehilangan nyawa dan konteks sosialnya yang asli. Lebih jauh lagi, yang paling berbahaya adalah hilangnya daya kritis dalam ruang redaksi kita.
Jika semua informasi diterima begitu saja dari tangan pertama tanpa ada upaya pembanding atau observasi mandiri, maka pers bukan lagi menjadi pilar keempat demokrasi, melainkan sekadar alat birokrasi informasi.
Media sosial mungkin menang dalam hal kecepatan, namun media massa seharusnya tetap menang dalam hal kebenaran faktual yang digali langsung dari sumbernya, bukan sekadar membebek pada apa yang sudah viral di internet.
Belenggu Kemalasan Intelektual
Kita memang harus jujur bahwa tuntutan kecepatan di era 2026 memang sudah di luar nalar manusiawi. Algoritma mesin pencari menuntut media untuk memproduksi ratusan konten setiap hari demi mengejar trafik dan pendapatan iklan.
Tekanan ekonomi ini memaksa wartawan untuk bekerja bak mesin yang tidak lagi punya waktu melakukan investigasi atau sekadar melakukan doorstop yang berkualitas dengan narasumber kunci.
Namun, jika alasan ekonomi terus dijadikan tameng untuk membenarkan kemalasan intelektual, maka kita sebenarnya sedang menggali lubang kubur bagi profesi ini sendiri.
Jika jurnalisme hanya berisi rilis yang disalin ulang, apa bedanya kita dengan mesin aggregator atau kecerdasan buatan yang bisa bekerja tanpa lelah selama dua puluh empat jam penuh. Padahal, esensi dari jurnalisme adalah mengungkap apa yang ingin disembunyikan oleh pihak lain.
Rilis, bagaimanapun indahnya, tetaplah sebuah alat pencitraan. Ketika kita berhenti memburu fakta dan mulai terbiasa disuapi data, saat itulah kita kehilangan hak untuk menyebut diri sebagai jurnalis. Kita perlu menyadari bahwa kepercayaan publik adalah mata uang utama dalam industri ini.
Sekali kepercayaan itu hilang karena publik merasa jurnalis hanya menjadi antek dari siaran pers, maka tidak akan ada teknologi atau algoritma secanggih apa pun yang bisa mengembalikannya. Kita harus berani memutus rantai kenyamanan ini sebelum profesi ini benar-benar kehilangan identitasnya.
Kembali Menemukan Fakta
Media yang akan bertahan di masa depan bukanlah media yang paling cepat menyalin rilis, melainkan media yang mampu menyajikan fakta yang tidak ditemukan oleh orang lain. Kepercayaan publik yang kian merosot hanya bisa diobati dengan orisinalitas dan keberanian untuk kembali ke jalanan.
Kita perlu mengingatkan kembali kepada generasi jurnalis baru bahwa fakta tersembunyi tidak akan pernah dikirimkan melalui lampiran dokumen PDF di aplikasi pesan.
Tangisan korban ketidakadilan tidak akan pernah bisa dirasakan getarannya hanya melalui layar ponsel, dan skandal kekuasaan tidak akan pernah dituliskan secara sukarela dalam siaran pers resmi pemerintah maupun korporasi.
Keaslian sebuah berita terletak pada pengalaman empiris jurnalisnya saat berhadapan langsung dengan realitas yang ada di masyarakat.
Jangan biarkan sepatu jurnalis tetap bersih dan mengkilap. Biarkan ia aus, kotor, dan berdebu karena mengejar kebenaran. Karena sejatinya, jurnalisme akan mati bukan karena sensor pemerintah atau tekanan ekonomi, melainkan karena rasa malas jurnalisnya sendiri untuk mencari fakta yang melampaui selembar kertas rilis.
Pers Indonesia harus bangun dari tidur nyenyaknya di balik meja redaksi yang dingin dan kembali merasakan panasnya aspal jalanan demi sebuah kebenaran yang utuh dan bermartabat.
Selamat Hari Pers Nasional 2026. Mari kembali berburu, bukan sekadar menunggu.
*) Fajar Rianto merupakan Jurnalis Ketik.com Biro Daerah Istimewa Yogyakarta
**) Isi tulisan di atas menjadi tanggung jawab penulis
***) Ketentuan pengiriman naskah opini:
- Naskah dikirim ke alamat email redaksi@ketik.com
- Berikan keterangan OPINI di kolom subjek
- Panjang naskah maksimal 800 kata
- Sertakan identitas diri, foto, dan nomor HP
- Hak muat redaksi.(*)