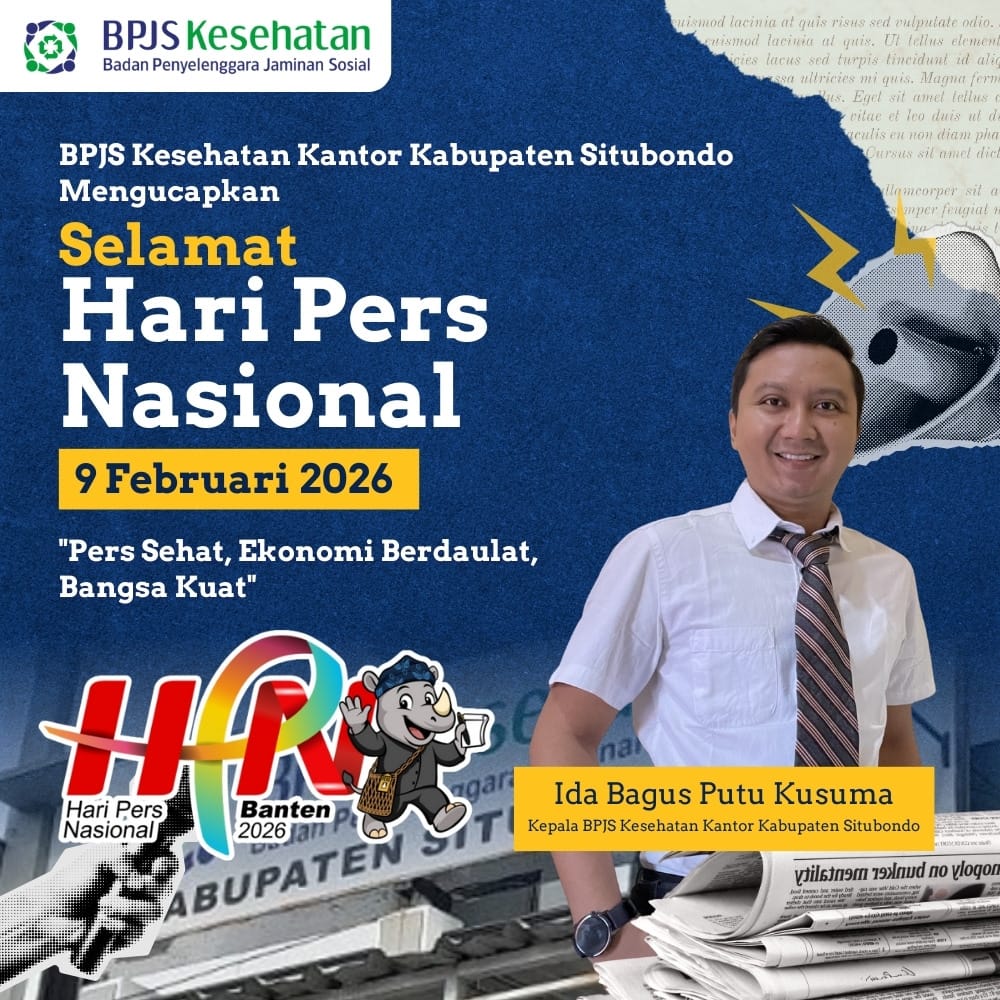KETIK, YOGYAKARTA – Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat sepanjang Januari–Desember 2025 sebanyak 88.519 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan masuk dalam program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Risiko PHK pada 2026 diperkirakan meningkat seiring tertahannya rekrutmen di sejumlah sektor.
Situasi ini semakin mengkhawatirkan karena struktur ketenagakerjaan Indonesia didominasi sektor informal. Badan Pusat Statistik (BPS) 2026 mencatat 57,70 persen atau sekitar 85 juta dari total 147,91 juta pekerja berstatus informal. Dari sisi pelaku usaha, lebih dari 90 persen merupakan UMKM. Ketika lapangan kerja menyempit dan PHK meluas, masyarakat tidak hanya kehilangan pendapatan, tetapi juga menghadapi ancaman kerentanan sosial.
Dosen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan UGM, Dr. Hempri Suyatna, menilai gelombang PHK tidak lepas dari tekanan ekonomi global. Namun, ia menegaskan dampaknya akan jauh lebih serius jika negara gagal mengantisipasi konsekuensi sosialnya.
“PHK bukan hanya perkara kehilangan pekerjaan, tetapi juga hilangnya aksesibilitas masyarakat kepada kebutuhan mendasar, seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan. Apabila dibiarkan secara terus-menerus, maka akan timbul frustasi sosial dan pola-pola negatif di masyarakat,” ujarnya.
Hempri mengkritik arah pembangunan nasional yang dinilai terlalu berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur, tetapi kurang memperhitungkan dampak sosial. Ia menilai model pembangunan tersebut cenderung menguntungkan kelompok elite, sementara masyarakat kecil semakin terpinggirkan akibat alih fungsi lahan produktif dan ekspansi properti.
Di sisi perlindungan sosial, ia melihat negara belum optimal melindungi korban PHK, terutama pekerja informal seperti petani, nelayan, dan pekerja lepas. Skema jaminan ketenagakerjaan masih berbasis logika formalitas kerja sehingga tidak menjangkau mayoritas tenaga kerja yang justru berada di sektor informal. “Ini menunjukkan bahwa kebijakan sosial kita masih eksklusif dan belum menjawab realitas struktur tenaga kerja Indonesia,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan dampak PHK tidak berhenti pada aspek ekonomi. Tekanan sosial dan gangguan kesehatan mental berpotensi meningkat, termasuk risiko kriminalitas dan bunuh diri, jika negara tidak segera menghadirkan solusi konkret. Menurutnya, ini adalah krisis sosial, bukan sekadar persoalan industri.
Hempri mendorong pemerintah melakukan realokasi anggaran secara berpihak. Ia menilai pemerintah perlu meninjau ulang kebijakan dan belanja yang kurang efektif, lalu mengalihkannya untuk perlindungan sosial dan penciptaan lapangan kerja yang lebih adil.
Ia menutup dengan penegasan bahwa PHK tidak boleh dipandang semata sebagai isu efisiensi industri. Dampaknya menyentuh dimensi sosial dan kemanusiaan. Karena itu, pembangunan harus dijalankan dengan pendekatan yang inklusif dan berpihak pada kelompok rentan. (*)