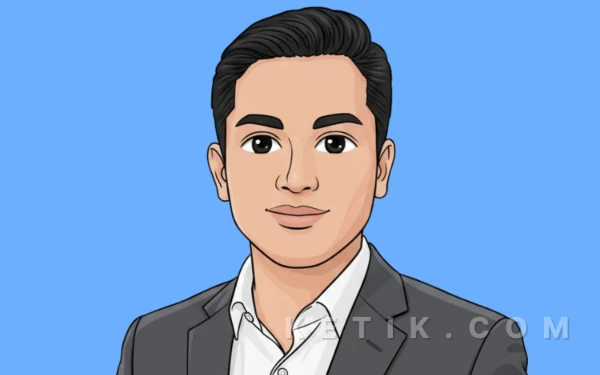Namanya Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Dia pernah membuat Indonesia, berhenti sejenak dari urusan macet, harga beras, dan cicilan. Bukan karena ia menteri keuangan, bukan pula karena ia menemukan ladang minyak baru. Ia hanya menawarkan satu hal yang terdengar sederhana tapi memabukkan. “Uang bisa digandakan. Bukan lewat pabrik, bukan lewat ekspor, melainkan lewat keyakinan”.
Ia berasal dari Probolinggo, membangun padepokan, mengumpulkan pengikut, dan menyusun narasi bahwa kekayaan bukan soal kerja keras. Melainkan soal keyakinan dan kepatuhan. Media menulis kisah hidupnya. Dari figur lokal, naik menjadi fenomena nasional. Lalu jatuh ke pengadilan dengan vonis pidana berat. Tapi sebelum semua itu runtuh, mimpi sudah terlanjur tumbuh di banyak kepala.
Nah kali ini penulis mau mengajak pembaca membayangkan mimpi sederhana itu. Kita bangun pagi tanpa cemas. Dompet tebal. Rekening gemuk. Tidak ada lagi kalimat “nanti dulu” ketika anak minta sepatu baru. Tidak ada lagi wajah masam di tanggal tua. Kita menyulap rumah menjadi lebih besar, motor diganti mobil, makan tanpa hitung harga, dan sesekali berkata, “yang penting keluarga senang.”
Dalam mimpi itu, hidup terasa ringan. Utang lunas. Orang tua kita berangkat umrah. Anak-anak sekolah tanpa khawatir SPP. Kita tersenyum di kasir karena tahu saldo lebih dari cukup. Bahkan sedekah terasa mudah, karena memberi tidak lagi mengurangi rasa aman. Inilah mimpi indah tentang uang banyak. Dan mimpi seperti ini, jujur saja, ada di kepala hampir semua orang.
Sekarang penulis mengajak pembaca berpikir agak serius sedikit. Uang, dalam dunia nyata, jelas tidak bekerja sendirian. Ia butuh barang. Ia butuh jasa. Ia butuh orang yang mau menanam, memproduksi, mengangkut, dan menjual. Jika uang datang tanpa proses itu, maka uang hanya menjadi kertas yang kehilangan arti.
Bayangkan jika klaim penggandaan uang itu benar dan dibuka untuk umum. Hari pertama, orang berbondong-bondong datang. Hari kedua, koper-koper pulang. Hari ketiga, tetangga ikut. Dalam seminggu, satu desa merasa kaya. Dalam sebulan, satu kabupaten merasa mapan.
Tapi lalu apa?
Harga mulai naik. Bukan karena pedagang jahat, tapi karena logika pasar bekerja. Ketika uang banyak mengejar barang yang sama, barang menjadi mahal. Beras naik, minyak goreng naik, harga rumah melonjak. Bahkan parkir motor tadinya cuma 2000, bisa naik jadi 200 ribu. Orang-orang mulai sadar, uang memang bertambah, tapi daya belinya menyusut.
Di titik ini, mimpi mulai retak. Kita punya uang banyak, tapi barang tidak bertambah. Kita kaya di angka, miskin di kenyataan. Uang menjadi cepat habis, bukan karena boros, tapi karena nilainya jatuh. Kita mulai merindukan hari-hari ketika harga masih masuk akal.
Lalu muncul masalah lain. Jika uang bisa didapat tanpa bekerja, siapa yang mau bekerja? Mengapa harus ke sawah jika doa lebih cepat? Mengapa harus buka toko jika ritual lebih menjanjikan? Produksi berhenti. Barang langka. Impor naik. Negara kehilangan pijakan ekonomi.
Bank sentral menjadi penonton. Kebijakan moneter kehilangan makna. Rupiah kehilangan kepercayaan. Investor pergi. Yang tersisa hanya tumpukan uang dan antrian panjang di pasar. Dalam kondisi seperti ini, yang paling cepat jatuh bukan orang kaya, melainkan orang kecil. Mereka yang tidak sempat ikut mimpi, tapi harus hidup di kenyataan.
Inilah ironi besar dari janji uang instan. Memang terdengar menyelamatkan, tapi diam-diam menghancurkan. Menjanjikan keadilan, tapi berujung ketimpangan baru. Ia terlihat religius, tapi berakhir matematis.
Kisah tertulis soal Dimas Kanjeng Taat Pribadi, juga tidak berdiri sendiri. Media mencatat, ada tokoh publik, purnawirawan, dan figur nasional yang pernah datang ke padepokannya. Penting dicatat dengan jujur, datang tidak selalu berarti percaya.
Banyak yang kemudian membantah meyakini klaim penggandaan uang. Ada yang sekadar silaturahmi, ada yang penasaran, ada pula yang datang karena undangan. Namun di era foto dan media sosial, kunjungan sering dibaca sebagai legitimasi. Sekali gambar beredar, klarifikasi menjadi kalah suara.
Bagi sebagian orang, kehadiran tokoh publik cukup untuk menguatkan keyakinan. “Kalau orang besar datang, berarti ini bukan main-main.” Padahal, sejarah berkali-kali membuktikan, orang besar pun bisa salah menilai. Mengapa semua ini bisa terjadi? Karena harapan sering lebih keras suaranya daripada logika.
Karena kemiskinan membuat orang bersedia percaya. Karena kerja keras tidak selalu berbanding lurus dengan hasil. Di titik lelah itulah, janji keajaiban terasa masuk akal.
Kita perlu jujur mengakui, mimpi punya uang banyak itu manusiawi. Tidak ada yang salah ingin hidup layak. Tidak ada yang keliru berharap keluar dari tekanan ekonomi. Yang menjadi masalah adalah ketika mimpi itu dicari lewat jalan yang mematikan nalar.
Ekonomi tidak pernah melarang orang bermimpi. Ia hanya memberi syarat, mimpi harus dibayar dengan produksi, inovasi, dan keadilan distribusi. Tanpa itu, mimpi berubah menjadi bencana.
Dimas Kanjeng kini adalah bagian dari catatan hukum. Namun kisahnya adalah cermin sosial. Ia menunjukkan betapa rapuhnya literasi ekonomi kita. Betapa mudahnya kita tergoda jalan pintas. Betapa seringnya kita ingin hasil tanpa proses. Mungkin yang perlu kita renungkan bukan soal apakah uang bisa digandakan, melainkan mengapa begitu banyak orang ingin mempercayainya.
Jawabannya ada pada mimpi indah yang belum terpenuhi. Tentang hidup tanpa cemas. Tentang masa depan yang terasa aman. Tentang keinginan sederhana untuk tidak terus-menerus kalah oleh keadaan.
Mimpi itu sah. Yang tidak sah adalah menjual mimpi seolah ia kenyataan. Dan jika suatu hari ada lagi yang datang menawarkan jalan serupa, barangkali kita perlu bertanya pelan-pelan, jika uang memang semudah itu, mengapa dunia masih bekerja? Mengapa negara masih repot memungut pajak? Mengapa petani masih menanam padi?
Ekonomi mungkin rumit, tapi ia jujur. Ia tidak bisa disihir. Ia hanya bisa diabaikan untuk sementara, sebelum akhirnya menagih dengan bunga paling mahal: krisis.
Pada akhirnya, mimpi indah tentang uang banyak seharusnya mendorong kita membangun sistem yang adil. Bukan mencari jalan pintas. Karena uang yang lahir dari kerja, meski sedikit, selalu lebih tahan lama daripada uang yang lahir dari ilusi, meski berkarung-karung.
*) Eko Hardianto merupakan jurnalis Ketik.com dan wakil ketua PWI Kota Probolinggo
**) Isi tulisan di atas menjadi tanggung jawab penulis
***) Ketentuan pengiriman naskah opini:
- Naskah dikirim ke alamat email redaksi@ketik.com
- Berikan keterangan OPINI di kolom subjek
- Panjang naskah maksimal 800 kata
- Sertakan identitas diri, foto, dan nomor HP
- Hak muat redaksi. (*)