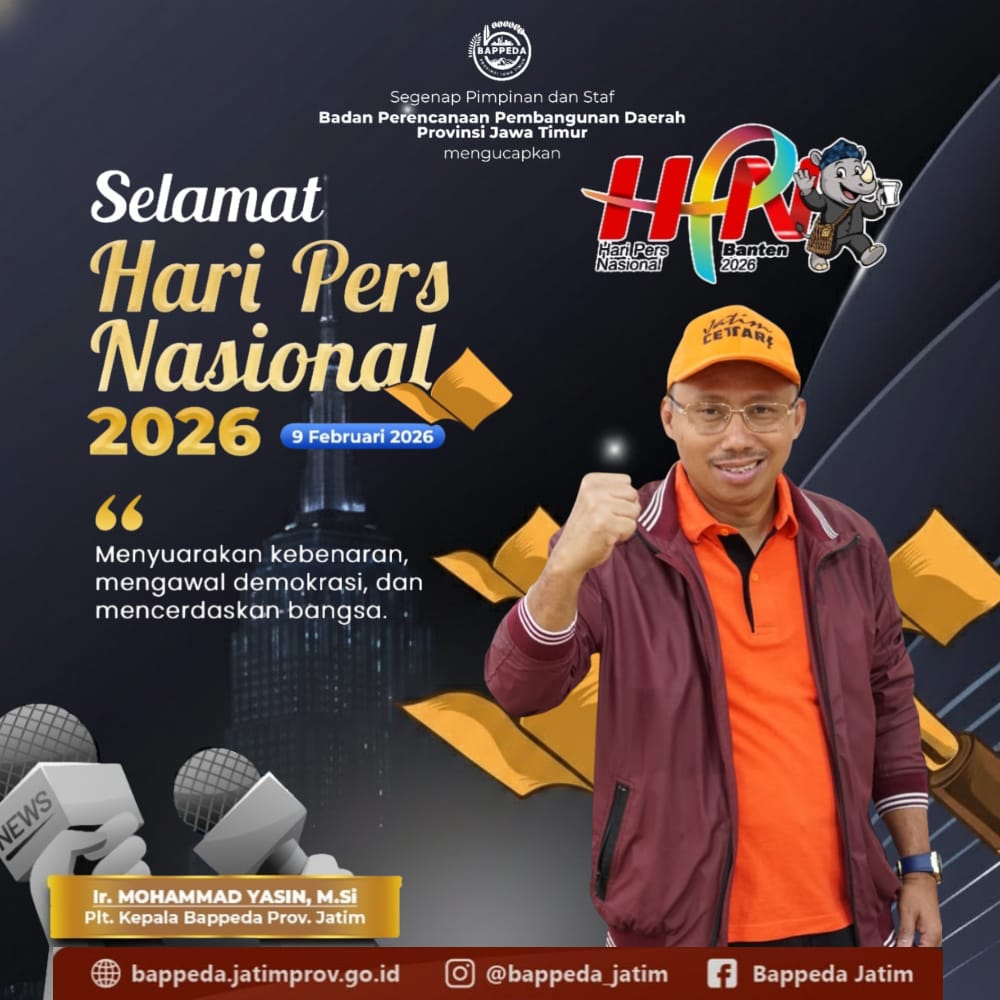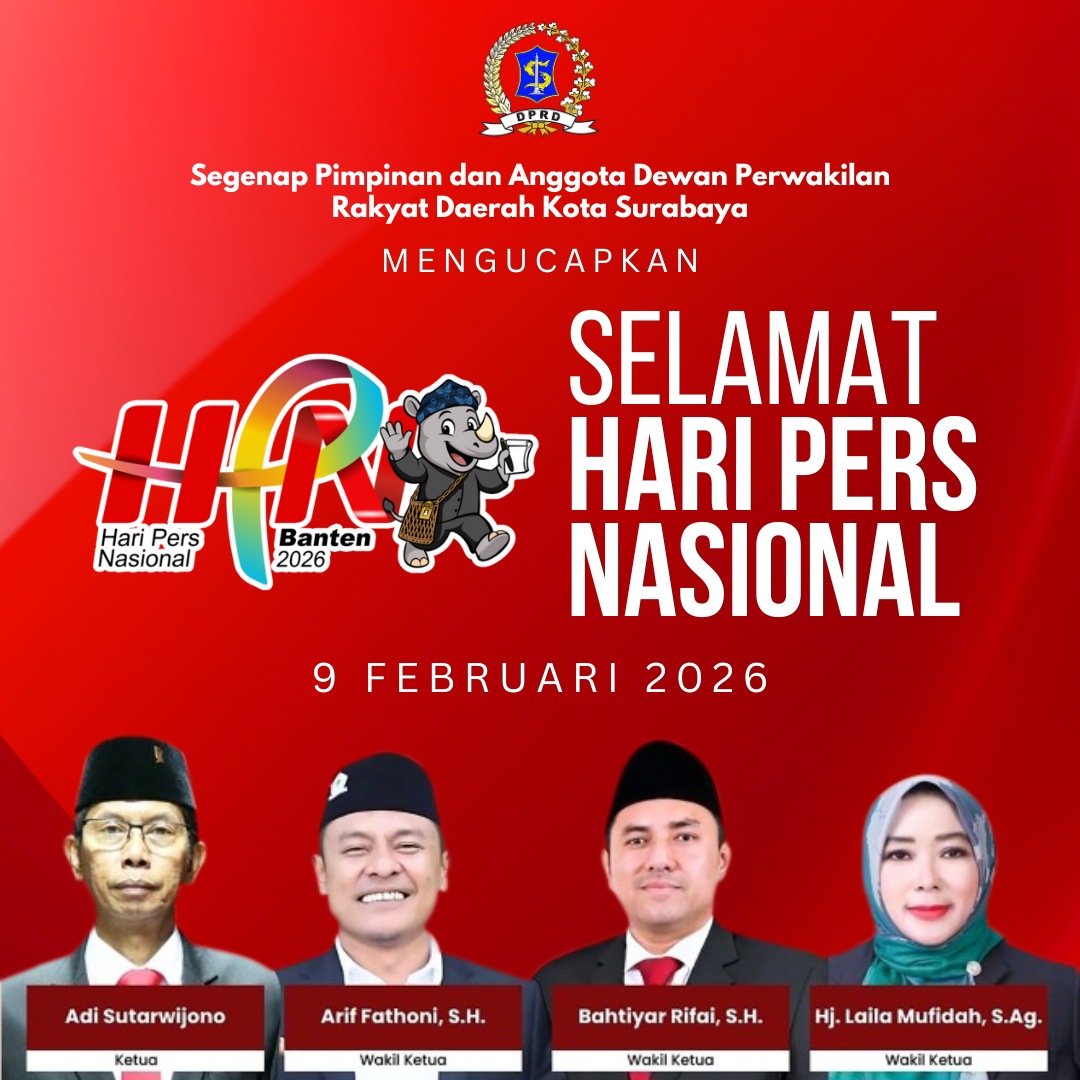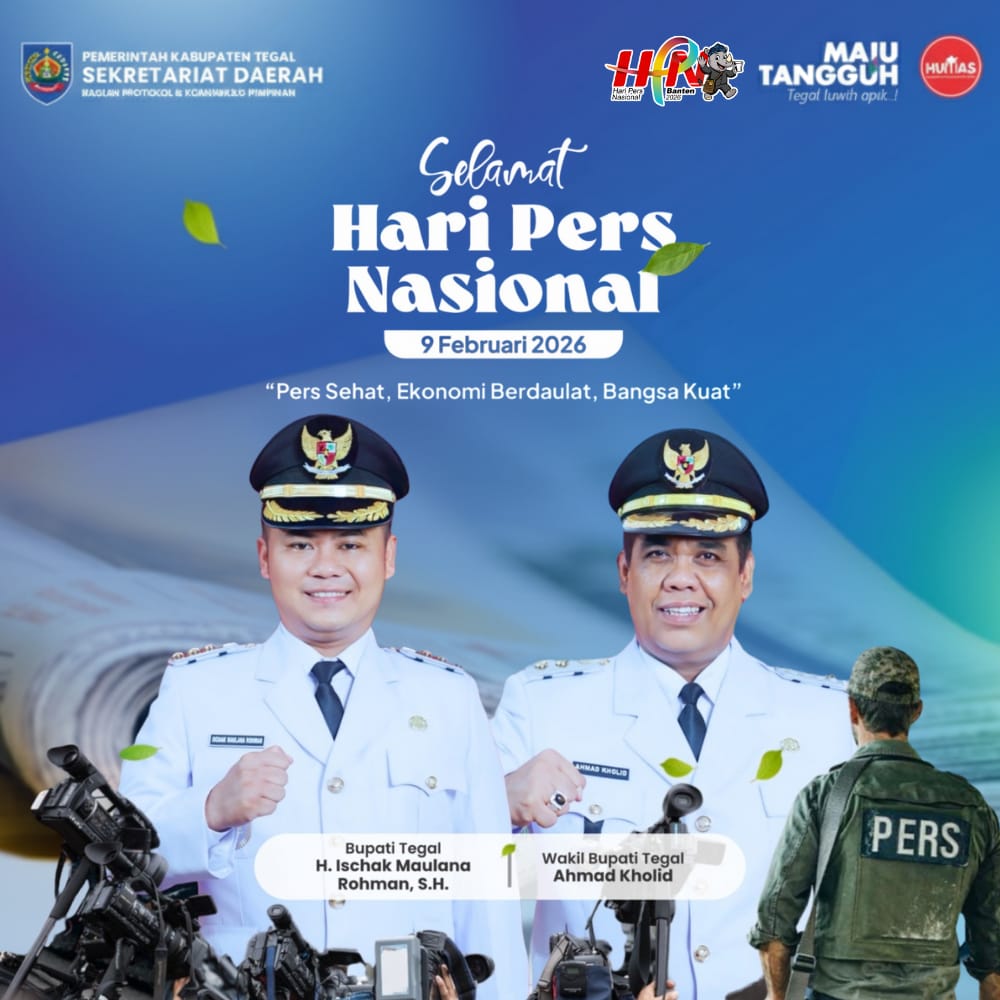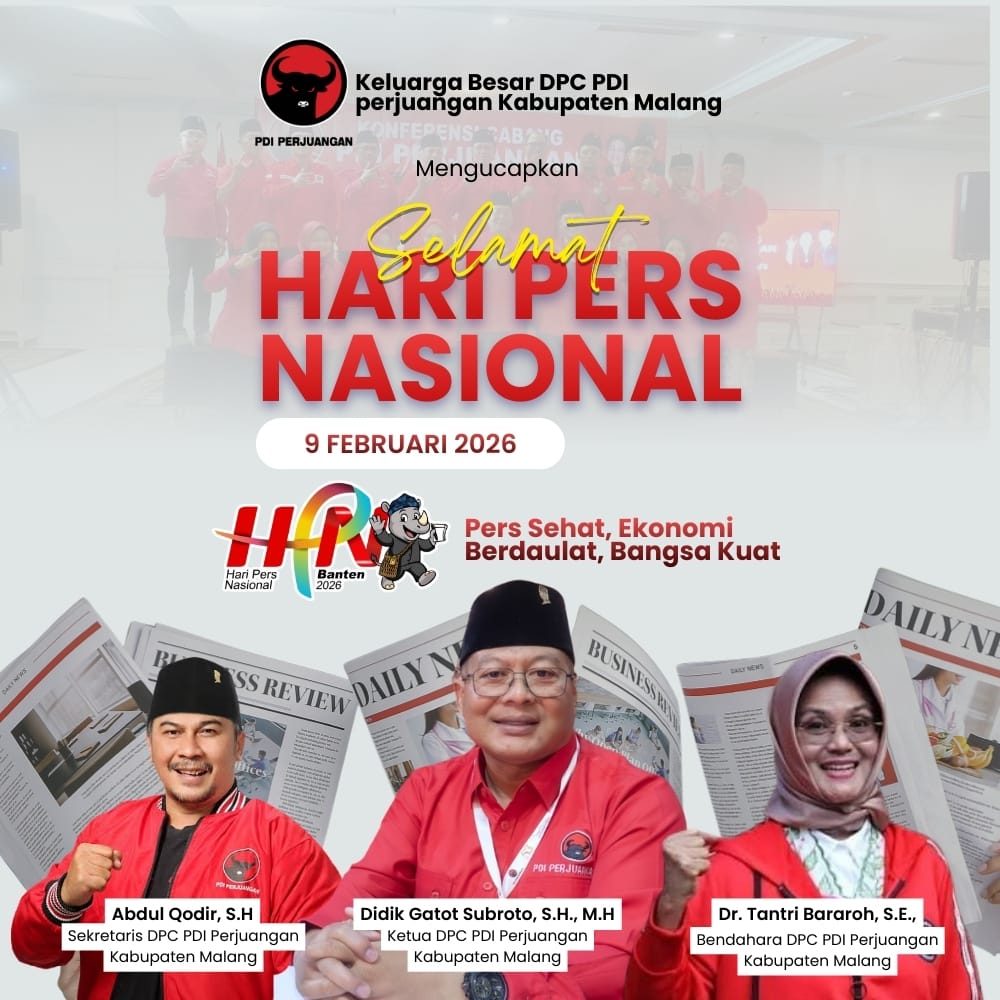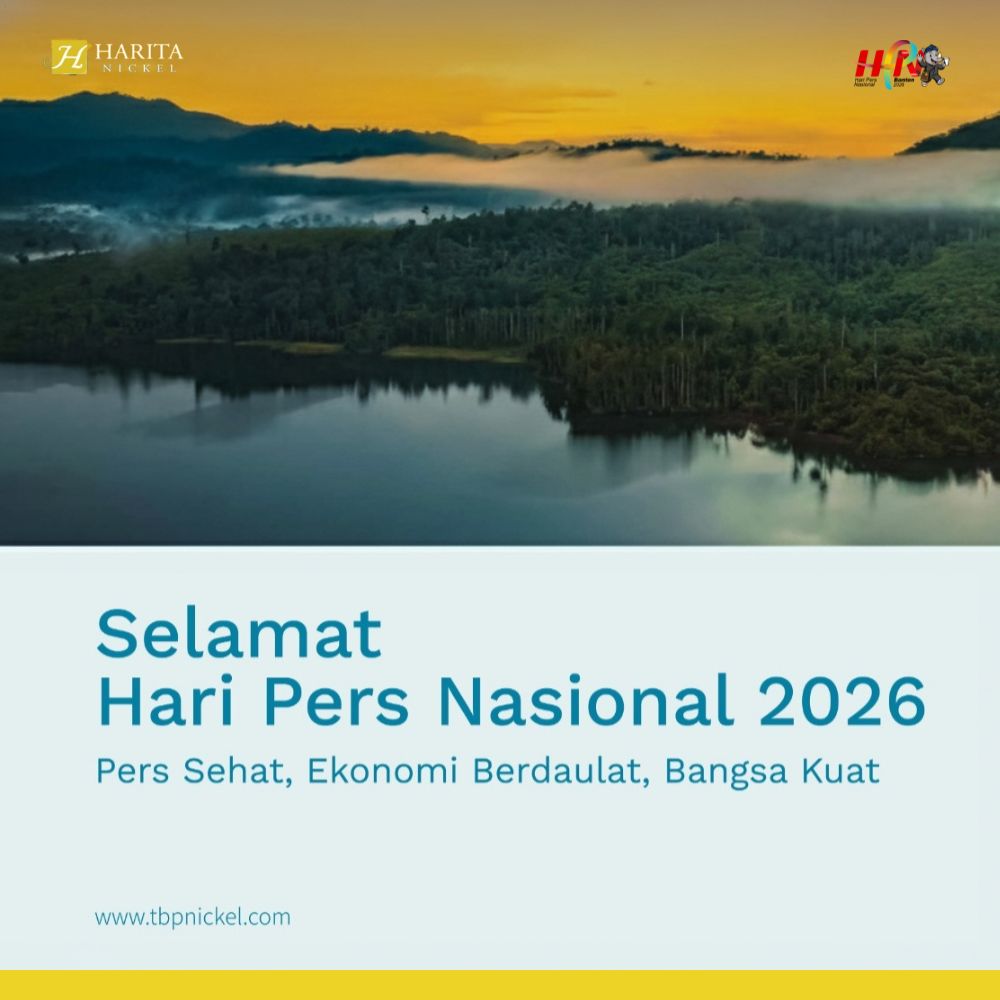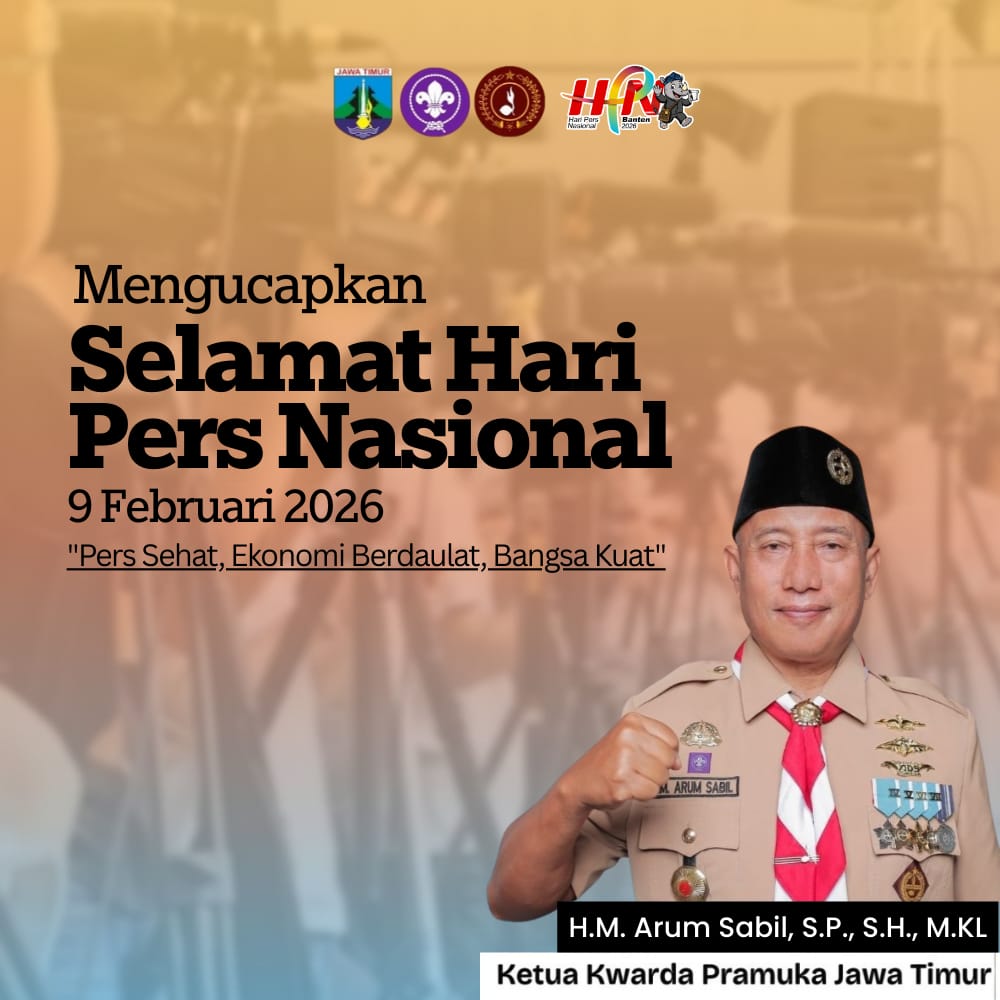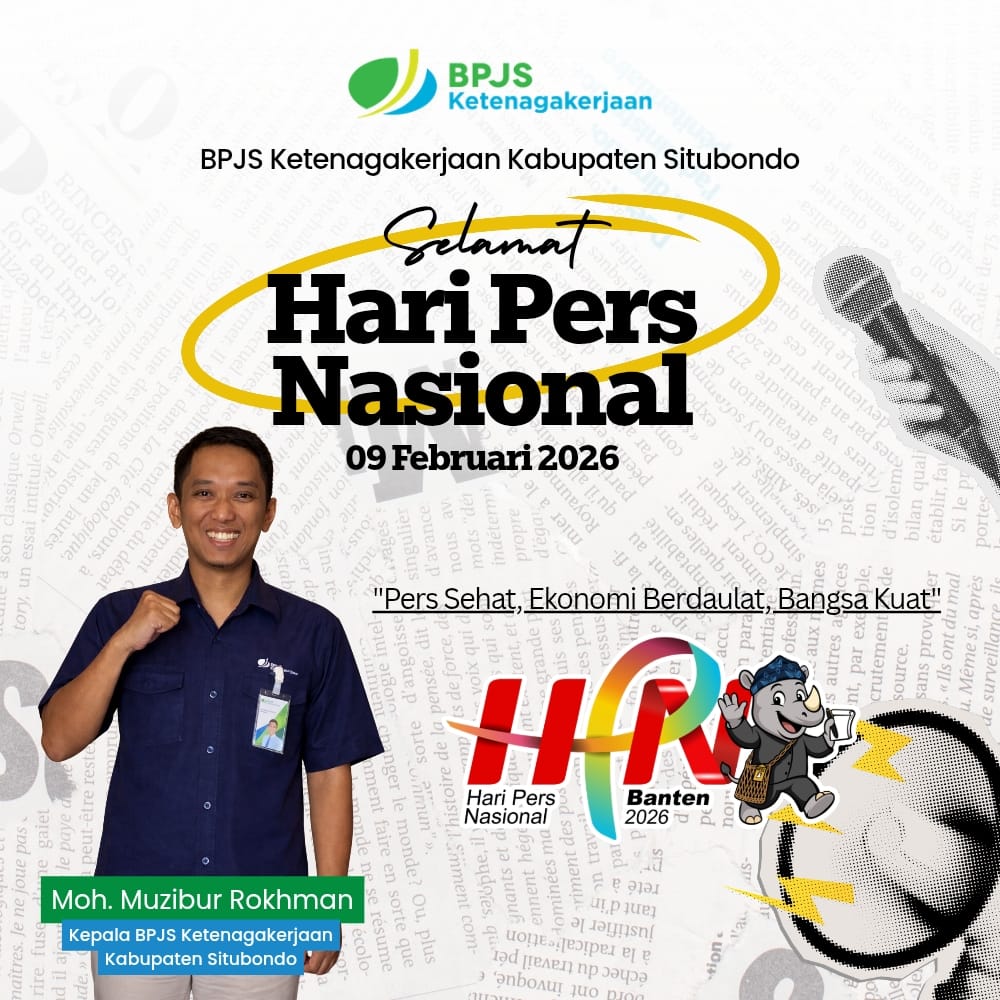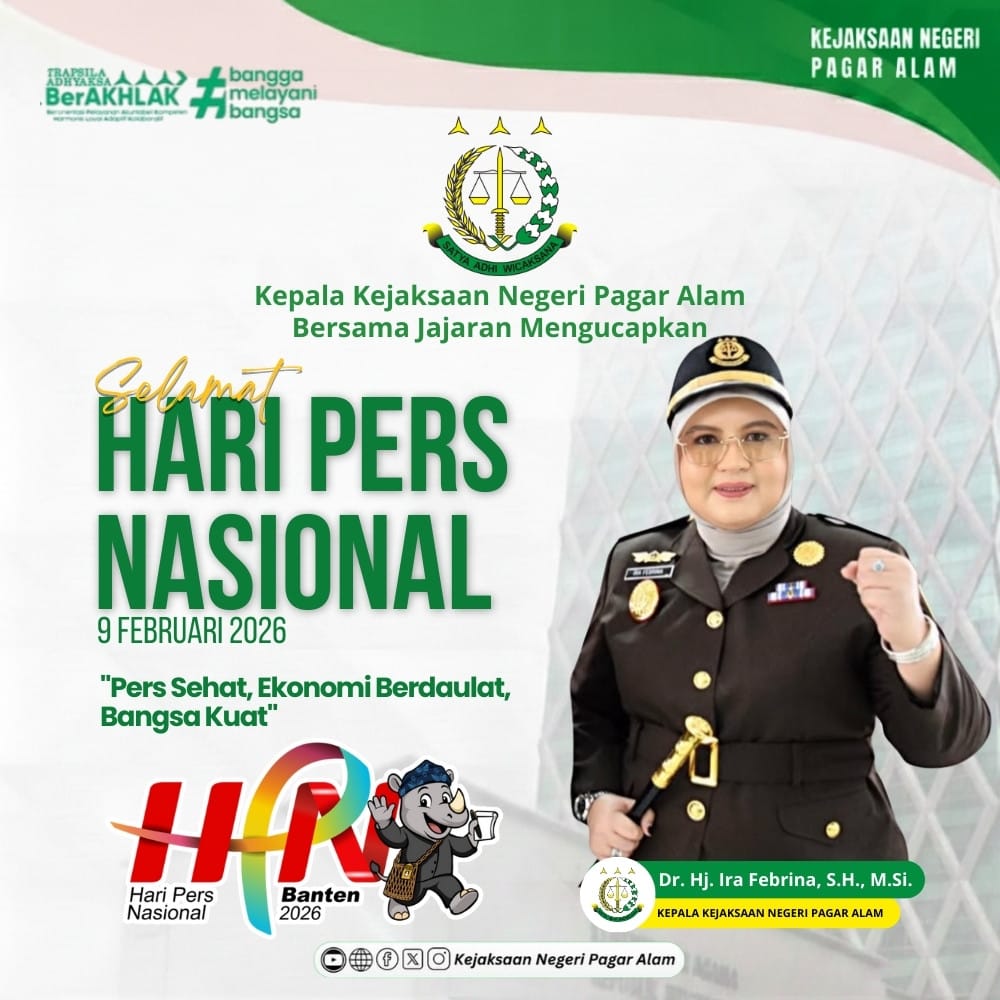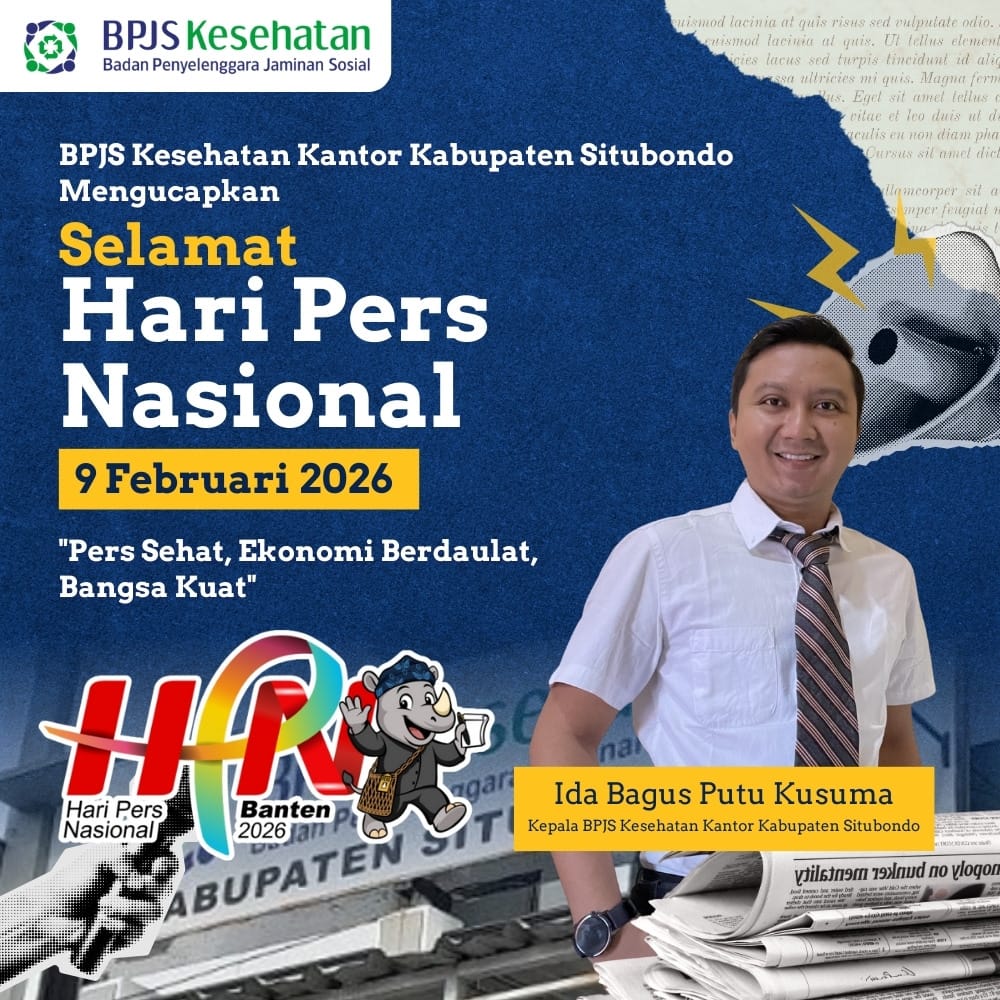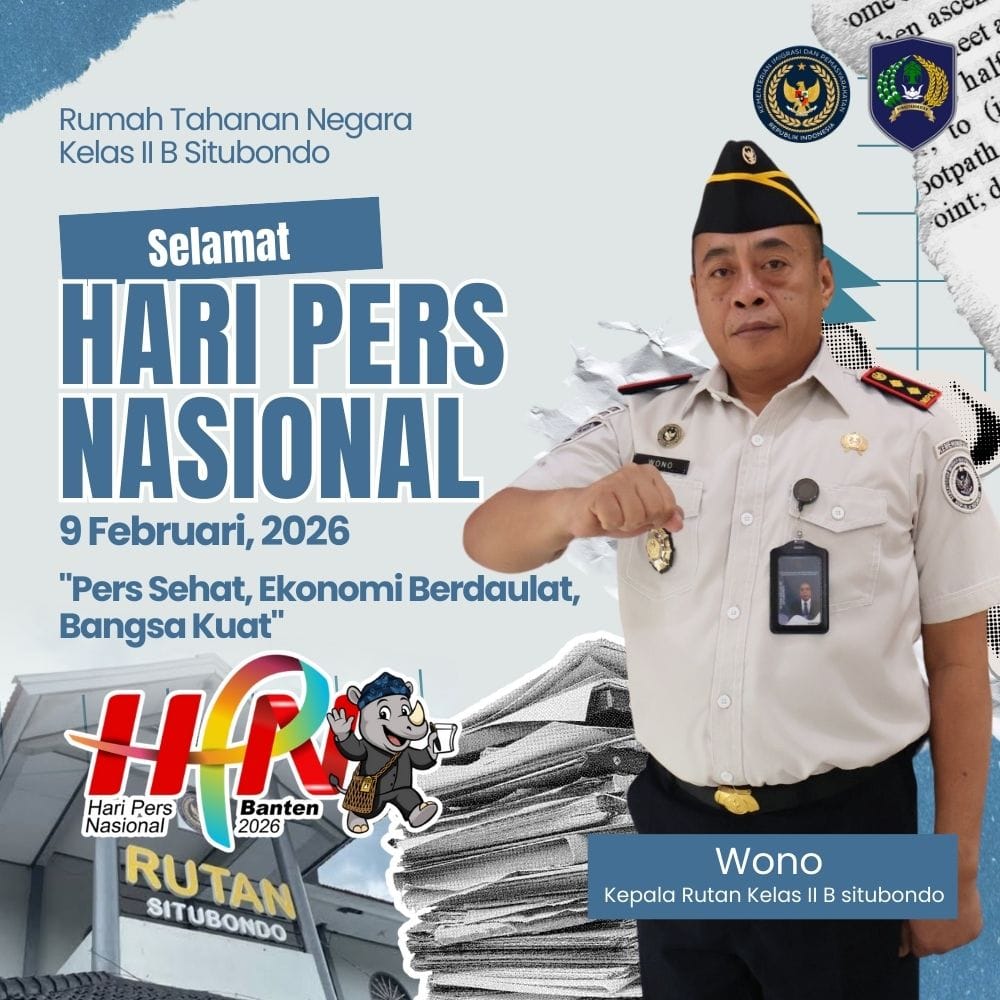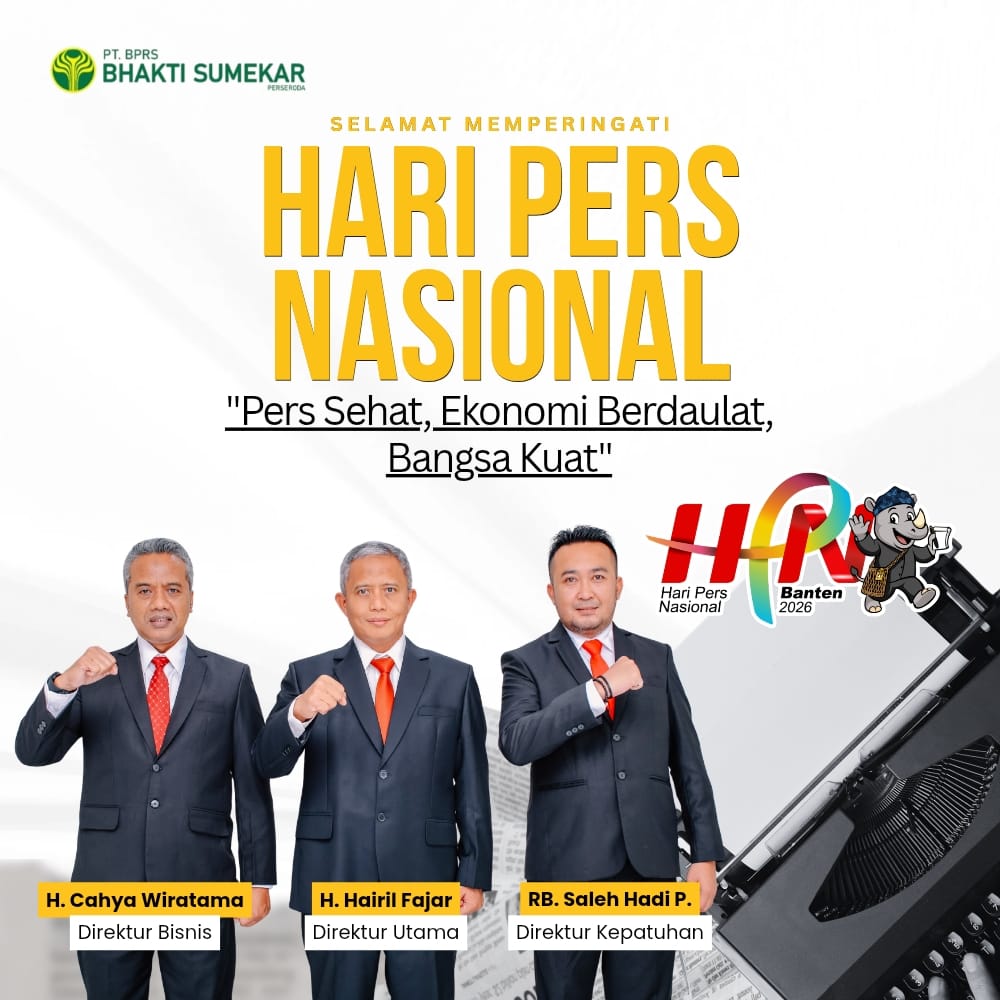Awal September 2025 kembali menorehkan babak baru dalam sejarah panjang demonstrasi di Indonesia. Laporan Tempo.co, 2025 mencatat, “unjuk rasa besar-besaran dimulai pada Senin, 25 Agustus 2025, awalnya memprotes besaran tunjangan anggota DPR…demonstrasi tersebut dengan cepat meluas ke berbagai kota, bertransformasi dari aksi protes damai menjadi kekerasan, perusakan fasilitas umum, hingga penjarahan rumah para anggota DPR”.
Pada 1 september 2025 digelarlah demo secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Dari sinilah muncul gerakan “17+8 Tuntutan Rakyat” yang mencakup pembekuan tunjangan DPR, pembebasan demonstran yang ditahan, hingga desakan pemberantasan korupsi melalui RUU Perampasan Aset. September pun kembali dipenuhi dengan suara rakyat yang menuntut perubahan.
Sejarah memperlihatkan bahwa bulan ini memang bukan bulan yang biasa. September 1965, misalnya, membuka bab gelap yang hingga kini masih menyisakan trauma. John Roosa (2008) dalam Dalih Pembunuhan Massal menulis bahwa “versi resmi Orde Baru tentang 1965 hanyalah dalih untuk pembunuhan massal… propaganda anti-PKI dijadikan alasan untuk melegitimasi penangkapan dan pembantaian besar-besaran”.
Demonstrasi kala itu bukanlah aspirasi rakyat murni, melainkan mobilisasi massa oleh negara. September 1965 menjadi awal hilangnya ruang demonstrasi bebas, ketika suara rakyat dipelintir demi kepentingan politik.
Dua dekade kemudian, pola serupa muncul kembali di Tanjung Priok pada 12 September 1984. Warga yang menolak asas tunggal Pancasila turun ke jalan dengan damai, tetapi negara menjawab dengan peluru. Puluhan hingga ratusan orang tewas, dan peristiwa itu ditutup rapat. Tragedi ini menunjukkan betapa aspirasi rakyat dipandang sebagai ancaman. Demonstrasi damai tidak semestinya dibalas dengan kekerasan, karena hal itu merupakan pengkhianatan terhadap prinsip demokrasi.
Memasuki era Reformasi pun, pola represi belum hilang. Tragedi Semanggi II pada 24 September 1999 menegaskan hal ini. Ribuan mahasiswa menolak RUU Penanggulangan Keadaan Bahaya yang dinilai membuka jalan kembali pada otoritarianisme. Namun, aparat justru menembaki massa, menewaskan mahasiswa dan masyarakat sipil. Peristiwa ini memperlihatkan bahwa demokrasi pasca-1998 bukan hadiah yang jatuh dari langit, melainkan perjuangan yang harus terus dijaga.
September 2004 mencatat tragedi lain dengan wajah berbeda. Munir Said Thalib, aktivis HAM yang dikenal vokal, diracun arsenik dalam penerbangan menuju Amsterdam. Artikel biografi menyebut, “Munir ialah sosok atau tokoh pemberani yang tidak kenal lelah dalam perjuangan membela kaum tertindas… pada 7 September 2004 ia dibunuh dengan racun arsenik di pesawat Garuda” (Wardani, 2020).
Kematian Munir memicu demonstrasi moral di berbagai kota. Hingga kini aktor intelektual di balik pembunuhan itu tidak pernah benar-benar terungkap. Tragedi Munir adalah cermin kegagalan negara melindungi warganya, sekaligus pengingat bahwa impunitas melemahkan fondasi keadilan.
Tragedi September tidak hanya lahir di kota-kota besar, tetapi juga di desa. Pada 2015, Salim Kancil, seorang petani di Lumajang, dibunuh karena menolak tambang pasir ilegal. Analisis konflik menulis, “Negara sendiri merupakan pihak yang sering disebutkan dalam hal kekerasan… kasus meninggalnya Salim Kancil meninggalkan berbagai pertanyaan terkait kompleksnya dunia pertambangan pasir di Kabupaten Lumajang” (Analisis Konflik Pertambangan Pasir, 2016).
Demonstrasi warga desa yang dipimpin Salim berakhir dengan penyiksaan dan pembunuhan brutal. Kasus ini memperlihatkan bahwa perjuangan rakyat di tingkat lokal pun rentan berhadapan dengan kekuatan yang lebih besar.
Gelombang September kembali membesar pada 2019 melalui gerakan Reformasi Dikorupsi. Ribuan mahasiswa turun ke jalan menolak revisi UU KPK dan RKUHP. Dalam buku Reformasi dikorupsi, demokrasi direpresi yang diterbikan LBH Jakarta menegaskan, “Setelah 21 tahun reformasi, demokrasi kita mengalami kemunduran signifikan… semangat yang tertuang dalam tuntutan reformasi pelan tapi pasti dikorupsi. Ruang publik yang semakin hari semakin menyempit menandai mandeknya konsolidasi demokrasi Indonesia” (LBH Jakarta, 2019).
Media Tirto.id juga memperlihatkan keberpihakannya, “Tirto menunjukkan keberpihakannya pada demonstrasi #ReformasiDikorupsi… pemerintah lalai sehingga dilawan oleh mahasiswa yang diposisikan sebagai representasi rakyat” (Muchammad Abdul Ghofur et al., 2021). Gerakan ini menunjukkan bahwa generasi milenial mewarisi semangat kritis, dengan cara baru: poster kreatif, kampanye digital, dan solidaritas nasional.
Akhirnya, tiba di September 2025, lahir wacana besar bernama Reset Indonesia. Selain memprotes tunjangan DPR, publik menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset. Kajian akademik menulis, “Aksi Demo 2025 yang menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset mencerminkan adanya kesadaran kolektif masyarakat terhadap urgensi penguatan regulasi dalam memberantas fraud keuangan negara” (Wahyudin et al., 2025).
Ini bukan sekadar penolakan, tetapi tawaran solusi konkret: memperkuat hukum agar korupsi tidak lagi merusak bangsa. September 2025 berpotensi menjadi titik balik, dari bulan yang identik dengan duka menjadi bulan harapan.
Jika ditarik benang merah, September dari 1965 hingga 2025 menunjukkan pola yang sama: rakyat berusaha menyuarakan aspirasi, sementara negara kerap merespons dengan represi atau abai. Namun, ada transformasi penting. Jika September 1965–2015 lebih banyak diingat dengan tragedi, maka September 2019 dan 2025 menghadirkan warna baru: rakyat, khususnya generasi muda, tidak hanya melawan, tetapi juga menawarkan agenda perubahan.
Dalam buku Reformasi dikorupsi, demokrasi direpresi yang diterbikan oleh LBH Jakarta memperingatkan, “ancaman terhadap matinya demokrasi sudah di depan mata. Pilihannya dua, kita diam pasrah atau bergerak melawan”.
September dengan demikian menjadi arena tarik-menarik antara rakyat dan negara. Sejarah panjang ini menegaskan bahwa suara rakyat tidak bisa dibungkam selamanya. Harapan ke depan, September tak lagi diingat sebagai bulan tragedi, melainkan bulan keberanian kolektif menuju Indonesia yang lebih adil, transparan, dan demokratis.
*) Agus Mahfudin Setiawan merupakan Pegiat Sejarah dan Kebudayaan Islam sekaligus Dosen Sejarah Peradaban Islam UIN Raden Intan Lampung
**) Isi tulisan di atas menjadi tanggung jawab penulis
***) Karikatur by Rihad Humala/Ketik.co.id
****) Ketentuan pengiriman naskah opini:
- Naskah dikirim ke alamat email redaksi@ketik.co.id.
- Berikan keterangan OPINI di kolom subjek
- Panjang naskah maksimal 800 kata
- Sertakan identitas diri, foto, dan nomor HP
- Hak muat redaksi.(*)