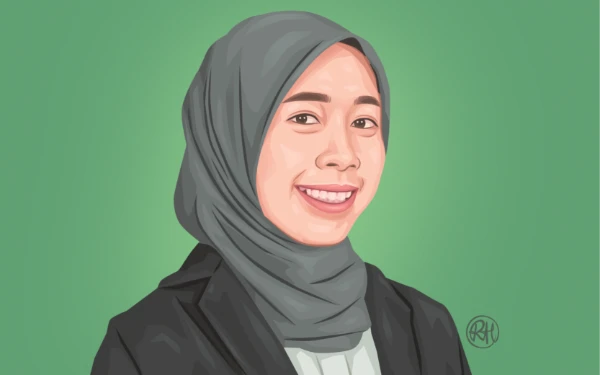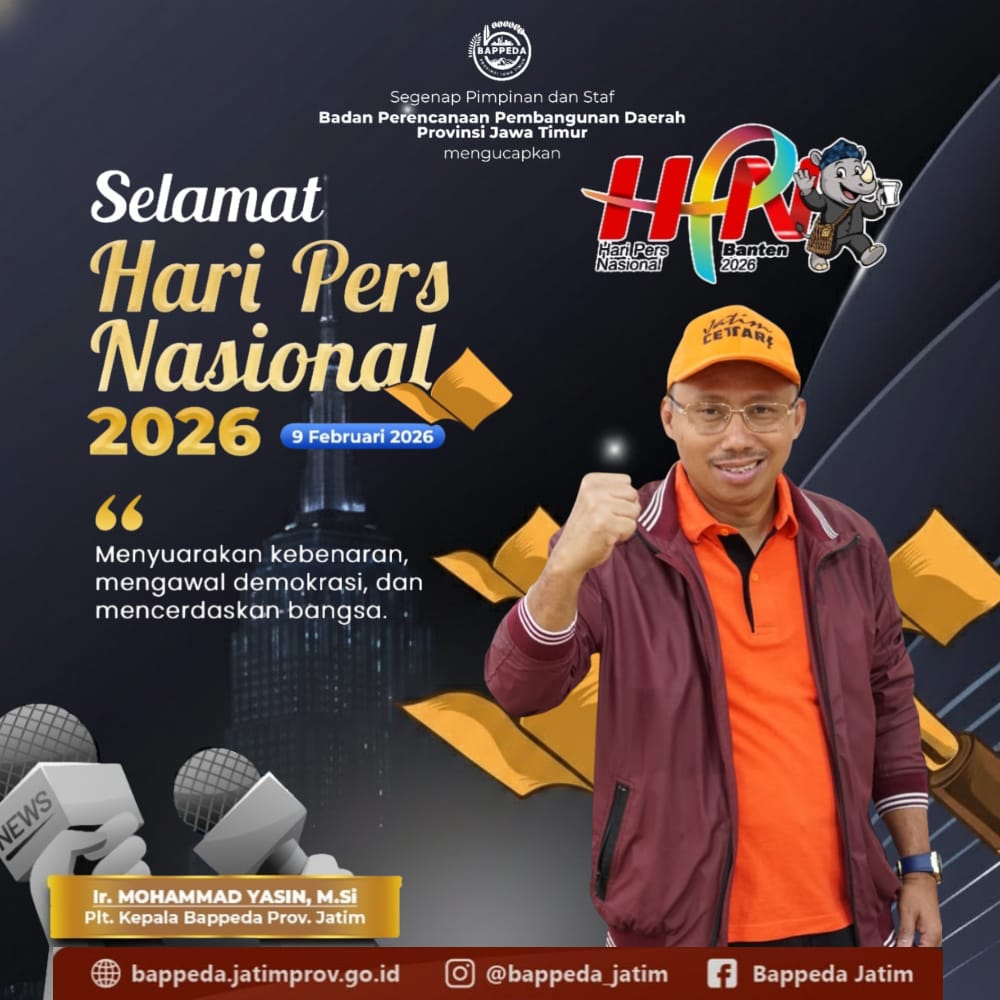Fenomena flexing atau pamer kekayaan di media sosial kini menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya digital. Mulai dari menampilkan barang bermerek, gaya hidup mewah, hingga pencapaian pribadi yang berlebihan, flexing menjadi “strategi” untuk menarik perhatian dan validasi sosial.
Namun, di balik layar gemerlapnya, muncul pertanyaan penting: apakah flexing adalah bentuk komunikasi strategis untuk membangun citra, atau justru cerminan krisis identitas digital yang semakin mengkhawatirkan?
Fenomena Flexing dalam Konteks Komunikasi Digital
Dalam perspektif ilmu komunikasi, flexing dapat dipahami sebagai bentuk komunikasi simbolik. Melalui unggahan dan narasi visual, individu menyampaikan pesan tentang siapa dirinya, apa yang dimilikinya, dan bagaimana ia ingin dipersepsikan oleh khalayak.
Dalam era media sosial, representasi diri (self presentation) menjadi penting karena citra digital sering kali lebih menentukan reputasi dibandingkan realitas sehari-hari.
Namun self presentation yang berlebihan dapat bergeser menjadi self promotion yang tak sehat. Fenomena ini dipicu oleh budaya algoritma media sosial yang memberi penghargaan pada popularitas, jumlah likes, dan interaksi, bukan pada substansi komunikasi.
Akibatnya, ruang digital dipenuhi pesan-pesan pamer yang membentuk norma sosial baru: bahwa nilai seseorang ditentukan oleh kemewahan yang ditampilkan, bukan oleh kontribusi atau karakter.
Krisis Nilai dan Identitas Sosial
Dari perspektif komunikasi sosial, flexing menimbulkan dampak terhadap nilai-nilai kemasyarakatan. Budaya pamer memunculkan kesenjangan simbolik antara “yang punya” dan “yang tidak punya”.
Hal ini dapat memicu rasa iri, rendah diri, hingga perilaku konsumtif demi meniru gaya hidup yang ditampilkan di media. Dalam konteks ini, flexing tidak lagi menjadi komunikasi positif, tetapi memunculkan disonansi sosial dan psikologis.
Lebih jauh, fenomena flexing juga mencerminkan krisis identitas digital. Banyak pengguna media sosial membangun persona yang berbeda jauh dari realitas hidupnya.
Identitas digital menjadi “topeng sosial” yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan akan pengakuan. Ketika pengakuan itu tak datang, muncul tekanan emosional, rasa tidak cukup, dan hilangnya makna autentik dalam berkomunikasi.
Peran Literasi Komunikasi Digital
Untuk memahami dan meredam dampak negatif flexing, literasi komunikasi digital menjadi kunci. Pengguna media sosial perlu diajak memahami bahwa setiap unggahan adalah pesan yang memiliki makna sosial.
Literasi komunikasi tidak hanya tentang cara menggunakan media, tetapi juga tentang memahami konsekuensi etis dan psikologis dari pesan yang disampaikan.
Institusi pendidikan, komunitas digital, dan para influencer memiliki peran penting dalam membangun budaya komunikasi yang lebih empatik dan reflektif. Alih-alih menormalisasi budaya pamer, ruang digital seharusnya menjadi tempat berbagi inspirasi, kolaborasi, dan nilai-nilai kemanusiaan.
Penutup
Fenomena flexing adalah cermin perubahan pola komunikasi di era digital. Ia bisa menjadi strategi untuk membangun citra, tetapi juga bisa menjadi gejala krisis identitas sosial jika dilakukan tanpa kesadaran etis.
Dalam dunia yang semakin terkoneksi, komunikasi bukan lagi sekadar tentang apa yang ditampilkan, melainkan tentang makna yang ingin dibangun. Karena pada akhirnya, kredibilitas dan empati jauh lebih bernilai daripada sekadar tampilan mewah di dunia maya.
*) Silvi Aris Arlinda, S.I.Kom., M.I.Kom merupakan Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Slamet Riyadi
**) Isi tulisan di atas menjadi tanggung jawab penulis
***) Ketentuan pengiriman naskah opini:
- Naskah dikirim ke alamat email redaksi@ketik.com
- Berikan keterangan OPINI di kolom subjek
- Panjang naskah maksimal 800 kata
- Sertakan identitas diri, foto, dan nomor HP
- Hak muat redaksi.(*)