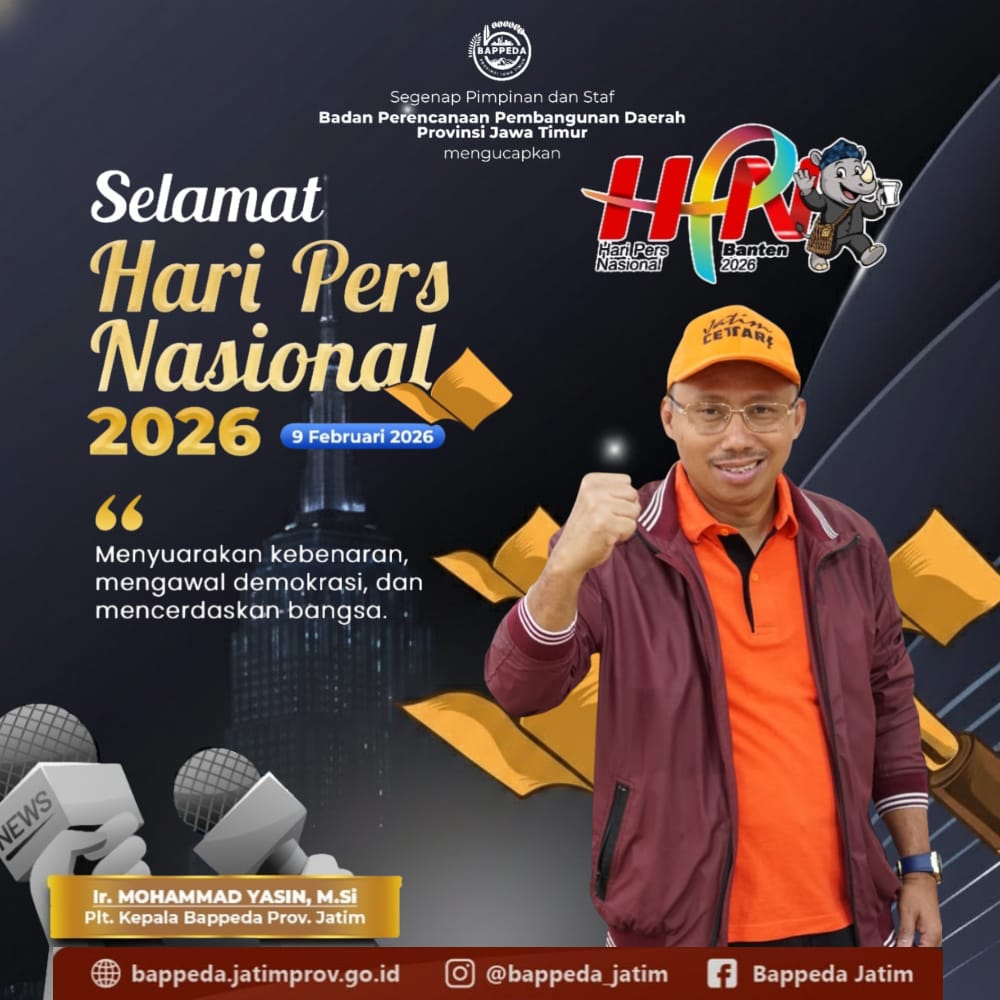Fenomena sound horeg atau pertunjukan musik keliling dengan sound system berdaya tinggi kini menjadi sorotan tajam, khususnya di wilayah Jawa Timur. Sorotan ini bukan hanya muncul karena tingkat kebisingannya yang melampaui batas wajar, tetapi juga karena hiburan tersebut kerap disertai tontonan yang dinilai tidak senonoh: joget-joget liar, musik remix keras, bahkan dalam beberapa kasus disertai konsumsi alkohol secara terbuka di ruang publik.
Respons atas keresahan itu datang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur melalui Fatwa Nomor 1 Tahun 2025, yang menetapkan bahwa penggunaan sound horeg dengan intensitas suara berlebih dan mengandung unsur kemungkaran hukumnya haram. Fatwa ini menjadi cerminan bahwa ulama tidak tinggal diam terhadap fenomena budaya populer yang dinilai merusak tatanan sosial dan moral masyarakat (MUI Jatim, 2025).
Namun, di balik substansi fatwa yang kuat secara normatif, muncul pertanyaan reflektif: apakah cukup mengandalkan label “haram” untuk menyelesaikan persoalan budaya populer yang tumbuh dari akar sosial dan ekonomi masyarakat?
Di banyak tempat di Indonesia, kita dapat menemukan bentuk hiburan serupa: parade musik keliling, pesta jalanan, dan pertunjukan dadakan yang menggunakan perangkat suara berkekuatan tinggi. Dalam konteks sosial, hiburan semacam ini sering muncul dari komunitas masyarakat desa, pemuda kampung, atau pelaku jasa penyewaan alat musik. Mereka tidak selalu memiliki akses ke panggung-panggung formal, namun tetap memiliki hasrat untuk tampil dan berekspresi.
Persoalan muncul ketika ekspresi tersebut berubah menjadi gangguan sosial. Banyak warga mengeluhkan suara keras yang mengganggu waktu istirahat, kaca rumah yang pecah akibat getaran, hingga munculnya perilaku menyimpang yang menyalahi norma agama dan budaya setempat. Dalam forum Bahtsul Masail di Pasuruan, tiga alasan utama dikemukakan sebagai dasar keharaman sound horeg: merugikan dan menyakiti orang lain, mengandung kemungkaran, serta merusak moral generasi muda (Kiai Muhib dalam mui.or.id).
Dalam perspektif Islam, prinsip la dharar wa la dhirar tidak boleh membahayakan dan tidak boleh saling membahayakan, menjadi dasar penting dalam menentukan batas antara kebebasan dan tanggung jawab. Maka sangat masuk akal bila MUI mengeluarkan fatwa haram sebagai alarm moral umat Islam.
Namun perlu dicatat bahwa fatwa tidak bersifat mengikat secara hukum negara. Ia berfungsi sebagai rambu-rambu etis dan spiritual yang menjadi pedoman bagi umat. Seperti ditegaskan oleh Sekretaris Komisi Fatwa MUI Pusat, KH Miftahul Huda, bahwa fatwa saja tidak cukup. Ia mengatakan, fenomena seperti sound horeg perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah dan aparat penegak hukum, karena sudah menyentuh aspek ketertiban umum (mui.or.id).
Dalam konteks ini, saya berpandangan bahwa pendekatan terbaik adalah jalan tengah: mendukung substansi fatwa MUI karena memuat kepedulian moral yang kuat, namun pada saat yang sama mengusulkan langkah-langkah lanjutan berupa pendekatan edukatif, dialogis, dan kolaboratif. Kita tidak bisa hanya melarang. Kita juga harus membimbing, menjelaskan, dan menawarkan alternatif yang lebih membangun.
Setidaknya ada tiga langkah yang bisa dilakukan secara bersamaan. Pertama, edukasi publik. Masyarakat perlu memahami bahwa sound horeg bukan hanya soal selera musik atau kesenangan sesaat, tetapi menyangkut hak orang lain atas ketenangan, keselamatan anak-anak, dan kesehatan lingkungan. Edukasi ini bisa dilakukan lewat media sosial, khutbah Jumat, forum pemuda, hingga kampanye digital kreatif yang melibatkan tokoh lokal dan kreator konten.
Kedua, regulasi pemerintah daerah. Pemerintah dapat menetapkan batasan teknis yang jelas seperti waktu operasional, ambang batas desibel suara, serta persyaratan izin keramaian. Aturan ini akan menjadi pelengkap dari fatwa, karena memiliki kekuatan hukum untuk mencegah pelanggaran.
Ketiga, penyediaan ruang ekspresi alternatif. Generasi muda perlu difasilitasi untuk tetap bisa menyalurkan kreativitas mereka dalam bentuk yang lebih aman, positif, dan mendidik. Festival budaya lokal, panggung seni desa, atau kegiatan kreatif komunitas bisa menjadi sarana ekspresi yang tidak merusak tatanan sosial.
Fatwa tentang sound horeg hanyalah satu dari sekian banyak kiprah MUI dalam membimbing umat. Sejak didirikan pada tahun 1975, MUI telah menjadi mitra strategis umat Islam dan pemerintah dalam isu-isu penting seperti ekonomi syariah, vaksin halal, bahkan etika penggunaan media sosial (Maimunah, 2020).
Namun agar terus relevan di tengah perubahan sosial yang cepat, MUI perlu memperkuat peran sosial-kulturalnya. Tidak cukup hanya sebagai lembaga fatwa, MUI harus hadir lebih dekat dengan realitas masyarakat, menjalin dialog lintas kelompok, melibatkan generasi muda, dan memanfaatkan teknologi digital untuk dakwah yang menyentuh kehidupan sehari-hari.
Kita hidup di era yang sangat bising, baik secara harfiah maupun simbolik. Di tengah hiruk-pikuk budaya populer yang sering kali kehilangan arah, suara ulama tetap dibutuhkan. Bukan untuk membentak atau menghakimi, tetapi untuk membimbing dan memberi arah yang lebih baik.
Fatwa tentang sound horeg adalah panggilan bagi kita semua ulama, pemerintah, pemuda, dan masyarakat luas untuk bersama-sama menciptakan ruang sosial yang sehat, damai, dan bermartabat. Suara yang keras belum tentu benar. Tetapi suara yang jernih, bijak, dan solutif, itulah yang seharusnya kita jaga agar tetap bergema dalam kehidupan kita bersama.
*) Agus Mahfudin Setiawan merupakan Pegiat Sejarah dan Kebudayaan Islam, Dosen Sejarah Peradaban Islam UIN Raden Intan Lampung
**) Isi tulisan di atas menjadi tanggung jawab penulis
***) Karikatur by Rihad Humala/Ketik.co.id
****) Ketentuan pengiriman naskah opini:
- Naskah dikirim ke alamat email redaksi@ketik.co.id.
- Berikan keterangan OPINI di kolom subjek
- Panjang naskah maksimal 800 kata
- Sertakan identitas diri, foto, dan nomor HP
- Hak muat redaksi.(*)