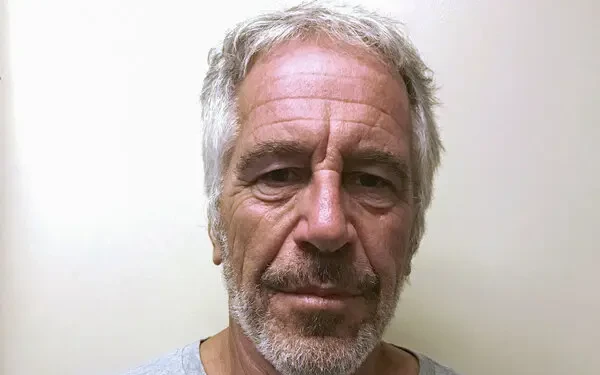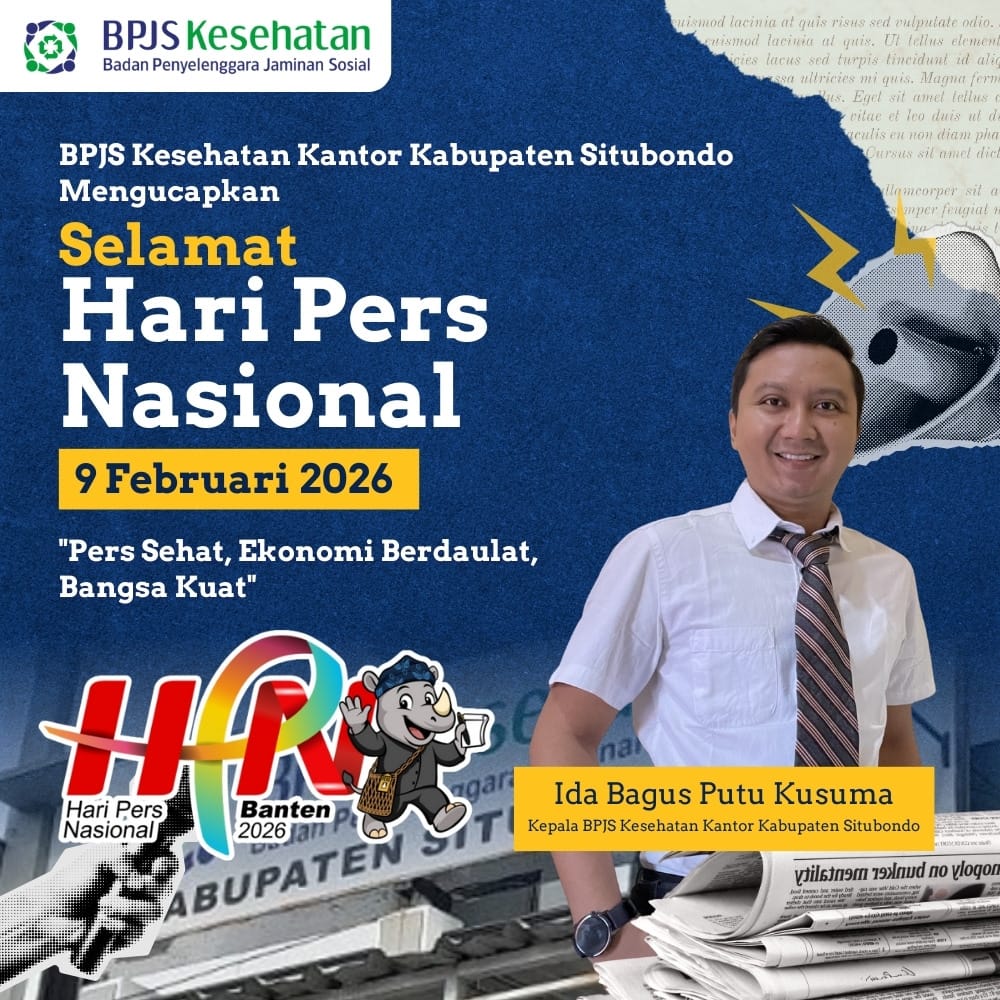Di suatu sore yang berjalan pelan, ketika kopi mulai mendingin dan tawa wartawan berbaur dengan suara kendaraan di jalanan di Bacan, Sahril Helmi sempat bernyanyi. Bukan lagu heroik, bukan pula mars perjuangan. Ia memilih sepotong lirik tentang cinta yang tak sanggup dilepaskan.
“Harus aku akui, aku tak mungkin bisa…”
Suaranya lirih. Matanya basah. Seperti seseorang yang sedang berbicara kepada kenangan, bukan kepada manusia di sekitarnya. Tak ada yang mengira, itulah lagu perpisahan.
Sudah empat tahun mengenalnya, dua tahun cukup dekat. Waktu yang pendek, tetapi cukup untuk memahami bahwa Sahril bukan wartawan biasa. Ia tertawa lebar, bercanda tanpa pamrih, dan memeluk dunia dengan cara sederhana, berbagi.
Ia bisa duduk bersama nelayan, aparat, aktivis, pejabat, atau tukang kopi tanpa mengubah wajahnya. Tak pernah merasa lebih tinggi, tak pernah ingin terlihat penting. Padahal, dalam diamnya, ia membawa beban besar. Istri tercinta meninggal saat melahirkan buah hati mereka.
Sejak saat itu, sebagian jiwanya seolah tinggal di makam. Barangkali itulah sebabnya, sehari sebelum berangkat meliput, Sahril memilih bermalam di pusara istrinya di Desa Amasing Kali. Ia berbaring di dekat tanah yang menyimpan cinta, seperti meminta izin, seperti berpamitan. Tak semua orang pamit sebelum pergi jauh. Sahril melakukannya.
Pagi itu, ia tetap berangkat. Padahal kawan-kawannya melarang. “Jangan pergi,” kata Koces, sambil menyeruput kopi. Sahril hanya tersenyum, senyum orang yang sudah memutuskan.
Ia naik speedboat, mengejar cerita tentang nelayan yang hilang, tentang keluarga yang menunggu, tentang manusia yang berharap ditemukan. Ia pergi mencari orang lain, tanpa tahu bahwa dirinya yang akan dicari.
Laut tak pernah bertanya siapa kita. Di hadapan ombak, wartawan dan pejabat sama kecilnya. Kamera mahal tak lebih berarti dari sandal jepit. Kartu pers tak bisa menawar badai. Speedboat itu karam. Empat orang meninggal. Tujuh selamat. Sahril hilang.
Enam hari lamanya, ibunya mengangkat tangan ke langit. Setiap pagi, setiap malam, di sela tangis dan lelah. Doa seorang ibu tak pernah sia-sia, hanya saja kadang jawabannya datang dalam bentuk yang paling menyakitkan. Sahril ditemukan terdampar di pantai Bacan Timur. Sunyi. Sendiri. Seperti selembar berita yang terlambat dibaca.
Ia pulang dalam peti, bukan dalam pelukan. Ia dimakamkan di Desa Bisui, tanah yang membesarkannya. Berdekatan dengan peringatan Hari Pers Nasional. Seakan waktu sengaja menaruhnya di sana, agar setiap perayaan pers selalu mengingat satu nama yang tak lagi bisa merayakan.
Sahril bukan pahlawan dengan patung. Ia tak punya monumen. Tak ada jalan bernama dirinya. Namun ia memiliki sesuatu yang lebih abadi, sebuah rekaman 15 detik.
Dalam video pendek itu, suaranya tegas dan jujur, tanpa retorika. "Apa yang saya kerjakan adalah misi kemanusiaan.” Tak ada kata rating, tak ada viral, tak ada klik. Hanya kemanusiaan. Ironis, di zaman ketika berita berlomba menjadi sensasi, Sahril justru mengingatkan bahwa jurnalisme bukan soal siapa tercepat, melainkan siapa paling peduli.
Kepergiannya genap satu tahun bertepatan dengan Puncak Hari Pers Nasional 2026 di Serang, Banten. Di antara ribuan insan pers yang hadir, beberapa sahabat Sahril dari Maluku Utara duduk dalam diam. Di tengah sorak perayaan, di balik spanduk dan pidato, nama Sahril kembali bergetar di ingatan mereka. Di aula besar itu, sebagian hati tertinggal di laut Halmahera.
Media sosial terus bergerak. Berita datang dan pergi. Trending topic berganti setiap jam. Nama Sahril tak lagi sering muncul. Begitulah dunia, cepat lupa pada mereka yang bekerja dengan tulus. Kita lebih rajin menghafal nama influencer daripada mengingat wartawan yang wafat demi satu laporan.
Kadang, kita merayakan pers dengan spanduk, tetapi lupa pada darah yang pernah tumpah di laut. Namun, di ruang redaksi kecil, di warung kopi, di pos liputan desa, nama Sahril masih hidup.
Ia hidup dalam wartawan muda yang tetap berangkat meski tak ada uang transport. Ia hidup dalam reporter yang memilih turun ke lapangan daripada menyalin siaran pers. Ia hidup dalam jurnalis yang masih percaya bahwa kebenaran layak diperjuangkan.
Sahril mengajarkan bahwa menjadi wartawan bukan soal terkenal, bukan soal undangan hotel, bukan soal foto bersama pejabat. Ia soal keberanian untuk tetap manusia.
Mungkin dunia tak banyak berubah setelah kepergiannya. Ketidakadilan masih ada. Hoaks masih ramai. Tekanan datang dari segala arah. Namun satu hal pasti, selama masih ada wartawan yang mengingat Sahril, jurnalisme belum mati. Selama masih ada yang percaya pada misi kemanusiaan, profesi ini belum kehilangan rohnya.
Kini, di suatu tempat yang tak kita ketahui, barangkali Sahril masih bernyanyi, masih tersenyum, masih menatap laut tanpa takut. Dan kita, yang masih hidup, memiliki satu tugas sederhana, menulis dengan jujur, bekerja dengan nurani, pergi meliput tanpa melupakan kemanusiaan.
Karena seperti yang telah Sahril tunjukkan, wartawan sejati tak pernah mati. Ia hanya berubah menjadi ingatan. Dan ingatan, jika dijaga, bisa lebih kuat dari waktu.