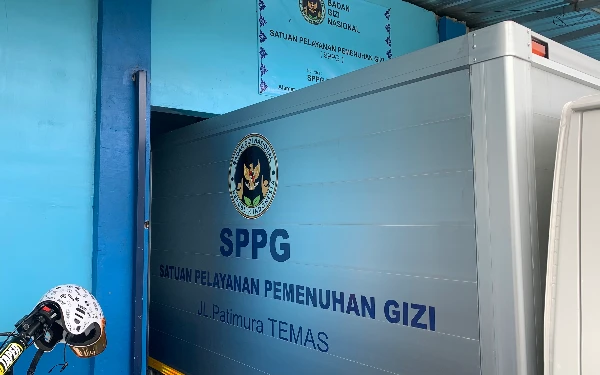KETIK, YOGYAKARTA – Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) merilis laporan yang mengungkap masih rendahnya upah jutaan pekerja di Indonesia. Dalam laporan tersebut, tercatat sekitar 14 juta pekerja menerima upah di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) -atau yang sebelumnya disebut Upah Minimum Regional (UMR).
Temuan ini cukup mengejutkan karena sebagian besar pekerja dengan upah rendah justru berasal dari kelompok pekerja berkerah putih, termasuk lulusan perguruan tinggi atau sarjana.
Menanggapi laporan tersebut, Dosen Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (PSdK) Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Hempri Suyatna, menilai fenomena rendahnya upah, termasuk yang dialami lulusan sarjana, tidak bisa dilepaskan dari kesenjangan di pasar tenaga kerja.
Menurut Hempri, salah satu faktor utama adalah ketidakseimbangan antara jumlah lapangan kerja dan pencari kerja. Kondisi ini menyebabkan posisi tawar (bargaining position) pekerja menjadi lemah.
“Situasi pasar tenaga kerja menunjukkan ketidakseimbangan karena jumlah lapangan kerja lebih sedikit dibandingkan pencari kerja. Akibatnya, posisi tawar pekerja menjadi lemah,” ujar Hempri, dikutip dari rilis UGM pada Kamis, 8 Januari 2025.
Ia menjelaskan, keterbatasan lapangan pekerjaan membuat pencari kerja tidak memiliki banyak pilihan. Dampaknya, pekerja terpaksa menerima standar upah yang rendah meskipun tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan mereka.
Selain faktor pasar tenaga kerja, Hempri juga menyoroti kondisi ekonomi makro yang turut memperparah situasi ketenagakerjaan. Menurutnya, gejala deindustrialisasi di sejumlah sektor, seperti industri tekstil, garmen, hingga industri digital, berkontribusi pada menyempitnya lapangan kerja.
“Dari sisi kemampuan perusahaan, kondisi ekonomi yang melemah membuat mereka tidak cukup kuat untuk menaikkan upah pekerja,” jelasnya.
Hempri menambahkan, kesenjangan pendapatan antarlapisan pekerja juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti jenis perusahaan, tingkat keterampilan tenaga kerja, serta risiko pekerjaan. Pekerjaan dengan risiko tinggi umumnya menawarkan upah lebih besar dibandingkan pekerjaan berisiko rendah.
Namun demikian, kesempatan kerja dengan upah tinggi tidak selalu berpihak pada lulusan pendidikan tinggi.
“Tingkatan keterampilan sangat memengaruhi apakah seseorang memperoleh gaji tinggi atau justru rendah,” katanya.
Ia juga menyoroti penerapan kebijakan upah minimum yang masih menghadapi tantangan, terutama di sektor informal. Hempri mengakui bahwa penetapan upah minimum sulit diterapkan secara ketat di sektor tersebut. Meski demikian, pemerintah dan perusahaan tetap memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan sosial bagi seluruh pekerja.
Menurutnya, perlindungan sosial seperti jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, khususnya di sektor informal.
“Menyamaratakan upah seluruh lapisan pekerja memiliki banyak tantangan. Yang paling penting adalah perlindungan sosial, seperti asuransi kesehatan dan jaminan sosial bagi pekerja informal,” ujarnya.
Sebagai solusi jangka panjang, Hempri mendorong penerapan demokrasi ekonomi dalam sistem ketenagakerjaan nasional. Ia menilai pekerja seharusnya tidak hanya diposisikan sebagai tenaga kerja, tetapi juga dilibatkan dalam pengambilan keputusan perusahaan.
“Solusinya ada pada demokrasi ekonomi, ketika pekerja dapat memberikan masukan dan bahkan memiliki saham di perusahaan,” ungkapnya.
Selain itu, ia mendorong perusahaan untuk lebih terbuka, termasuk dengan melantai di bursa atau go public, sehingga kebijakan perusahaan dapat lebih berpihak kepada pekerja. Menurut Hempri, langkah tersebut dapat membantu negara menciptakan sistem ketenagakerjaan yang lebih adil dan berkelanjutan. (*)