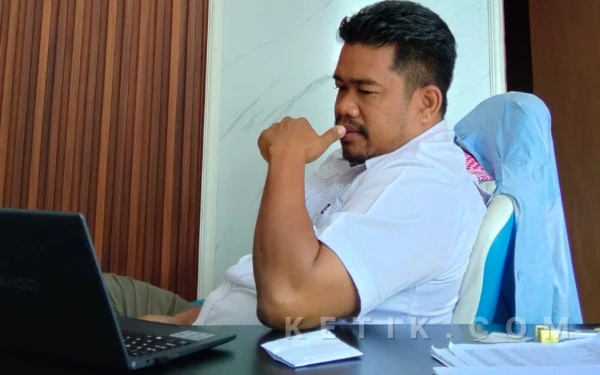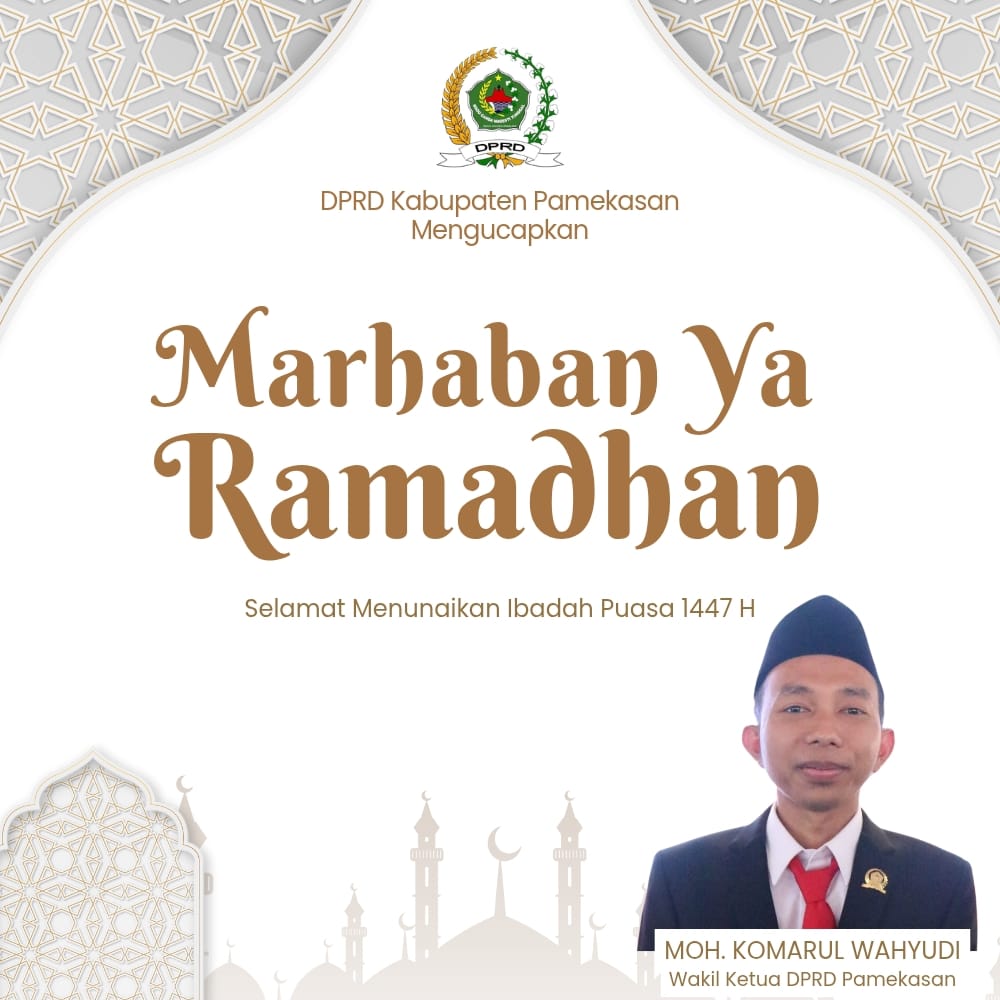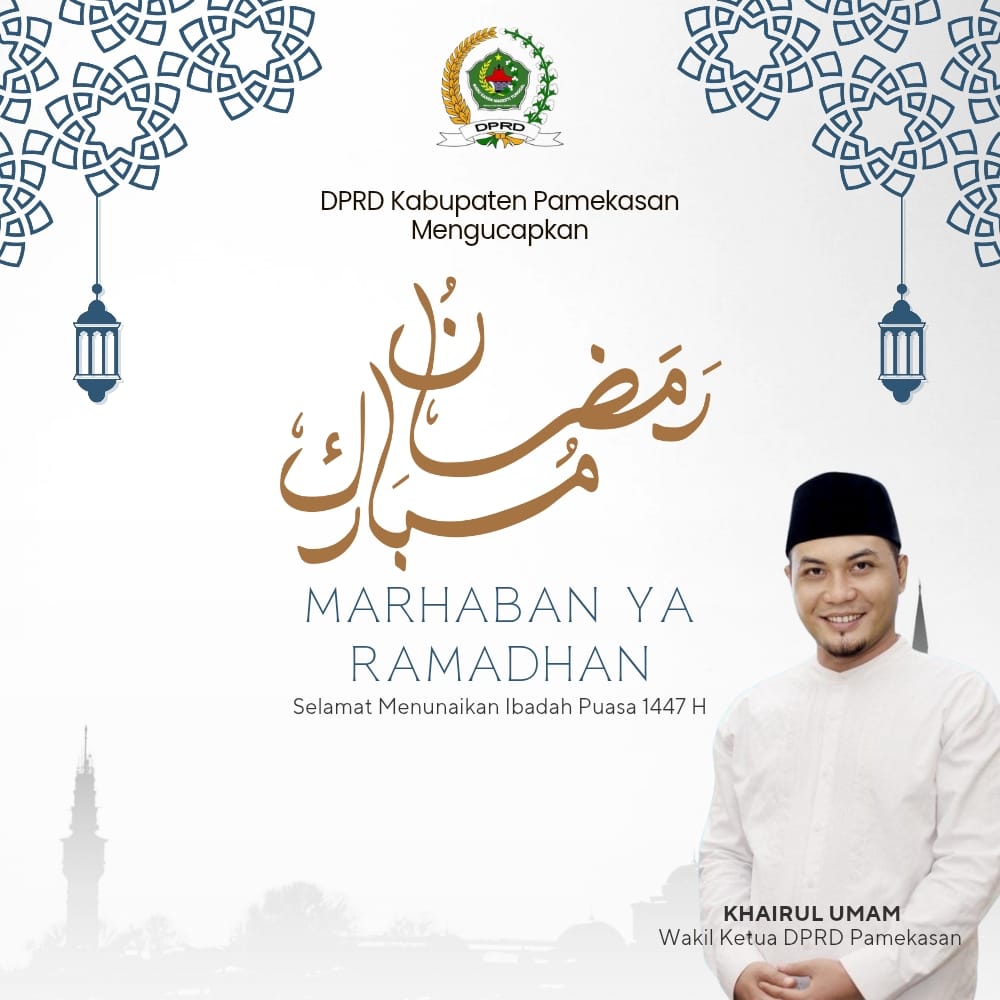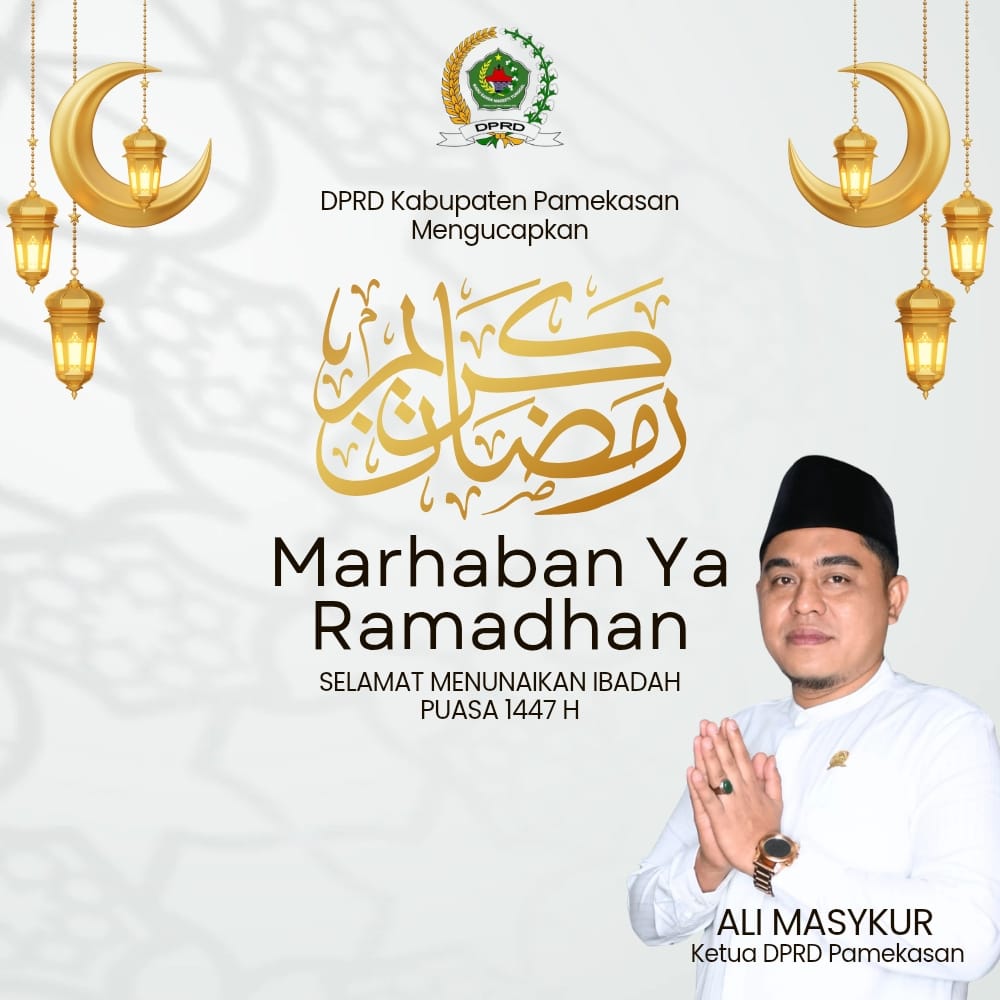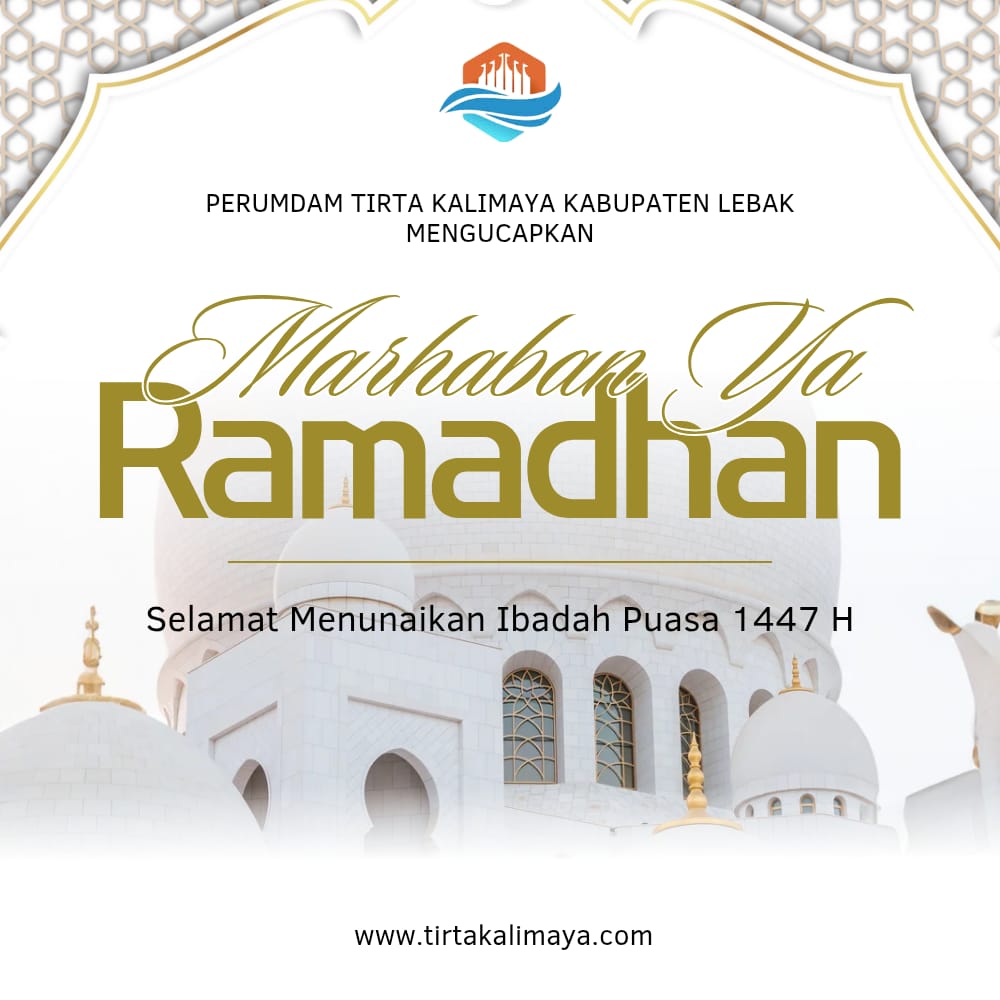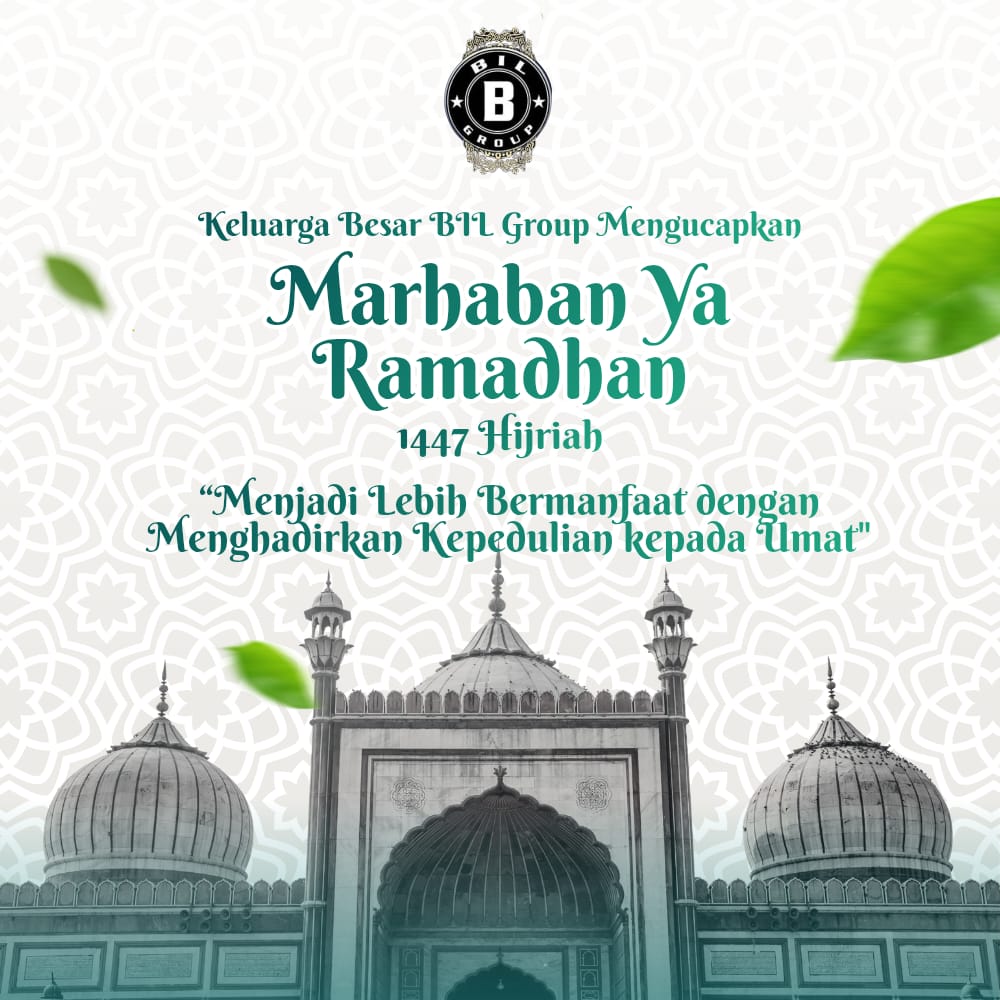Fenomena gantung diri di Indonesia memasuki fase memprihatinkan. Dalam tiga tahun terakhir, sejak 2023 hingga 2025, data kepolisian menunjukkan angka bunuh diri tetap tinggi. Dan mayoritas korban memilih metode gantung diri. Meski angka pastinya dapat bervariasi antar laporan, tren umumnya konsisten. Kasusnya bukan menurun, tetapi stagnan bahkan meningkat.
Kita seolah menyaksikan krisis sunyi yang terus berlangsung tanpa penanganan komprehensif. Menurut penulis, bunuh diri bukan sekadar persoalan psikologis semata. Melainkan problem sosial yang kompleks. Mulai tekanan ekonomi, relasi sosial yang berubah, akses kesehatan mental yang timpang, hingga kultur yang masih memandang depresi sebagai kelemahan moral. Banyak orang tidak melihat depresi sebagai kondisi medis yang membutuhkan perawatan profesional.
Pertanyaannya, apa sebenarnya yang terjadi dan mengapa angka ini sulit ditekan? Data Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Polri menunjukkan, dalam rentang 2023 hingga pertengahan 2025, tercatat ratusan hingga lebih dari seribu kasus bunuh diri terjadi. Dalam banyak laporan, lebih dari 80 persen di antaranya menggunakan metode gantung diri.
Beberapa ilustrasi pola umum yang penulis dapatkan, pada 2023, lebih dari 900 kasus bunuh diri tercatat, dengan dominasi metode gantung diri. Lalu 2024, angka serupa kembali muncul, bahkan meningkat pada kuartal tertentu. Dan pada 2025, dalam lima bulan pertama, polisi sudah menerima lebih dari setengah angka tahun sebelumnya. Di balik setiap angka ada manusia, keluarga, dan komunitas yang kehilangan anggotanya tanpa sempat memberi pertolongan.
Dalam perspektif akademik, seperti dibahas dalam buku “The Noonday Demon: An Atlas of Depression” (Andrew Solomon) dan “Why People Die by Suicide” (Thomas Joiner), angka-angka seperti ini mencerminkan adanya mental health burden serius yang tidak tertangani secara sistemik. Banyak negara lain yang mengalami tren serupa merespons dengan reformasi besar pada kebijakan kesehatan mental. Indonesia, belum melakukan hal itu secara komprehensif dan cepat.
Mengapa Gantung Diri Menjadi Metode Dominan?
Dalam kajian forensik dan psikologi klinis, sebagaimana dibahas dalam “Suicide and Attempted Suicide” (Geo Stone) serta “The Tipping Point of Suicide Behaviour” (David Lester & Muriel Lezak), ada beberapa faktor yang membuat metode gantung diri dominan.
1. Alat sangat mudah didapat. Seperti tali, ikat pinggang, kabel, atau kain panjang tersedia di rumah mana pun.
2. Persepsi efektivitas. Metode gantung diri memiliki high lethality rate.
3. Minim pengawasan lingkungan. Banyak kasus terjadi di ruang privat.
4. Kurangnya literasi publik. Banyak keluarga mengaku tidak melihat tanda apapun sebelum kejadian.
Metode gantung diri bukan pilihan spontan semata, tetapi hasil dari kondisi lingkungan yang tidak menyediakan pagar pengaman sosial maupun psikologis.
Dalam literatur psikologi sosial seperti “The Broken Ladder: How Inequality Affects the Way We Think, Live, and Die” (Keith Payne) dan “Scarcity: Why Having Too Little Means So Much” (Sendhil Mullainathan & Eldar Shafir), ekonomi disebut sebagai stress amplifier. Tahun 2023–2025 bukan periode mudah. Biaya hidup naik, utang meningkat, lowongan kerja stagnan, dan tekanan finansial menumpuk.
Untuk banyak orang, terutama laki-laki usia produktif, tekanan ekonomi tidak diungkapkan tetapi dipendam. Depresi yang tidak tersalurkan menjadi bom waktu. Ketika mental mencapai batas, keputusan ekstrem sering terlihat sebagai jalan pintas.
Sementara itu untuk pemberitaan bunuh diri, WHO sudah menegaskan pedoman. Antara lain jangan sebut metode, lokasi spesifik, barang yang digunakan, atau detail dramatik. Namun sebagian media Indonesia, masih memuat detail kronologis yang terlalu gamblang.
Fenomena copycat suicide atau Werther Effect telah diteliti luas. Salah satunya dalam buku klasik “Night Falls Fast: Understanding Suicide” (Kay Redfield Jamison). Ketika media mempublikasikan detail yang memicu, risiko terjadinya kasus serupa meningkat. Terkait hal ini, Indonesia, membutuhkan pedoman yang lebih ketat bukan sekedar anjuran moral bagi redaksi.
Di sisi lain, Indonesia, masih kekurangan tenaga profesional kesehatan jiwa. Buku “The Globalization of Mental Health” (Fernando & Weerasinghe) menyebutkan bahwa negara berkembang seperti Indonesia, sering mengalami treatment gap yang sangat besar.
Lebih dari separuh psikiater Indonesia, berada di kota besar. Sementara kasus bunuh diri justru banyak terjadi di pedesaan dan pinggiran kota. Puskesmas memang menyediakan layanan kesehatan jiwa, tetapi sangat terbatas. Indonesia, juga belum memiliki hotline nasional bunuh diri yang mudah diakses dan beroperasi 24 jam.
Selain itu, kultur sosial yang menghakimi seperti kalimat terlontar “kurang kuat iman,” “kurang bersyukur” justru memperburuk kondisi. Dalam buku “Daring Greatly” (Brené Brown) dijelaskan, rasa malu (shame) adalah salah satu faktor psikologis paling berbahaya bagi manusia ketika berada dalam kondisi rentan. Dan stigma jelas membuat orang enggan mencari bantuan.
Sampailah bahasan penulis pada pencegahan bunuh diri. Terkait hal ini harus berbasis bukti ilmiah sebagaimana direkomendasikan dalam “The Suicide Prevention Handbook” (Alan Berman & David Rudd) dan standar WHO.
Beberapa langkah penting antara lain. Edukasi publik tentang depresi dan tanda-tanda awal. Kemudian hotline nasional dengan operator terlatih. Penguatan pelayanan kesehatan jiwa di puskesmas. Protokol sekolah dan tempat kerja untuk mendeteksi risiko. Pengawasan pedoman media oleh lembaga independen. Intervensi berbasis komunitas dan tokoh lokal. Dan akses layanan kesehatan mental yang terjangkau dan tanpa stigma.
Tidak ada solusi instan, tetapi setiap langkah kecil dapat mencegah tragedi besar berikutnya. Fenomena gantung diri bukan sekadar angka. Ini potret hening masyarakat yang kesulitan menyediakan ruang aman bagi warganya.
Dalam banyak kasus, yang dibutuhkan seseorang hanyalah percakapan sederhana. Misalnya “Kamu baik-baik saja?” Kalimat kecil seperti itu, menurut berbagai studi intervensi krisis, dapat menyelamatkan nyawa. Bagi siapa pun yang sedang berada dalam masa kelam, depresi dapat ditangani, bantuan tersedia, dan kemungkinan untuk pulih selalu ada. (*)
Disclaimer: Tulisan ini tidak bertujuan menginspirasi, mendorong, atau menggambarkan bunuh diri sebagai pilihan. Artikel ini disusun untuk kepentingan edukasi publik. Bila Anda atau orang di sekitar Anda mengalami gejala depresi, pikiran ingin melukai diri sendiri, atau tanda-tanda krisis mental, segera hubungi tenaga kesehatan, psikolog, psikiater, atau layanan darurat terdekat.
*) Eko Hardianto adalah Wartawan Ketik.com bertugas di Probolinggo Raya
**) Isi tulisan di atas menjadi tanggung jawab penulis
***) Ketentuan pengiriman naskah opini:
- Naskah dikirim ke alamat email redaksi@ketik.com
- Berikan keterangan OPINI di kolom subjek
- Panjang naskah maksimal 800 kata
- Sertakan identitas diri, foto, dan nomor HP
- Hak muat redaksi.(*)