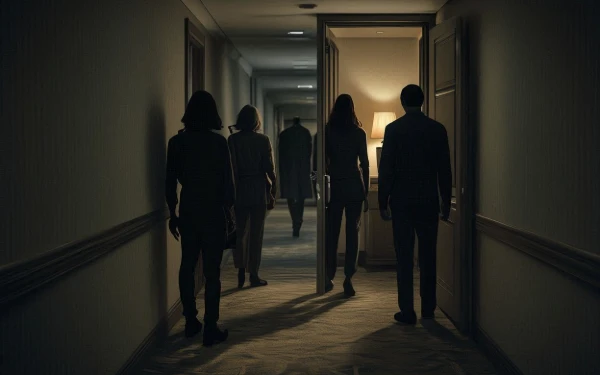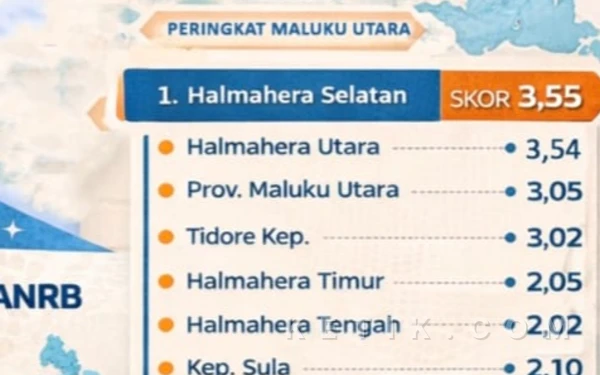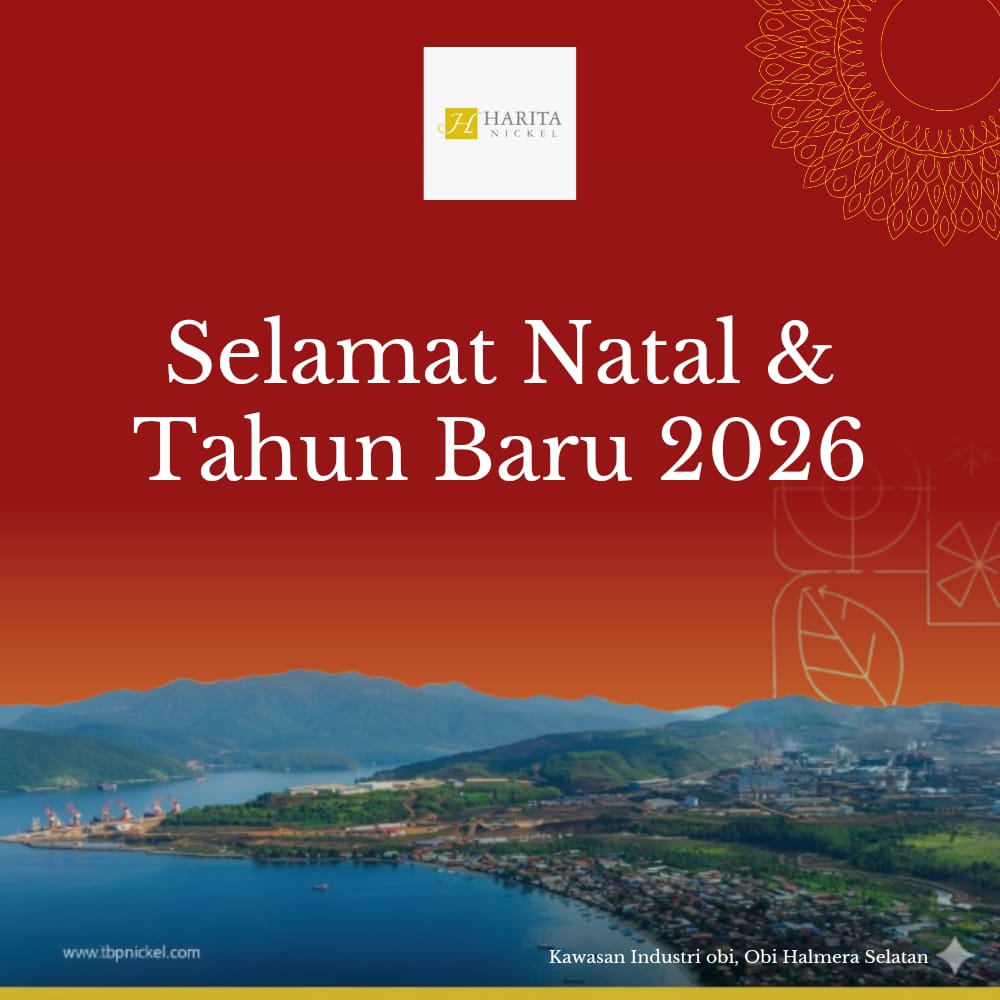Kepemimpinan dalam pemerintahan daerah merupakan faktor strategis yang menentukan arah pembangunan, efektivitas tata kelola, serta stabilitas politik. Dalam konteks otonomi daerah, peran seorang pemimpin tidak hanya terbatas pada pengambilan keputusan administratif, tetapi juga mencakup kemampuan membangun legitimasi sosial dan menjaga harmoni politik.
Northouse (2019) mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses memengaruhi sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Dalam pemerintahan, hal ini menuntut perpaduan antara visi politik, keterampilan manajerial, dan pengakuan dari masyarakat yang dipimpin.
Kerangka Teori Kepemimpinan Barat
Kajian manajemen dan politik mengenal berbagai gaya kepemimpinan dengan karakteristik dan efektivitas yang berbeda. Lewin, Lippitt, dan White (1939) memperkenalkan model kepemimpinan otokratik, yang menempatkan kendali penuh pada pemimpin. Gaya ini efektif dalam situasi darurat atau krisis, namun berpotensi menekan kreativitas dan partisipasi bawahan.
Sebaliknya, kepemimpinan demokratik mengedepankan partisipasi dan musyawarah. Menurut Yukl (2013), pendekatan ini dapat meningkatkan komitmen dan rasa memiliki di kalangan anggota, meskipun terkadang memperlambat proses pengambilan keputusan.
Selain itu, Weber (1947) memperkenalkan konsep charismatic authority, di mana daya tarik personal pemimpin menjadi sumber legitimasi dan inspirasi. Terdapat pula gaya otoriteristik yang mirip dengan otokratik, tetapi lebih menekankan pada kedisiplinan struktural dan prosedur yang kaku. Sementara itu, kepemimpinan laissez-faire memberikan keleluasaan besar kepada bawahan, efektif untuk tim yang sangat profesional, namun berisiko kehilangan arah bila pengawasan minim (Bass & Bass, 2008).
Kepemimpinan dalam Perspektif Budaya Jawa
Di luar kerangka teori Barat, masyarakat Jawa mengembangkan model kepemimpinan yang berakar pada nilai budaya dan filosofi tradisional. Koentjaraningrat (1985) menjelaskan bahwa kepemimpinan Jawa berpijak pada prinsip harmoni (rukun), empati (tepa selira), dan kesederhanaan (prasojo).
Nilai-nilai ini terwujud dalam falsafah Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani, yang dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Falsafah ini memposisikan pemimpin sebagai teladan di depan, penggerak di tengah, dan pendorong di belakang, sehingga menciptakan kedekatan emosional sekaligus legitimasi moral di mata rakyat.
Panduan etis kepemimpinan Jawa juga tercermin dalam konsep Asta Brata, yang berasal dari Serat Rama. Konsep ini mengajarkan delapan sifat kepemimpinan yang meneladani alam: memberi penerangan seperti matahari (Surya Brata), kesejukan seperti rembulan (Chandra Brata), keteladanan seperti bintang (Kartika Brata), kesabaran seperti bumi (Bumi Brata), keluasan wawasan seperti samudra (Samudra Brata), ketanggapan seperti angin (Bayu Brata), ketegasan seperti api (Agni Brata), dan pemberi kesejahteraan seperti hujan (Indra Brata). Poespoprodjo (1999) menilai Asta Brata sebagai perpaduan antara etika, spiritualitas, dan strategi pemerintahan.
Jika dibandingkan, kepemimpinan Jawa unggul dalam menjaga stabilitas sosial, menghindari konflik terbuka, dan memperkuat legitimasi melalui simbol budaya. Model ini memiliki kemiripan dengan kepemimpinan demokratik dalam hal musyawarah, tetapi juga menyerap ketegasan dari gaya otokratik. Tantangannya terletak pada potensi lambatnya pengambilan keputusan akibat orientasi pada konsensus, serta kecenderungan menghindari konfrontasi karena ewuh pakewuh.
Studi Kasus Yogyakarta, Surakarta, dan Sleman
Penerapan prinsip kepemimpinan Jawa dapat diamati secara nyata pada figur pemimpin di wilayah Yogyakarta dan Surakarta. Di Yogyakarta, Gubernur Sri Sultan Hamengku Buwono X menampilkan kepemimpinan yang memadukan kharisma budaya, komunikasi persuasif, dan visi pembangunan berorientasi ganda: pelestarian budaya dan inovasi ekonomi. Studi Suyanto (2017) menunjukkan bahwa pendekatan ini berhasil menjaga stabilitas politik sekaligus menguatkan citra Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai provinsi yang harmonis namun progresif.
Di Surakarta, gaya kepemimpinan Jawa juga terlihat pada masa pemerintahan Wali Kota Joko Widodo (2005–2012). Penelitian Aspinall & Mietzner (2014) menyoroti metode blusukan yang dilakukan Jokowi sebagai wujud prinsip ing madya mangun karsa, di mana pemimpin hadir langsung di tengah masyarakat untuk membangun partisipasi dan kepercayaan publik. Keberhasilannya memadukan nilai-nilai budaya dengan efisiensi pelaksanaan kebijakan membuktikan bahwa kepemimpinan Jawa dapat beradaptasi dengan kebutuhan pemerintahan modern.
Contoh yang tak kalah menarik datang dari Kabupaten Sleman saat ini. Bupati memilih untuk tetap tinggal di rumah pribadi di kampung bersama warga, alih-alih menempati rumah dinas bupati. Rumah dinas tersebut justru dimanfaatkan sebagai fasilitas publik bagi masyarakat untuk mengadakan berbagai kegiatan positif.
Selain itu, bupati menerapkan gaya kepemimpinan tanpa pengawalan ketat, bahkan tanpa foreder di jalan raya, sehingga aktivitasnya tidak menciptakan jarak sosial dengan rakyat. Pendekatan ini memungkinkan warga berinteraksi secara natural dan merasa nyaman bergaul dengan pemimpinnya.
Di kantor pemerintahan, masyarakat Sleman juga dapat langsung menemui bupati untuk menyampaikan aspirasi tanpa prosedur yang berbelit. Praktik ini mencerminkan filosofi kepemimpinan Jawa yang mengedepankan kedekatan, keterbukaan, dan kesederhanaan. Lebih dari itu, langkah ini menjadi warisan nilai bagi generasi muda bahwa jabatan pemimpin sebaiknya dijalankan dengan prinsip tepa selira, rendah hati, dan selalu menjaga hubungan emosional dengan rakyatnya.
Kesimpulan
Kepemimpinan Jawa bukan sekadar warisan budaya, tetapi modal sosial yang relevan dan strategis bagi pemerintahan daerah. Nilai-nilai yang dikandungnya memberi legitimasi moral, memperkuat ikatan emosional antara pemimpin dan rakyat, serta menciptakan stabilitas sosial-politik.
Ketika diintegrasikan dengan prinsip-prinsip manajemen modern, model ini dapat menghasilkan pemerintahan yang responsif, efektif, dan berakar pada identitas budaya. Pengalaman Yogyakarta, Surakarta, dan Sleman menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan berbasis budaya dapat diadaptasi untuk menghadapi tantangan modern, sekaligus menjadi teladan bagi generasi penerus dalam membangun pemerintahan yang manusiawi dan berkeadaban.
*) Harda Kiswaya merupakan Bupati Sleman periode 2025-2030 dan Chaidir adalah jurnalis di Yogyakarta
**) Isi tulisan di atas menjadi tanggung jawab penulis
***) Karikatur by Rihad Humala/Ketik.co.id
****) Ketentuan pengiriman naskah opini:
- Naskah dikirim ke alamat email redaksi@ketik.co.id.
- Berikan keterangan OPINI di kolom subjek
- Panjang naskah maksimal 800 kata
- Sertakan identitas diri, foto, dan nomor HP
- Hak muat redaksi.(*)