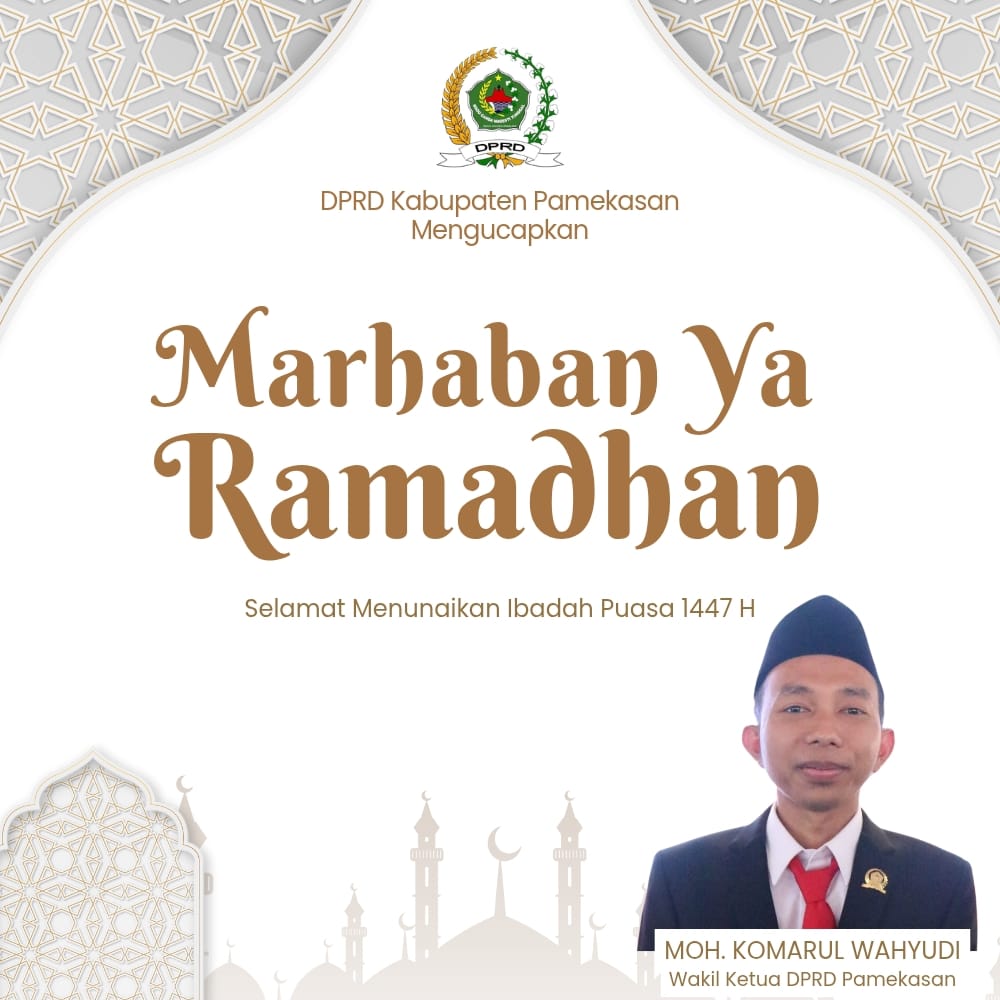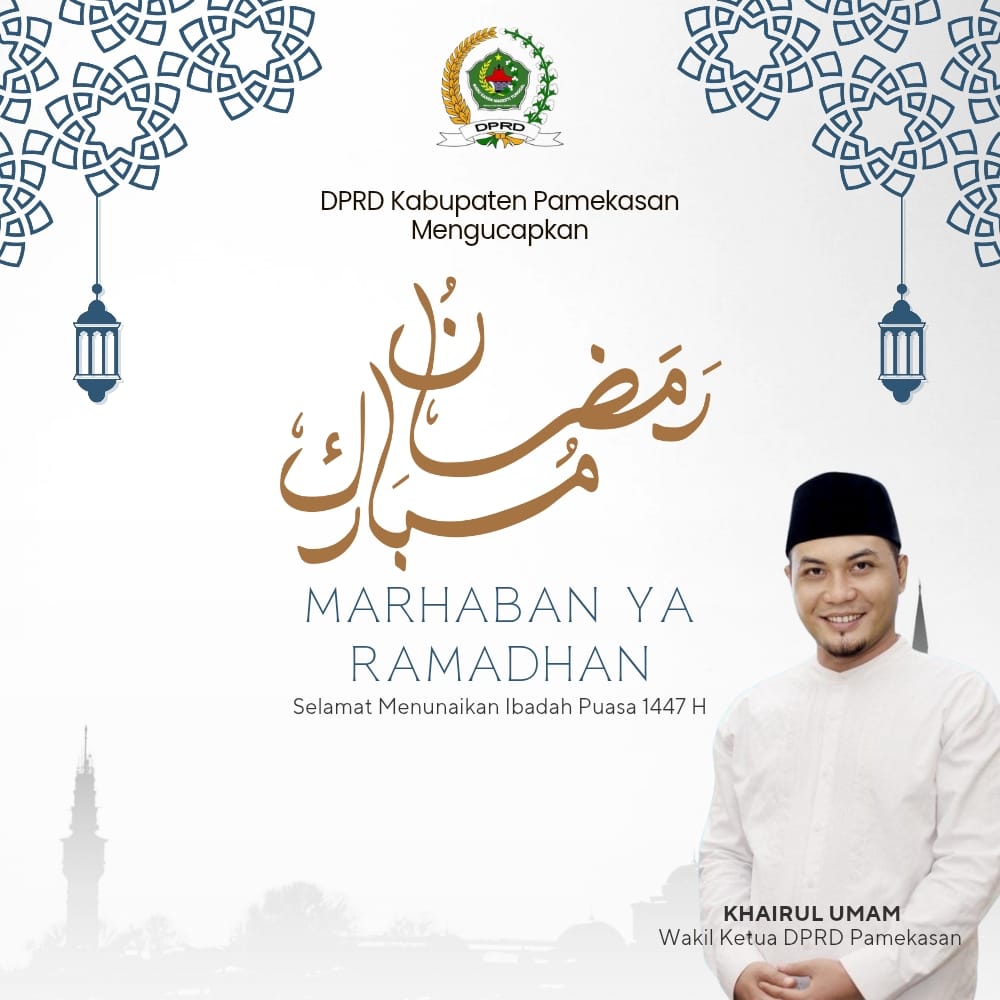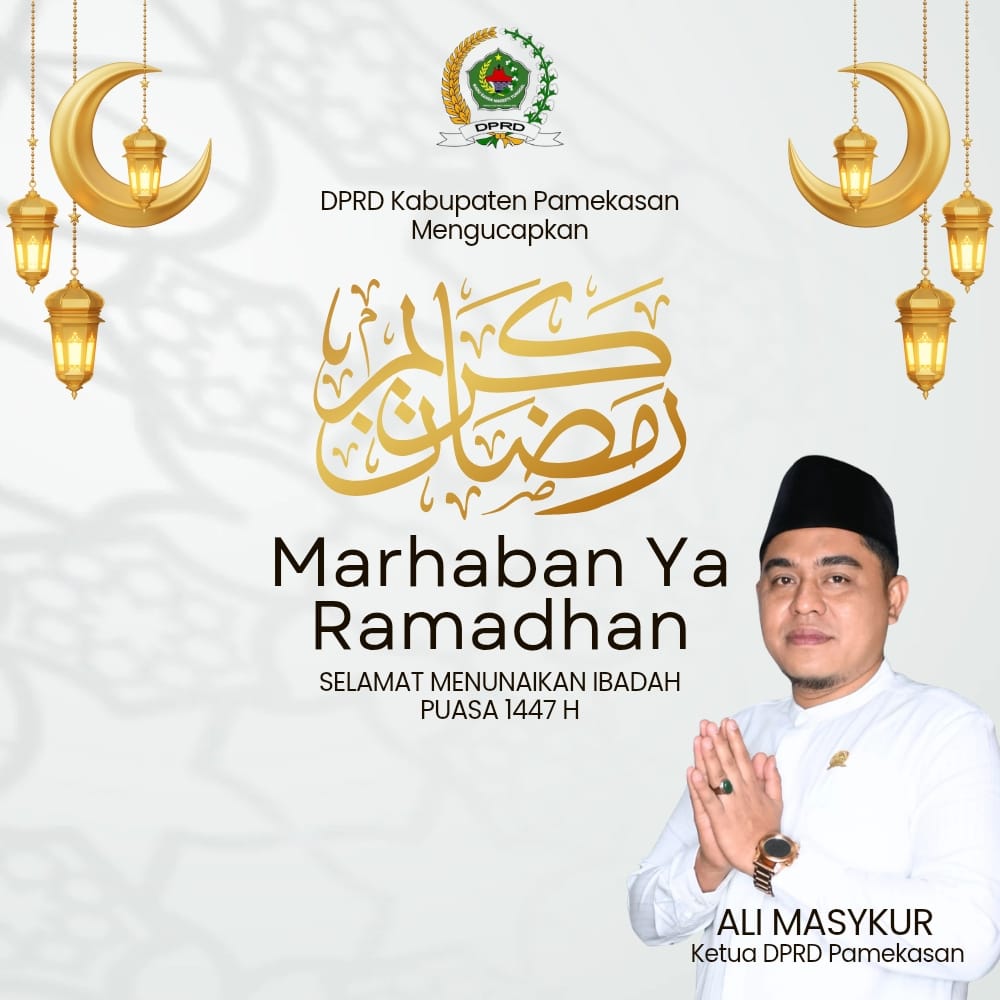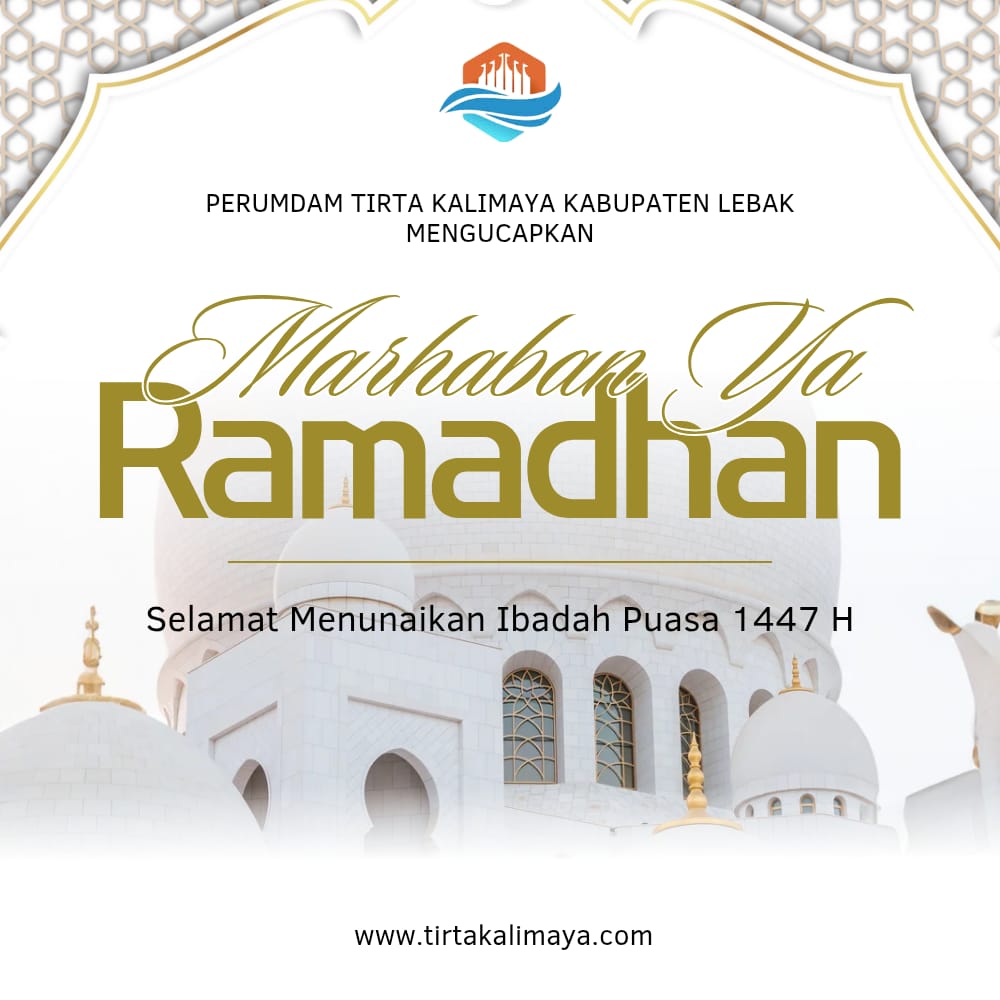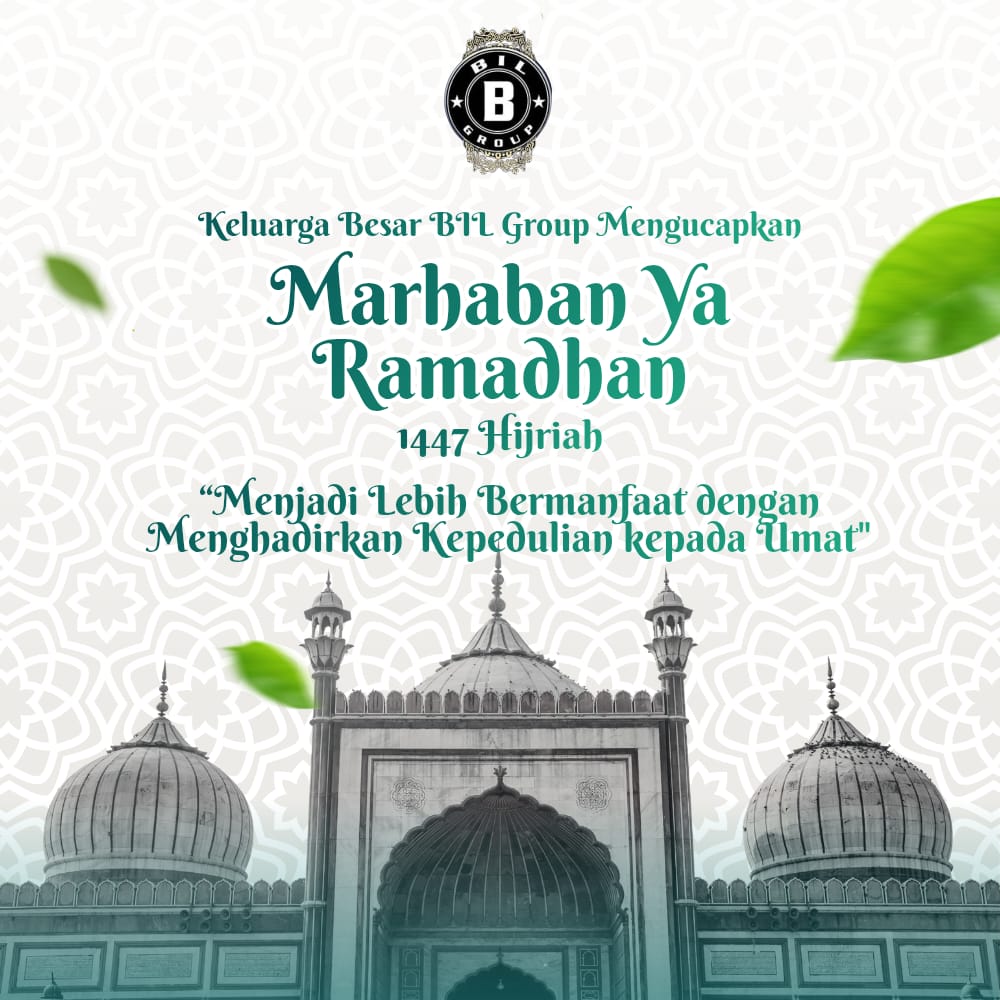Keterbukaan (transparansi) merupakan salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan desa (Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014). Terkait dengan hal itu, pemerintah desa yang dipimpin kepala desa punya kewajiban “memberikan informasi kepada masyarakat Desa (Pasal 26 Ayat 4). Tak mengherankan jika UU Desa juga mewajibkan kepala desa untuk “memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran” (Pasal 27 poin d).
Desa yang memiliki pemerintahan yang terbuka dalam makna yang sebenarnya akan mengarah pada partisipasi warga dan membuat pemerintahan desa terkontrol oleh kekuatan rakyatnya. Kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah merupakan perwujudan dari kehendak dan aspirasi rakyat desa. Pemerintah desa menjalankan amanat rakyat yang telah mengusulkan ide-ide dan masukan untuk memajukan desa. Kegiatan pembangunan, baik yang menggunakan anggaran maupun tidak, dilakukan berdasarkan perencanaan dari warga masyarakat—pun juga kegiatannya melibatkan warga masyarakat.
Ketika usulan kegiatan dari warga merupakan kegiatan yang strategis dan berdampak bagi kemajuan, maka desa akan terus bergerak maju menuju keberdayaan masyarakat. Ide-ide maju disampaikan. Masing-masing warga dan kelompok social di desa berlomba-lomba untuk menyampaikan ide kegiatan dan kemudian dalam musyawarah desa ditetapkan kegiatan terbaik dalam artian punya dampak bagi kemajuan desa. Ide dan rencana program dan kegiatan terbaik berhasil ditetapkan karena disepakati sebagai kegiatan yang dianggap paling berdampak baik. Lalu eksekusi kegiatan benar-benar riil, serta melibatkan partisipasi masyarakat.
Sehingga tidak ada lagi anggapan bahwa desa sepi dari kegiatan. Apalagi sejak desa-desa mendapatkan transfer dana (anggaran) dari pusat yang pertahun rata-rata Rp1 Miliar. Kegiatan berbasis anggaran bisa direncanakan dengan baik lewat mekanisme demokratis yang sudah diatur oleh perundang-undangan. Musyawarag-musyawarah mulai basis terkecil (RT, RW, Dusun, hingga pada tingkat desa). Rencana program dan kegiatan berbasis anggaran disepakati setelah musyawarah dilaksanakan dengan penuh kualitas di mana para peserta rapat aktif menyuarakan gagasan dan rencana kegiatan.
Belum lagi jika warga desa lewat komunitas, ormas, dan forum-forum warga juga punya kemampuan untuk membuat kegiatan-kegiatan dengan anggaran mandiri. Semakin banyak kegiatan baik yang menggunakan dana Negara maupun dana swadaya di sebuah desa, maka semaraknya kegiatan warga desa dan pemerintah desa akan menjadi daya dongkrak kemajuan desa. Apalagi jika ada kegiana ekonomi produktif, edukatif, dan bukan sekedar hiburan atau hura-hura. Meskipun banyak kegiatan, tapi bentuk kegiatannya hanya berupa pesta dan hiburan, maka juga tak akan mampu meningkatkan kekuatan produktif. Uang yang dikeluarkan akan menguap begitu saja. Senang-senang saat acara berlangsung, seteahnya tak ada dampak signifikan.
Kegiatan produktif adalah kegiatan yang mendorong warga menghasilkan suatu yang bias bermanfaat dan menghasilkan produk barang atau jasa. Konsep “Satu Desa Satu Produk” (“One Village One Product”/OVOP) jika bias diterapkan secara nyata akan membuat tiap desa punya produk unggulan masing-masing—yang tentunya juga harus didorong bisa menjadi produk unggul tingkat global. Jika ruang keterbukaan yang ada di desa benar-benar nyata, diikuti dengan peran pemerintah desa yang melakukan edukasi dan pelatihan-pelatihan, upaya meningkatkan masyarakat produktif-kreatif di desa akan bisa benar-benar terwujud. Desa tidak lagi hanya menyediakan bahan mentah untuk daerah perkotaan, yang akan dijual lagi ke desa oleh pengusaha dari kota dengan harga yang lebih mahal. Sehingga, desa juga bukan tempat penyedia tenaga kerja murah dalam bentuk warga desa yang mencari kerja di kota-kota. Harapannya, desa akan menjadi tempat usaha rakyat dengan produk unggulan sesuai potensi lokalnya masing-masing.
Ya, selama ini fungsi desa adalah menyediakan bahan mentah dan sebagian adalah tenaga kerja. Pemilik modal di kota yang membangun usaha menikmati keuntungan dari usahanya. Para pengusaha besar berpusat di kota membelanjakan sebagian besar dari duitnya di kota. Karena itulah, ketimpangan kota dan desa yang paling mencolok sebenarnya adalah pada peredaran uang yang memang merupakan faktor pendorong pertumbuhan ekonomi.
Oleh karena itulah, upaya mendorong pertumbuhan ekonomi di pedesaan adalah dengan membuat peredaran uang dan modal di desa meningkat. Caranya adalah menumbuhkan usaha di desa dengan mengundang investor untuk membangun usaha di area pedesaan dan pinggiran. Negara-negara kemajuannya berjalan cepat dan mengalami pemerataan kesejahteraan seperti Cina, mereka telah mengalihkan pembangunan dari kota dipindah di desa, membangun klaster-klaster industri di desa.
Penyakit Korupsi
Sayangnya, gambaran ideal yang saya uraikan di atas masih belum terwujud. Ternyata yang terjadi bukanlah keterbukaan dan partisipasi. Yang terjadi bukan munculnya ruang-ruang terbuka untuk lahirnya ide dan masukan-masukan rakyat untuk pembangunan. Rata-rata desa masih tertutup. Banyak desa yang sepi dari kegiatan. Lembaga-lembaga kemasyarakatan desa (RT, RW, Karangtaruna, PKK, Posyandu,LPM) tidak begitu hidup. Pada hal secara konsepsional, LKD (lembaga kemasyarakatan desa) adalah wadah partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di desa.
Sebagaimana hasil penelitian Litbang Kompas hasilnya dimuat dalam Kompas (18/02/2025) dalam judul liputannya “Dana Desa Diselewengkan Lewat Laporan Fiktif”, ditemukan bahwa lebih dari 59 persen kasus korupsi dana desa terjadi karena adanya laporan keuangan palsu. Dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa justru dimainkan dengan berbagai manipulasi data. Hasil penelusuran Tim Jurnalisme Harian Kompas terhadap 591 putusan kasus korupsi dana desa selama 2014–2024 dari Direktori Putusan Mahkamah Agung, ditemukan modus manipulasi laporan fiktif mendominasi dengan 59,83 persen, diikuti pembangunan fiktif atau proyek di bawah spesifikasi (54,49 persen).
Kalau kita coba lihat kasus korupsi di Trenggalek, melihat kasus korupsi yang terjadi di desa, korupsi dengan membuat laporan palsu juga tampak dominan. Ambil contoh kasus Korupsi yang pelakunya sudah divonis penjara, yaitu yang terjadi di desa Melis Kecamatan Gandusari. Modusnya juga memanipulasi dokumen pendukung laporan pertanggungjawaban (Jawa Pos, Radar Tulungagung, 09/09/2024). Kegiatan fiktif dan laporan fiktif adalah modus korupsi yang banyak dilakukan, selain melakukan ‘mark up’.
Korupsi dan ketidakterbukaan selalu menjadi kondisi yang terjadi berbarengan. Desa yang korup jelas merupakan desa yang tidak terbuka. Desa yang sepi kegiatannya. Apalagi kalau modusnya adalah kegiatan fiktif: Kegiatan tidak ada, tapi dilaporkan dengan cara memalsu dokumen pendukung laporan kegiatan. Misal tidak pernah ada acara sosialiasi atau pembinaan atau pemberdayaan dengan mengundang warga desa di balai desa, tapi dibuat laporan ada. Dokumen pendukun dibuat ada, missal ada bukti kwitansi pembelian snack dan nasi kotak. Ada kwitansi cetak banner. Ada tandatangan peserta, tapi tandatangan palsu. Semua bukti palsu dan tidak riil. Kadang kegiatan tidak riil, tapi ada foto-foto. Pada hal foto yang disertakan sebagai bukti bukan foto kegiatan riil, atau bisa jadi foto editan.
Uang yang seharusnya dibuat kegiatan pelatihan dan pemberdayaan warga malah dikorupsi. Kegiatan tidak ada, dilaporkan ada, tapi uang masuk ke kantong koruptor di desa. Koruptor sebagai pelaku maling uang Negara tentunya akan tidak mau tindakan-tindakannya diketahui warga. Maka, koruptor cenderung tidak suka jika banyak orang banyak terlibat di desa atau dekat dengan koruptor. Maling akan cenderung melakukan tindakan agar aksinya tidak diketahui. Makanya, ia menyukai sepi daripada ramai.
Karena itulah desa yang penuh kejahatan korupsi biasanya sepi. Partisipasi warga minim. Tak ada atau jarang warga yang kritis, suka bertanya. Bahkan membicarakan desanya saja seperti tabu. Desa yang rakyatnya tidak ada suara di ruang-ruang terbuka kemungkinan besar adalah desa yang korupnya menaun. Bisa jadi masih ada sedikit kegiatan, tapi yang terlibat adalah rang-orang atau segelintir warga yang tidak suka bertanya dan tidak kritis. Bisa jadi warga yang tak paham apa-apa, yang mudah diajak kegiatan karena motivasi oportunis seperti senang karena dapat amplop dan dapat makan.
Kegiatan kadang ada, tapi juga tidak substansial, hanya formalistis, dan jauh dari kualitas. Ada musyawarah desa yang seharusnya jadi ruang paling demokratis bagi perwakilan warga. Tetapi yang diundang adalah orang-orang yang tidak kritis, sehinga suara rakyat tidak ada. Sehingga seperti musyawarah yang beku dan tidak menjadi ajang bagi penyampaian aspirasi yang sadar dan merdeka dari warga yang berbasis pada pemajuan desa dan tujuan bersama.
Situasi itu bisa mengarah pada semakin mundurnya situasi desa. Bukan pada arah kemajuan dan terakomodasinya kepentingan bersama. Tapi harapan rakyat kian hilang. Lalu yang terjadi adalah ketidakpedulian dan apatisme. Desa yang seharusnya berjalan maju, akhirnya bukan hanya jalan di tempat, tapi mundur jauh. Arah desa dikendalikan kepentingan pribadi dan segelintir elit. Rakyat desa tak merasa memiliki desanya. (*)
*) Nurani Soyomukti merupakan pendiri Institute Demokrasi dan Keberdesaan (INDEK), sedang nyantri di paca-Sarjana UIN Tulungungagung jurusan Akidah dan Filsafat Islam.
**) Isi tulisan di atas menjadi tanggung jawab penulis
***) Karikatur by Rihad Humala/Ketik.co.id
****) Ketentuan pengiriman naskah opini:
- Naskah dikirim ke alamat email redaksi@ketik.co.id.
- Berikan keterangan OPINI di kolom subjek
- Panjang naskah maksimal 800 kata
- Sertakan identitas diri, foto, dan nomor HP
- Hak muat redaksi.(*)