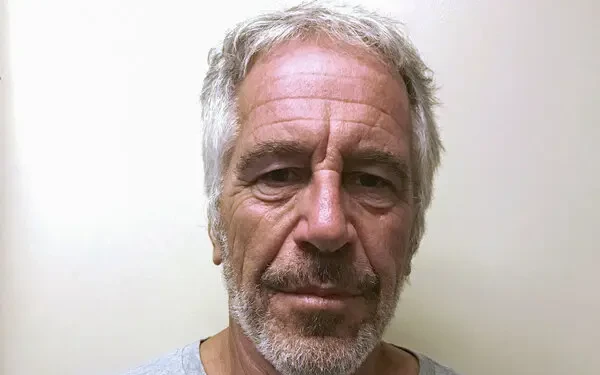KETIK, SURABAYA – Di sebuah desa bernama Selopanggung, Kediri, tembakan dilepaskan. Seorang lelaki yang selama puluhan tahun hidup dalam pelarian, penjara, dan pengasingan, akhirnya roboh di tanah republik yang turut ia perjuangkan kelahirannya. Nama lelaki itu: Tan Malaka.
Tujuh puluh tujuh tahun telah berlalu. Namun kisahnya masih menyisakan tanya—bukan hanya tentang bagaimana ia mati, tetapi juga mengapa seorang tokoh revolusi bisa tersingkir dalam pusaran konflik internal di republik yang masih berusia muda.
Nyaris seluruh usia dewasanya ia habiskan untuk memperjuangkan kemerdekaan dari negeri yang sangat ia cintai. Ironisnya, ia gugur bukan di tangan penjajah asing, tetapi justru di tangan militer yang sedang dalam pembentukn menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Tan Malaka bukan sekadar pejuang bersenjata. Ia adalah guru, organisator, pemikir, sekaligus oposisi ideologis yang keras terhadap kompromi politik yang menurutnya terlalu lunak terhadap Belanda. Dalam sejarah Indonesia, namanya sering muncul di pinggir narasi besar. Padahal jejaknya melintasi benua dan gagasannya melampaui zamannya.
Dari Sumatera Barat ke Panggung Dunia
Tan Malaka lahir dengan nama Ibrahim pada 2 Juni 1897 di Pandam Gadang, Sumatera Barat. Latar Minangkabau membentuk karakter intelektualnya: tradisi berpikir kritis, diskusi, dan keberanian berargumentasi.
Ia memperoleh pendidikan di sekolah guru di Bukittinggi sebelum melanjutkan studi ke Belanda. Pada masa itu, seorang putra bangsa yang masih terjajah bisa menuntut ilmu ke Eropa tentu menjadi kemewahan tersendiri. Namun, Tan Malaka tak larut dalam privilige tersebut.
Di negeri penjajah itulah pergaulan intelektualnya meluas. Ia bersentuhan dengan gagasan sosialisme, pergerakan buruh, serta dinamika politik internasional awal abad ke-20.
Pengalaman di Eropa membentuknya sebagai intelektual revolusioner. Ia tidak hanya memikirkan kemerdekaan Indonesia sebagai pelepasan dari kolonialisme, tetapi juga sebagai proyek pembebasan sosial yang menyeluruh.
Jejaknya kemudian membawanya ke berbagai negara: Filipina, Tiongkok, hingga Uni Soviet. Ia menjadi salah satu aktivis Indonesia pertama yang berkiprah dalam jaringan gerakan internasional. Dalam banyak hal, Tan Malaka adalah revolusioner global jauh sebelum istilah itu populer.
Republik Tanpa Kompromi
Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Tan Malaka melihat momentum itu sebagai awal revolusi total. Ia meyakini bahwa kemerdekaan tidak boleh dinegosiasikan setengah hati.
Pada 1946, ia menggagas Persatuan Perjuangan, sebuah front politik yang menuntut pengakuan kedaulatan 100 persen tanpa kompromi dengan Belanda. Dalam pandangannya, perundingan yang memberi ruang konsesi justru melemahkan posisi republik.
Pandangan ini menempatkannya dalam posisi berbeda dengan arus utama kepemimpinan nasional, termasuk Presiden pertama Indonesia, Sukarno, yang memilih jalur diplomasi sebagai bagian dari strategi mempertahankan eksistensi negara yang masih rapuh.
Perbedaan itu bukan sekadar soal taktik, melainkan soal prinsip. Tan Malaka percaya bahwa revolusi harus berdiri tegak tanpa kompromi. Ia khawatir diplomasi akan menggerus semangat perjuangan dan memberi ruang bagi kembalinya dominasi kolonial dalam bentuk baru.
Sejarah mencatat bahwa perjanjian-perjanjian seperti Linggarjati dan Renville memicu perdebatan keras di kalangan elite republik. Dalam pusaran itulah Tan Malaka kerap diposisikan sebagai oposisi—keras, lantang, dan tak segan mengkritik.
Madilog dan Proyek Pencerahan Bangsa
Jika banyak tokoh revolusi dikenal karena perannya di medan tempur, Tan Malaka juga meninggalkan warisan intelektual yang kuat. Salah satu karya terpentingnya adalah Madilog, ditulis pada 1943 saat ia berada dalam pengasingan.
Madilog—singkatan dari Materialisme, Dialektika, dan Logika—bukan sekadar buku filsafat. Ia adalah proyek pendidikan politik bagi rakyat Indonesia. Tan Malaka mengajak bangsa yang baru merdeka untuk berpikir rasional, ilmiah, dan sistematis.
Menurutnya, bangsa yang terjajah bukan hanya kehilangan kedaulatan politik, tetapi juga terkungkung cara berpikir mistis dan irasional. Kemerdekaan sejati, dalam pandangannya, menuntut revolusi mental berbasis nalar.
Dalam konteks kekinian, gagasan itu terasa relevan. Di tengah derasnya arus informasi, polarisasi, dan emosi politik, seruan untuk berpikir logis dan kritis tetap menemukan gaungnya.
Tan Malaka tidak ingin revolusi berhenti pada simbol dan slogan. Ia menginginkan transformasi kesadaran.
Konflik di Tengah Perang
Tahun 1948–1949 adalah masa paling genting dalam sejarah republik. Agresi militer Belanda, konflik internal, serta perpecahan ideologis menciptakan situasi yang kompleks dan berbahaya.
Dalam situasi perang gerilya, garis antara kawan dan lawan sering kali kabur. Kecurigaan mudah tumbuh, terutama terhadap kelompok atau tokoh yang berbeda pandangan.
Tan Malaka berada dalam posisi rentan. Sebagai tokoh yang vokal dan kritis, ia tidak sepenuhnya berada dalam lingkar kekuasaan resmi republik. Situasi darurat militer mempersempit ruang dialog dan memperbesar risiko salah tafsir.
Pada 21 Februari 1949, ia ditangkap dan kemudian ditembak mati di Kediri. Versi resmi menyebutkan tindakan itu terjadi dalam situasi perang dan berdasarkan keputusan komandan setempat. Namun peristiwa tersebut hingga kini masih menjadi perdebatan sejarah.
Apakah ia menjadi korban kesalahpahaman? Apakah konflik ideologi berperan? Sejarawan, termasuk Harry A. Poeze, telah melakukan riset panjang untuk merekonstruksi peristiwa tersebut dan mengidentifikasi lokasi makamnya.
Apa pun detailnya, fakta tak terbantahkan adalah ini: Tan Malaka gugur bukan di tangan penjajah, melainkan dalam konflik internal republik yang ia perjuangkan.
Dari Terpinggirkan ke Pahlawan Nasional
Sejarah bergerak dengan ironi. Pada masa hidupnya, Tan Malaka lebih sering hidup dalam pelarian dan penjara daripada menikmati pengakuan.
Namun pada 1963, pemerintah menetapkannya sebagai Pahlawan Nasional. Pengakuan itu datang di era Sukarno, yang sebelumnya juga menjadi figur yang berbeda strategi dengannya.
Penetapan tersebut menunjukkan bahwa sejarah tidak selalu hitam-putih. Perbedaan pandangan dalam revolusi tidak serta-merta menghapus kontribusi seseorang terhadap bangsa.
Namun pengakuan formal tidak otomatis menjadikan namanya akrab di ruang publik. Dalam periode tertentu, terutama pada masa Orde Baru, narasi tentang Tan Malaka cenderung redup karena dikaitkan dengan sejarah kiri yang sensitif secara politik.
Baru dalam beberapa dekade terakhir, diskusi tentang Tan Malaka kembali mengemuka—baik di ruang akademik maupun di kalangan generasi muda yang mencari alternatif narasi sejarah.
Pelajaran dari Seorang Oposisi
Kisah Tan Malaka bukan sekadar cerita tentang masa lalu. Ia menyentuh pertanyaan yang terus relevan: bagaimana negara memperlakukan perbedaan pendapat, terutama dalam situasi krisis?
Dalam setiap fase sejarah, republik dihadapkan pada pilihan antara stabilitas dan kebebasan berpendapat. Tan Malaka berdiri di posisi yang menuntut konsistensi prinsip, bahkan ketika itu berisiko membuatnya tersisih.
Ia menunjukkan bahwa revolusi tidak hanya membutuhkan kepemimpinan, tetapi juga kritik. Tanpa kritik, idealisme bisa berubah menjadi kompromi berlebihan. Namun tanpa strategi, idealisme juga bisa berujung pada isolasi.
Di situlah paradoks Tan Malaka: ia adalah simbol keberanian intelektual sekaligus korban dinamika politik yang keras.
Warisan yang Tak Selesai
Tujuh puluh tujuh tahun setelah kematiannya, Indonesia telah menjadi negara demokrasi elektoral dengan institusi yang relatif mapan dibandingkan era revolusi. Namun pertanyaan tentang kualitas demokrasi, ruang oposisi, dan rasionalitas publik tetap menjadi diskursus.
Warisan Tan Malaka mungkin bukan pada model politik yang harus ditiru mentah-mentah, melainkan pada etos berpikir dan keberanian moralnya.
Ia mengingatkan bahwa kemerdekaan bukan hadiah, melainkan proses yang harus terus dirawat. Bahwa berpikir kritis adalah bagian dari cinta pada tanah air. Dan bahwa berbeda pendapat tidak identik dengan pengkhianatan.
Selopanggung, Kediri, mungkin hanya sebuah titik kecil di peta Jawa Timur. Namun pada 21 Februari 1949, titik itu menjadi saksi bahwa revolusi juga menyimpan tragedi internal.
Tan Malaka gugur dalam republik yang ia impikan berdiri tegak tanpa kompromi. Ironi itu membuat namanya tidak pernah benar-benar selesai dibicarakan.
Dan mungkin, di situlah letak relevansinya: Tan Malaka bukan hanya tokoh sejarah. Ia adalah pertanyaan yang terus diajukan kepada bangsa ini—tentang keberanian, konsistensi, dan harga yang harus dibayar oleh sebuah keyakinan. (*)





![Thumbnail Berita - [FOTO] Hangat dan Penuh Keakraban, Ah Pek Kopitiam Malang Jadi Tempat Favorit Kumpul Keluarga dan Sahabat](https://ketik.com/assets/upload/57072026021417515410001454080.webp)