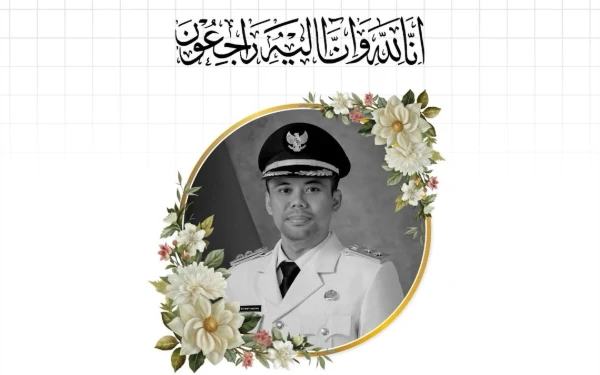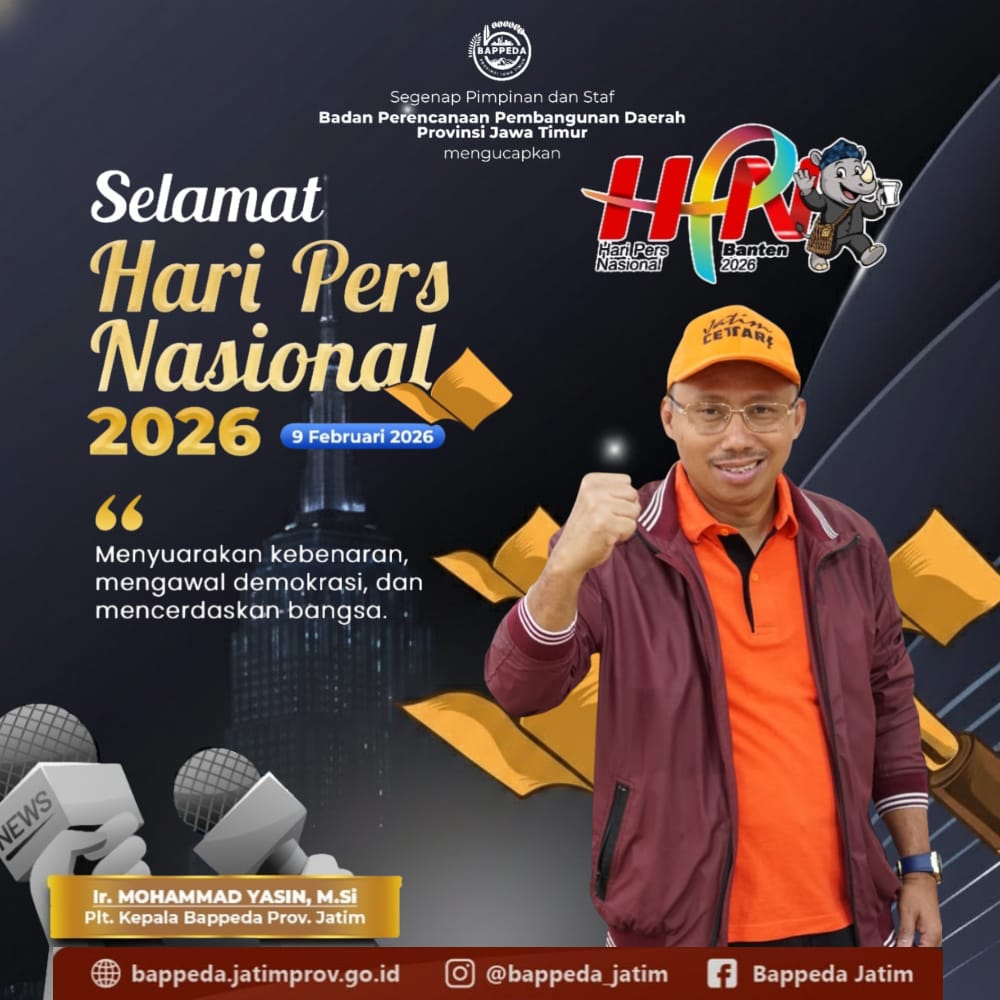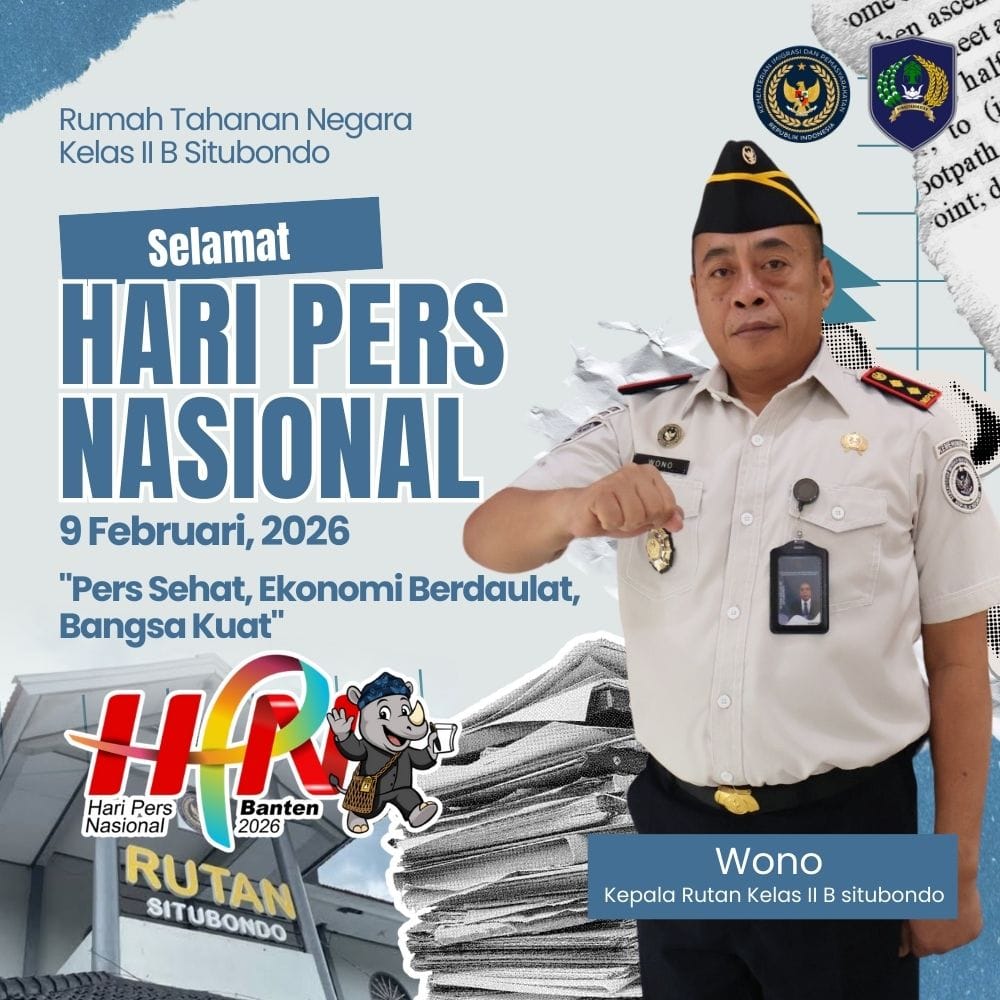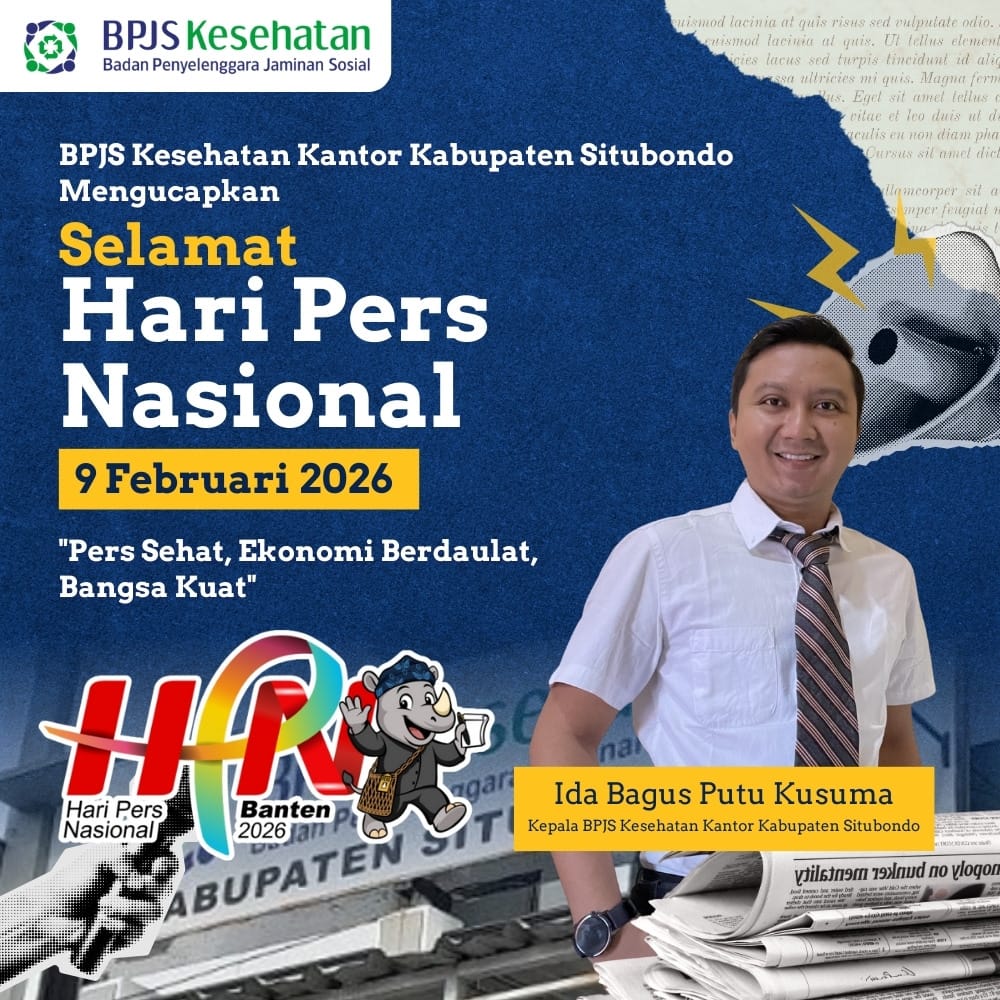Setiap tahun, ratusan ribu mahasiswa diwisuda dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, membawa ijazah sebagai simbol keberhasilan akademik. Namun, tak sedikit dari mereka yang kemudian tersandung realita dunia kerja yang jauh dari ekspektasi kampus.
Gelar akademik yang diperjuangkan selama empat tahun atau lebih tak serta-merta menjadi tiket menuju lapangan kerja yang layak. Maka muncul pertanyaan kritis: apakah perguruan tinggi benar-benar mencetak lulusan yang siap kerja, atau justru memperbanyak jumlah pengangguran terpelajar?
Isu ini bukan sekadar asumsi pesimistis. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun-tahun terakhir menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka tertinggi justru berasal dari lulusan diploma dan sarjana. Artinya, ada sesuatu yang keliru dalam jembatan antara dunia akademik dan dunia profesional.
Perguruan tinggi sering mengklaim bahwa kurikulumnya telah disesuaikan dengan kebutuhan industri. Namun, fakta di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan nyata antara keterampilan lulusan dan tuntutan pasar kerja yang dinamis dan kompetitif.
Banyak mahasiswa dididik untuk menjadi pekerja yang patuh, bukan pemecah masalah. Mereka dilatih untuk menghafal teori, bukan menganalisis realitas. Mahasiswa lebih sibuk mengejar indeks prestasi kumulatif (IPK) tinggi, tetapi tidak memiliki pengalaman kerja, keterampilan komunikasi, kemampuan berpikir kritis, maupun kemampuan beradaptasi yang dibutuhkan dunia profesional. Kurikulum sering kali kaku dan terlepas dari perkembangan zaman—masih fokus pada teori-teori lama yang tak lagi relevan di era disrupsi digital ini.
Belum lagi sistem pendidikan tinggi yang terlalu berorientasi pada output administratif ketimbang outcome nyata. Banyak kampus lebih fokus menyelesaikan akreditasi, memenuhi indikator kinerja, dan mengejar publikasi semata, dibanding menciptakan ekosistem pembelajaran yang membentuk karakter, kompetensi, dan kesiapan kerja mahasiswa. Padahal, tantangan hari ini bukan hanya menghasilkan lulusan yang cerdas secara akademik, tetapi juga resilien, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan zaman.
Ironisnya, narasi “kesiapan kerja” sering digaungkan sebagai jargon pemasaran kampus, bukan sebagai komitmen transformasi sistem pendidikan. Banyak kampus menyematkan label “link and match dengan industri” dalam brosur promosi, tetapi tak memiliki kemitraan nyata dengan dunia usaha. Kegiatan magang pun sering hanya bersifat formalitas tanpa substansi, tidak memberikan pengalaman kerja yang bermakna.
Di sisi lain, industri pun tak sepenuhnya bisa disalahkan. Banyak perusahaan mengeluhkan bahwa lulusan baru tidak memiliki soft skill dasar seperti kemampuan komunikasi, kolaborasi tim, inisiatif, dan etos kerja yang kuat. Beberapa bahkan menganggap bahwa dunia kampus terlalu “terlindung” dan kurang memberikan simulasi situasi riil dunia kerja, termasuk tekanan, konflik, dan ambiguitas dalam pekerjaan.
Realitas ini mengisyaratkan bahwa dunia pendidikan tinggi harus melakukan refleksi mendalam. Sudah saatnya kampus berhenti menjual mimpi bahwa semua lulusan akan langsung bekerja sesuai bidang studinya. Sebaliknya, kampus perlu jujur bahwa dunia kerja tidak selalu adil, kompetitif, dan menuntut daya saing tinggi—dan karena itu, mahasiswa harus dibekali dengan resiliensi, kreativitas, dan kemampuan belajar sepanjang hayat (lifelong learning).
Langkah awalnya bisa dimulai dengan membangun sinergi nyata antara kampus, industri, dan masyarakat. Kolaborasi ini tidak cukup hanya dengan MoU di atas kertas, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk kurikulum adaptif, proyek riil lintas sektor, dosen tamu dari industri, hingga mentor profesional bagi mahasiswa. Program magang wajib pun harus diarahkan pada pengalaman kerja yang autentik dan bukan sekadar pengisi SKS.
Selain itu, pembelajaran harus berpusat pada pengembangan karakter dan kompetensi. Kampus perlu menata ulang metode pembelajarannya agar tidak hanya berbasis ceramah dan ujian, tetapi lebih menekankan pada proyek, riset terapan, dan pembelajaran kontekstual yang melibatkan mahasiswa secara aktif. Evaluasi keberhasilan pendidikan pun tidak hanya diukur dari IPK atau lama studi, tetapi juga dari sejauh mana lulusan mampu bertahan dan berkembang di dunia kerja maupun menciptakan peluang kerja sendiri.
Tentu, tidak semua tanggung jawab bisa dibebankan pada kampus. Pemerintah juga memegang peranan penting untuk merancang kebijakan pendidikan tinggi yang lebih progresif dan responsif terhadap kebutuhan zaman. Begitu pula dunia industri yang harus membuka lebih banyak ruang kerja sama dengan kampus dalam membentuk ekosistem pembelajaran yang saling menguntungkan.
Namun yang paling penting, mahasiswa sendiri harus menyadari bahwa kuliah bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari tantangan yang lebih kompleks. Gelar hanyalah alat, bukan jaminan. Maka, mereka harus proaktif membentuk dirinya: belajar di luar kelas, mencari pengalaman, membangun jejaring, dan terus mengasah diri. Kampus bisa menjadi batu loncatan, tetapi mereka sendirilah yang menentukan arah lompatan.
Akhirnya, kita harus bertanya ulang: apakah kita masih ingin terus membanggakan angka wisuda, atau mulai serius menyiapkan mahasiswa untuk hidup pasca-wisuda? Kampus bukan pabrik ijazah, tetapi seharusnya menjadi ruang tumbuh yang membekali generasi muda menghadapi dunia nyata—apapun bentuknya.
*) Ahmad Afskar N. A merupakan Recruitment Officer PT Permata Indonesia Sejahtera
**) Isi tulisan di atas menjadi tanggung jawab penulis
***) Karikatur by Rihad Humala/Ketik.co.id
****) Ketentuan pengiriman naskah opini:
- Naskah dikirim ke alamat email redaksi@ketik.co.id.
- Berikan keterangan OPINI di kolom subjek
- Panjang naskah maksimal 800 kata
- Sertakan identitas diri, foto,dan nomor HP
- Hak muat redaksi.(*)