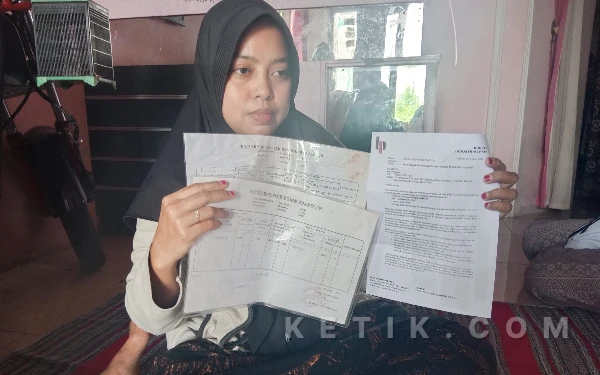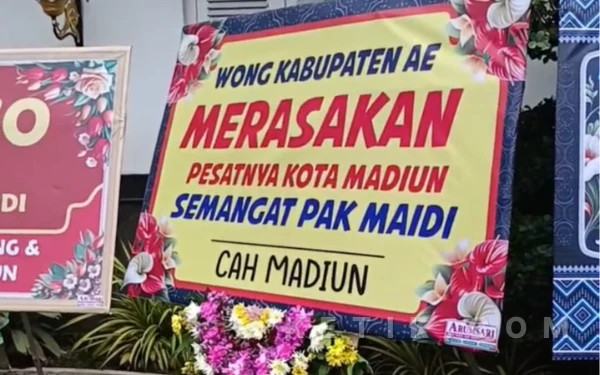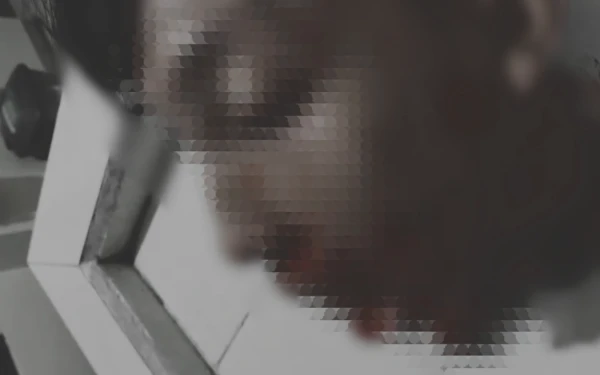Kekuatan moral sepertinya mulai tumbuh. Ia bisa kita lihat dari ungkapan-ungkapan warga yang menyatakan ketidaksukaannya pada kaum yang melakukan penyimpangan moral. Kekuatan moral ada pada masyarakat yang membuat mereka berani melakukan protes terhadap sifat-sifat tamak, sombong, dan egois elit-elitnya maupun kaum yang menyombongkan kekuasaan, posisi, dan jabatan.
Adanya sikap orang-orang mengutuk tindakan yang buruk dan jahat merupakan tanda bahwa moralitas masih terjaga—dan mungkin tumbuh. Ketika ketamakan elit politik dipertontonkan, banyak orang yang memprotesnya. Ketika beberapa bulan lalu elit politik yang seharusnya jadi ‘wakil rakyat’ menaikkan keesejahteraan yang terlalu tinggi dan yang layak disebut sebagai ketamakan, rakyat melakukan kritik dan peringatan. Sifat sombong elit dan tak mau diingatkan oleh rakyat itu bahkan membuat rakyat marah.
Kemarahan ini oleh sebagian kalangan dengan cara yang anarkis. Tapi sesungguhnya di balik itu masih ada moralitas untuk menghalangi tindakan tak bermoral itu sendiri. Moral elit terhadang oleh moralitas orang banyak. Keadilan sebagai ukuran moral kemanusiaan mulai dibicarakan lagi. Ketimpangan sebagai bagian dari moralitas ala kapitalis dan elit penguasa mulai banyak dibicarakan akhir-akhir ini. Ini pertanda bahwa keyakinan masyarakat pada moralitas masih terjaga dan, sekali lagi, sedang tumbuh.
KETIDAKPERCAYAAN PADA MORAL
Ketidakpercayaan pada moral sesungguhnya merupakan hal yang membahayakan. Ketidakpercayaan pada moral sesungguhnya sudah lama terjadi akibat kapitalisme. Dalam kapitalisme, moral telah menjadi bagian dari sesuatu yang diperjual-belikan untuk mencari keuntungan.
Moral, sebagai bagian dari kebudayaan, juga ikut berebut pasar. Moral begitu mudahnya masuk, dalam bentuk kemasan (kitch) yang layak jual: para agamawan dan dakwahnya, juga simbol-simbol dan atribut-atributnya seperti kopyah, kerudung, baju ‘taqwa’, dan berbagai penampakan agamis lainnya tampil di TV, majalah, koran bersamaan dengan ‘propaganda’ iklan.
Anjuran-anjuran moral, termasuk ukuran-ukuran tentang halal dan haram yang ada di dalamnya, muncul seiring dengan upaya mencari keuntungan oleh pihak produser acara TV dan sekaligus bergandengan secara rukun dengan kapitalis (pemilik pabrik yang menghasilkan produksi untuk dijual) yang menginginkan produk-produknya tersebut laku karena dengan menonton iklan-iklan yang terus-menerus menyerang, diharapkan masyarakat akan menjadi konsumen yang setia.
Sedangkan, moralitas yang didakwahkan para penceramah agama juga tampak kosong dan absurd. Penceramah yang menjadi kaya raya dari kegiatan berceramah juga dianggap kontradiksi dengan ajakan-ajakan mereka agar masyarakat ”tidak usah memikirkan dunia” dan agar masyarakat memikirkan akhirat.
Ceramah dengan honor bukan hanya jutaan dan belasan juta tapi juga puluhan juta sekali tampil, jumlah uang yang mungkin bisa didapat oleh buruh tani yang bekerja selama bertahun-tahun, menjadi bahan perbincangan—bahkan cemoohan.
Keluarnya anjuran dari penceramah agama yang seakan sering mengajak masyarakat hidup ”suhud” dan menjauhi upaya menghabiskan waktu ”mengejar dunia” juga tampak absurd ketika para penceramah itu rajin mengkoleksi barang-barang mewah berupa mobil dan motor, juga yang menggunakan waktu luangnya untuk hobi yang sifatnya duniawi.
Ditambah dengan berita tentang liarnya nafsu dan hasrat seks mereka—sebuah nafsu duniawi yang tak bisa dikendalikan oleh meeka—ketika terjadi tindakan pencabulan oleh kiai dan gus terhadap para santri-santrinya. Masyarakat dengan pikiran waras dan nalar kritis memperbincangkan tentang bagaimana orang yang mengajak menekan hawa nafsu duniawi ternyata justru yang paling liar nafsu duniawinya.
Kedekatan para tokoh agama yang sering berceramah dengan para elit politik, misal pujian seorang Gus terhadap tokoh politik yang namanya jeblok di hadapan rakyat yang menghadiri acara pengajian di jamaah rutinannya, juga menambah persepsi tentang bagaimana agawan dan penguasa anti-akyat ternyata adalah sekutu.
Hal itu bahkan oleh sebagian penyuka sastra dan ilmu sejarah dianggap membenarkan apa yang pernah ditulis Kahlil Gibran dalam ”Jiwa-Jiwa Pemberontak”: “Tidakkah kalian tahu bahwa pembesar-pembesar agama dan anak-anak bangsawan yang mewarisi kekayaan orang tuanya sama berkomplot untuk menundukkan, melecehkan dan meneteskan darah di kalbumu?”
MORAL KAPITALISTIK
Bagi orang yang kritis dan muak pada hegemoni moral feudal-borjuis di jaman liberal ini, mereka begitu jijik dengan cekokan moral, moral, moral, dan moral—terutama melihat orang-orang kotor yang tampil dan berdandan sok suci. Hingga ketidakpercayaan pada moral justru kian kuat di masyarakat kapitalis.
Lihatlah kisah ”Moral” dalam cerpen yang ditulis Djenar Maesa Ayu ini: “Kemarin saya melihat moral di etalase sebuah toko. Harganya seribu rupiah. Tapi karena saya tertarik dengan rok kulit mini seharga satu juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah, akhirnya saya memutuskan untuk menunda membeli moral”.
Pada posisi itulah, moral (bahkan agama), seakan berada pada posisi yang sama dengan produk kapitalis, bahkan dalam acara TV ia juga merupakan produk itu sendiri. Produser menghasilkan film-film dakwah, menjual kaset berisi anjuran moral agamis, membuat tayangan ga’ib yang menceritakan kebesaran Tuhan dan keberadaan dunia’ setan’ dan ‘jin’.
Semua itu berjalan sesuai dengan berjalannya mekanisme kerja kapitalisme pasar bebas. Jadi, tak salah jika Djenar menyamakan ‘moral’ dengan ‘rok mini’, yang sama-sama produk yang dipajang di etalase toko: moral-agama dan produk barang sama-sama diperjual-belikan.
Moralitas kapitalisme terbingkai dalam logika pasar dan transaksional. Yang seringkali saya contohkan adalah tentang kapitalisme kesehatan. Keberadaan obat, sebenarnya itu adalah kebutuhan orang sakit agar sembuh ataukah kebutuhan kapitalis farmasi dan penjual obat untuk melihat orang sakit.
Logikanya, kalau kapitalis farmasi ingin mencari keuntungan, maka ia butuh orang yang sakit. Untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, maka akan baik bagi mereka jika banyak orang yang sakit.
Moral kapitalistik dan transaksional juga terjadi dalam politik. Yang terpilih dan menang untuk menduduki jabatan dan kekuasaan adalah mereka yang punya modal besar. Calon-calon adalah yang punya duit untuk membeli kendaraan politik saat mau maju. Meskipun bukan dari partai politik, dengan uang besar kendaraan politik berupa partai politik bisa membuatnya maju lewat partai dan gabungan partai. Lalu mereka juga membeli suara pemilih. Semakin banyak uang yang dikeluarkan, juga kian besar potensi kemenangannya.
Dunia politik bukan lagi urusan siapa memiliki integritas, ideologi, dan jalan merubah Negara untuk melakukan perubahan memperjuangkan nasib rakyat. Dunia politik adalah urusan transaksi antara mereka yang yang punya uang untuk membeli suara.
Di satu sisi rakyat sendiri juga sudah berada pada tingkat kerusakan moral akibat politik transaksional yang meracuni mereka. Rakyat tak lagi tahu bahwa politik adalah jalan meerubah keadaan lewat peerubahan cara pandang terhadap kekuasaan.
Kebanyakan rakyat hanya tahu bahwa politik itu hanyalah nyoblos di TPS. Mereka tidak tahu bahwa potensi politik ada di pikiran dan perasaan mereka, sikap mereka, gerak mereka, suara mereka, dan persatuan atau solidaritas di antara rakyat yang bisa membangun kekuatan sebagai control terhadap sikap dan perilaku politisi dan pejabat publik.
Di luar nyoblos, mereka tidak melihat peluang politik yang ideologis dan berbasis pada penggalangan sumber daya manusia (politisi) yang punya integritas. Mereka hanya melihat bahwa uang adalah satu-satunya alat dan sumberdaya untuk berpolitik!
MEMBANGUN KEPERCAYAAN
Membangun kepercayaan diri bahwa tiap individu merupakan agregat yang bisa jadi potensi perubahan adalah penting. Hal ini bisa dilakukan dengan anjuran moral yang berbobot dengan pengajur moral yang tidak munafik. Berarti ada dua unsur di sini: Sumber ajaran moral dan contoh dari para penganjur moral dan tokoh-tokoh masyarakat.
Misalnya, keberadaan kiai dan gus yang antara yang dikatakan dengan tindakan kesehariannya yang konsisten. Misal, ada gus yang ceramahnya ilmunya kuat, kaya, dan kontekstual, diikuti dengan konsistensinya antara ucapan dan perilaku kesehariannya. Misal ada Gus seperti Gus Bahak yang ilmunya kaya, diundang tidak perlu tariff tinggi, hidupnya sangat sederhana, tidak feodal dan terkesan tidak gila hormat.
Juga Gus dan Kiai yang tidak gila kekuasaan dan kritis pada penguasa. Agamawan yang meengelaborasi ajaran agama dengan menekankan pada anjuran-anjuran berbuat adil, menasehati para penguasa agar tidak gila harta dan tidak korup, juga menggali nilai-nilai keadilan dan keberpihakan pada rakyat banyak. Bukan Kiai atau Gus yang beraninya hanya menonjolkan ajaran yang menyuruh rakyat sabar dan pasrah, tidak kritis, tapi sikapnya pada penguasa, pejabat dan politisi munduk-munduk dan suka menjilat.
Dukungan tokoh agamawan pada pada elit yang di mata masyarakat banyak korup dan sombong justru akan membuat citra agamawan buruk—dan kadang dampaknya membuat orang tidak percaya pada nilai-nilai agama.
Contoh dan keteladanan juga bisa ditunjukkan oleh para pejabat publik dan tokoh masyarakat. Menjalankan amanat rakyat dan menduduki posisi dan jabatan sebagai jalan untuk mengabdi pada rakyat dan mencegah terjadinya nafsu untuk memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi adalah sikap yang bisa memulihkan kepercayaan rakyat. Apalagi adanya pendidikan politik dari para pimpinan masyarakat yang membuat masyarakat semakin paham dan sadar akan negaranya, dan membuat mereka sadar tentang kukuatannya.
Dari kalangan warga masyarakat juga harus muncul orang-orang yang berani bersuara pada kekuasaan, pemerintah, dan otoritas-otoritas. Kumpulan-kumpulan massa dan forum-forum masyarakat dimaksimalkan perannya untuk pemberdayaan, bukan dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk mengambil keuntungan pribadi.
Selama ini banyak organisasi, komunitas, dan forum di masyarakat yang awalnya dibangun lalu tidak berfungsi kecuali hanya jadi pijakan bagi elit-elitnya untuk karier dan memanfaatkan keuntungan ekonomis dan politik. Mendemokratiskan organisasi dan komunitas adalah jalan paling utama untuk membangun kepercayaan yang berbasis pada akar rumput.(*)
*) Nurani Soyomukti adalah penulis dan pegiat literasi, pendiri INDEK (Institute Demokrasi dan Keberdesaan), dan saat ini sedang ‘nyantri’ di Pasca-Sarjana Akidah dan Filsafat Islam Universitas Negeri Tulungagung. Fb Nurani Soyomukti dan IG @soyomuktinurani.
**) Isi tulisan di atas menjadi tanggung jawab penulis
***) Ketentuan pengiriman naskah opini:
- Naskah dikirim ke alamat email redaksi@ketik.com
- Berikan keterangan OPINI di kolom subjek
- Panjang naskah maksimal 800 kata
- Sertakan identitas diri, foto, dan nomor HP
- Hak muat redaksi.(*)