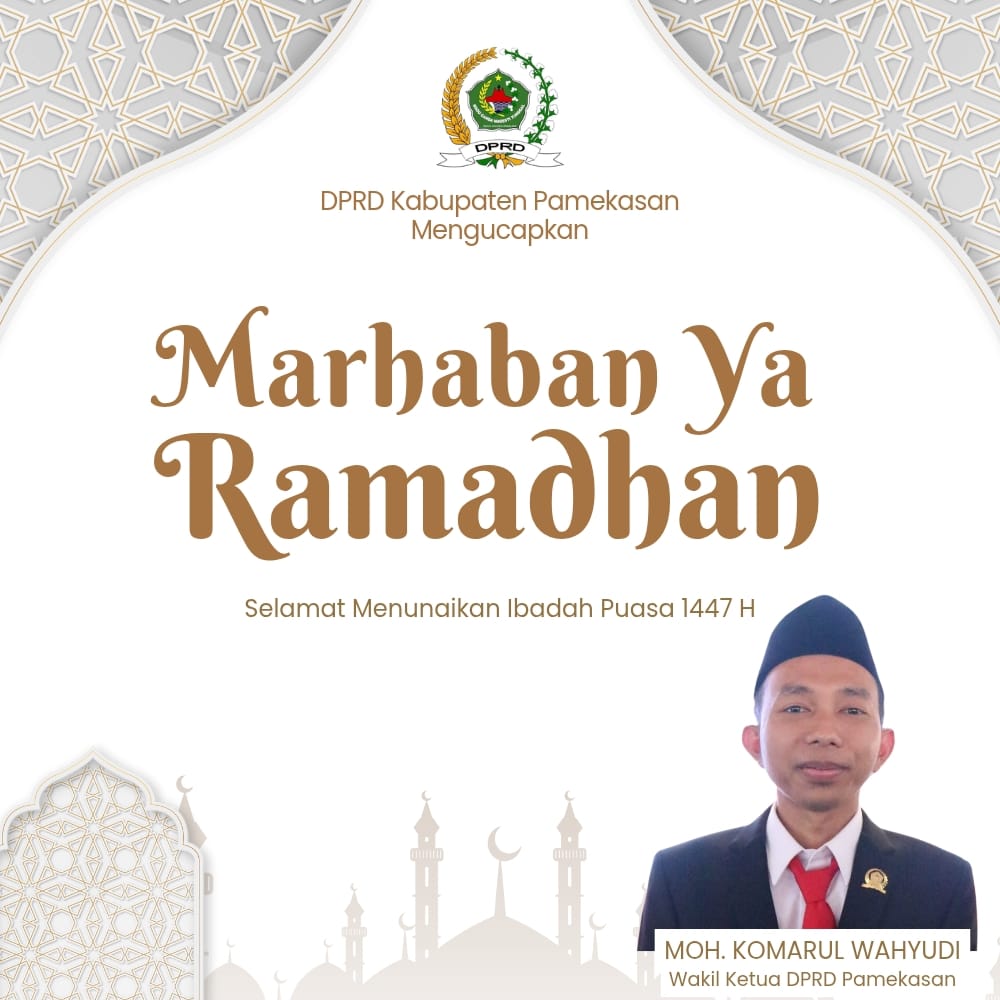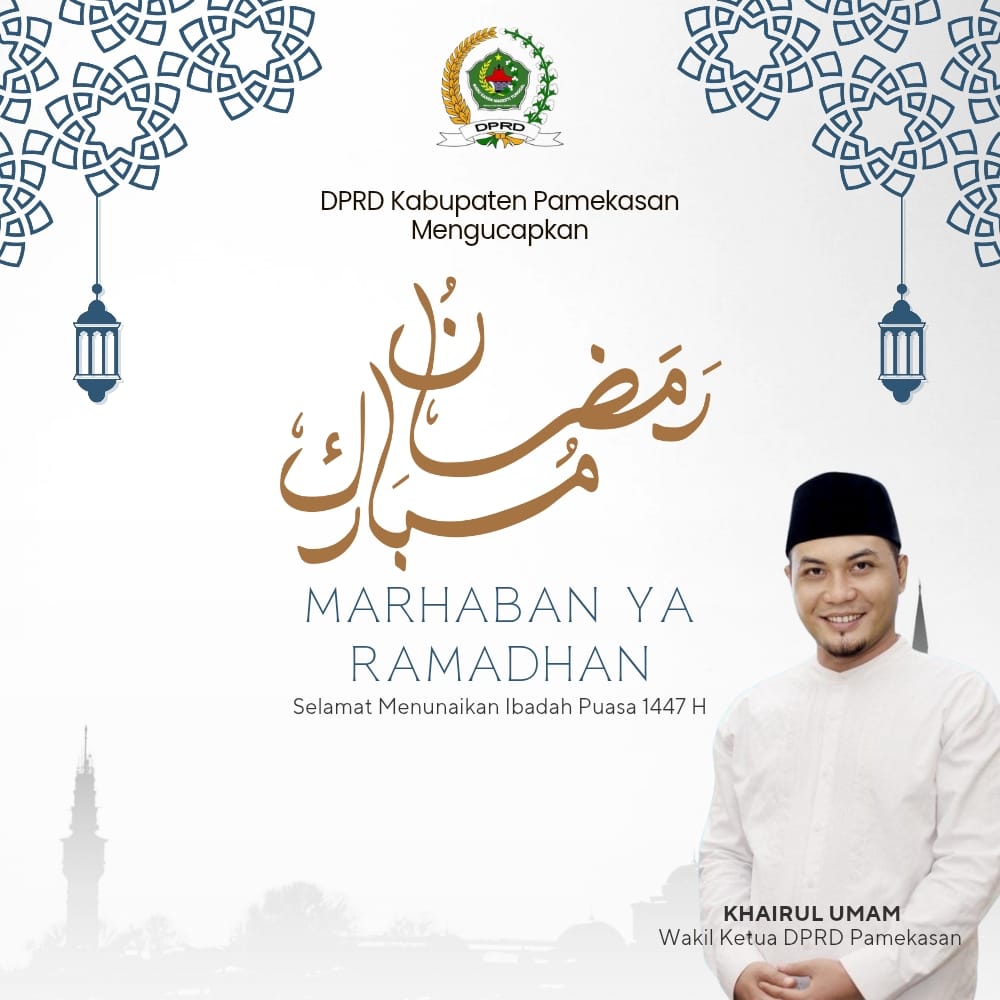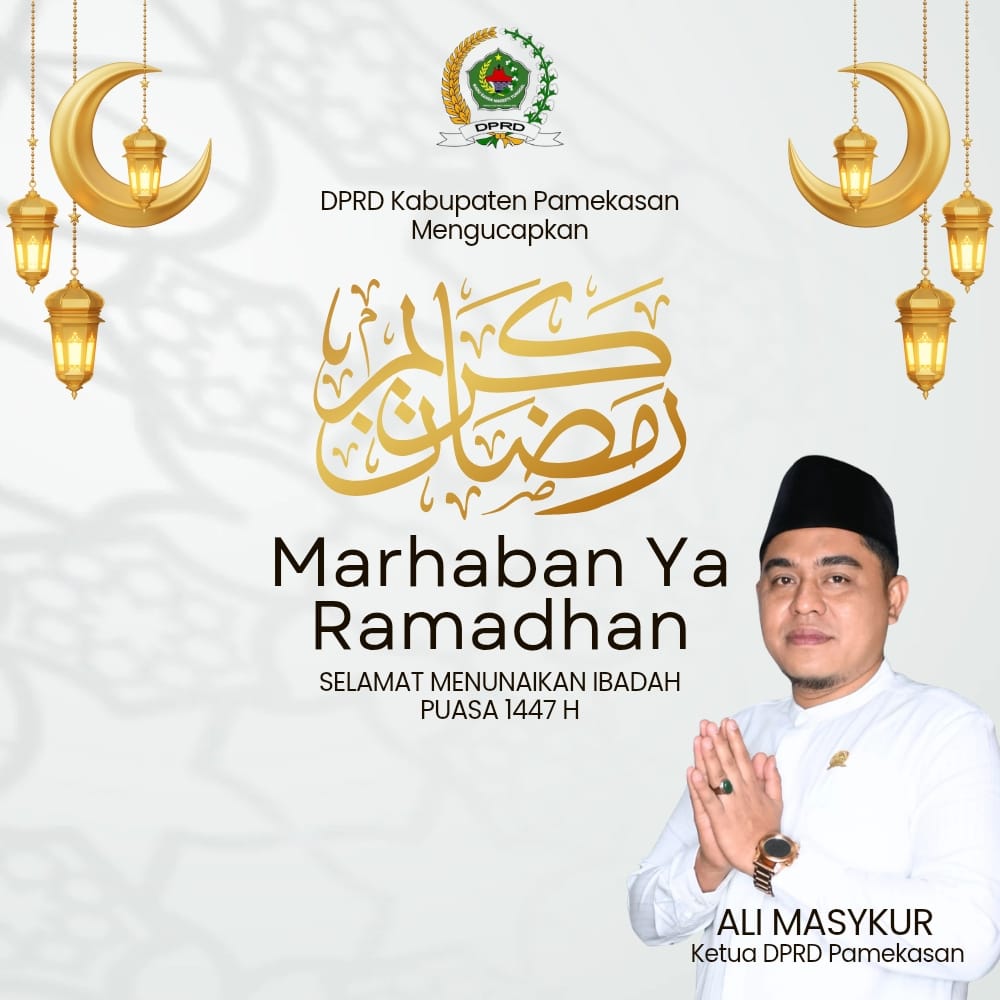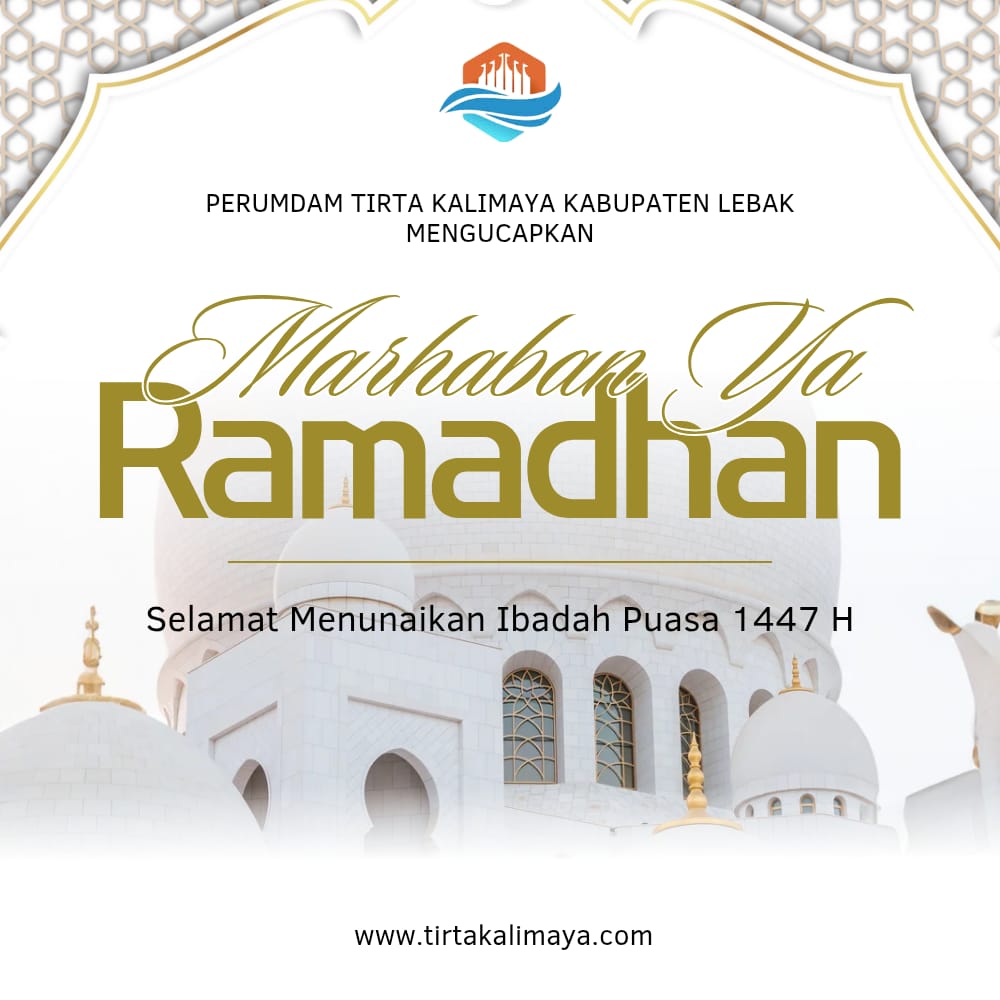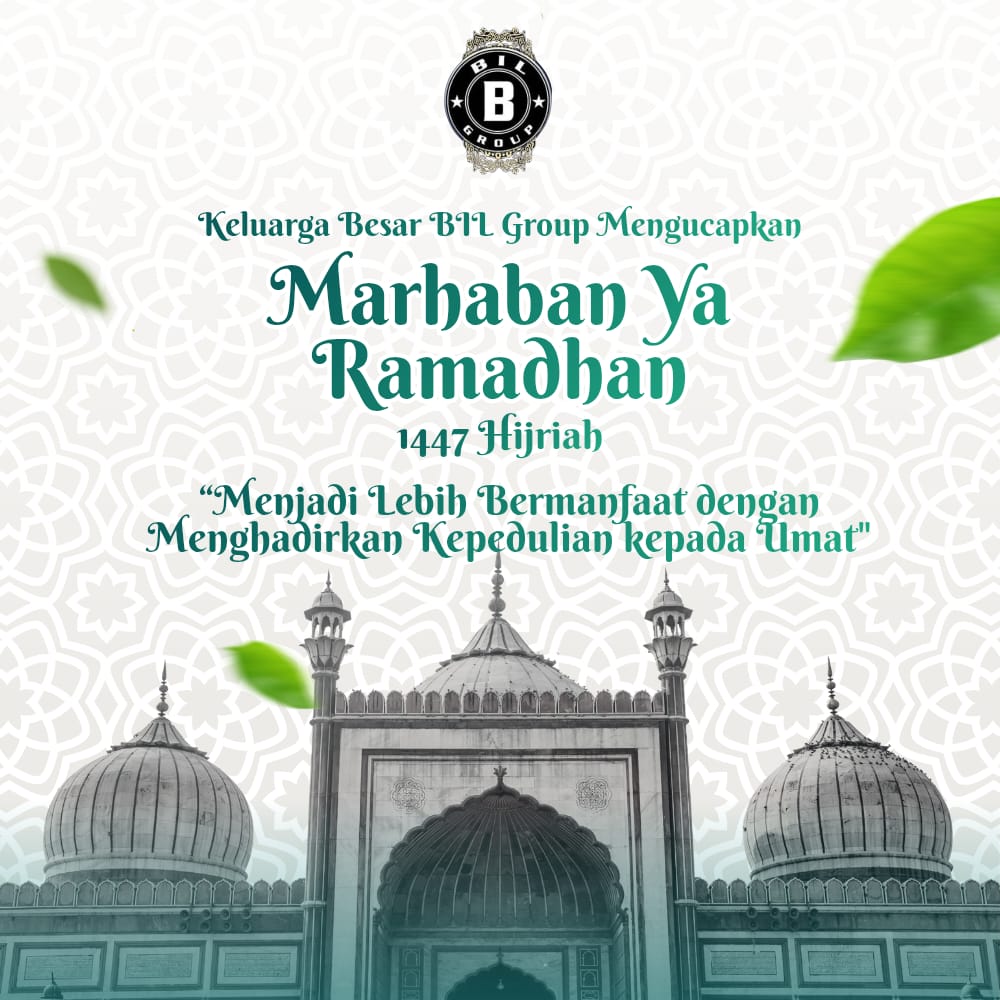Membaca berita bahwa tingkat kegemaran membaca di Kabupaten Trenggalek meningkat dalam tiga tahun terakhir tentu saja membuat pikiran saya dihinggapi harapan. Hati menjadi senang, dengan senyum mengembang. Sebagai penyuka literasi baca-tulis yang kadang-kadang juga ikut membuat kegiatan terkait budaya membaca dan menulis, sepertinya ada perasaan bangga, seakan-akan kita ikut berkontribusi membangun minat baca di Trenggalek.
Perasaan itu boleh dikatakan berlebihan. Tapi perasaan itu sah-sah saja hinggap di kepala dan dada kita. Seakan ada kesimpulan bahwa literasi Trenggalek berkembang baik—khususnya literasi baca-tulis. Itu salah satu jenis literasi, dan masih ada jenis literasi yang lain. Kalau mengikuti alur peta jalan literasi yang dibuat Kementerian Kebudayaan tahun 2017, selain literasi baca-tulis ada literasi lainnya, misalnya literasi numerik, literasi sains, literasi digital, literasi keuangan, literasi budaya dan kewarganegaraan.
Literasi adalah proses pencerdasan manusia atau kelompok manusia (masyarakat) berbasis pada penggunaan ‘litera’ (huruf, aksara) sebagai alat untuk memahami dunia dan meningkatkan pemahaman agar bisa berpartisipasi penuh—“fully participation” menurut UNESCO—dalam kehidupan. Basis kegiatan literasi adalam mendorong masyarakat untuk bisa memiliki banyak kosakata agar dunianya bisa terjelaskan dan terpahami dengan baik. Sehingga, literasi adalah kegiatan membuat manusia yang “illiterate” (buta huruf) menjadi “literate” (melek huruf) agar kemampuan itu bisa digunakan untuk menjelaskan dan menghadapi dunia.
Dulunya yang dimaksud “buta huruf” (illiterate) adalah ketidakmampuan dalam hal membaca dan menulis. Sekarang pengertian tentang “illiterate” bukan lagi ketidakmampuan baca-tulis, melainkan ketidakmampuan dalam hal mengakses informasi untuk menambah wawasan, kecerdasan, pemahaman yang lebih utuh, ketrampilan menggunakan bahasa dan pengetahuan untuk mengatasi suatu permasalahan.
Tak mengherankan jika UNESCO mendefinisikan literasi (literacy) sebagai “ability to identify, understand, interpret, create, communicate and compute, using printed and written materials associated with varying contexts”. Dalam pengertian UNESCO tersebut, literasi melibatkan proses pembelajaran yang bisa membuat individu dapat menggapai tujuannya, mengembangkan pengetahuan dan potensinya, dan membuatnya mampu berpartisipasi secara penuh dalam masyarakatnya secara lebih luas (“enabling individuals to achieve their goals, to develop their knowledge and potential, and to participate fully in their community and wider society”).
Kemampuan membaca adalah dasar yang cukup penting sebab dengan membaca manusia mendapatkan pengetahuan dan informasi. Informasi dan pengetahuan diharapkan bisa merubah cara pandang, bisa memberikan kecakapan teknis, hingga bisa menyadarkan. Budaya MEMBACA itu sendiri, bagi perkembangan anak, adalah cara membuat imajinasi kian terbuka, logika kian berjalan, dan kecerdasan kian bertambah. Ketika setiap kata (baik kata benda konkrit maupun benda abstrak), kalimat, paragraf, dan kumpulan kalimat dalam sebuah artikel dan buku bisa membuat orang menambah wawasan dan pengetahuan. Sebab setiap kata pada dasarnya adalah mewakili benda-benda dan hubungan benda-benda yang konkrit dalam kehidupan. Gabungan kata bisa menjadi pemahaman konseptual yang bisa membuat manusia menjelaskan hubungan-hubungan antara materi dalam kehidupan.
Menambah kosa-kata—serta menggunakannya untuk memahami dunia dan hubungan-hubungan material dalam kehidupan sebagai pilar kemajuan, menggunakannya untuk memperoleh pengetahuan dan bertindak dalam kehidupan, berkomunikasi dan mengatasi masalah—merupakan alur literasi baca-tulis dalam hubungannya dengan proses berpikir serta melakukan aksi mengatasi kesulitan hidup dan mengembangan kehidupan. Di situlah saya kita literasi Baca-Tulis menjadi hal paling dasar, sehingga peta jalan literasi nasional menempatkannya di urutan paling atas (nomor satu) dari tujuh jalan literasi.
Perjalanan Literasi Trenggalek
Kalau saya boleh bilang, peran komunitas dalam membangun gerakan literasi Trenggalek cukup besar. Pengalaman kami menunjukkan bahwa ketika tahun 2010 mulai berdiri forum literasi yang bernama Arisan Sastra yang tiap bulannya para penulis dan peminat budaya membaca dan meenulis berkumpul, pihak pemerintah Kabupaten Trenggalek masih jauh tertinggal. Misalnya, kondisi perpustakaan yang sangat tua dan tidak menarik, tingkat kunjungan yang sepi. Pimpinan perpustakaan juga terkesan bukan orang yang suka buku.
Saya masih ingat ketika kami datang untuk menawarkan kerjasama bedah buku, bahkan istilah “bedah buku” saja tidak paham. Dan memang tidak pernah ada bedah buku yang dilakukan atau difasilitasi oleh pemerintah daerah. Sementara tiap bulan para pegiat literasi Arisan Sastra berkumpul membedah buku, membedah karya, kampanye baca, yang tak jarang didatangi para penulis dari luar kota, perpustakaan daerah sama sekali tidak punya peran kecuali menunggu perpustakaannya didatangi pengunjung.
Demikian juga pemimpin kabupaten (bupati) waktu itu yang tampaknya juga tidak begitu tertarik dengan buku. Seorang penulis sejarah senior, almarhum Kung Hamid Wilis, pernah bercerita bahwa naskah bukunya tentang sejarah Trenggalek pernah ditawarkan pada bupati agar difasilitasi penerbitannya. Tapi keinginannya tidak direspon. Buku itu baru terbit setelah pemerintahan Trenggalek dipimpin oleh bupati dan wakil bupati muda (Emil-Ipin). Memang, mana kedua tokoh ini punya basis literasi yang jauh lebih kuat dibanding para pemimpin sebelumnya yang tergolong tua secara umur dan secara idelogis—juga dengan kepala perpustakaannya yang juga ‘sepuh’.
Sejak dikepalai Pak Ahmadi di era pimpinan bupati dan wakil bupati muda, gebrakan langsung dibuat. Merombak bangunan perpustakaan yang sudah sangat tua direncanakan, lalu segera terealisasi. Bentuk pelayanan diperbaiki. Pengadaan buku ditingkatkan. Membuka masukan dan kerjasama dengan komunitas literasi juga dilakukan. Saya ingat bagaimana saya dan teman-teman komunitas dipanggil untuk diskusi tentang bagaimana membangun kerjasama antara perpustakaan daerah dan gerakan literasi.
Perubahan mulai terasa. Banyak kegiatan yang dilakukan. Mulai bedah buku hingga diskusi. Pembinaan terhadap perpustakaan sekolah, perpustakaan desa, dan taman baca masyarakat juga dilakukan. Meskipun terlambat karena tugas-tugas tersebut sebenarnya sudah termuat dalam Undang-Undang Perpustakaan yang terbit pada tahun 2007 (UU Nomor 43 Tahun 2007) dan Undang-Undang tentang Serah Terima Karya Cetak dan Karya Rekam (Nomor 13 Tahun 2018).
Adanya dorongan dari UU Nomor 13 Tahun 2018 itulah yang membuat, mau tak mau, pihak perpustakaan menjalin kedekatan dengan komunitas-komunitas yang juga menerbitkan buku sebagai karya cetak. Dalam undang-undang tersebut, setiap penerbit wajib menyerahkan 2 (dua) eksemplar dari setiap judul Karya Cetak yang diterbitkan kepada Perpustakaan Nasional dan 1 (satu) eksemplar kepada Perpustakaan Provinsi tempat domisili penerbit. Atas kepentingan itulah perpustakaan harus melakukan komunikasi, setidaknya melakukan sosialisasi atas undang-undang tersebut. Itulah yang kemudian membuat perpustakaan daerah Trenggalek semakin intensif menjalin hubungan dengan para pegiat komunitas dan para penulis.
Perlu Pengarustamaan Literasi
Di Trenggalek, penghargaan terhadap penulis juga sudah ditunjukkan, misalnya, dengan memfasilitasi penerbitan karya-karya lokal atau membeli karya-karya penulis lokal. Hal itu dianggarkan tiap tahunnya. Lomba-lomba seputar literasi dilakukan tiap tahunnya, juga pameran buku yang menggandeng penerbit dari luar kota. Bahkan tahun 2025 ini, kegiatan-kegiatan perpustakaan daerah Trenggalek bisa dikatakan amat padat merayap.
Bedah buku saja dilaksanaan dua kali. Salah satunya menghadirkan penulis cilik yang viral, yaitu De Liang, yang pada usia sebelas tahun sudah menulis 40-an judul buku. Dan ternyata dia adalah anaknya orang Trenggalek. Bedah buku satunya adalah buku karya Misbahus Surur, penulis Trenggalek. Lomba-lomba diselenggarakan untuk memacu kreativitas literasi, termasuk pembukuan karya. Mulai dari workshop menulis konten lokal, workshop pembuatan video tema literasi, sosialisasi naskah kuno, lomba bercerita, lomba membuat video kontek literasi, dan lain-lain.
Ada kegiatan pelatihan-pelatihan computer gratis untuk anak-anak. Ada juga kegiatan pelatihan “membaca cepat” untuk meningkatkan kualitas membaca. Ruang baca perpusda juga menjadi tempat diskusi rutin komunitas literasi. Pelatihan dan peningkatan kapasitas pegiat perpustakaan di desa dan lembaga pendidikan juga dilakukan. Perpustakaan dengan mobil keliling juga dilakukan untuk menajangkau titik-titik keramaian agar akses terhadap bahan bacaan terjangkau.
Meskipun kegiatan-kegiatan literasi yang padat di tahun 2025 ini menggunakan anggaran dari pusat lewat anggaran DAK-Non Fisik, tapi ini harus dilihat sebagai kegigihan semangat para pegawai perpustakaan untuk bagaimana memanfaatkan berbagai sumber biaya untuk kegiatan-kegiatannya. Sebab tidak semua, hanya sedikit, perpustakaan kabupaten/kota yang mendapatkan anggaran DAK-NF tersebut. Di satu sisi, kalau menggunakan anggaran daerah, perpustakaan daerah selalu mendapatkan porsi yang sangat sedikit karena tampaknya literasi masih dianggap kurang penting oleh “penggedog” anggaran.
Politisi di gedung “wakil rakyat” tampaknya perlu lebih menyadari pentingnya pembangunan sumber daya manusia masyarakat lewat jalan literasi. Bukan hanya lebih menekankan pembangunan fisik yang hasilnya lebih “tampak” dibanding pembangunan cara berpikir dan pembangunan budaya kebiasaan membaca dan menulis sebagai pilar kemajuan peradaban. Perubahan berpikir manusia memang tidak tampak, sedangkan membangun “plengsengan” atau jalan lebih jelas terlihat.
Sebenarnya bukan hanya dinas perpustakaan dan arsip yang bisa menjadi “leading sector” pembangunan budaya literasi. Dinas yang membidangi pendidikan dan yang membidangi seni-budaya (dalam hal ini Dikpora dan Dikbudpar). Dinas pendidikan punya tangungjawab meliterasikan masyarakat lewat jalur pendidikan. Dinas Budaya memajukan literasi baca-tulis lewat pengembangan kesenian yang berbasis literasi, yaitu seni-sastra. Sejauh yang saya amati, beberapa tahun belakangan ini, seni-sastra sama sekali tidak diperhatikan oleh dinas pariwisata budaya.
Justru OPD atau dinas-dinas lain ada kalanya memperhatikan upaya membudayakan literasi, terutama baca-tulis. Badan Kesatuan Kebangsaan dan Politik (Kesbangpol), misalnya, pernah mengadakan lomba dan workshop menulis bertema Literasi Politik, lalu karya-karya berupa esai dibukukan. Yang unik lagi, Bakeuda saat dipimpin Pak Yudy Sunarko juga membuat terobosan mengadakan Lomba Menulis Esai bertema pajak dan pendapatan daerah. Kepala badan yang suka baca buku itu waktu itu bahkan beberapa kali menghadirkan baca puisi di acara-acara lembaganya.
Acara festival gagasan yang di-“leading sector”-i oleh Bapeda juga merupakan kegiatan yang nuansa literasinya kuat, termasuk literasi baca tulis. Sebab keterlibatan masyarakat baik individu maupun kelompok untuk menuliskan gagasannya juga merupakan keegiatan bernuansa literasi yang kental. Berpikir, merencanakan usulan kegiatan, menulis, dan menyampaikan gagasan, adalah proses literasi yang mencerdaskan sekaligus partisipatif—memberi ruang pada masyarakat untuk merencanakan sekaligs mengeksekusi kegiatan pembangunan di daerahnya. Kegiatan lomba menulis surat, cerpen dan puisi, bertema lingkungan hidup juga pernah diadakan oleh komunitas yang dibiayai oleh anggaran pemerintah daerah, dalam hal ini dinas yang menangani LH, pada tahun 2018 lalu.
Memang harus diakui, masukan dan dorongan dari pihak luar, terutama lembaga/organisasi atau komunitas literasi sangatlah dibutuhkan pada OPD-OPD. Selain itu, dalam banyak hal sosok pemimpin suatu pemerintah daerah atau kepala-kepala dinaslah yang menentukan sejauh mana budaya literasi berkembang atau tidak. Bukan OPD yang secara tupoksi menangani pemajuan budaya baca-tulis sekalipun, kalau pemimpinnya suka buku dan suka tradisi membaca dan menulis, ternyata kegiatan-kegiatan berbasis literasi akan dilakukan.
Sebenarnya “literacy-mainstreaming” (pengarusutamaan literasi) di jajaran pemerintah daerah Kabupaten Trenggalek bisa dijadikan gerakan oleh Pak Bupati. Sebagai “top leader” ia bisa “mengintervensi” atau melakukan “cipta kondisi” agar OPD-OPD di Trenggalek “aware” akan adanya kebutuhan menyebarkan budaya gemar membaca dan menulis. Sebuah birokrasi yang “melek baca” dan gemar membaca akan menjadi birokrasi yang cerdas dan rasional. Apalagi Bupati Trenggalek juga tergolong sebagai penulis dan daya bacanya juga ada. Sebuah gerakan reformasi birokrasi tentunya tak bisa meninggalkan budaya membaca. (*)
*) Nurani Soyomukti adalah Ketua Komunitas Literasi QLC (Quantum Litera Center), pendiri INDEK (Institute Demokrasi dan Keberdesaan), saat ini sedang “nyantri” di Pasca Sarjana UIN Satu Tulungagung jurusan Akidah Filsafat Islam.
**) Isi tulisan di atas menjadi tanggung jawab penulis
***) Ketentuan pengiriman naskah opini:
- Naskah dikirim ke alamat email redaksi@ketik.com
- Berikan keterangan OPINI di kolom subjek
- Panjang naskah maksimal 800 kata
- Sertakan identitas diri, foto, dan nomor HP
- Hak muat redaksi.(*)