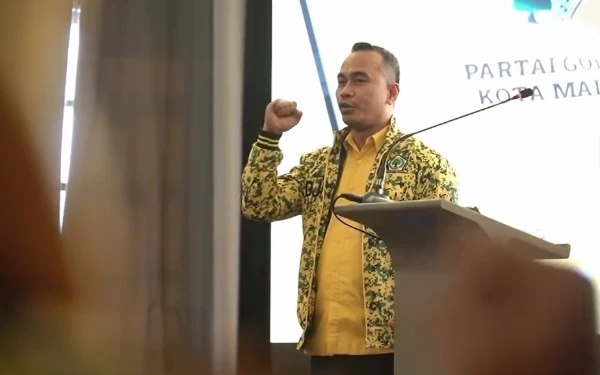Bicara tentang desa, tak hanya sebatas wilayah administrasi semata atau sebuah titik dalam peta, terlebih desa bukan lagi entitas yang tunduk pada birokrasi kabupaten. Desa merupakan ruang hidup, dimana nilai-nilai gotong royong, solidaritas dan tumbuh dan berkembang secara alami.
Diakui atau tidak pasca lahirnya Undang-Undang Desa tahun 2014 silam, mampu merubah wajah desa. Ini bukan soal miliaran rupiah yang mengalir ke Rekening Kas Desa (RKD) setiap tahunnya, dengan harapan mampu membawa kesejahteraan bagi warga desa.
Di balik besarnya dana yang dikelola oleh pemerintah desa setiap tahun, muncul persoalan baru, yakni bagaimana memastikan tata kelola pemerintahan bisa berjalan tak hanya partisipatif, tapi transparan serta berkeadilan.
Di sinilah peran krusial pendamping desa, mereka tak hanya menjadi penghubung antara kebijakan dan masyarakat tapi juga menjadi koneksi antar kekuasaan dan nurani sosial.
Selain itu peran strategis pendamping desa adalah membantu tata kelola, pemberdayaan masyarakat serta pengembangan ekonomi di desa sebagaimana spirit UU Desa.
Keberadaan pendamping desa merupakan mandatori dari UU Desa hal ini dikarenakan negara ingin memastikan bahwa transformasi desa, semula sebagai objek pembangunan, menjadi subjek dalam sistem ketatanegaraan bisa berjalan dengan pengawasan dan dukungan yang memadai.
Namun, realita di lapangan tidaklah semudah membaca regulasi yang ada. Banyak pendamping desa dihadapkan dengan kondisi yang cukup kompleks, mulai dari kapasitas aparatur desa yang beragam, konflik kepentingan lokal, tekanan politik bahkan paling parah adalah menghadapi resistensi terhadap perubahan itu sendiri.
Posisi pendamping desa itu ibarat playmaker dalam sebuah permainan bola, tak hanya bertugas untuk mengendalikan pemain dan menciptakan peluang gol, tapi juga menjadi penghubung serta mampu membaca permainan yang seringkali tidak ada ruang aman bagi mereka.
Oleh karenanya, menjadi penting untuk membaca kembali peran para pendamping sebab peran mereka tak cukup hanya disebut sebagai fasilitator semata. Bagi penulis mereka adalah aktor perubahan sosial yang siap bekerja dengan medan yang penuh tantangan dimana imbalan moral lebih besar daripada material.
Tak hanya itu, pendamping desa memiliki kewajiban untuk memastikan musyawarah warga yang ada di desa berjalan secara inklusif di mana keputusan tidak boleh dikuasai oleh segelintir elit serta memastikan anggaran benar-benar menyentuh warga desa.
Sebab mereka paham bahwa tata kelola pemerintahan desa yang baik bukanlah sebatas diatas kertas semata, namun memiliki makna keadilan sosial dan akuntabilitas moral.
Tentu tujuan dari semua itu adalah tata kelola yang ideal sehingga memerlukan sinergi antar pihak baik dari aparatur itu sendiri, keterlibatan masyarakat serta pendamping yang independen, namun kolaboratif.
Di satu sisi pendamping desa wajib mengingatkan kepala desa dan BPD agar berpegang pada prinsip partisipatif, di sisi lain mereka juga harus berani menegur tanpa harus merusak hubungan sosial yang terjalin, harus bisa menjelaskan regulasi tanpa terlihat menggurui
Yang tak kalah penting, pendamping desa harus bisa menjadi katalis antara kepentingan negara dan kepentingan warga desa. Tentunya, pendamping yang baik tahu kapan harus menjadi penuntun, kapan harus diam, serta kapan harus mendorong agar warga mau berbicara.
Adanya pendamping desa sering kali menjadi cermin dari dari tata kelola pemerintahan itu sendiri. Meski dalam realita, masih banyak pendamping desa dianggap sebagai ancaman bukan sebagai mitra strategis, hal ini dikarenakan desa dikuasai politik patronase yang cukup kental.
Karenanya menjadi pendamping desa itu berada diantara garis tipis idealisme dan realitas sosial. Mereka dituntut menjaga kepercayaan masyarakat tanpa harus terputus dengan pemerintah desa, tak hanya itu mereka juga diharuskan menulis laporan yang objektif tanpa kehilangan empati kepada warga.
Sering kali di sela-sela istirahat, penulis sering mengajak diskusi dengan para pendamping desa, sekedar menanyakan sejauh mana outcome dari kegiatan yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa.
Sebagian dari mereka mampu menjelaskan dampak kegiatan yang sudah dilakukan oleh desa, sebagian lagi mengisahkan tentang pemerintah desa sedikit “bebal” sehingga perlu dilakukan asistensi lebih lanjut dan sebagian lagi hanya diam.
Namun, penulis yakin dibalik diamnya banyak menyimpang kisah, tentang kepala desa yang jujur namun tersisih, tentang seorang perempuan desa yang sedang berjuang di ujung dapur, atau tentang harapan para petani yang sedang belajar literasi digital.
Kini, satu dekade sudah pendamping desa berjalan. Sudah saatnya menata ulang paradigma, pendamping desa tak boleh lagi diposisikan sebagai “pekerja lapangan proyek”. Mereka perlu dilihat dari kacamata sebagai agen penguatan tata kelola pemerintah desa yang strategis.
Sebagaimana diatur dalam Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2015 beserta turunannya, maka pertama yang harus dilakukan adalah mengembalikan makna pendampingan ke ruh semula, di mana pendamping bukan sekedar mengisi formulir atau menandatangani berita acara semata.
Namun diberikan ruang untuk membangun refleksi dan belajar bersama aparatur desa. Kedua, perlu adanya ekosistem kolaboratif agar tata kelola pemerintahan tidak stagnan dalam rutinitas administratif.
Menempatkan pendamping sebagai bagian dari learning organization desa, komunitas pembelajar yang terus memperbaiki diri melalui refleksi dan partisipasi. Dalam kerangka ini, pendamping menjadi katalisator perubahan sosial, bukan sekadar pelaksana kebijakan.
Ketiga, kesejahteraan dan jaminan profesi pendamping desa harus diperhatikan. Bagaimana mungkin seseorang dapat menjaga integritas dan profesionalismenya jika statusnya saja tak pasti dan sering dihantui ketidakjelasan kontrak?.
Status kerja yang lebih stabil, sistem evaluasi berbasis kinerja sosial, dan forum pembelajaran antarpendamping. Dengan demikian, pendamping dapat menjalankan fungsinya secara profesional sekaligus kontekstual.
*) Abdul Mufid merupakan Sekretaris Camat Pujer- Kabupaten Bondowoso
**) Isi tulisan di atas menjadi tanggung jawab penulis
***) Ketentuan pengiriman naskah opini:
- Naskah dikirim ke alamat email redaksi@ketik.com
- Berikan keterangan OPINI di kolom subjek
- Panjang naskah maksimal 800 kata
- Sertakan identitas diri, foto, dan nomor HP
- Hak muat redaksi.(*)