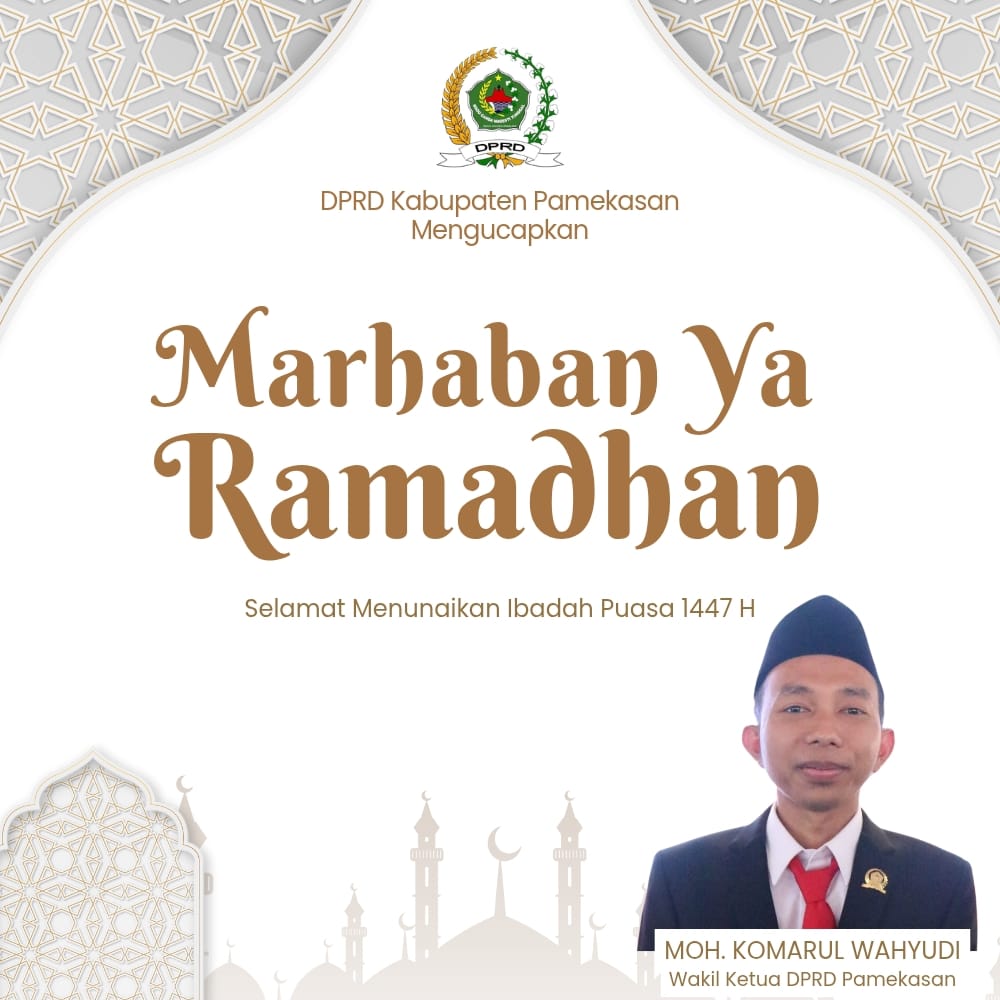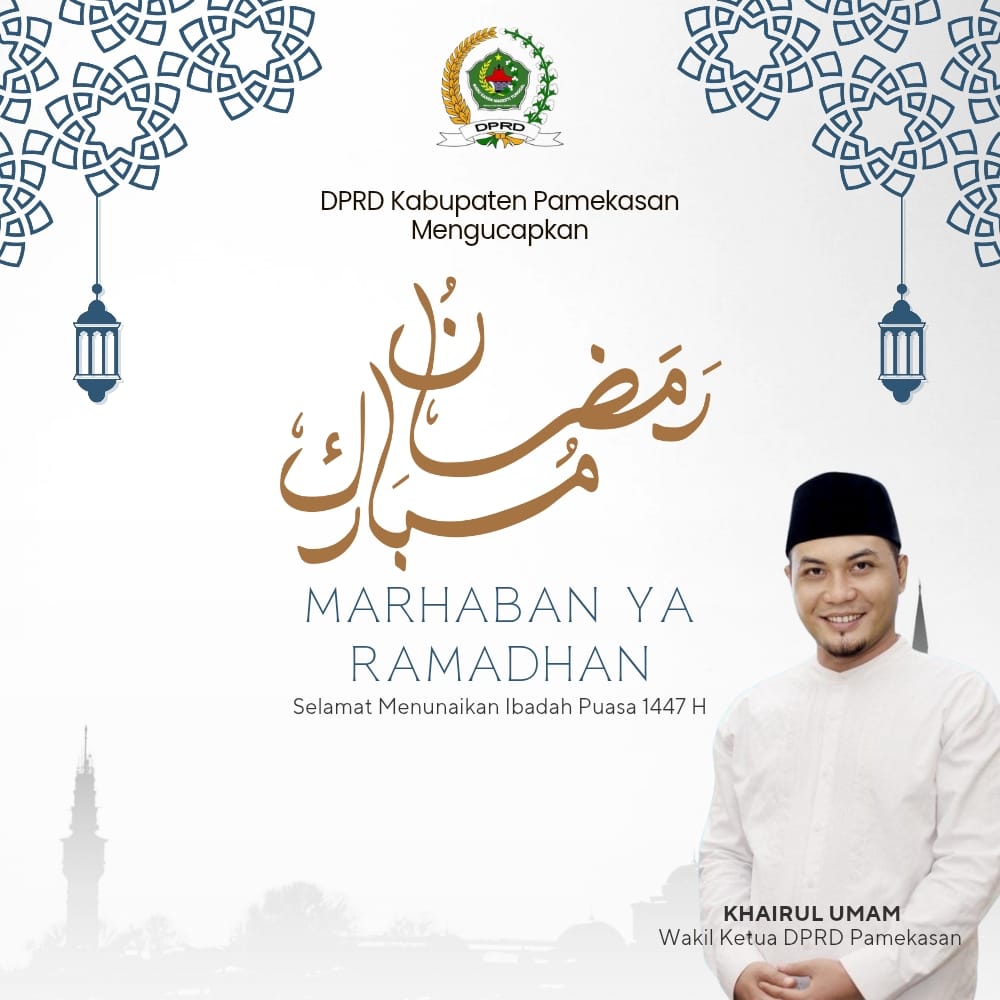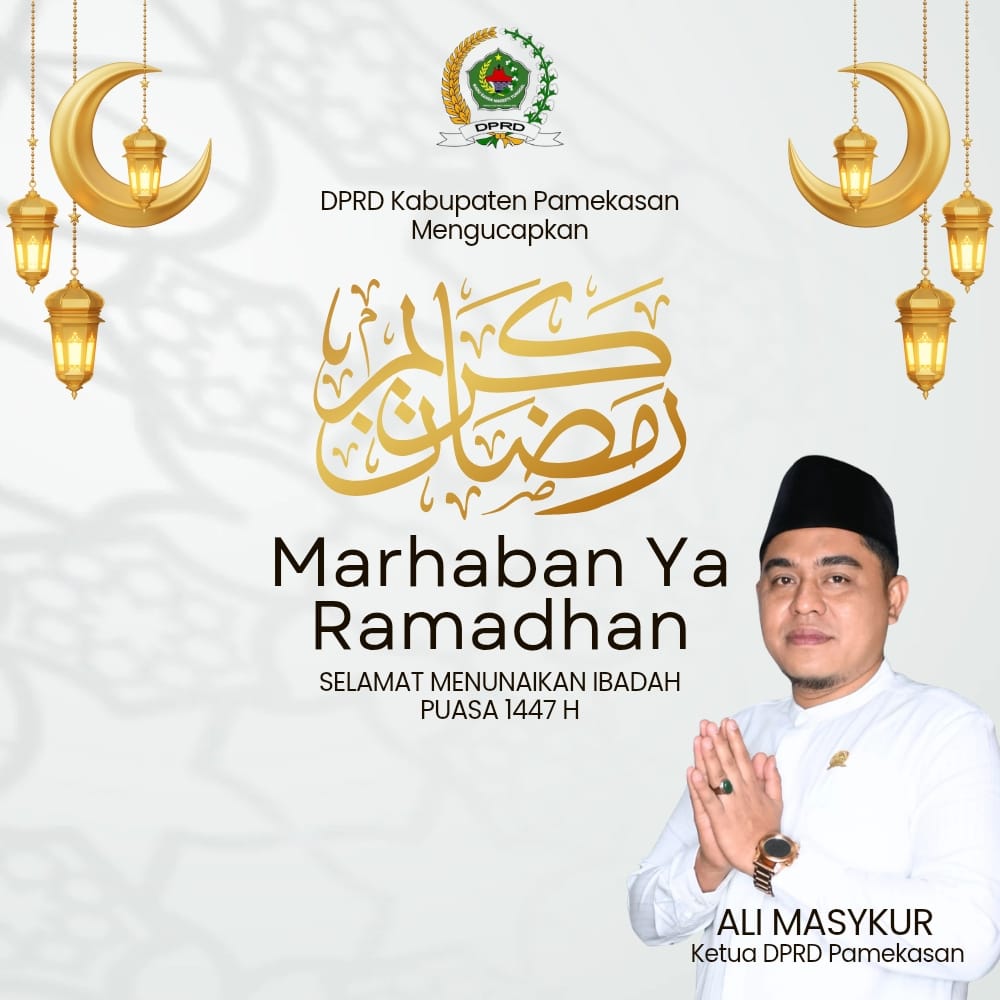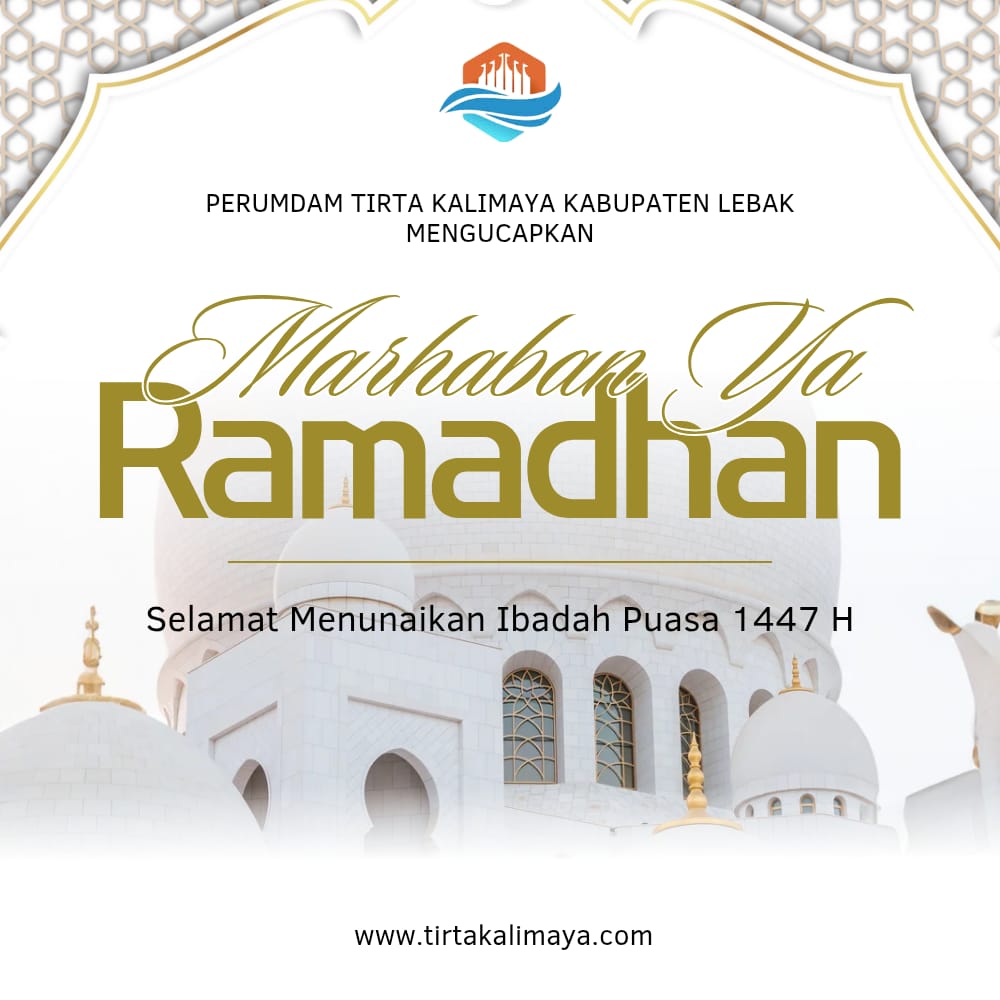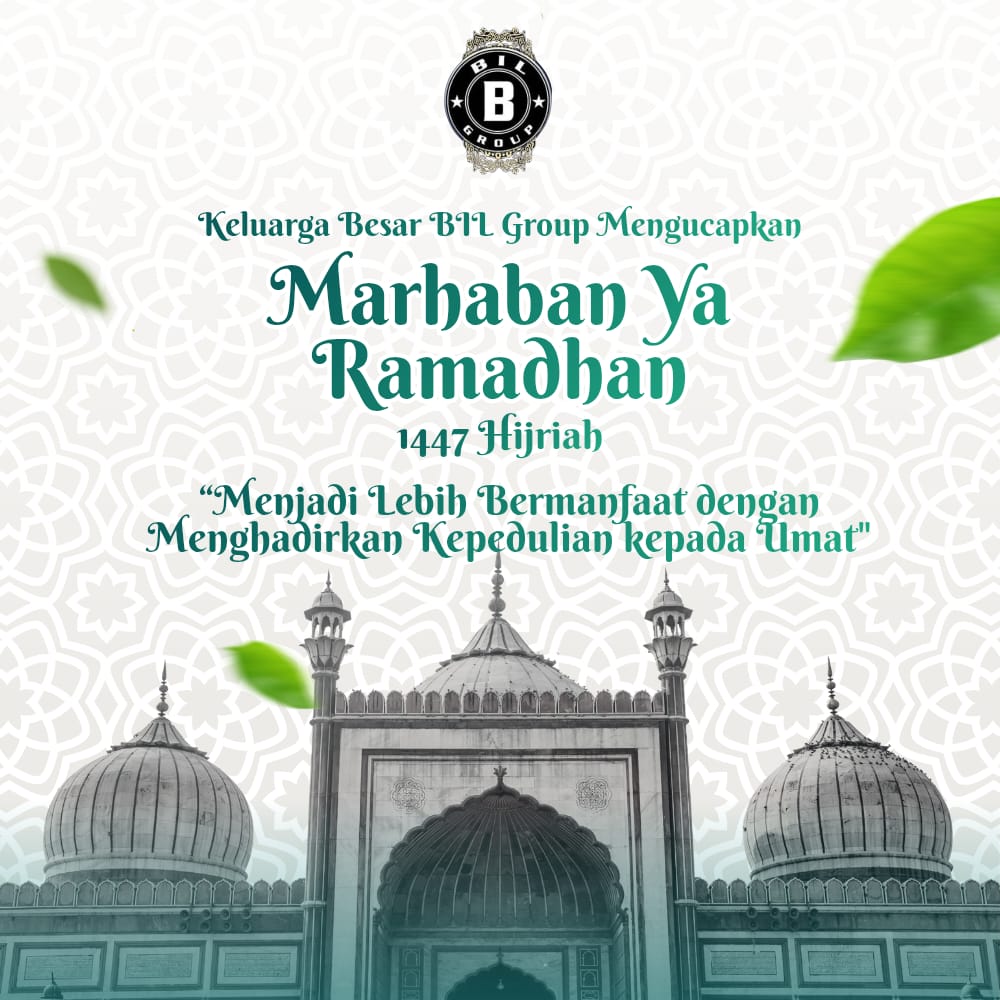Oleh : M..Dwi Cahyono*
Sedari masa amat lampau, Semeru merupakan gunung berapi aktif (vulcan). Erupsinya tercatat pertama kali pada November 1818, yang menjadi "titik awal" dokumentasi aktivitas vulkanik Semeru. Setelah itu, tercatat banyak letusan lainnya, utamanya pasca 1940-an. Tercatat letusan berikutnya terjadi antara tahun 1829– 1878, tapi sayang tidak terdeskripsikan secara detail.
Sejak tahun 1941-1942, catatan mengenai erupsi terdokumentasi dengan lebih baik. Aktivitas vulkanik berikut berturut-turut terjadi antara tahun 1945 - 1960, yang bahkan berlangsung hampir setiap tahun. Antara tahun 1967 - 1990-an tercatat serangkaian erupsi kecil hingga sedang. Letusan yang terbilang besar terjadi tahun 1994. Menyusul kemudian terjadi banyak erupsi vulkanik pasca 1994 hingga teraktual terjadi pada Rabu, 19 November 2025 lalu dan erupsi-erupsi susulannya hingga pada saat ini.
Meski belum didapati catatan mengenai letusan Semeru pada sebelum tahun 1818, bukan berarti sebelum tahun itu Semeru tak melakukan aktivitas vulkanik. Sangat mungkin gunung api purba, yang sekaligus merupakan gunung suci (holy mountain) dan gunung tertinggi di Jawa ini, berulang kali meletus pada masa Hindu-Buddha.
Berbeda dengan belasan aktivitas vulkanik Gunung Kampud, nama arkais dari Gunung Kelud, yang tercatat dalam kitab gancaran "Pararaton" dan sekali letusan di kakawin "Nagarakretagama", erupsi Mahameru belum diperoleh catatannya pada susastra kuna Jawa. Ada sedikit gambaran, yakni tentang kaldera Semeru secara simbolik hadir sebagai kawah (jedi) "Candragoh-mukha (bahasa Jawa Baru "Condrodimuko"), yakni kawah untuk merebus orang-orang yang berdosa di neraka, sebagaimana terpahat pada relief cerita "Kunjarakarnadharmmakatana" di teras I -- bersambung ke pelipit bawah teras II Candi Jajaghu (Jago) era Singhasari-Majapahit (XIII- XIV Masehi).
Arah aliran lava kala itu tak diketahui dengan pasti. Namun, bila menilik karakter bebatuan di hulu Kali Amprong dan Lesti, ada aliran lava yang mengarah ke lereng barat Seneru menuju wilayah Malang Timur.
Sejak dulu, paparan dampak vulkanik Semeru memang lebih kuat menuju ke ke arah selatan, baik dalam wilayah Malang Selatan ataupun Lumajang Selatan. Di wilayah Kabupaten Malang, area yang banyak terpapar dampak vulkanik Semeru meliputi Kecamatan Dampit, Tirtoyudo, serta Ampelgading.
Wilayah Ampelgading, kecamatan paling timur di Kabupaten Malang dan berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Lumajang sisi selatan, adalah areal yang paling banyak terkena dampak vulkanik Semeru. Karenanya, ikhtiar mitigasi bencana vulkanik, termasuk mitigasi bencana secara "religio-magis", terjejaki bukti arkeologisnya di daerah Ampelgading. Salah satu di antaranya berupa arca 'Ganesha berdiri' asal lereng selatan Semeru.
Arca Ganesha Berdiri Asal Lereng Selatan Semeru
Salah satu benda cagar budaya (BCB) -yang pada tahun 2024 lampau direpatriasi dari Belanda ke Indonesia- adalah arca Ganesha utuh dan artistik dalam posisi berdiri. Arca batu andesit berwarna abu-abu keputihan ini lebih dikenal dengan sebutan "Ganesha Semeru Selatan".
Dalam dokumen tertulis bahwa arca ini ditemukan pada medio Agustus 1836 di Petoeng Ombo Ampelgading, lereng selatan Semeru. Arca ini ditemukan Residen Pasuruan, Johan Frederick Walvaren van Nes, saat melakukan pendakian dari arah selatan Semeru.
Tujuh tahun kemudian, pada 1843, arca yang amat bagus ini dibawa ke Belanda, dan dikontribusikan ke Stichting NMVW (Nationaal Museum Van Werelcultiren) di Leiden, dengan no. inventaris RV 1403-1789. Selama hampir dua abad lamanya arca Ganesha ini berada di Belanda dan baru 2024 lalu dikembalikan lagi ke negeri asalnya. Kini, arca tersebut berada di Museum Nasional Jakarta.
Apabila menilik gaya pemahatannya, arca Ganesha dengan tinggi 159 sentimeter ini memperlihatkan pengaruh gaya ikonografi Phala, yaitu gaya ikonografi asal India (sekitar Tekuk Benggala). Di Jawa, gaya ini banyak ditemui dalam dua periode, era Mataram dan Singhasari. Sangat mungkin arca ini berasal dari era Singhasari (abad XIII Masehi). Jika benar demikian, arca Ganesha berdiri dari lereng selatan Semeru ini menjadi salah satu di antara dua buah arca Ganesha berdiri era Singhasari, selain arca Ganesha berdiri di Karangkates.
Petung Ombo yang terletak di lereng selatan Gunung Semeru, tempat penemuan arca ini pada tahun 1836, terhitung sejak tahun 1948 dijadikan sebagai "Desa Darurat", dan diubah namanya dari "Petung Ombo" menjadi "Simodjajan" di wilayah Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang.
Ada pendapat unsur sebutan "simo" pada nama Simojayan ini untuk mengabadikan peristiwa sejarah era Perang Kemerdekaan RI (1945-1948), di mana Petung Ombo pernah menjadi markas Batalyon Macan Kumbang. Kata "simo" bersinonim arti dengan "macan".
Pendapat lainnya, unsur nama "simo" berkenaan dengan status desa ini pada masa Hindu-Buddha, yang boleh jadi berstatus "desa perdikan (sima). Hal ini terkait dengan adanya candi Hindu di tempat ini.
Selanjutnya, pada 24 Sep-tember 1966 staus Simojayan direvitalisasikan dari "desa darurat" menjadi "desa resmi" oleh Bupati Malang Moch. Sunan SH.
Desa Simojayan terdiri empat dusun, yaitu: Dusun Simojayan Krajan -konon pedukuhan Petung Ombo dan Jampung Ledok, Dusun Putukrejo -konon Pedukuhan Lemah Duwur, Dusun Sukodono -konon pedukuhan Sumbersari, dan Dusun Kalirejo -konon pedukuhan Kali Manjing. Sebagai daerah yang berada di lereng Semeru, tanah Desa Simojayan berwarna kehitaman.
Tanah berwarna kehitaman ini banyak dipengaruhi oleh aktivitas gu-nung berapi, yang menghasilkan jenis tanah seperti andosol dan aluvial kelabu kehitaman yang kaya mineral. Abu dan lahar yang telah melapuk selama bertahun-tahun menjadikan tanah di daerah ini sangat cocok untuk pertanian dan perkebunan.
Arca Ganesha di lereng Semeru memiliki empat tangan (caturbhyuja), dengan rincian: tangan kiri belakang memegang tasbih (aksamala), tangan kanan belakang menggenggam kapak (parasu), dan kedua tangan depan memegang mangkuk berupa belahan tengkorak sisi muka (kapala).
Mahkota yang dikenakan berupa Jathamakuta, yaitu rambut yang disanggul tiga tingkat dan diakhiri dengan tusuk konde di kemuncaknya. Ornamentasi yang menghiasi pengikat sanggul antara lain berupa tengkorak (kapala). Ornamen kapala juga hadir sebagai anting-anting (kapala kundala), kelat bahu (keyura), dan hadir di sisi depan cawatnya. Hal ini menjadi petunjuk adanya pengaruh Tantra.
Kapala yang dipadu dengan bulan sabit menjadi tengkorak di atas bulan sabit (dalam bahasa Sanskreta "ardhacandrakapala") terdapat di sanggul tingkat pertama sisi depan, merupakan atribut khas bahwa dirinya adalah putera dari Dewa Siwa. Pasalnya, ardhacandrakapala juga menjadi atribut khas (laksana) Dewa Siwa.
Arca berwujud antropomorfis, yakni setengah manusia setengah binatang (gajah), memiliki kepala gajah, lengkap dengan belalainya yang mengarah kiri ke arah mangkok kapala yang dipegangnya. Sebagaimana lazimnya gajah, telinganya pun lebar. Tubuh, sepasang tangan dan kakinya berunsurkan manusia (antrophos), hanya saja tapak kaki dan jemarinya lebih me- nyerupai gajah. Sementara, telapak dan jari tangan mirip dengan manusia.
Tubuh bagian atas bertelanjang dada, hanya mengenakan aksesoris berupa tali kendit serta tali kasta (upawita) -- berupa naga yang menyelempang dan melingkar tubuh dari pundak kiri kerah pinggang kanan. Kedua tangannya mengenakan aksesoris kelat bahu (keyura) di ruas tangan atas dan gelang (kankana) di ruas tangan bawah (pada sekitar pergelangan tangan). Gelang kaki (binggel) dikenakan di sekitar pergelangan kaki.
Tubuh bagian bawah mengenakan kain panjang (ken) hingga sebatas mata kaki, dilengkapi dengan sampur yang diikatkan di kanan kiri pinggang, menyerupai jalinan pita kupu-kupu, dan sisanya digeraikan ke bawah sejajar kanan-kiri kaki. Sebagian sampur dilengkungkan tiga tingkat di depan paha, dan disertai dengan sepasang uncal yang terjulur di sisi depan kaki.
Posisi kain pada bagian bawah dari perutnya yang gendut (lambodhara) diperkuat dengan sabuk ikatan (bandha). Arca berdiri di permukaan atas singgasana yang berbentuk teratai merah merekah (padmasana).
Fungsi Religio-Magis "Vicneswara" Dewa Ganesha
Tentu ada pertimbangan khusus untuk menempatkan arca Ganesha berukuruan besar -apalagi dengan posisi berdiri. Sebagaimana halnya dengan arca Ganesha berdiri di Karangkates yang berada di tepian jeram curam Kali Lahor, yang memiliki fungsi religio-magis penolak bahaya, arca Ganesha berdiri di lereng selatan gunung Semeru pun sangatlah mungkin juga berfungsi protektorik.
Arca Ganesha yang mulanya berada di punden Jimbe yaitu pertemuan (tempuran) Kali Jimbe dan Brantas juga berfungsi serupa. Fungsi yang sama juga dimiliki Arca Ganesha di Candi Angka Tahun pada kompleks Candi Penataran di lembah lembah sisi barat gunung api Kelud. Arca Gaja Singha -yang berasal dari lembah Brantas sekitar tempuran Kali Gampeng serta Kali Warujayeng dengan Brantas- juga berfungsi serupa, yaitu sebagai media religio-magis buat menolak, meredam atau paling tidak meminimalkan bahaya.
Dalam agama Hindu, fungsi khusus Ganesha demikian dinamai dalam bahasa Sanskreta dengan "Vicnesvara". Vicnesvara terdiri dari dua kata: vighna (rintangan, halangan, bahaya) dan ishvara (penguasa atau tuan). Jadi, sebutan "Vighneshvara" berarti Penguasa Rintangan, Dewa Penguasa Rintangan, atau dapat juga diartikan sebagai penolak bahaya.
Sebutan lain untuk fungsinya yang demikian dalam bahasa Sanskerta adalah "Vighnaharta", yang berarti Penghancur Rintangan. Kata "harta" berarti penghancur atau penghapus. fungsi Ganesha ini dapat juga disebut sebagai "Vighnarāja", yang berarti Raja Rintangan.
Dalam tradisi Hindu, Ganesha dipuja pada awal upacara atau pekerjaan baru dengan tujuan untuk memohon agar segala rintangan atau bahaya dapat disingkirkan.
Terkait dengan fungsi protektorik Ganesha untuk menyingkirkan bahaya, penempatan arca Ganesha berukuran besar dan dengan posisi berdiri di lereng selatan gunung berapi Semeru adalah untuk menyingkirkan bahaya yang bisa terjadi lantaran erupsi Semeru. Terlebih lagi, aliran magma, lahar dingin, awan panas, debu, dan pasir cenderung mengarah ke lereng dan lembah di selatan gunung api aktif ini, antara lain ke daerah Ampel Gading dan di sekitarnya.
Upaya menghindarkan dampak erupsi Semeru penting artinya, karena di lereng selatan Semeru dulu terdapat beberapa tempat suci (candi), mandala utama seperti Kukup -kini berada di area perkebunan Jawar, mandala di Gerbo, mandala Pasrujambe di Lumajang Selatan, Umpak Songo di lereng selatan atas Semeru, dan lain-lain.
Mandala di Kukup -yang diberitakan oleh kitab Tantu Panggelaran- adalah satu di antara "Caturbhasmamandala (empat mandala utama)" pada era Majapahit, yang berfungsi sebagai "mandalakadewagurwan" pada abad XV Masehi. Mandala utama lain adalah Mandala Pajarakan dan Lesan, yang mewakili arah timur atau utara, dan Mandala Kasturi -di wilayah Turen- yang mewakili arah barat.
Ganesha berdiri dari situs Petung Ombo (kini Simojayan) di wilayah Kecamatan Ampelgading, berdekatan dengan Mandala Kukup, yang kini berada di areal perkebunan Jawar, lereng selatan Gunung Widodaren. Selain itu, arca ini terletak tak jauh dari situs Jurangpeteng di Desa Taman Kastruan, tempat ditemukannya miniatur Candi Ampelgading A dan B,
Selain itu, di wilayah Dampit Selatan, yaitu di areal perkebunan Gerbo, terdapat mandala lainnya. Hal ini memberi gambaran bahwa di wilayah Ampelgading dan Dampit pada masa Majapahit menjadi area hunian, bahkan sentra pembelajaran yang penting. Karena pentingnya wilayah ini, perlu adanya pengamanan dari kemungkinan terpapar aktivitas vulkanik Mahameru. Untuk keperluan itu, ikhtiar mitigatif, termasuk mitigasi bencana secara "religio-magis", antara lain dengan menjadikan arca Ganesha tersebut sebagai media protektorik" menjadi penting artinya. (*)
*Sejarawan dan Dosen