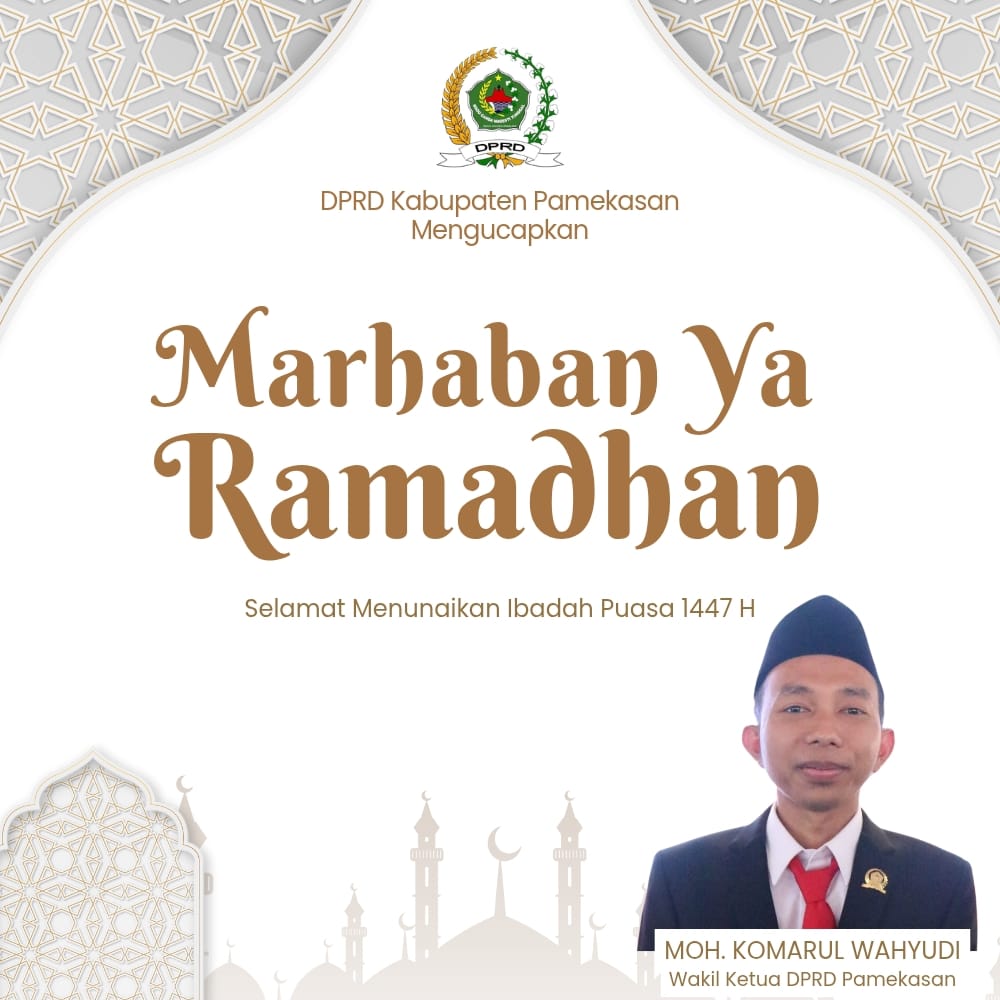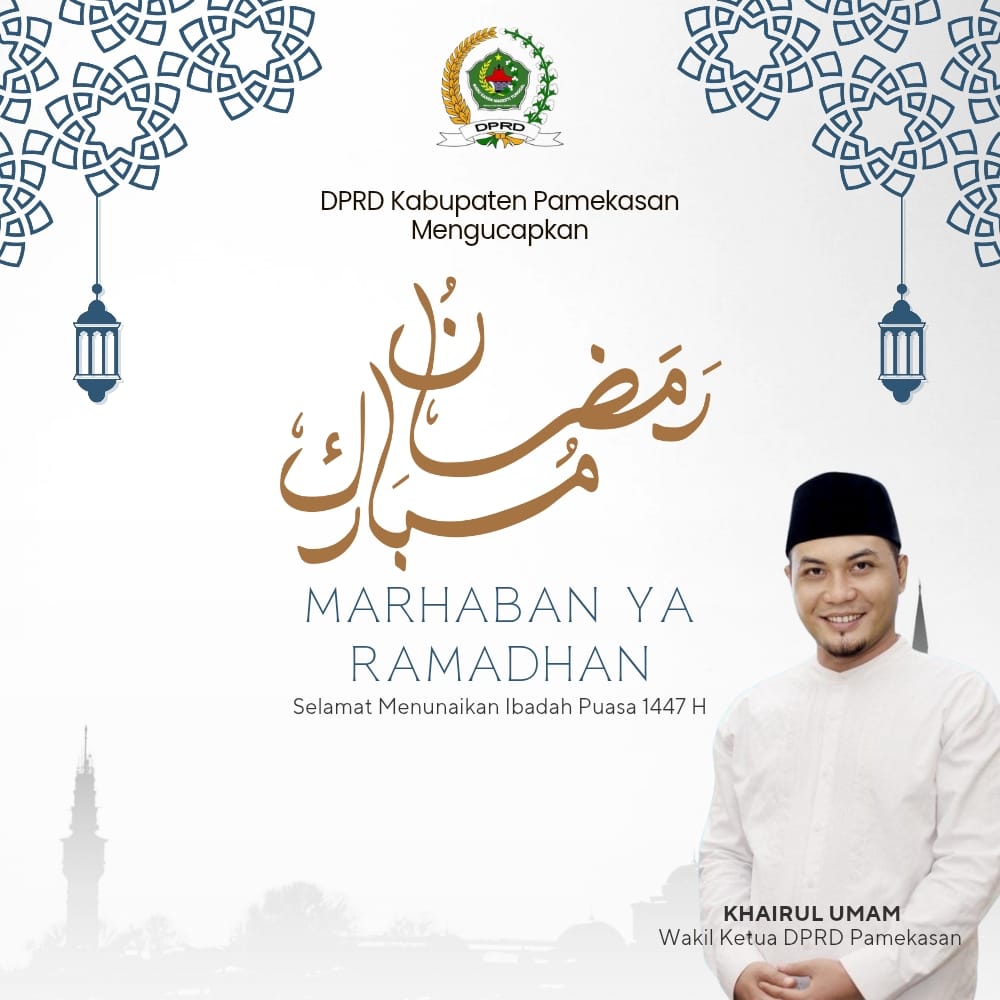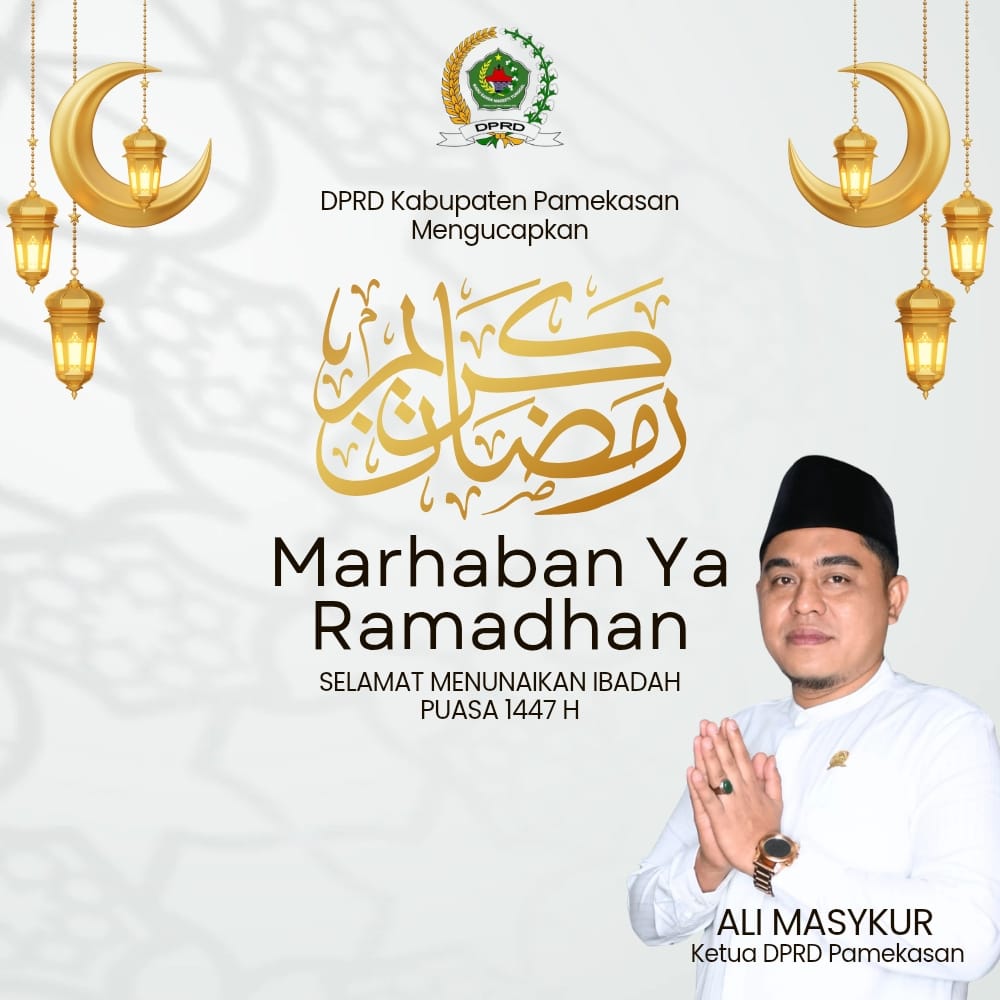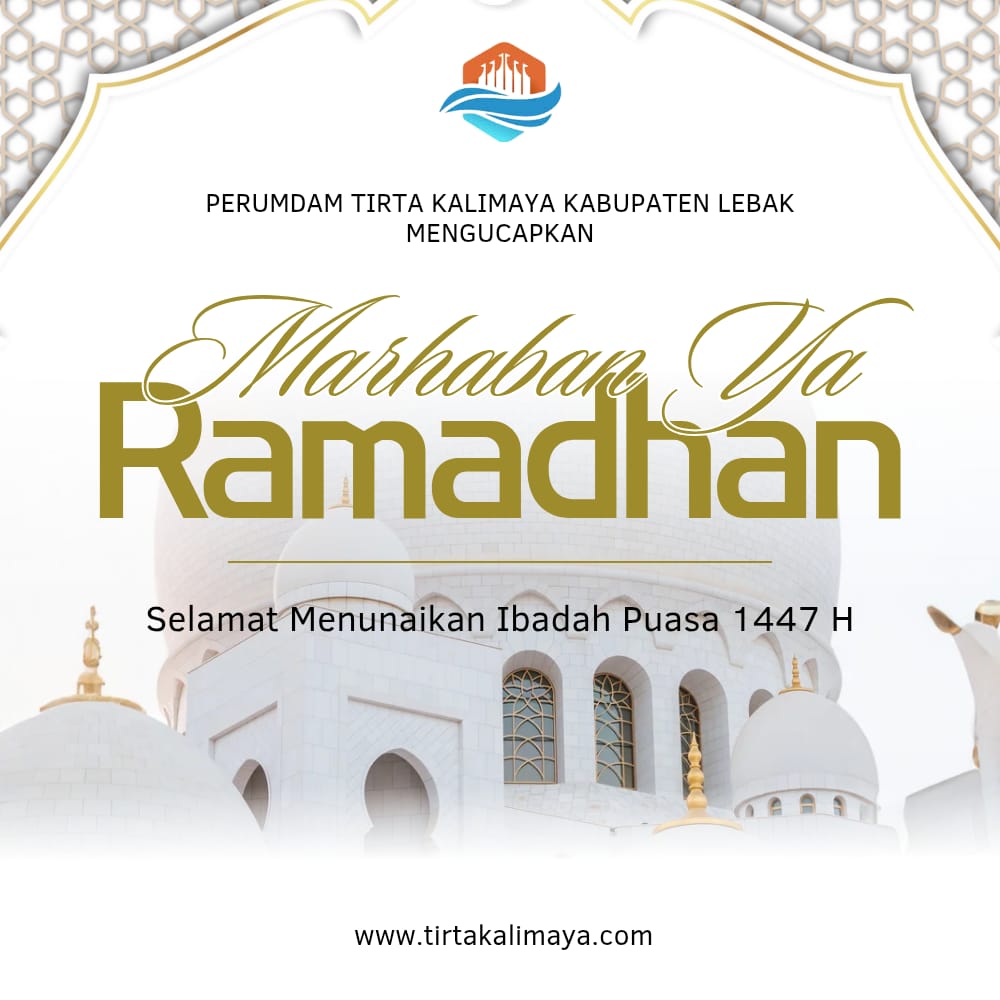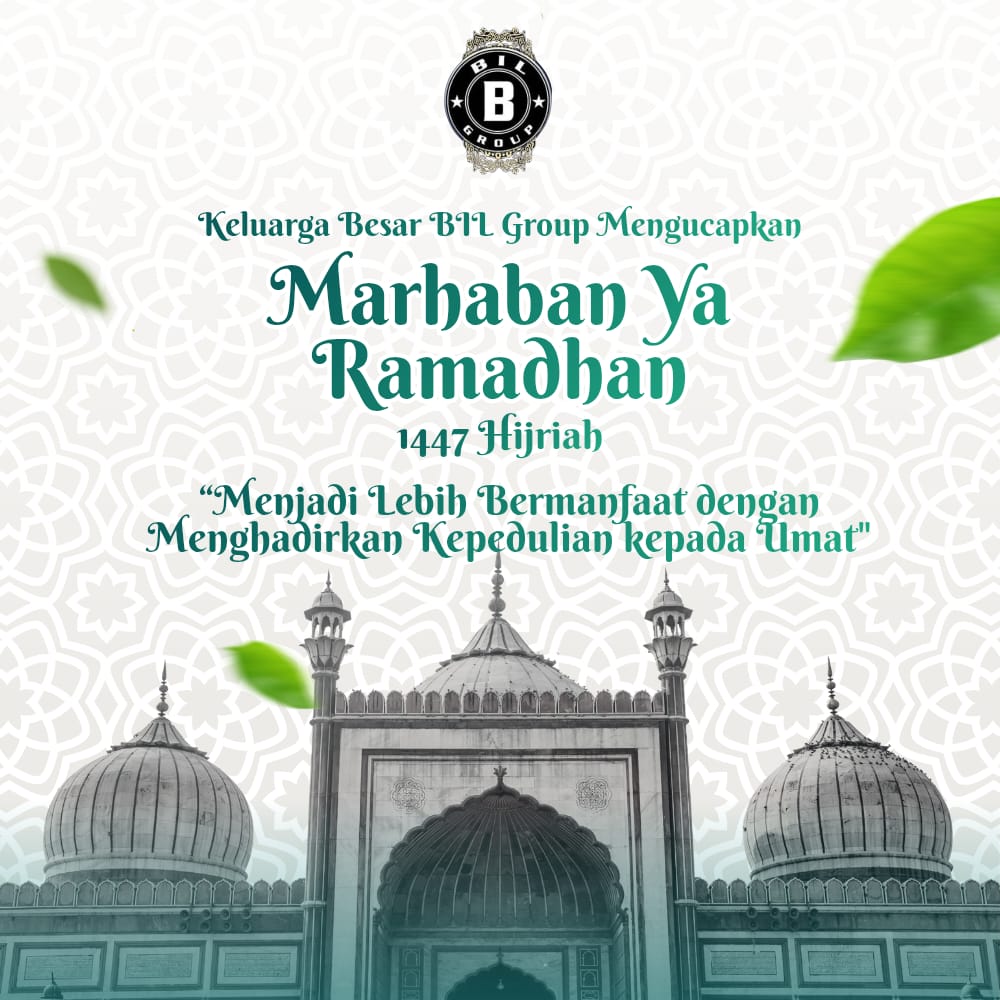Ruang-ruang kelas dan halaqah di pesantren, yang seharusnya menjadi oase ketenangan dan transmisi ilmu yang sarat keberkahan, kini seringkali diwarnai ketegangan dan, yang lebih mengkhawatirkan, konflik terbuka.
Berita-berita belakangan ini silih berganti menayangkan kasus kekerasan—baik yang dilakukan oleh guru terhadap murid/santri sebagai dalih pendisiplinan, maupun yang sebaliknya, di mana murid dengan keberanian yang terkesan tanpa adab melawan, mengancam, bahkan merekam tindakan sang guru.
Fenomena kesalahpahaman yang berujung pada viralitas dan persekusi publik menjadi pemandangan yang menyakitkan, seolah-olah ikatan suci (sacred bond) antara murid dan murobbi telah putus.
Ironisnya, krisis ini terjadi justru di lembaga-lembaga pendidikan beragama, tempat etika dan moralitas diajarkan sebagai pilar utama.
Kasus-kasus ini bukan sekadar insiden tunggal atau masalah kedisiplinan yang bisa diselesaikan di ruang kepala sekolah. Ini adalah gejala akut dari sebuah krisis filosofis: degradasi makna Adab.
Adab, yang dalam tradisi keilmuan Islam dimaknai sebagai fondasi sebelum ilmu itu sendiri, telah tereduksi menjadi etiket kosong—sebuah formalitas tanpa substansi nilai yang mengikat.
Oleh sebab itu, urgensi terpenting saat ini bukanlah menghukum lebih keras atau membuat peraturan yang lebih ketat, melainkan melakukan reinterpretasi filosofis etika Adab dalam relasi guru-murid kontemporer.
Tulisan opini ini bertujuan membongkar akar masalah di balik konflik yang terjadi, serta menawarkan pembacaan ulang terhadap adab sebagai etika komitmen timbal balik yang berbasis pada nilai keadilan dan integritas.
Hanya dengan kembali kepada fondasi filosofis inilah, pendidikan beragama dapat menghentikan krisis dan mengembalikan marwahnya.
Konflik yang terekspos di media hanyalah puncak gunung es. Keretakan hubungan guru-murid berakar pada pergeseran fundamental dalam tata nilai.
Dalam tradisi, guru diposisikan sebagai pewaris nabi (waratsat al-anbiya’), menjadikan relasi bernuansa sakti (suci). Namun, di era modern, relasi ini mengalami sekularisasi.
Guru dipandang sebagai tenaga profesional atau penyedia jasa yang digaji, sementara murid atau orang tua menganggap diri mereka sebagai konsumen. Pergeseran ini meruntuhkan dasar ta'dzim yang bersifat spiritual menjadi sekadar transaksi, di mana tuntutan atau perlawanan muncul ketika "layanan" dianggap tidak memuaskan.
Media sosial dan budaya informasi instan memainkan peran besar dalam merusak struktur adab. Otoritas ilmu kini telah terdesentralisasi melalui internet, memberikan murid akses tanpa batas ke informasi, yang seringkali memicu arogansi epistemik—kesombongan dalam pengetahuan—di mana penguasaan informasi disamakan dengan kebijaksanaan.
Lebih jauh, kemampuan merekam dan memviralkan konflik memberikan kekuatan luar biasa kepada murid untuk mengadili guru di ruang publik, menyebabkan guru rentan terhadap persekusi siber dan memilih menjaga jarak, yang ironisnya semakin menipiskan wibawa mereka.
Lembaga pendidikan—baik sekolah maupun pesantren—seringkali gagal menjadi penengah yang ideal. Institusi terkadang masih membiarkan praktik otoritarianisme yang menggunakan adab sebagai alat kontrol kaku, membenarkan kekerasan atas nama “pendisiplinan” tanpa mengindahkan etika ihsan (berbuat baik) dalam mendidik.
Sebaliknya, ketika konflik meledak, banyak yang lebih mengutamakan citra lembaga daripada penyelesaian etis-filosofis yang mendalam, memilih solusi instan seperti mengeluarkan murid atau memindahkan guru, tanpa pernah membahas akar filosofis dari kegagalan relasi adab tersebut.
Setelah mendiagnosis keretakan, solusi harus bersifat fundamental: mengembalikan adab ke kedudukan filosofisnya.
Merujuk pada pemikir pendidikan Islam, adab dimaknai sebagai tindakan meletakkan sesuatu pada tempatnya yang benar (proper place). Krisis terjadi karena kegagalan meletakkan tiga hal pada tempatnya: ilmu, diri sendiri, dan relasi. Adab adalah jembatan etis yang menghubungkan hierarki pengetahuan, bukan hanya hierarki kekuasaan.
Reinterpretasi filosofis mendesak adab dipahami sebagai etika komitmen timbal balik. Bagi sang murid, adab utama adalah menghormati otoritas ilmu (ta’dzim), bukan kepatuhan absolut pada pribadi guru.
Ta’dzim adalah pengakuan bahwa ilmu didapatkan melalui proses dan transmisi yang sah. Jika murid gagal menempatkan ilmu lebih tinggi dari egonya, dan malah melawan guru yang membawa ilmu, ia melanggar etika yang mengikatnya pada tanggung jawab untuk merawat ilmu tersebut.
Sebaliknya, adab juga menuntut kewajiban etis yang tinggi dari pihak guru. Guru dituntut untuk menjaga integritas (amanah) dalam transfer ilmu dan keadilan (ihsan) dalam tarbiyah (pendidikan karakter).
Ihsan berarti guru harus mendidik dengan kesadaran bahwa ia diawasi oleh Tuhan, sehingga kekerasan, arogansi, atau penggunaan kekuasaan yang berlebihan adalah pelanggaran adab terhadap peran sucinya sendiri sebagai pewaris ilmu.
Kunci reinterpretasi adab terletak pada fondasi Tauhid (Keesaan Tuhan). Relasi guru-murid tidak boleh hanya diatur oleh kontrak sosial. Ketika adab didasarkan pada Tauhid, relasi tersebut menjadi tanggung jawab transendental.
Guru dan murid sama-sama menyadari bahwa mereka terikat pada Adab Tertinggi kepada Sang Pencipta. Konflik tidak lagi dilihat sebagai pertarungan ego, tetapi sebagai pelanggaran etika kosmis yang harus diselesaikan dengan hikmah dan keadilan.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa adab dalam konteks pendidikan beragama adalah sebuah kebutuhan filosofis. Ia adalah bingkai etika yang menyeimbangkan ta'dzim (rasa hormat pada ilmu) dengan ihsan (keadilan dalam mendidik).
Tanpa bingkai ini, relasi guru-murid akan terus menjadi rapuh, rentan terhadap tuntutan sekuler, dan mudah meledak menjadi konflik. Oleh karena itu, tantangan selanjutnya adalah menerjemahkan kerangka filosofis ini menjadi tindakan dan mekanisme nyata di lapangan.
Reinterpretasi filosofis tentang adab harus diterjemahkan menjadi perubahan struktural. Ini dimulai dengan Pelatihan Filosofis Guru, fokus pada etika profesional berbasis ihsan yang melatih guru untuk membangun wibawa melalui integritas dan keadilan.
Di sisi murid, harus ada Kurikulum Reflektif yang mendorong mereka melakukan muhasabah tentang tujuan ilmu dan pentingnya ta’dzim sebagai praktik kesadaran spiritual.
Ketika konflik terjadi, institusi harus menjauhi mekanisme penghukuman instan. Lembaga harus menerapkan prosedur yang berbasis pada prinsip ihsan dan keadilan. Perlu dibentuk Forum Musyawarah Etika yang bertugas menganalisis akar konflik secara etis-filosofis, bukan sekadar mencari siapa yang bersalah.
Solusi harus berorientasi pada Restorasi Relasi, di mana kedua pihak difasilitasi untuk memahami pelanggaran adab yang mereka lakukan dan berkomitmen untuk memperbaiki komitmen etisnya.
Adab harus menjadi sebuah ekosistem kolektif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pendidikan Adab bagi Orang Tua harus menjadi prioritas. Orang tua perlu menyadari bahwa adab adalah investasi jangka panjang, bukan sekadar nilai yang bisa mereka tuntut dari guru, sehingga pola asuh di rumah selaras dengan nilai-nilai di sekolah.
Lembaga juga harus berani menguatkan otoritas moral guru yang sejati sambil secara tegas menindak guru yang menggunakan adab sebagai alat penindasan.
Konflik guru-murid adalah panggilan darurat yang harus dijawab dengan solusi mendalam. Kita harus berhenti bersikap reaktif terhadap insiden viral dan mulai bersikap proaktif dengan menanamkan fondasi filosofis yang kokoh.
Hanya dengan mengembalikan nilai filosofis etika adab—yang menyeimbangkan otoritas dengan keadilan, ta'dzim dengan ihsan—pada tempatnya yang benar, lembaga pendidikan beragama dapat menghentikan arus krisis ini.
Tantangan saat ini bukan hanya tentang mengajarkan ilmu, tetapi tentang mengembalikan spiritualitas dan martabat dalam proses transfer ilmu itu sendiri.
Semoga upaya reinterpretasi filosofis adab ini menjadi langkah awal untuk mengembalikan marwah pendidikan kita, menjadikan ruang kelas sebagai tempat yang menumbuhkan ilmu, karakter, dan adab yang luhur, sesuai dengan cita-cita pendidikan beragama.
Penulis:
Rizki Pradana S.ag, mahasiswa Pascasarjana Ilmu Agama Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.