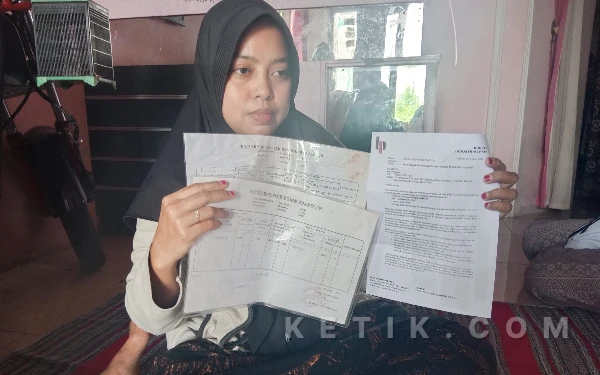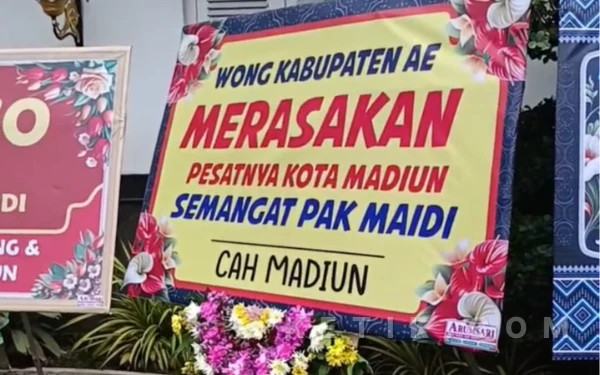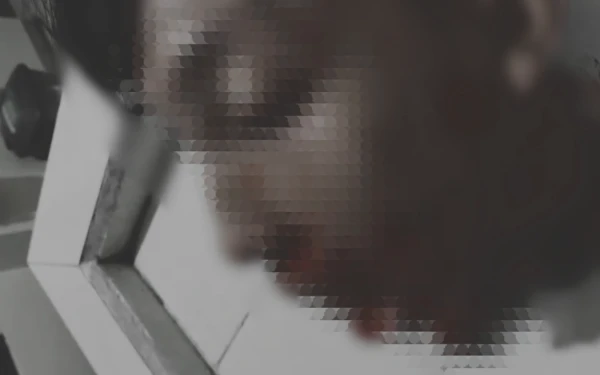Sejumlah 157 desa dan kelurahan yang dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem kewilayahan, sistem administrasi, dan sistem sosial budaya menyebar di Kabupaten Trenggalek.
Penduduknya tidak sampai 1 juta. Sebagian besar mereka tinggal di daerah pegunungan. Ada yang di pinggir tebing dan bahkan di pucuk-pucuk bukit. Bahkan sebagian juga di ceruk yang untuk menuju ke sana harus menuruni jalan pinggir julan dan daerah pemukimannya tak kelihatan ketika dilihat dari tempat sebelum kita menuruni jalan itu.
Medan yang tak disangkal lagi sulit. Terpencil dan jauh dari akses. Mencerminkan wilayah Trenggalek jika dilihat dari perspektif regional bersama beberapa kota di sekitarnya.
Kebanyakan penduduk Trenggalek memanfaatkan tanah. Tapi tidak semua kebutuhan bisa disediakan dari tanah yang ada. Dan bahkan masih saja tak sedikit orang yang tak punya tanah—atau tak punya akses untuk menggarap tanah. Mereka yang mendapatkan penghasilan dari bertanampun, tak sedikit yang memiliki tanah itu—karena tanah itu adalah tanah perhutani.
Maka cerita tentang manusia yang tidak berdaulat dimulai dari sini. Ketika orang tak bisa dicukupi oleh tanah kelahirannya sendiri karena tanah itu bukan miliknya, dan tanah yang ada juga tak bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Alangkah sengsaranya hidup mereka, tinggal di medan yang kadang sangat sulit dan jauh dari akses untuk pemenuhan hidup yang layak.
Mereka lahir di desa, tapi desa tak bisa memenuhi hak-hak mereka untuk hidup layak. Jauh hari sebelum ada TV yang menyuguhkan berbagai kebutuhan melalui iklan dan gaya hidup orang-orang metropolis, mungkin kebutuhan tak begitu disadari.
Tapi ketika kebutuhan terus dipicu oleh iklan dan perkembangan jaman, hidup sesuai dengan tingkat adaptasi terhadap alam yang ada saja—serta rela hidup dan mati sebagai bagian dari alam—barangkali merupakan hal yang tak bisa lagi dilakukan.
Pikiran dan perasaan telah tercerabut dan dicabut dari akar-akar alam dan lingkungan. Modernisasi telah menarasikan cita-cita hidup melampaui ketersediaan alam yang ada. Melampaui kemampuan manusia untuk pasrah pada kondisi alam dan kosmos. Maka ketakberdaulatan pertama yang terjadi adalah bahwa keinginan telah mengembara melampaui kemampuan tubuh berinteraksi dengan alam. Semakin banyak jumlah manusia, semakin dalam logika modal menggerakkan manusia merusak alam, ternyata kedaulatan semakin enyah.
Bencanapun lebih banyak datang dari kontradiksi yang lahir dari dominasi modal dan logikanya, daripada datang dari dialektika alam. Dulu, ancaman terhadap orang-orang di pedesaan dan pegunungan ini adalah binatang dan medan yang sulit. Pada waktu saya masih kecil, bukan pandangan yang mengagetkan kalau orang mati karena digigit Ular yang mematikan. Ada tetangga yang mati karena jatuh dari pohon. Dan yang tragis, ada saudara yang meninggal tenggelam di delta di bawah Gunung Kumbakarna (Kecamatan Watulimo) sehabis pulang dari mencari kayu dari Hutan itu untuk dibuat rumah dan dijual.
Seiring berjalannya hari, tanah, hutan, sawah, dan ladang tak mampu lagi menjadi sumber penghidupan. Orang-orang bermigrasi ke luar, merantau ke luar kota, luar pulau, dan bahkan luar negara. Pada saat yang sama penetrasi modal dari luar juga terus merasuk. Produk-produk perkotaan dan produk-produk luar negara. Bersama iklan-iklan yang kian semarak, hingga acara TV utama adalah iklan dan lainnya adalah selingan.
Berita tentang orang mati dimakan binatang buas, tenggelam di lautan dan sungai, jatuh dari pohon, hampir jarang terdenagar lagi. Berita yang kadang terdengar adalah tentang buruh migran yang mati disiksa majikannya. Tetangga yang mati tertimbun tanah akibat menggali emas di daerah Kalimantan. Selebihnya yang terbanyak adalah remaja yang mati karena kecelakaan, ada motornya ditabrak truk hingga alat transportasinya hancur dan kepala si pengendara hancur. Otaknya pecah bersebaran di jalan raya.
Cerita kematian yang ada ini adalah tentang kecelakaan dari barang-barang teknologinya yang dikonsumsinya dari membeli produk-produk pemilik modal dari luar kota dan luar negeri yang mempekerjakan buruh-buruh yang sebagian datang dari daerah pedesaan.
Ancaman berikutnya adalah kematian dan kian pendeknya umur orang-orang yang tinggal di daerah pedesaan. Selain mati karena disiksa majikan, tabrakan di jalan raya, maka ancaman kematian datang dari barang-barang yang dikonsumsi untuk tubuh. Apa saja, mulai dari produk pertanian yang telah mengandung zat kimia, minuman penyegar dan nutrisi yang juga mengandung hal yang sama, hingga apa yang justru dianggap sebagai obat.
Kandungan kimia zat makanan dan minuman yang masuk ke tubuh ternyata mengandung unsur perusak organ-organ tubuh yang luar biasa parah. Minuman penyegar yang merusak ginjal, hingga semua makan dan minuman yang mengandung perusak sel-sel tubuh dan darah. Dulu “stroke” adalah penyakit orang tua renta, sekarang orang yang masih berumur 30-an sudah terserang stroke. Mulai umur segitu juga, orang sudah kena asam urat. Umur manusia di desa yang dulu terkenal lama, minimal 80 tahun, kini jika di rata-rata tampaknya 50-an tahun.
Isu penetrasi modal dengan membawa efek pelemahan raga orang-orang desa ini jarang didiskusikan. Sedangkan bentuk serangan semacam ini tak disadari oleh orang-orang desa. Orang-orang desa tampaknya tak ada masalah dengan sumber-sumber air yang kian hilang. Mereka malah bangga megonsumsi air mineral yang diproduksi dari luar negeri. Orang-orang desa tampaknya juga masih dikondisikan tidak berpikir kritis pada keadaan. Depolitisasi terhadap orang-orang pedesaan sejak Orde Baru hingga sekarang, tampaknya menjadi penyebab kenapa mereka bisa dengan mudahnya “ditipu” kaum kapitalis dari perkotaan.
Kehidupan yang susah tidak disadarinya sebagai bagian dari upaya membuat mereka tertindas dan teraniaya. Produksi budaya dan relasi sosial yang ada justru malah membuat penjajahan dari kota terus berjalan tanpa pertanyaan dan perlawanan. Forum-forum kumpulan tak memberi penyadaran apapun. Berkumpul dan membaca doa, yang dilakukan tiap minggu, juga hanya terus saja seperti itu yang terjadi. Tak ada peningkatan kesadaran dan gerak yang mengarah pada dinamika menuju kemajuan. Situasi masih mandeg. Ide-ide alternatif tentang kehidupan di desa masih stagnan.
Pada saat ada inisiatif dari atas (pemerintah) untuk membangun desa dengan keluarnya UU Desa, Anggaran Desa, pada praktiknya semangatnya masih belum kelihatan berubah di mana-mana—terutama di daerah pedesaan. Artinya program ini masih belum membawa hasil.
Apakah ada potensi perubahan?
Jelas ada. Perubahan adalah hukum material sejarah. Tidak ada yang tidak berubah. Materi selalu berubah, alam selalu berubah. Pun ide dan pikiran manusia-manusia yang ada di dalamnya juga berubah. Kekuatan materialnya yang ada apakah terarahkan untuk produktivitas ataukah hanya justru terjadi kemandegan atau malah kemunduran?
Ternyata sumber daya manusia (SDM) adalah yang menentukan. Kemajuan sosio-ekonomi tergantung bukan hanya bahan-bahan material yang ada, tetapi juga modal dan tenaga manusia. Juga ilmu pengetahuan dan teknologi. Jika semua mandeg, maka tak aka nada perubahan ke arah yang maju.
Di Trenggalek, apakah cukup punya modal? Ini adalah kabupaten yang mandeg karena peredaran uang dan modal amatlah minim. Modal bisa menjadi faktor produski utama. Bahan mentah ada, tenaga kerja ada, tapi jika tidak ada modal tidak akan menghasilkan sesuatu produk. Jika produktivitas tumpul, maka kemajuan juga tidak terjadi.
Upaya mendatangkan modal besar amatlah minim. Adakah besar dari luar yang datang lalu membangun usaha hingga menyerap tenaga kerja hingga orang-orang yang awalnya menganggur terserap dalam pekerjaan yang menghasilkan upah? Ada, tapi tidak terlalu banyak dibanding wilayah lain. Apakah dibangunnya usaha dan industri itu membuat bahan-bahan baku yang ada di Trenggalek laku sebagai bahan mentah industri?
Katakanlah ada pabrik kecap. Apakah yang bekerja di sana adalah warga Trenggalek? Seberapa banyak? Lalu apakah bahan-bahan dari kecap itu, kedelai misalnya, adalah hasil pertanian Trenggalek? Ataukah kedelai impor? Persoalannya apakah para petani Trenggalek menanam kedelai yang berkualitas unggul untuk bahan baku industri kecap atau bahkan tempe yang diproduksi oleh usaha kecil?
Memangnya apakah pertanian Trenggalek sekeren itu? Wong sayur saja asalnya dari Pasar Ngemplak (Tulungagung), dan yang menanam adalah orang Tulungagung dan orang-orang daerah Malang (kabupaten) dan Batu. Untuk kebutuhan sayur dan buah konsumsi keseharian saja dari luar Trenggalek, apalagi kedelai dan produk pertanian sebagai bahan baku industri seperti pabrik kecap.
Modal tidak berkembang dari hasil produktivitas lokal. Uang yang datang ke Trenggalek praktis adalah yang receh-receh dari pribadi-pribadi warga, para perantau dari luar negeri (Hongkong, Taiwan, Singapura, sebagian Jepang, Korea, dan lain-lain) yang dikirim ke keluarga di rumah. Bayangkan jika tidak banyak yang merantau, tentu Trenggalek kolap secara ekonomi.
Bagaimana dengan transfer dana desa? Ia adalah uang dari luar Trenggalek, tepatnya dari pusat yang ditransfer ke desa-desa se-Indonesia, termasuk ke desa-desa di Trenggalek. Tujuannya agar uang beredar di desa-desa, dimana pemerintah desa menggunakannya untuk memajukan desa-desa. Apakah dana desa itu sudah banyak mendongkrak perekonomian dan kemajuan sosial-budaya di desa? Atau jangan-jangan terjadi kebocoran penggunaannya, yang seharusnya untuk belanja barang dan jasa dalam rangka untuk perlindungan sosial, peningkatan sarana dan prasarana pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan, tetapi justru menguap tidak jelas? Atau jangan-jangan sekedar habis dan bisa di-SPJ-kan tetapi dampaknya tak dipikirkan? (*)
*) Nurani Soyomukti adalah Pendiri Institute Demokrasi dan Keberdesaan (INDEK), santri di Pasca-Sarjana di Akidah Filsafat Islam UIN Satu Tulungagung.
**) Isi tulisan di atas menjadi tanggung jawab penulis
***) Karikatur by Rihad Humala/Ketik.com
****) Ketentuan pengiriman naskah opini:
- Naskah dikirim ke alamat email redaksi@ketik.com
- Berikan keterangan OPINI di kolom subjek
- Panjang naskah maksimal 800 kata
- Sertakan identitas diri, foto, dan nomor HP
- Hak muat redaksi.(*)