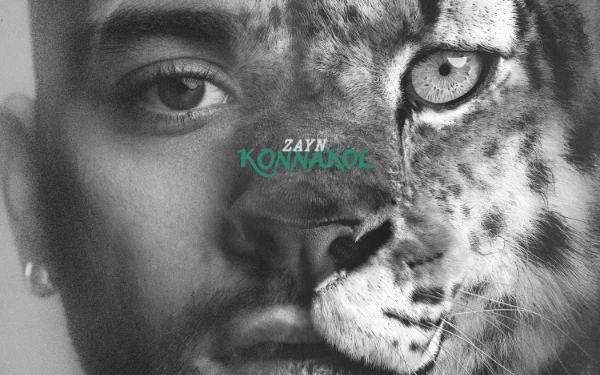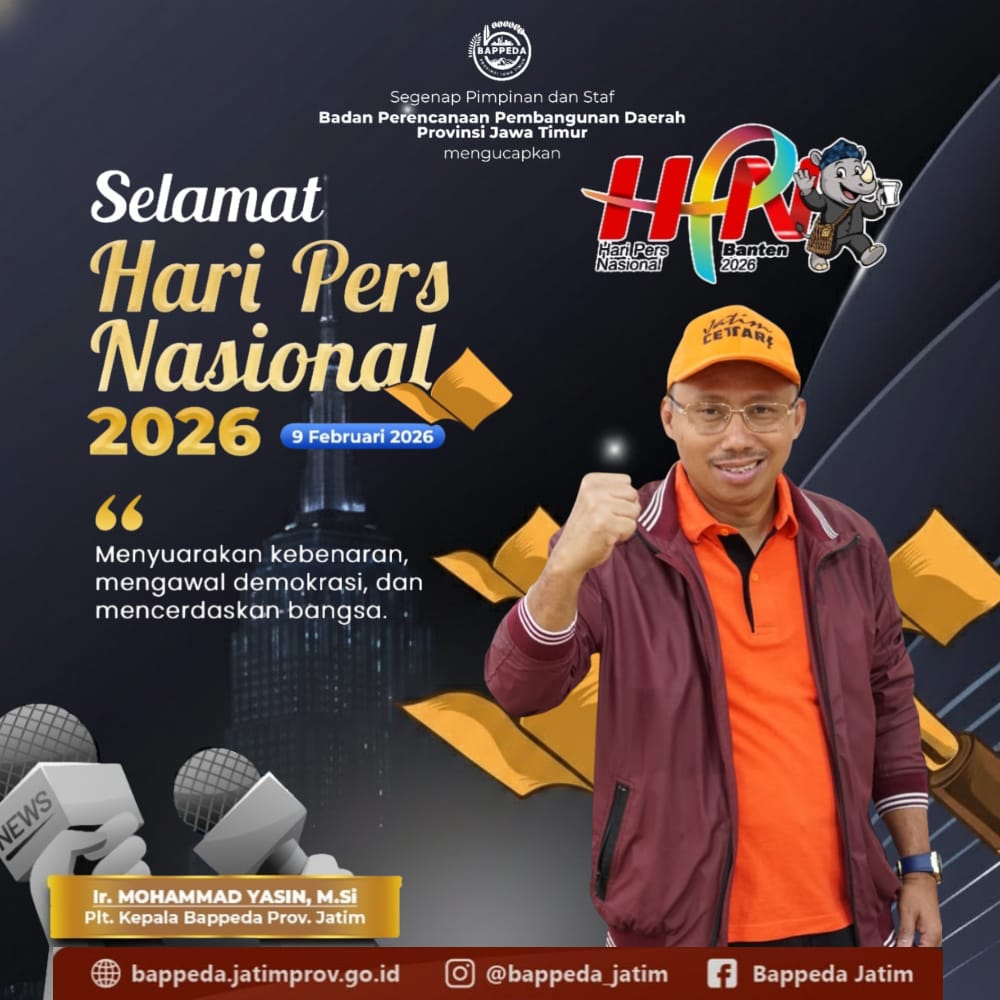Air adalah cermin peradaban bukan sekadar kebutuhan. Tanpa air bersih, tak ada pangan, tak ada kesehatan, dan tak ada masa depan.
Air bersih termasuk masalah yang rumit dan berkaitan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) ke-6 yang menegaskan pentingnya menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk. Namun, pada banyak daerah di Indonesia, mimpi itu masih terasa jauh.
Indonesia dikenal sebagai negara dengan curah hujan tinggi dan ribuan sungai besar. Namun ironisnya, sebagian masyarakatnya masih kesulitan mendapatkan air bersih.
Di pedalaman Nusa Tenggara Timur, musim kemarau bisa berlangsung lebih dari enam bulan, membuat warga menempuh perjalanan untuk memperoleh air dari sumur dangkal yang hampir kering.
Di sisi lain, kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya justru menghadapi kelebihan air bukan dalam bentuk berkah, melainkan bencana. Curah hujan ekstrem yang tak terserap oleh tanah berubah menjadi banjir, sementara penggunaan air tanah berlebihan menyebabkan penurunan muka tanah dan intrusi air laut.
Fenomena ini menunjukkan bahwa air berlimpah, tetapi tidak terkelola dengan baik. Kajian Badan Pusat Statistik Indonesia pada 2023 mencatat bahwa sekitar 12,7 juta rumah tangga di Indonesia masih belum memiliki akses air minum layak, dan hampir 20% penduduk belum terlayani sistem sanitasi aman. Artinya, satu dari lima orang Indonesia masih hidup dalam kondisi rawan air bersih.
Data Kementerian PUPR menyebutkan bahwa lebih dari 70% total kebutuhan air nasional berasal dari sektor pertanian. Sebagian besar sistem irigasi masih belum efisien dengan kehilangan air sekitar 40–50% berarti separuh dari air yang dialirkan dari bendungan dan saluran irigasi hilang sebelum mencapai lahan pertanian.
Kondisi ini menandakan bahwa krisis air di Indonesia bukan hanya soal kekurangan pasokan, tetapi juga kegagalan dalam distribusi dan manajemen. Sebuah studi menunjukkan bahwa penerapan irigasi hemat air di lahan hortikultura meningkatkan produktivitas hingga 20% dengan volume air yang lebih sedikit. Inovasi sederhana seperti ini perlu diperluas untuk mengatasi tekanan air di masa depan.
Survei yang dilakukan penulis pada Maret 2024 menggunakan alat pengukur digital kualitas air menemukan bahwa Sungai Brantas memiliki nilai pencemaran air yang jauh di atas baku mutu. Limbah industri, deterjen rumah tangga, dan pestisida pertanian menjadi penyebab utama pencemaran sehingga air yang mengalir di sungai tidak layak untuk digunakan bahkan berisiko tinggi bagi kesehatan manusia dan ekosistem.
Persoalan air bersih bukan hanya urusan lingkungan, tetapi juga persoalan kesehatan publik dan ketimpangan sosial. Perubahan iklim memperparah situasi dengan pola curah hujan yang tidak menentu menyebabkan banjir ekstrem di wilayah lain dan kekeringan berkepanjangan di satu wilayah.
Hasil kajian BMKG menunjukkan bahwa potensi hujan berkurang tetapi beberapa wilayah masih menunjukkan aktivitas hujan yang cukup signifikan akibat pengaruh sejumlah dinamika atmosfer yang masih aktif. Kondisi ini mengganggu sistem hidrologi alami, mengubah debit sungai, dan memperbesar risiko krisis air bersih di masa depan.
Eksploitasi air tanah tanpa kendali juga mempercepat penurunan muka tanah di kota pesisir. Pada wilayah Jakarta Utara, penurunan tanah telah mencapai 10–15 cm per tahun, sebagian besar akibat pengambilan air tanah berlebihan untuk kebutuhan domestik dan industri.
Jika dibiarkan, kota ini berisiko tenggelam sebagian pada 2050. Beberapa solusi yang telah dilakukan dengan pembangunan tanggul laut raksasa dirasa belum cukup, sehingga diperlukannya perbaikan tata kelola air dari hulu ke hilir yang dapat mengurangi ekstraksi air tanah dan meningkatkan penyerapan air hujan.
Rehabilitasi daerah tangkapan air di hulu dengan reboisasi dan konservasi tanah harus dibarengi pembangunan waduk kecil, embung, dan sumur resapan di dataran rendah. Sedangkan, wilayah pesisir harus berkombinasi dengan teknologi baru seperti desalinasi energi surya serta penanaman mangrove yang dilakukan untuk menjaga keseimbangan air tanah sekaligus melindungi wilayah dari intrusi air laut. Namun, semua upaya teknis ini tidak akan berhasil tanpa perubahan perilaku masyarakat.
Pemerintah Indonesia juga telah berupaya mewujudkan target layanan dasar melalui Program 100-0-100, yaitu 100% akses air minum layak, 0% kawasan kumuh, dan 100% akses sanitasi layak, sebagai bagian dari RPJMN yang sejalan dengan SDGs nomor 6 tentang air bersih dan sanitasi layak untuk semua.
Meskipun terdapat kemajuan di beberapa daerah, tantangan masih dihadapi berupa keterbatasan infrastruktur, penurunan kualitas sumber air, serta rendahnya pengelolaan sanitasi.
Dengan mempertimbangkan keterkaitan antara faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, keberhasilan dalam mencapai SDGs ke-6 tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik, tetapi juga oleh tata kelola air yang baik serta partisipasi aktif masyarakat agar akses air bersih dan sanitasi dapat terwujud secara merata dan berkelanjutan. (*)
*) Amalia Aprilliani Saiful adalah Mahasiswa Teknik Pengairan Universitas Brawijaya Malang
**) Isi tulisan di atas menjadi tanggung jawab penulis
***) Ketentuan pengiriman naskah opini:
- Naskah dikirim ke alamat email redaksi@ketik.com
- Berikan keterangan OPINI di kolom subjek
- Panjang naskah maksimal 800 kata
- Sertakan identitas diri, foto, dan nomor HP
- Hak muat redaksi.(*)













![Thumbnail Berita - [FOTO] Demo Buruh Jatim di Surabaya Tuntut Kenaikan UMP 2026](https://ketik.com/assets/upload/20251127192701whatsapp-image-2025-11-27-at-1410.webp)