Beberapa hari terakhir, ruang publik kembali gaduh oleh tayangan Trans7 dalam program Xpose Uncensored yang membahas kehidupan pesantren, khususnya Pondok Pesantren Lirboyo di Kediri.
Tayangan itu menggambarkan tradisi penghormatan santri kepada kiai secara tendensius: narasi yang seolah menunjukkan hubungan feodal, praktik amplop yang dipelintir menjadi sumber kekayaan kiai, serta ritual keseharian santri yang dikemas dengan nada merendahkan.
Reaksi masyarakat tak bisa dihindarkan. Alumni pesantren, tokoh Nahdlatul Ulama, Majelis Ulama Indonesia, hingga Komisi Penyiaran Indonesia menyatakan keberatan keras. Tayangan itu dinilai melecehkan nilai luhur pesantren, menyesatkan publik, dan melanggar etika penyiaran. Di media sosial, tagar #BoikotTrans7 sempat menjadi trending, menandakan betapa dalam luka kolektif umat terhadap pemberitaan yang dianggap tidak proporsional itu.
Namun di balik kegaduhan itu, ada pertanyaan mendasar yang perlu direnungkan: apakah media kita masih memegang teguh profesionalisme dan tanggung jawab etik dalam memberitakan lembaga keagamaan dan kebudayaan bangsa?
Jurnalistik yang Abai pada Verifikasi
Salah satu prinsip utama jurnalistik profesional adalah verifikasi. Setiap informasi yang disiarkan ke publik harus melalui proses klarifikasi dan konfirmasi dari berbagai pihak terkait. Sayangnya, tayangan Xpose Uncensored tampak abai terhadap prinsip tersebut.
Dalam segmen yang menyinggung kehidupan pesantren, narasi disampaikan secara monologis dan sepihak. Tidak tampak ada upaya menghadirkan suara dari pihak pesantren, kiai, atau santri yang menjadi objek pemberitaan. Akibatnya, tayangan berubah dari laporan jurnalistik menjadi semacam monolog provokatif yang mengundang kesan buruk terhadap tradisi pesantren.
Padahal, etika jurnalistik yang diatur oleh Dewan Pers maupun Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) jelas menuntut prinsip cover both sides. Mengabaikan prinsip ini sama saja dengan mengingkari hak publik atas informasi yang utuh dan berimbang. Media tidak boleh menjadi hakim yang menjatuhkan vonis sebelum fakta terverifikasi.
Sensitivitas Budaya yang Diabaikan
Kesalahan kedua dan paling fatal adalah kegagalan memahami konteks budaya dan religius dari pesantren.
Pesantren bukan sekadar lembaga pendidikan; ia adalah pusat peradaban Islam di Nusantara yang mengakar dalam sejarah panjang bangsa ini. Hubungan santri dan kiai bukan relasi ekonomi, melainkan spiritual dan keilmuan. Tradisi seperti mencium tangan kiai bukan bentuk perendahan, melainkan simbol adab dan penghormatan terhadap ilmu.
Ketika tradisi seperti ini disajikan dalam tone sinis dan ironi, media telah gagal menempatkan diri sebagai jembatan pemahaman. Media seharusnya menjadi penerang, bukan pengabur.
Dalam konteks masyarakat plural seperti Indonesia, setiap jurnalis seharusnya peka terhadap keberagaman budaya dan agama. Penayangan yang sembrono terhadap simbol-simbol religius sama saja dengan membuka luka sosial dan menebar prasangka. Dan ketika yang diserang adalah pesantren luka itu terasa lebih dalam
Pelanggaran Etika Penyiaran
KPI menilai bahwa tayangan Trans7 tersebut telah menyalahi sejumlah ketentuan dalam P3SPS, terutama terkait penghormatan terhadap nilai agama dan budaya lokal. Etika penyiaran menegaskan bahwa media wajib menjaga martabat lembaga pendidikan, tokoh agama, dan tradisi masyarakat.
Dalam kasus ini, Trans7 jelas tergelincir ke wilayah sensasionalisme. Demi menarik perhatian, isu yang seharusnya dikemas secara edukatif justru diolah menjadi bahan provokatif.
Jurnalistik yang mengejar sensasi tanpa empati bukan lagi bentuk keberanian, melainkan kecerobohan. Ia menyalahi prinsip dasar media sebagai public trust institution, lembaga yang dipercaya untuk mendidik publik.
Membahayakan Keberagaman
Lebih jauh, kesalahan semacam ini memiliki dampak sosial yang serius. Tayangan seperti Xpose Uncensored tidak hanya melukai kalangan pesantren, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap media arus utama.
Ketika masyarakat merasa agamanya dilecehkan, tradisinya disalahpahami, dan tokoh panutannya dihina, maka yang muncul bukan sekadar kritik, melainkan polarisasi. Kepercayaan publik terhadap media runtuh, dan ruang dialog antarbudaya semakin menyempit.
Inilah bahaya laten dari ketidakprofesionalan media: ia bukan hanya merusak reputasi institusi penyiaran, tetapi juga menebar api di tengah kerapuhan sosial bangsa. Dalam situasi masyarakat yang mudah terpecah karena informasi yang viral, media seharusnya tampil sebagai penenang, bukan pemantik.
Permintaan Maaf Bukan Akhir
Trans7 memang telah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka, mengakui adanya kekeliruan dalam proses produksi dan editing. Namun, permintaan maaf bukanlah akhir dari tanggung jawab moral.
Media perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses redaksi, mulai dari riset, penulisan naskah, hingga pengawasan etik di ruang produksi. Selain itu, penting bagi redaksi untuk membangun literasi kultural di kalangan jurnalisnya, memahami bahwa setiap narasi yang menyentuh soal agama, pesantren, atau tradisi lokal harus didekati dengan empati dan kehati-hatian.
Pada akhirnya, profesionalisme media bukan hanya soal teknis peliputan, tetapi juga soal moralitas. Media adalah cermin bangsa. Bila cermin itu buram, wajah bangsa tampak kelam. Dalam konteks ini, Trans7 perlu bercermin dan bertanya: apakah tayangan yang mereka hadirkan masih mencerdaskan publik, atau justru menjerumuskan dalam prasangka?
Kebebasan pers adalah pilar demokrasi. Namun kebebasan itu harus dibingkai oleh tanggung jawab sosial dan rasa hormat terhadap nilai-nilai masyarakat. Tanpa itu, kebebasan berubah menjadi kebebalan.
Trans7 boleh meminta maaf. Tetapi pelajaran bagi dunia jurnalistik Indonesia jauh lebih besar: bahwa profesionalisme bukan hanya tentang kecepatan dan eksklusivitas, tetapi tentang kearifan, empati, dan rasa hormat kepada nilai-nilai bangsa. Usut tuntas Trans7.
*) KH. Ahmad Ghozali Fadli adalah Rois Syuriah MWC NU Wonosalam Jombang sekaligus Pengasuh Pondok Pesantren Bumi Alquran Wonosalam Jombang
**) Isi tulisan di atas menjadi tanggung jawab penulis
***) Karikatur by Rihad Humala/Ketik.com
****) Ketentuan pengiriman naskah opini:
- Naskah dikirim ke alamat email redaksi@ketik.com.
- Berikan keterangan OPINI di kolom subjek
- Panjang naskah maksimal 800 kata
- Sertakan identitas diri, foto, dan nomor HP
- Hak muat redaksi. (*)



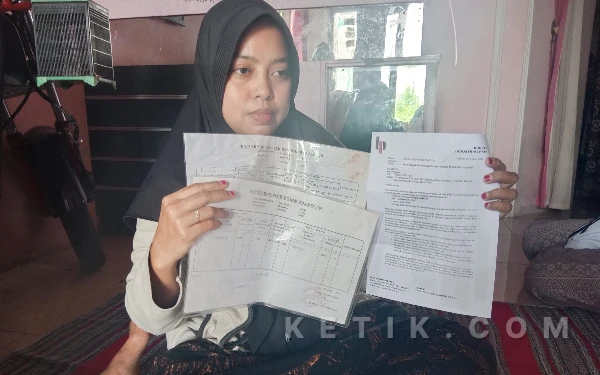
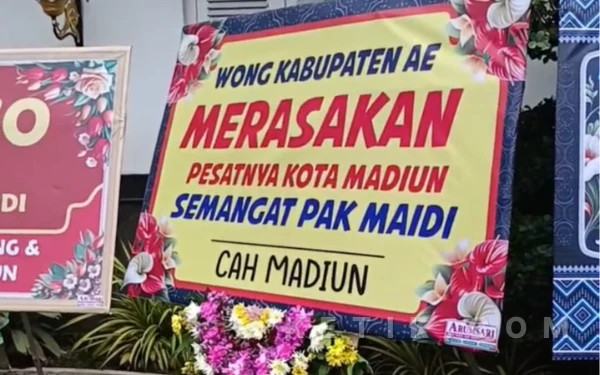

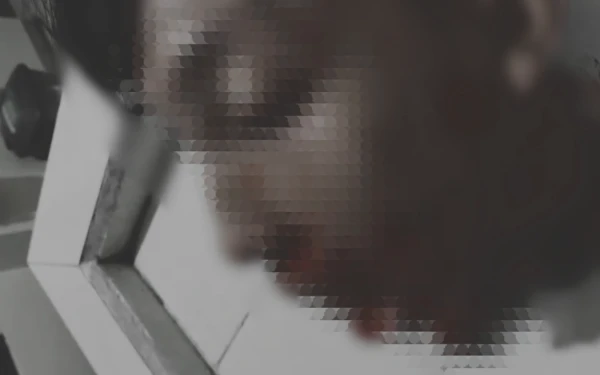





![Thumbnail Berita - [FOTO] Demo Buruh Jatim di Surabaya Tuntut Kenaikan UMP 2026](https://ketik.com/assets/upload/20251127192701whatsapp-image-2025-11-27-at-1410.webp)






















