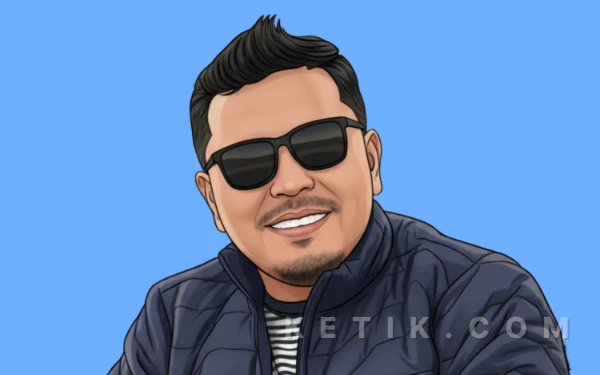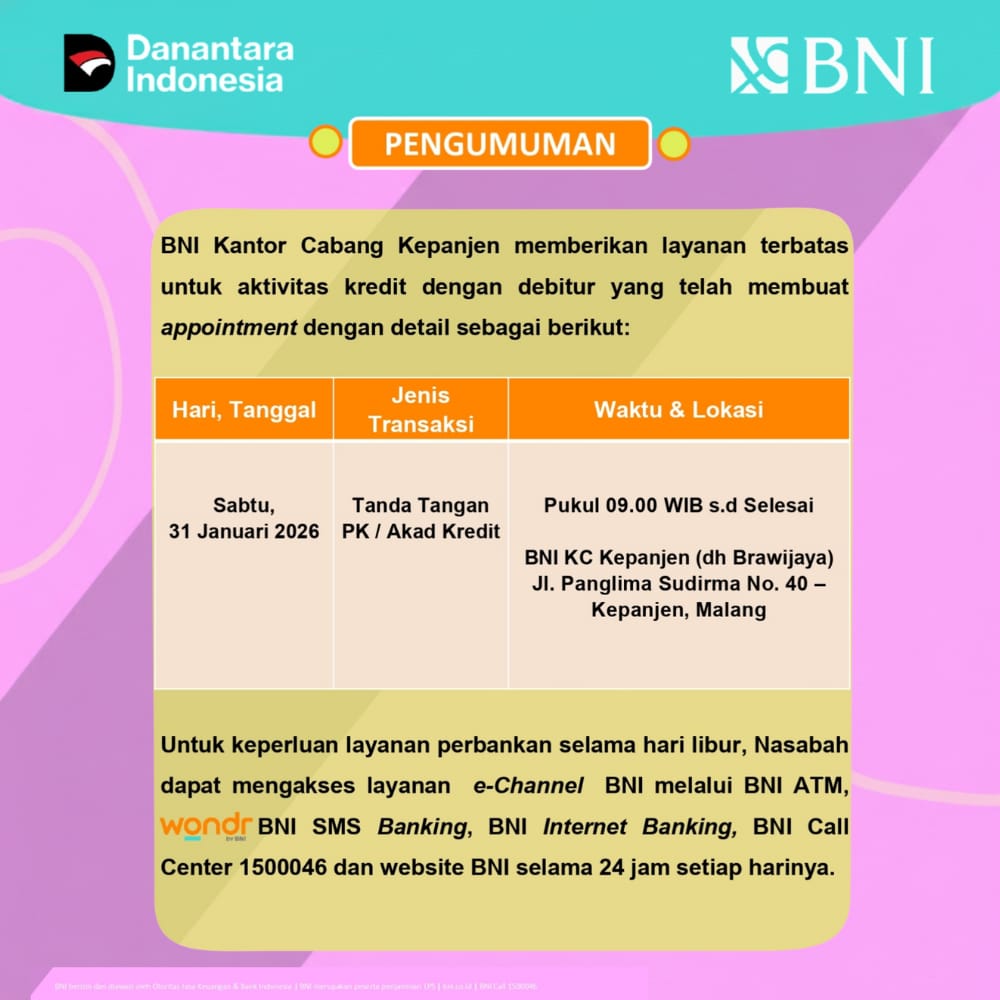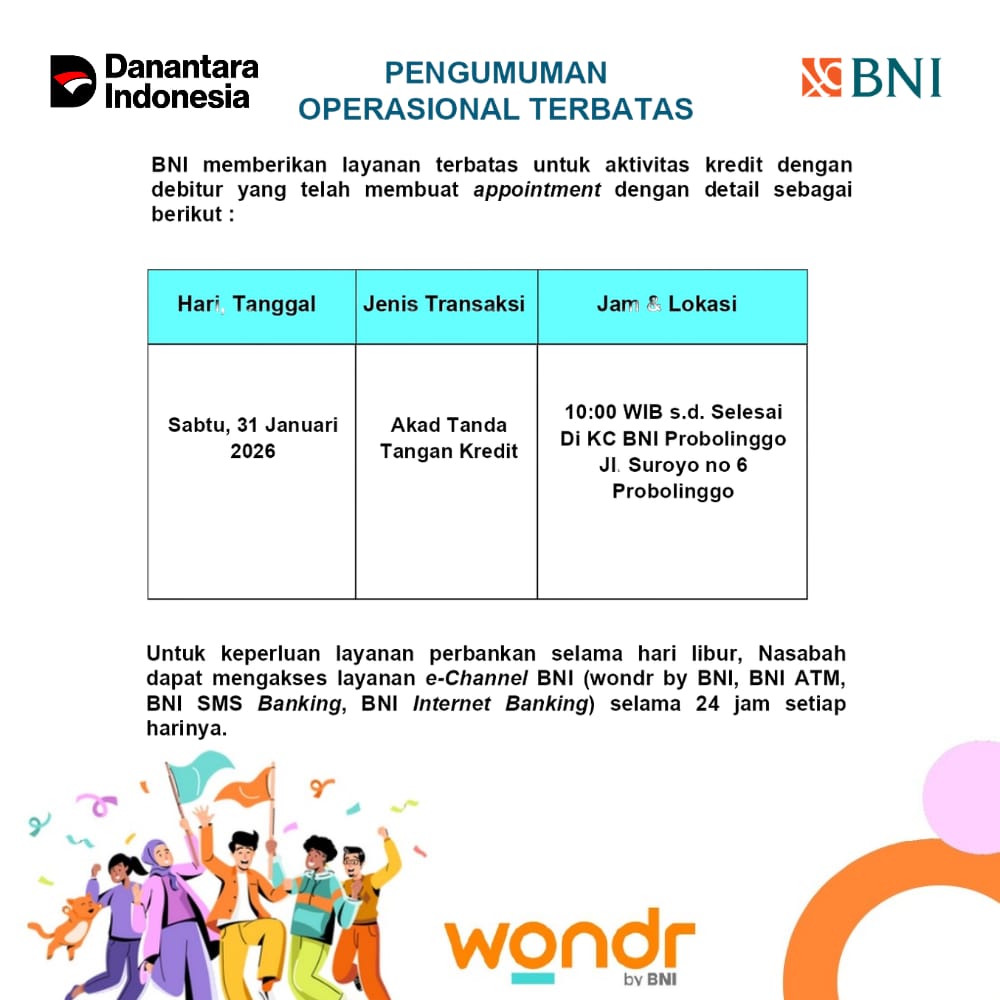Sirah Nabawiyah, kisah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW sejak sebelum kelahiran hingga wafatnya, bukan sekadar rangkaian peristiwa sejarah; ia adalah cermin yang memantulkan nilai-nilai universal yang dibutuhkan setiap muslim―dan bahkan manusia mana pun―untuk menavigasi realitas kontemporer. Dengan menelusuri jejak Nabi, kita menemukan panduan praktis tentang cara menjadi pribadi beriman sekaligus aktor sosial yang konstruktif.
Urgensi mengkaji Sirah Nabawiyah berawal dari prinsip dasar Islam bahwa Nabi Muhammad adalah uswah hasanah, teladan terbaik. Tanpa memahami sirah, ungkapan itu akan tinggal slogan; mempelajarinya memungkinkan kita mengekstraksi kebijaksanaan kontekstual, bukan sekadar mengagumi figur Nabi dari kejauhan.
Melalui sirah, kita menyaksikan bagaimana seorang Nabi menyatukan dimensi spiritual dan profan secara seimbang. Beliau menjalankan relasi vertikal lewat ibadah mendalam tetapi tak mengabaikan keadilan ekonomi, kesehatan masyarakat, dan diplomasi antarsuku. Konsep keseimbangan inilah yang kerap hilang dalam diskursus keagamaan modern yang condong pada reduksi—baik spiritualisme murni maupun aktivisme kosong.
Sirah juga menawarkan peta mental tentang manajemen perubahan sosial. Episode hijrah ke Madinah, misalnya, mendemonstrasikan strategi relokasi, konsolidasi kekuatan, dan rekayasa sosial melalui Piagam Madinah. Dokumen itu masih relevan sebagai model kontrak sosial berlandaskan keragaman dan hak asasi, sesuatu yang dicari banyak negara plural hari ini.
Lebih jauh, keteguhan Nabi saat menghadapi boikot Quraisy atau tragedi Uhud memperlihatkan paradigma ketahanan psikologis. Di tengah krisis pandemi, konflik, dan ketidakpastian ekonomi global, umat membutuhkan figur resilien semacam itu agar tidak terjebak dalam keputusasaan kolektif.
Sirah Nabawiyah juga sarat dengan etika kepemimpinan inklusif. Nabi mempraktikkan konsultasi (syūrā) dengan para sahabat, mematahkan model otoriter yang dulu dominan di Jazirah Arab. Ketika pemimpin masa kini sering terjebak ego sentralistik, sirah mengajarkan bahwa otoritas yang menumbuhkan partisipasi adalah kunci keberhasilan jangka panjang.
Kritik sosial Nabi terhadap ketimpangan gender—mewajibkan pewarisan bagi perempuan—dan pembebasan budak menunjukkan bahwa sirah adalah narasi emansipasi. Mengkajinya membuat kita lebih tajam menolak diskriminasi dan eksploitasi, sekaligus memberdayakan kelompok rentan di lingkungan modern.
Sirah bukan sekadar arsip kemenangan; ia memuat momen kegagalan taktis seperti Perang Uhud. Alih-alih mengecilkan wibawa Rasul, insiden itu justru menegaskan sifat manusiawi Nabi serta pentingnya evaluasi dan perbaikan berkelanjutan (muḥāsabah). Paradigma ini mendorong kita meninggalkan budaya anti-kritik.
Pembacaan sirah yang mendalam berimplikasi pada dakwah moderat. Konteks penghormatan Nabi terhadap Ahlul Kitab, dan sikapnya kepada tetangga non-Muslim, menjadi penangkal ideologi kekerasan yang kerap mengatasnamakan agama tanpa memahami akar historisnya.
Bagi kalangan pendidik, sirah merupakan kurikulum karakter yang holistik. Keteladanan kejujuran Nabi dalam perdagangan, keuletannya menuntut ilmu bersama Malaikat Jibril, dan kesederhanaannya di rumah memberi materi ajar konkret yang melampaui teori moral abstrak.
Sirah juga berfungsi sebagai fondasi optimisme peradaban. Melihat masyarakat Quraisy yang awalnya rentan perpecahan berubah menjadi ummah solid, kita percaya transformasi sosial itu mungkin—asal dikelola dengan visi, kesabaran, dan inklusivitas ala Nabi.
Dalam perspektif fikih, banyak preseden hukum bersumber dari peristiwa sirah. Perjanjian Hudaibiyah, misalnya, dipelajari ulama modern untuk merumuskan fiqh sulḥ (jurisprudensi perdamaian), memberi inspirasi penyelesaian konflik kontemporer yang berlarut-larut.
Mengkaji sirah juga membina kepekaan empati. Kisah Nabi menenangkan budak Zayd ibn Ḥārithah atau mengusap kepala anak yatim menjadi terapi spiritual bagi masyarakat yang cenderung individualistis. Ia mengingatkan kita bahwa religiusitas sejati menyatu dengan kepedulian sosial.
Dalam ranah keluarga, sirah menampilkan Nabi sebagai suami, ayah, dan kakek penuh kasih. Interaksinya dengan Khadijah, Aisyah, dan cucu-cucu beliau menjadi pedoman relasi rumah tangga egaliter yang sering diabaikan karena bias patriarkis atau budaya lokal.
Sirah juga berdimensi ekologi. Nabi melarang menebang pohon secara sembarangan dan menegaskan hak hewan, menantang pandangan bahwa kepedulian lingkungan hanya wacana modern. Dengan demikian, sirah relevan bagi krisis iklim yang menuntut etika bumi holistik.
Metodologi studi sirah mengasah literasi sejarah kritis: menimbang sanad, menganalisis konteks sosio-kultural, serta membaca intertekstualitas Al-Qur’an dan ḥadīth. Kemampuan ini mempersenjatai umat agar tidak terjebak hoaks agama yang kian marak di era digital.
Bagi generasi muda, sirah memberikan narasi heroik yang sehat. Daripada mengidolakan tokoh fiksi tanpa nilai etis, mereka menemukan inspirasi dari pemuda Ali bin Abi Ṭālib yang pemberani atau sahabiyah Asma binti Abu Bakr yang cerdas dalam logistik hijrah.
Mengintegrasikan sirah dalam kebijakan publik—misalnya konsep wakaf produktif yang digarap Nabi dan sahabat—dapat memperkuat ekonomi umat sekaligus mempersempit kesenjangan dengan model keuangan sosial Islam yang terbukti tahan krisis.
Kehadiran sirah di ruang wacana ilmiah membangun citra Islam sebagai tradisi rasional sekaligus spiritual. Ia menolak dikotomi Barat bahwa agama identik dengan irasionalitas, karena Nabi mendorong penggunaan akal dalam strategi perang, administrasi pasar, dan tata kota.
Akhirnya, pengkajian Sirah Nabawiyah menumbuhkan kecintaan sejati kepada Rasulullah, bukan sekadar slogan “cinta Nabi” yang diucapkan tanpa pemahaman. Cinta yang berbasis ilmu melahirkan ketaatan otentik, melandasi etos kerja, dan memandu kita menjadi umat yang baik―sebagaimana ideal yang dicanangkan Allah dalam Al-Qur’an: “Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia.”
*) Ponirin Mika merupakan Ketua Lakpesdam MWCNU Paiton dan Anggota Community of Critical Social Research
**) Isi tulisan di atas menjadi tanggung jawab penulis
***) Karikatur by Rihad Humala/Ketik.co.id
****) Ketentuan pengiriman naskah opini:
- Naskah dikirim ke alamat email redaksi@ketik.co.id.
- Berikan keterangan OPINI di kolom subjek
- Panjang naskah maksimal 800 kata
- Sertakan identitas diri, foto, dan nomor HP
- Hak muat redaksi.(*)