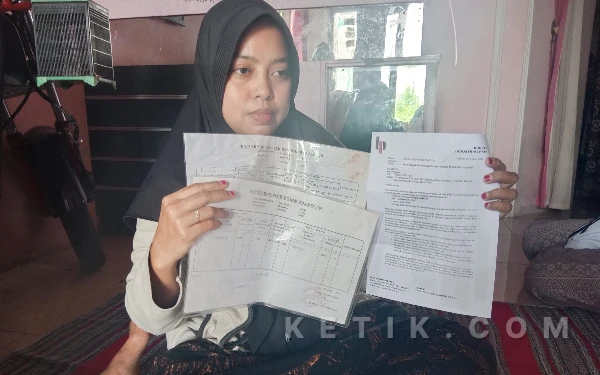Indonesia, jangan kebanyakan gaya, Kau ini suka sekali berdandan. Kadang pakai baju demokrasi, kadang pakai jas otoriter, tergantung siapa yang sedang berkuasa. Panggung politik kita mirip drama tanpa naskah, penuh improvisasi, penuh akting, tapi minim solusi.
Kita mendengar slogan “kedaulatan pangan”, tapi faktanya petani masih menjual gabah di harga rendah sementara beras impor masuk lewat jalur istimewa. Kita mendengar narasi “subsidi tepat sasaran”, tapi pupuk di desa langka dan nelayan kesulitan membeli solar bersubsidi yang makin sulit diakses.
Data BPS Agustus 2025 mencatat harga beras kualitas premium di penggilingan sebesar Rp13.838 per kilogram, sementara harga eceran konsumen menembus Rp15.393/kg—bahkan di 214 kabupaten/kota mencapai Rp15.432/kg, melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp14.900/kg (BPS, 2025; Tempo, 2025; Bisnis, 2025). Ini angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Ironisnya, petani tidak ikut menikmati keuntungan karena rantai distribusi dan impor lebih menguntungkan tengkulak.
Di sisi lain, alokasi pupuk subsidi juga tidak terpenuhi penuh: hanya 85,08% untuk Urea, 58,69% untuk NPK, dan 31,34% untuk pupuk organik (Laporan Kinerja DKPP, 2025). Akibatnya banyak petani terpaksa membeli pupuk nonsubsidi dengan harga tinggi misalnya pupuk SP bisa mencapai Rp185.000 per sak.
Nelayan pun bernasib sama kuota solar bersubsidi di SPBU nelayan sering habis lebih cepat daripada mereka bisa berlayar. Semua ini wajah asli Indonesia di balik dandanan gemerlap pembangunan.
Kekecewaan itu kini meledak di jalanan. Demonstrasi bukan lagi agenda tahunan, tapi hampir jadi rutinitas bulanan. Publik menyaksikan bagaimana demonstrasi mahasiswa dan massa lain di Jakarta berujung kerusuhan.
Polisi mengamankan 1.240 orang, sebagian besar dari luar Jakarta. Sebanyak 22 halte TransJakarta rusak, 6 di antaranya dibakar dan dijarah, dan 16 lainnya dicoret-coret. Kerugian ditaksir mencapai Rp55 miliar (Katadata, 2025; CNA Indonesia, 2025; Jawapos, 2025).
Ini bukan angka kecil, apalagi jika kerusakan itu justru menghantam pelayanan publik yang sehari-hari dipakai rakyat kecil. Apakah ini sekadar marah spontan? Tidak. Ini akumulasi dari kekecewaan panjang.
Gedung-gedung megah DPR dan istana sering menutup pintu dialog. Maka jalanan berubah menjadi mimbar rakyat. Poster, spanduk, hingga cat semprot di tembok menjadi alfabet alternatif bagi mereka yang tidak diberi pena. Tapi tentu saja, aksi ini punya sisi gelap: ketika provokasi dan penyusup masuk, aspirasi berubah jadi anarki. Yang rugi akhirnya rakyat itu sendiri.
Di tengah situasi panas ini, publik menoleh ke DPR. Sayangnya, DPR lebih sering jadi Dewan Perwakilan Retorika ketimbang rakyat. Perdebatan alot di Senayan jarang berujung pada solusi konkret. Ketika rakyat sibuk mengatur strategi agar dapur tetap ngebul, wakil rakyat sibuk mengatur jadwal reses dan ongkos bensin. Kursi yang mereka duduki seolah dianggap hak pribadi, padahal itu hanya titipan rakyat.
Jika titipan itu dipakai untuk tidur siang, jangan salahkan bila rakyat kelak menendangnya. Kita butuh DPR yang hadir di tengah rakyat, bukan DPR yang sibuk mempercantik citra di TikTok politik. Presiden, siapapun orangnya, juga tak lepas dari sorotan.
Rakyat sudah kenyang dengan slogan indah yang berakhir di baliho raksasa. Ingat, rakyat tidak makan narasi besar. Rakyat makan nasi, dan nasi hari ini makin mahal. Meresmikan proyek memang perlu, tapi jika itu hanya menjadi seremoni potong pita, rakyat akan melihatnya sebagai gaya-gayaan, bukan kerja nyata.
Penting dicatat, rakyat marah bukan berarti benci, justru karena cinta. Tapi cinta itu jangan mabuk. Aksi vandalisme, penjarahan, dan perusakan fasilitas publik tidak bisa dibenarkan. Merusak halte TransJakarta sama saja menendang meja makan sendiri. Justru tindakan seperti itu membuat penguasa punya alasan lebih besar untuk menutup telinga.
Kita butuh marah yang bermartabat, marah yang tepat sasaran, bukan marah yang membakar rumah sendiri. Meski penuh luka, negeri ini belum mati. Guru di pelosok tetap mengajar meski gajinya bikin miris. Petani masih menanam meski pupuk mahal. Nelayan tetap melaut meski solar bersubsidi makin sulit didapat.
Negeri ini masih hidup berkat rakyat kecil yang bertahan dengan cara sederhana, bukan berkat pejabat yang sibuk konferensi pers. Pejabat yang kebanyakan tidur siang sebaiknya malu. Bangsa ini berdiri di atas keringat orang kecil, bukan di atas baliho dan pencitraan.
Obat memang pahit, tapi harus diminum. Kalau tidak, penyakit bangsa ini bisa kronis. Demokrasi bisa berubah jadi dekorasi, rakyat bisa berubah jadi tontonan, dan sejarah bisa mencatat kita sebagai bangsa yang pandai berwacana tapi gagal membangun peradaban. Indonesia memang tidak sempurna.
Tapi justru karena itu kita harus berani menegur, mengkritik, dan memperbaiki. Aspirasi rakyat jangan lagi dipandang sebagai gangguan. Itu justru alarm bahwa ada yang salah di tubuh bangsa ini. Sebelum sabar rakyat benar-benar habis, pemerintah harus sadar, yang dibutuhkan rakyat bukan gaya, bukan slogan, tapi solusi nyata.
Dunia akan menertawakan kita bila bangsa besar ini hanya sibuk pencitraan, rakyat sibuk demonstrasi, dan sejarah sibuk mencatat kegagalan. Itu terlalu konyol untuk negeri yang katanya gemah ripah loh jinawi.(*)
*) Sunardi, S.Pd merupakan Ketua 1 Kaderisasi PC PMII Pacitan Periode 2024-2025
**) Isi tulisan di atas menjadi tanggung jawab penulis
***) Karikatur by Rihad Humala/Ketik.co.id
****) Ketentuan pengiriman naskah opini:
- Naskah dikirim ke alamat email redaksi@ketik.co.id.
- Berikan keterangan OPINI di kolom subjek
- Panjang naskah maksimal 800 kata
- Sertakan identitas diri, foto, dan nomor HP
- Hak muat redaksi.(*)