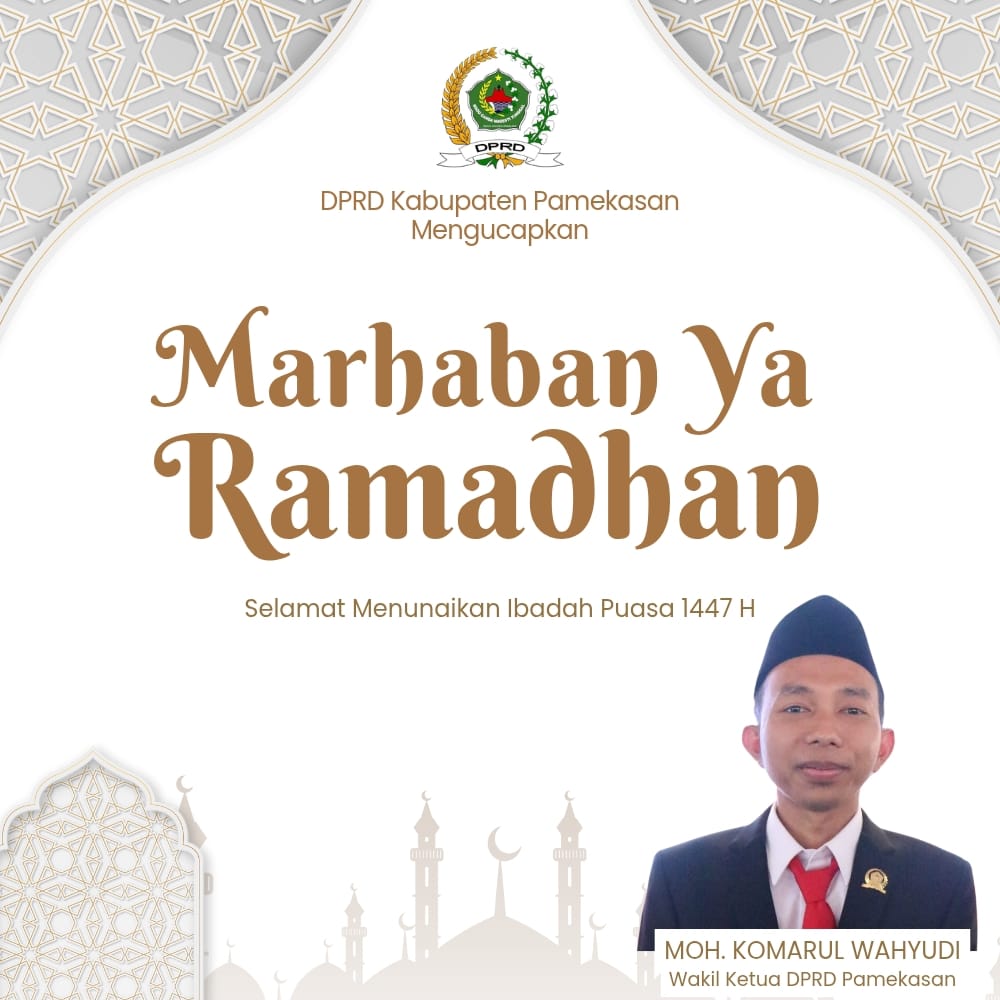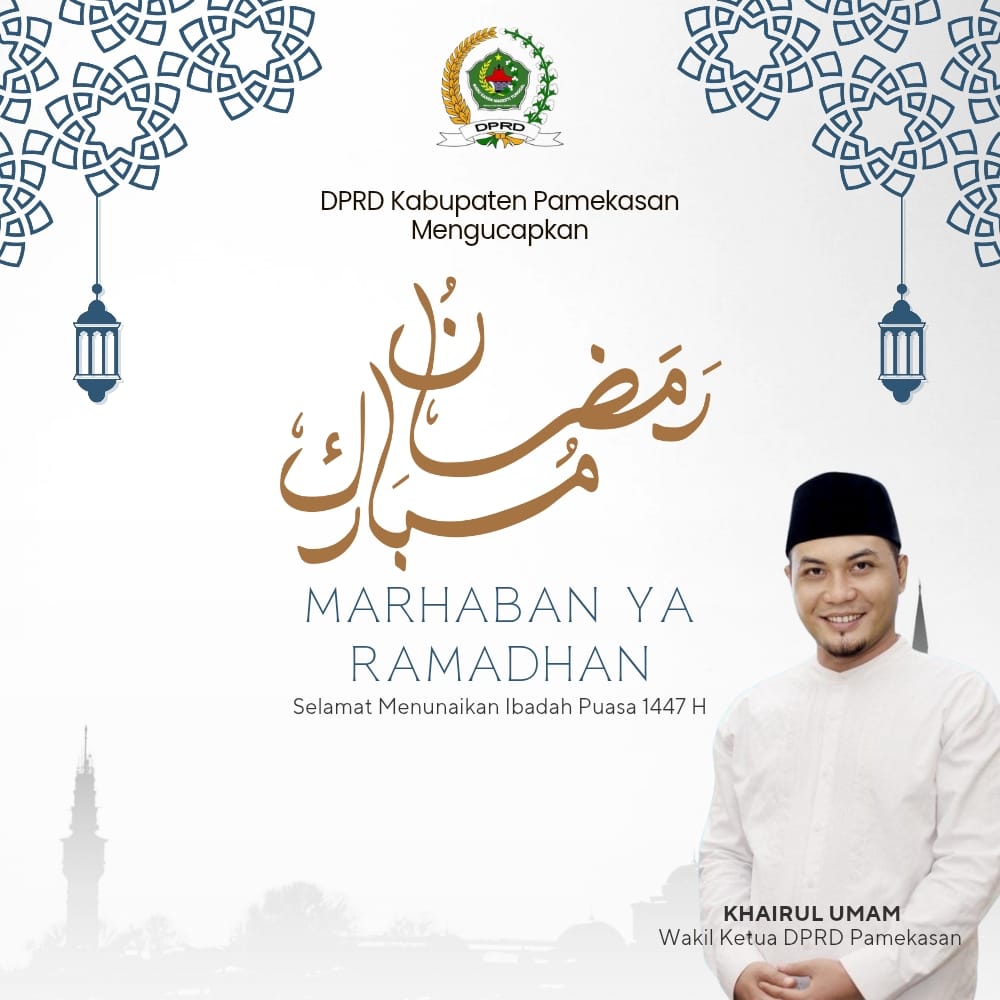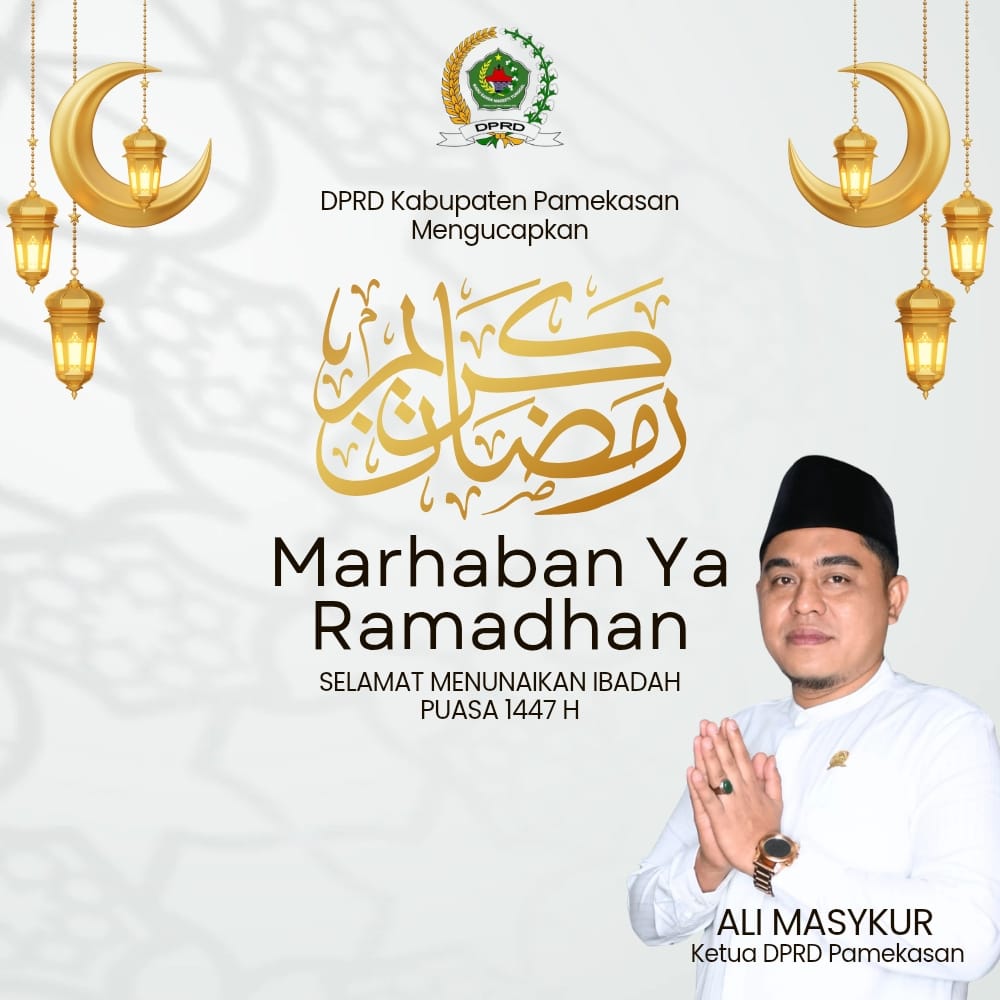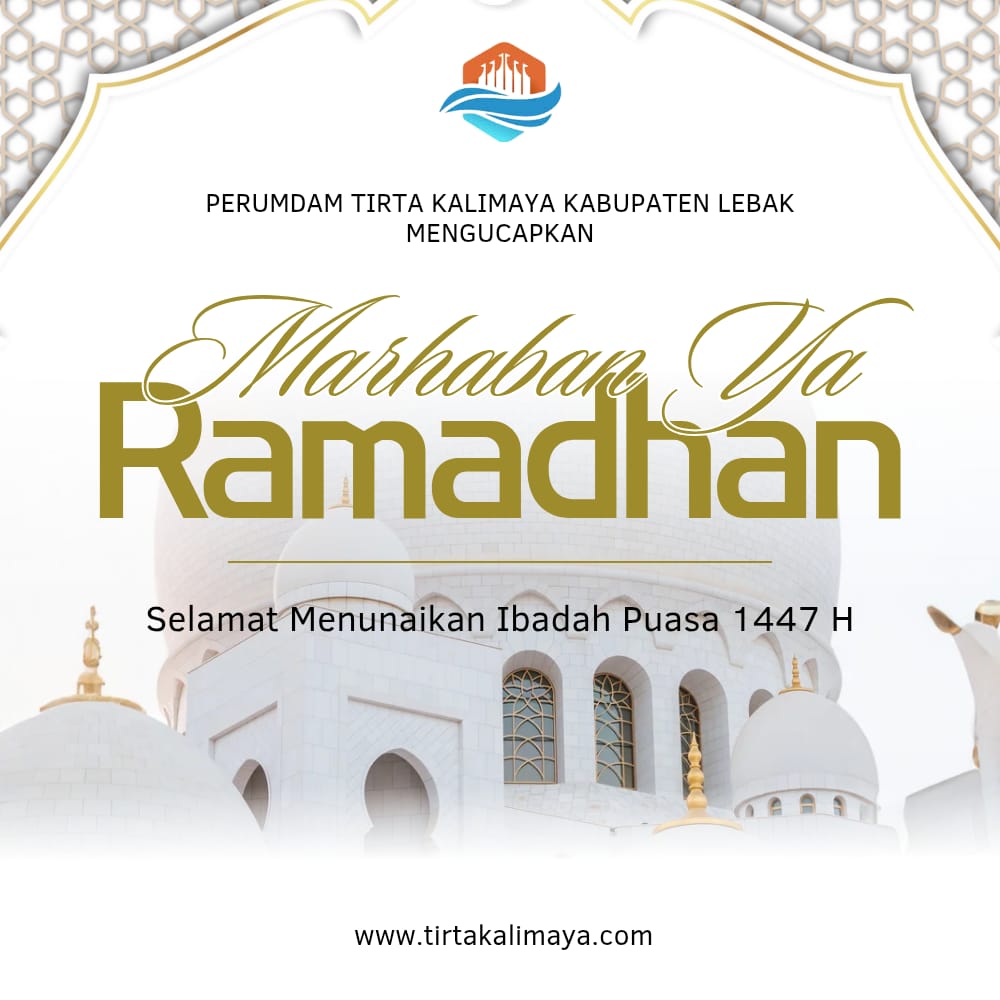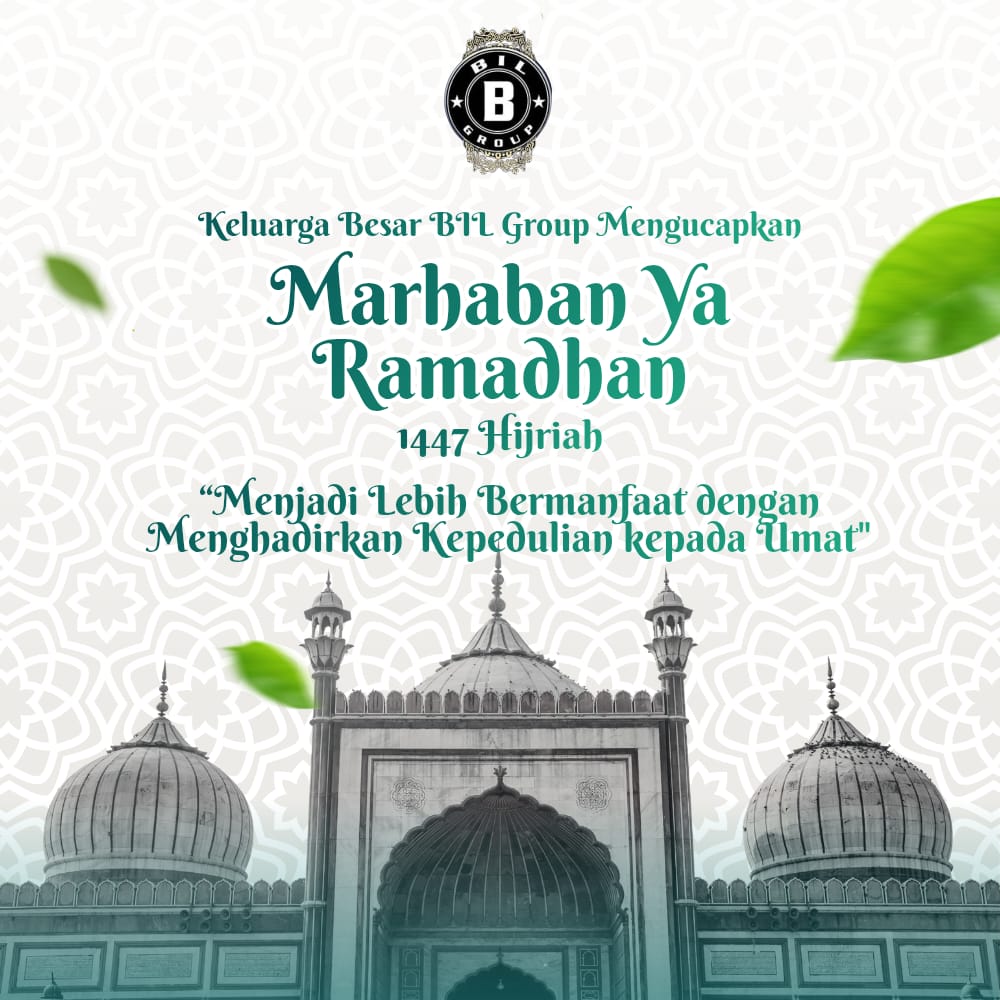KETIK, BATU – Gelaran musik hardcore di Kota Batu berakhir tragis. Ritual ekspresif musik cadas yang dikenal sebagai “moshing” berujung pada tindak kekerasan brutal, mencederai dua musisi.
Dua musisi dari band hardcore asal Kabupaten Malang dilaporkan menjadi korban pengeroyokan di area mosh pit saat acara berlangsung baru-baru ini.
Salah satu korban bahkan menderita luka serius akibat sabetan senjata tajam. Insiden ini merusak citra mosh pit yang seharusnya menjadi ruang solidaritas dan ekspresi kolektif.
Peristiwa ini menarik perhatian terhadap fenomena moshing itu sendiri. Beberapa orang pencinta musik punk, hardcore, dan metal menyalurkan kecintaannya melalui gerakan “moshing”, yang merupakan simbol energi kolektif.
Namun, apa jadinya jika ritual kolektif yang seharusnya menjadi simbol energi dan solidaritas komunitas justru berujung pada kekerasan brutal? Kasus di Kota Batu ini mempertegas garis tipis antara ekspresi fisik dalam musik cadas dan aksi kriminalitas yang mengancam nyawa.
Berikut ulasan ketik.com mengenai sejarah dan esensi moshing, dihimpun dari berbagai sumber.
Fenomena moshing sudah terbentuk sejak akhir 1970-an. Menurut catatan sejarah, gerakan moshing lahir dari kebiasaan “pogo” komunitas punk di Los Angeles, Amerika Serikat, sekitar tahun 1975–1980.
Pada masa awal skena punk di AS, para penggemar suka bergerak dengan cara sederhana: melompat vertikal ke atas dan ke bawah mengikuti musik. Tarian ini dikenal sebagai pogo.
Seiring berkembangnya musik dan intensitas konser, muncul bentuk tarian yang lebih “fisik”: slam dancing. Di sini, peserta tak lagi hanya lompat-lompat, tetapi mulai saling mendorong, berjalan mengitari area, serta membuat kontak tubuh yang lebih sengit.
Istilah moshing digunakan untuk menggambarkan perilaku ini. Lokasi di depan panggung, tempat para mosher (sebutan untuk pelaku moshing) berkumpul untuk melakukan aksi tersebut, kemudian dikenal sebagai mosh pit.
Menurut Wikipedia, kata “mosh” sendiri berasal dari salah dengar kata “mash”. Saat vokalis band Bad Brains (scene hardcore) menyanyikan salah satu lagunya “Banned in D.C.” dan melafalkan lirik lagunya menjadi “mash it, mash down babylon”, beberapa penonton mendengarnya sebagai “mosh it”, kemudian istilah itu berkembang dan melekat kuat.
Awalnya berkembang di komunitas hardcore di California (sekitar Huntington Beach dan Long Beach) pada akhir 1970-an. Dari sana, moshing menyebar ke skena lain seperti di Washington D.C., Boston, dan New York pada dekade 1980-an, dan kemudian merambah ke musik metal.
Seiring waktu, mosh pit pun mengalami variasi: tidak hanya sekadar saling dorong, tetapi muncul gaya lain seperti circle pit, dan bentuk pit yang lebih tertata.
Lebih dari sekadar “aksi kacau”, moshing menjadi simbol energi kolektif di konser. Penonton yang “mosh” bukan hanya mengekspresikan kegembiraan, tetapi merespons intensitas musik dengan cara fisik sebuah komunikasi non-verbal antara musisi dan audiens.
Keberadaan mosh pit pun menjadi ruang ritualistik: selain sebagai tempat “melepaskan diri”, beberapa penonton menyebutnya sebagai momen solidaritas komunitas di mana seseorang yang jatuh akan diangkat, dan semua peserta memahami “aturan tak tertulis” agar tidak sengaja melukai teman di sekitarnya.(*)




![Thumbnail Berita - [FOTO] Hangat dan Penuh Keakraban, Ah Pek Kopitiam Malang Jadi Tempat Favorit Kumpul Keluarga dan Sahabat](https://ketik.com/assets/upload/57072026021417515410001454080.webp)