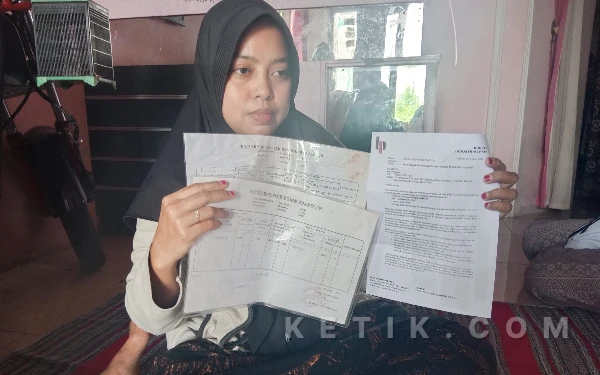Kepercayaan publik itu seperti kaca. Sekali retak, sulit kembali utuh. Beberapa tahun terakhir, kita merasakan retakan itu makin lebar dalam hubungan antara pemerintah dan warga. Bukan hanya karena berita bohong atau hoaks, tapi karena cara pemerintah berbicara dengan publik tidak lagi sejalan dengan cara publik hidup dan berinteraksi di era digital.
Hari ini, kita hidup di tengah arus informasi yang diatur algoritma, di mana perhatian menjadi rebutan, dan emosi sering menang atas argumen. Dalam situasi seperti itu, komunikasi pemerintah tidak bisa lagi berhenti pada laporan kinerja dan konferensi pers. Yang diuji bukan cuma isi pesannya, tapi kehadiran, cara merespons, dan konsistensi.
Para peneliti komunikasi politik digital seperti Klinger, Kreiss, dan Mutsvairo (2025) mengingatkan: platform digital bukan sekadar “pengeras suara”, melainkan aktor yang ikut menentukan apa yang tampak di layar gawai kita dan bagaimana kita memaknai peristiwa. Artinya, pemerintah tak bisa merasa sudah “komunikatif” hanya karena rajin mengunggah infografis dan siaran pers.
Di Indonesia, penelitian Nur Atnan dan Abrar (2023) menemukan hal yang cukup menampar: yang paling berpengaruh terhadap perilaku komunikasi warga di kanal resmi pemerintah adalah literasi media sosial dan trust, bukan kualitas informasinya. Dengan kata lain, seakurat apa pun datanya, kalau warganya sudah tidak percaya, ya tetap akan diabaikan.
Tulisan ini ingin mengajak kita melihat sejenak: di mana sebenarnya letak salah urus komunikasi pemerintah di era digital, dan apa pilar yang perlu dibangun kalau kita sungguh-sungguh ingin mengembalikan kepercayaan publik.
Ketika Pemerintah Hanya “Melaporkan”, Bukan Hadir
Jika kita menyimak, cukup banyak akun resmi pemerintah di media sosial mirip papan pengumuman digital: rapi, formal, tapi dingin. Saya mencatat beberapa persoalan dari cara mengelola akunnya.
Pertama, pemerintah masih betah dengan pola satu arah. Tugas dianggap selesai setelah laporan diposting. Warga bertanya di kolom komentar, tapi dibiarkan menggantung seperti bicara pada tembok.
Kedua, komunikasi sering terjebak menjadi promosi, bukan hubungan. Yang tampil adalah deretan keberhasilan: diresmikan, di-launching, dihadiri, dibuka. Jarang ada pengakuan kesulitan, keraguan, atau dialog tentang konsekuensi kebijakan. Di mata publik, ini tampak seperti jarak, bukan kepemimpinan.
Ketiga, ketika ada kesalahan atau kritik, respons pemerintah sering defensif. Klarifikasi terlambat, bahasa kaku, dan kesan enggan mengakui kekeliruan. Di dunia yang bergerak secepat notifikasi, keterlambatan koreksi ini terbaca sebagai ketidakjujuran, bukan sekadar keterlambatan birokrasi.
Keempat, yang nyaris hilang adalah empati. Di platform yang logikanya menjual emosi, pemerintah kerap hadir dengan bahasa teknokratis dan dingin. Di tengah warga yang marah, cemas, atau kebingungan, muncul kalimat kering: “Sesuai dengan ketentuan yang berlaku…”. Rasional, tapi tidak menyentuh.
Kelima, koordinasi antarinstansi masih sering berantakan. Satu lembaga bilang A, lembaga lain bilang B, pejabat lain lagi bilang C. Bagi publik, ini bukan soal “kompleksitas administrasi”, tapi kesan bahwa negara tidak punya narasi yang jelas.
Jadi persoalannya bukan sekadar “kurang sosialisasi”, tetapi model komunikasi yang tidak cocok dengan ekologi media digital.
Politik Narasi di Tangan Platform
Dalam buku Platforms, Power, and Politics (2025), Klinger, Kreiss, dan Mutsvairo menjelaskan bagaimana struktur platform menentukan apa yang tampak, apa yang viral, dan apa yang lenyap di timeline. Di situ, pemerintah bukan lagi satu-satunya sumber kebenaran. Ia hanya satu pemain di tengah banyak aktor: influencer, media, buzzer, sampai akun anonim.
Di media sosial, yang menentukan apakah sebuah pesan “naik ke permukaan” bukan sekadar jabatan pengirimnya, tetapi bentuk, emosi, dan interaksi yang terjadi di sekitarnya. Infografis resmi pemerintah bisa saja tenggelam, sementara video pendek seorang influencer yang marah-marah tentang kebijakan yang sama justru viral dan menjadi bahan obrolan di warung, grup WhatsApp, hingga podcast.
Bayangkan kasus sederhana. Pemerintah daerah mengumumkan kebijakan penataan PKL di sebuah alun-alun kota lewat siaran pers resmi dan poster rapi: ada infografis, ada peta zonasi, ada kalimat “untuk ketertiban bersama”.
Di saat yang sama, seorang pedagang kecil mengunggah video 30 detik: wajah berkeringat, suara bergetar, bercerita bahwa ia khawatir tidak bisa lagi berjualan di tempat yang selama ini menghidupi keluarganya.
Secara algoritmik, platform akan lebih “mengangkat” video pendek yang penuh emosi itu: orang menonton sampai habis, komentar mengalir, dan share terus bertambah.
Poster resmi pemerintah yang berisi informasi lengkap bisa saja tetap ada di lini masa, tetapi tidak dilihat, tidak dibaca, dan tidak diingat. Di sinilah terlihat bahwa platform bukan ruang netral; ia punya selera sendiri terhadap jenis konten yang “didorong” ke banyak orang.
Grossmann dan Hopkins (2016) juga mengingatkan bahwa publik tidak lagi menilai pemerintah dari rumitnya detail teknis, tetapi dari koherensi narasi. Masyarakat tidak membaca semua dokumen; mereka menangkap pesan dari potongan-potongan pernyataan yang beredar.
Misalnya, pagi hari seorang pejabat mengatakan “situasi banjir terkendali”, siang harinya pejabat lain mengakui “ada pompa yang tidak berfungsi”, lalu malam hari keluar pernyataan baru lagi yang menyalahkan perilaku warga karena “buang sampah sembarangan”. Publik tidak akan repot mengurai mana yang paling akurat. Yang tertinggal di kepala mereka sederhana saja: “negara tidak kompak” dan “kalau salah, yang disalahkan selalu rakyat”.
Di banyak daerah di Indonesia, kita sering melihat pola seperti ini saat musim hujan. Warga mengunggah video banjir di gang sempit, memperlihatkan air setinggi lutut, motor mogok, anak-anak harus digendong untuk berangkat sekolah. Video-video ini disertai komentar yang emosional: “Katanya sudah dinormalisasi, kok tiap tahun begini terus?” Narasi semacam ini dengan cepat menyebar dan membentuk persepsi, jauh sebelum pemerintah sempat menjelaskan proyek drainase yang sebenarnya memang ada dan berjalan.
Sementara itu, studi Pureklolon, Pawe, dan Pramono (2024) atas Indonesia, India, dan Brasil menunjukkan bahwa aktor politik yang berhasil justru mereka yang menggabungkan informasi dengan pengalaman emosional: narasi yang mudah dibagikan, mudah diingat, dan terasa dekat.
Mereka tidak sekadar berkata, “Kami sudah menyalurkan bantuan,” tetapi mengajak publik “ikut masuk” ke dalam cerita: memperlihatkan proses, bertemu warga yang menerima manfaat, merekam kegelisahan di lapangan, dan menunjukkan bagaimana keputusan diambil.
Contoh lain mudah kita temukan saat penyaluran bantuan sosial. Akun resmi pemerintah mengumumkan: “Bantuan tahap kedua telah disalurkan kepada 10.000 keluarga penerima manfaat,” lengkap dengan foto seremonial dan daftar kecamatan.
Di sisi lain, ada video dari sebuah kampung yang memperlihatkan antrean panjang, sebagian warga mengeluh belum terdata, ada lansia yang datang tapi pulang dengan tangan kosong. Video ini diberi caption, “Katanya bantuan untuk rakyat kecil, kok kami tidak kebagian?”
Walaupun di atas kertas data penyaluran bantuan itu benar, yang dipercaya publik adalah pengalaman yang terlihat di layar, bukan angka di laporan. Pemerintah bisa saja merasa sudah transparan dengan mempublikasikan angka, tetapi di mata warga, narasi yang menang adalah narasi yang mereka lihat, dengar, dan rasakan sendiri.
Di titik inilah pemerintah Indonesia masih sering terjebak pada logika “pengumuman”: merasa tugas selesai setelah informasi diposting. Padahal, di ruang digital, yang dibutuhkan bukan hanya pengumuman, tetapi percakapan dan pengelolaan narasi. Pemerintah perlu hadir bukan hanya sebagai “juru bicara kebijakan”, tetapi sebagai pihak yang bersedia menjelaskan dengan bahasa yang bisa dipahami, mendengar keluhan dengan serius, dan ikut mengalami kegelisahan warganya.
Enam Pilar Komunikasi Pemerintah di Era Digital
Gambaran di atas menunjukkan satu hal: pola lama komunikasi pemerintah sudah tidak memadai untuk menjawab tantangan zaman. Jika cara berbicara tidak berubah, kepercayaan publik akan terus terkikis pelan-pelan. Karena itu, kita perlu menata ulang fondasi komunikasinya. Kalau kepercayaan publik ingin dibangun ulang, setidaknya ada enam pilar komunikasi yang perlu diperkuat.
1. Hadir sebagai Manusia, Bukan Sekadar Lembaga
Kehadiran pemerintah di media sosial tidak diukur dari seberapa banyak unggahan, tetapi seberapa serius menjawab warga. Warga berkomentar bukan sekadar ingin “didengar”, tapi ingin diakui.
Artinya, akun resmi tak cukup hanya menjadi etalase program, tapi juga ruang dialog. Ada saatnya merilis data, ada saatnya menjelaskan dengan bahasa sederhana, ada saatnya sekadar mengatakan, “Kami mengerti Anda marah, dan ini yang sedang kami lakukan.”
2. Transparan pada Proses, Bukan Hanya Hasil
Sering kali pemerintah baru bicara ketika keputusan sudah final. Publik diajak “menerima”, bukan “memahami”. Padahal, kepercayaan tumbuh ketika warga diajak mengikuti perjalanan keputusan, bukan cuma diberi tahu hasil akhirnya.
Menjelaskan kenapa opsi A dipilih ketimbang B, apa risiko kebijakan, dan apa yang akan dievaluasi, membuat publik merasa diperlakukan sebagai mitra, bukan obyek sosialisasi.
3. Berani Mengakui Salah, Cepat Mengoreksi
Di dunia digital, yang lambat akan digilas narasi lain. Karena itu pemerintah perlu punya protokol koreksi cepat: kapan harus merespons, siapa yang bicara, dan melalui kanal apa.
Mengakui salah tidak mengurangi wibawa; justru sebaliknya, memperlihatkan kematangan. Warga jauh lebih mudah memaafkan kesalahan yang diakui, dibanding kesalahan yang disapu di bawah karpet.
4. Menjadikan Empati sebagai Infrastruktur Komunikasi
Empati bukan sekadar “hiasan” dalam pidato. Ia adalah fondasi. Pada saat terjadi bencana, kenaikan harga, atau kebijakan yang menimbulkan ketidaknyamanan, publik ingin merasakan bahwa pengambil kebijakan memahami beban mereka.
Kalimat seperti “Kami tahu ini berat bagi Anda” mungkin sederhana, tapi ketika tulus dan diikuti tindakan, ia lebih kuat dari seribu infografis.
5. Menyusun Satu Tulang Punggung Narasi
Pemerintah perlu memiliki tulang punggung naratif yang disepakati lintas instansi: apa yang ingin dibangun, masalah apa yang diakui, dan harapan apa yang ingin dibagi. Dari situ, masing-masing instansi boleh berbicara dengan gaya sendiri, tapi tetap dalam satu garis besar.
Tanpa itu, perbedaan penjelasan akan terus dibaca publik sebagai pertentangan, bahkan kecurigaan.
6. Mengajak Publik Menjadi Bagian dari Cerita
Kepercayaan tidak lahir dari monolog. Ia tumbuh dari kolaborasi. Pemerintah perlu membuka ruang bagi masyarakat sipil, akademisi, komunitas lokal, dan figur publik untuk ikut merumuskan pesan, memeriksa data, dan menyebarkan narasi.
Di sini, komunikasi bukan lagi “pemerintah bicara, rakyat mendengar”, tetapi “kita bicara bersama, mencari jalan keluar yang masuk akal”.
Menyaring sebelum Mengucap
Era digital memaksa pemerintah untuk berubah. Tidak cukup sekadar memperbanyak akun, mempercantik desain, atau menggelar konferensi pers. Yang dibutuhkan adalah kerendahan hati untuk mendengar, keberanian mengakui salah, dan kesediaan berbagi panggung dengan publik.
Komunikasi publik, pada akhirnya, bukan sekadar soal teknik: ia adalah ruang politik yang menentukan apakah pemerintah masih dipercaya atau tidak. Di sini, saya teringat nasihat Sayyidina Ali yang relevan untuk setiap pejabat, juru bicara, dan pengelola akun resmi: “Mengetahui apa yang perlu disampaikan itu penting.. Tapi mengetahui apa yang tidak perlu disampaikan, jauh lebih penting”.
Mungkin, di era digital yang bising dan serba cepat ini, kepercayaan publik justru mulai dibangun dari kemampuan pemerintah menyaring sebelum mengucap, mendengar sebelum menjawab, dan hadir sebelum mengklaim berhasil. (*)
*) Suko Widodo adalah Akademisi Universitas Airlangga, Surabaya
**) Isi tulisan di atas menjadi tanggung jawab penulis
***) Karikatur by Rihad Humala/Ketik.com
****) Ketentuan pengiriman naskah opini:
- Naskah dikirim ke alamat email redaksi@ketik.co.id.
- Berikan keterangan OPINI di kolom subjek
- Panjang naskah maksimal 800 kata
- Sertakan identitas diri, foto, dan nomor HP
- Hak muat redaksi. (*)