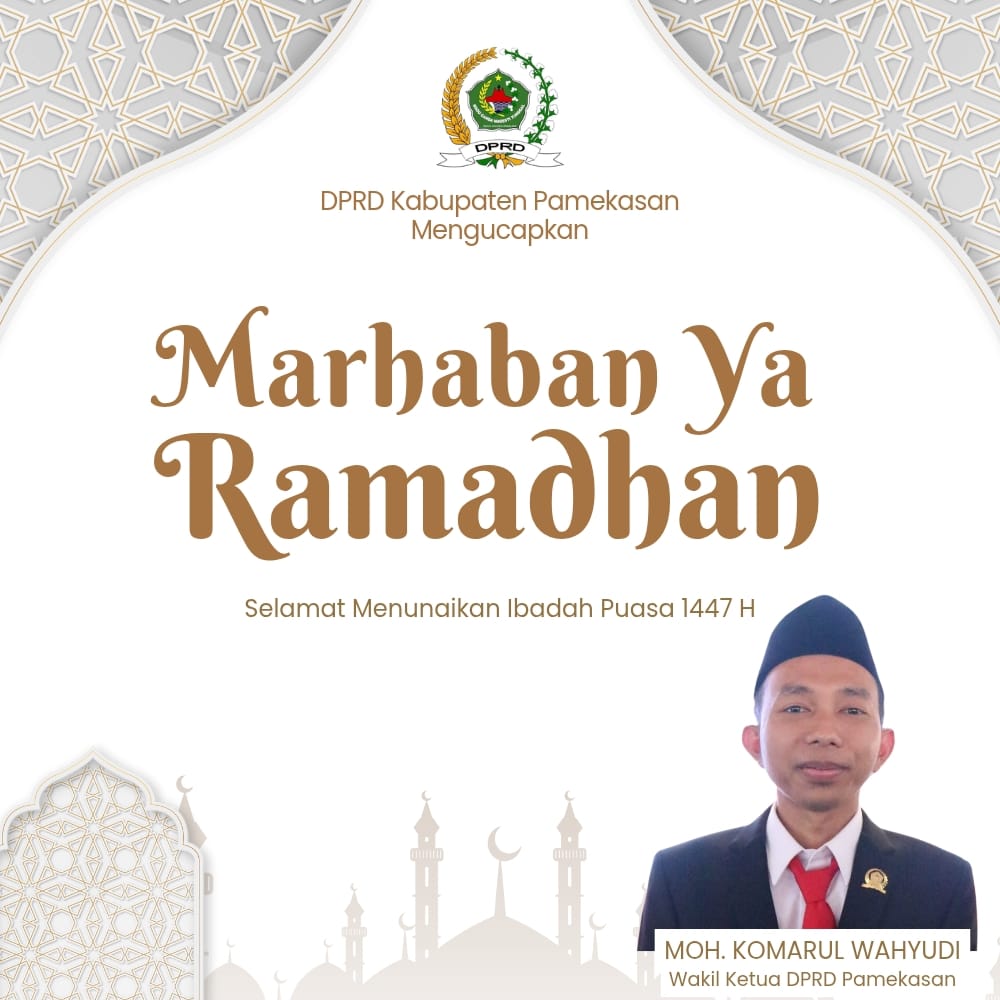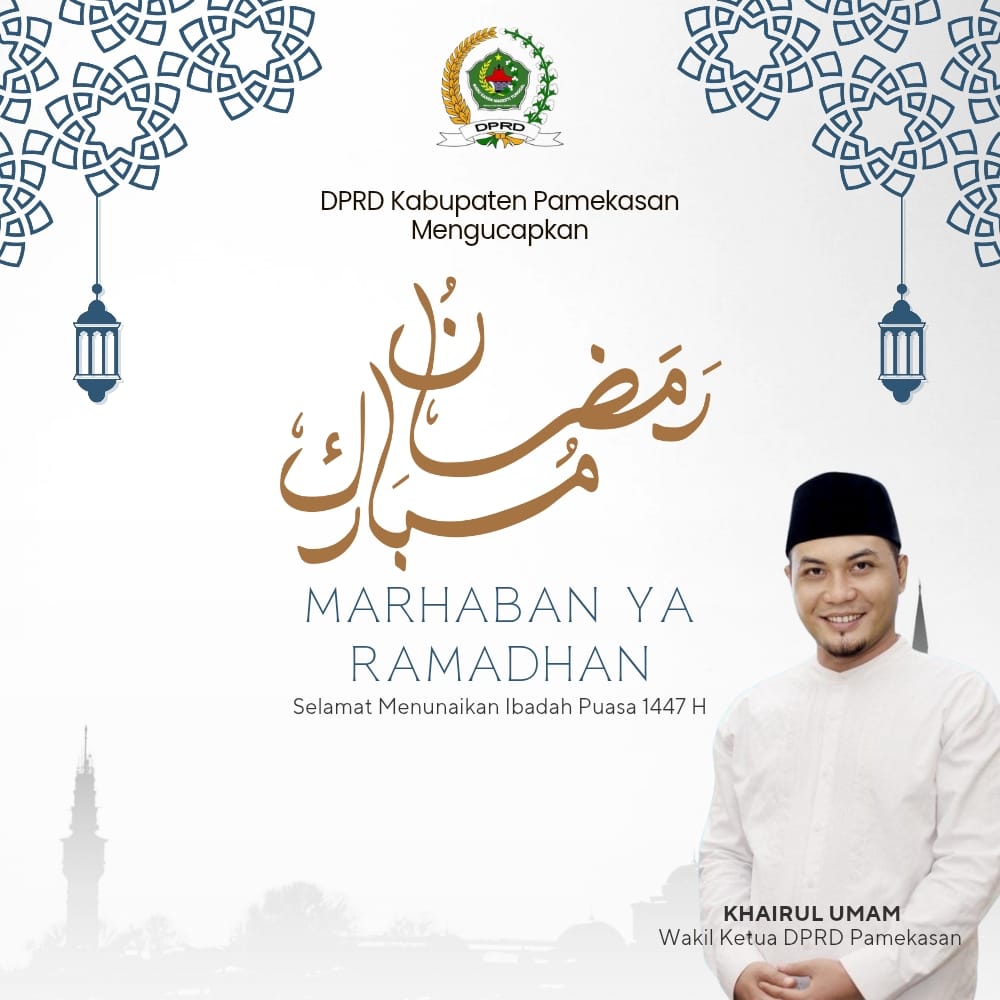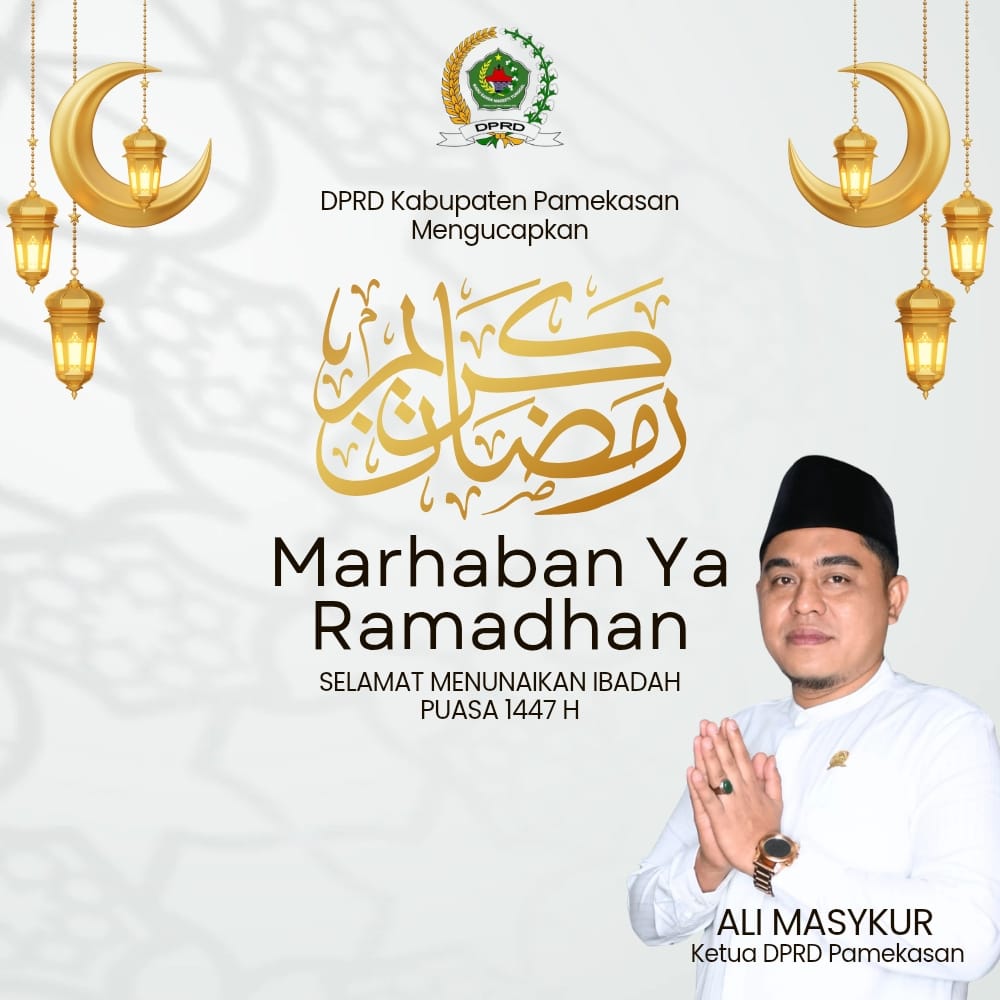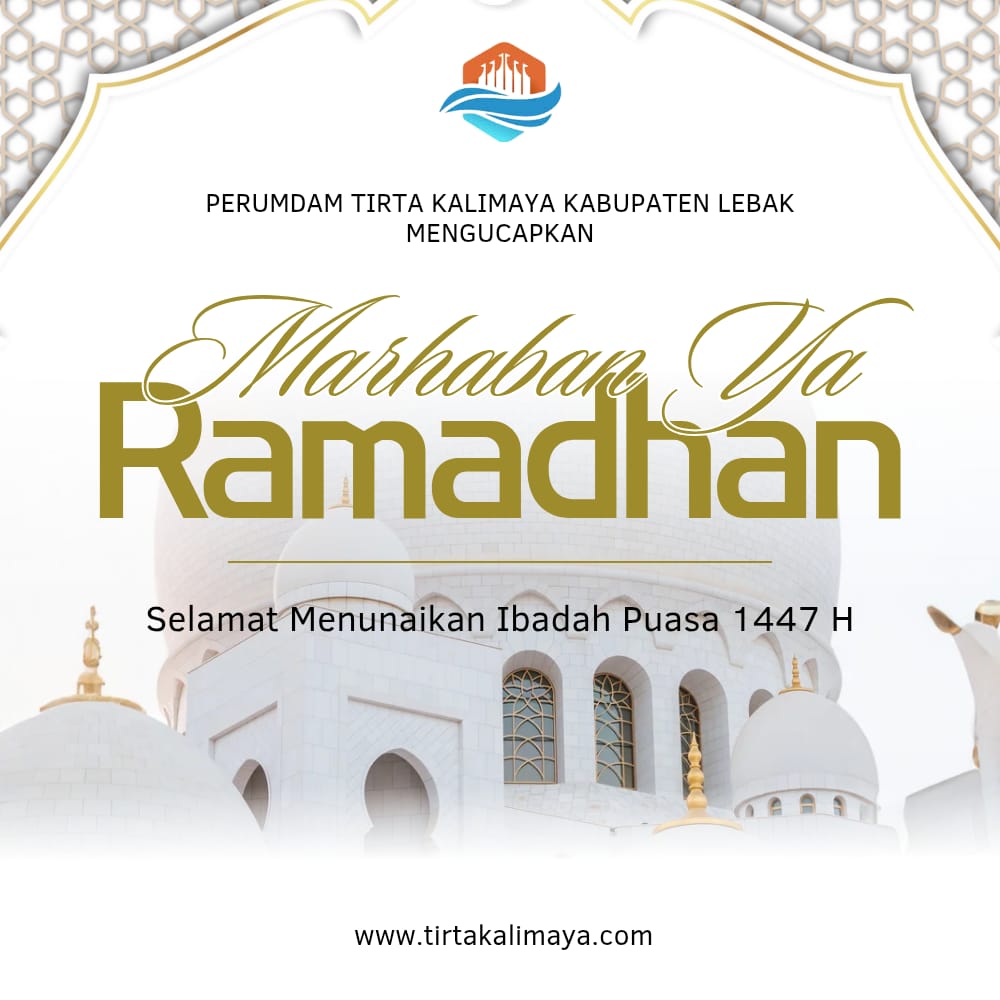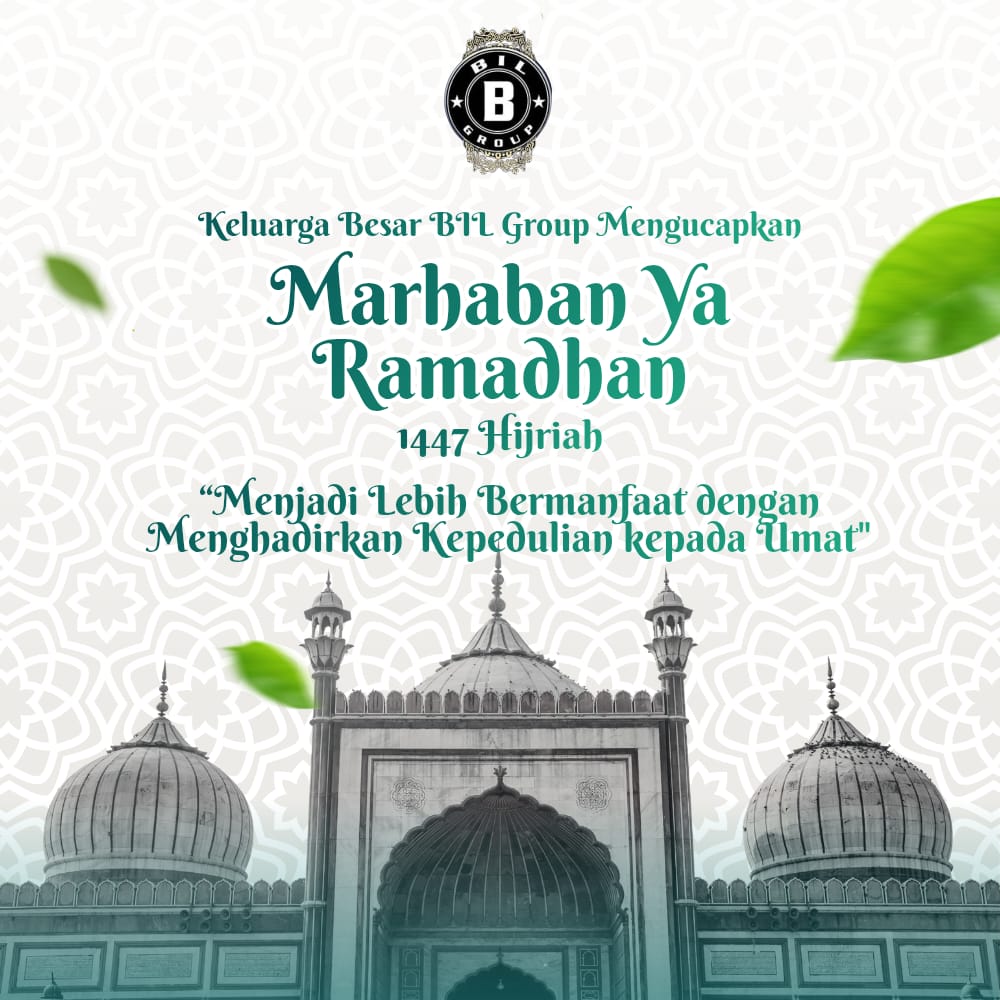Tulisan ini tentu saja berangkat dari pemaknaan terhadap sebuah eksistensi. Dan penulis, jujur saja, dan ini diakui oleh banyak orang, adalah orang yang haus akan eksistensi (eksistensialis). Penulis merasa bahwa hidupnya tak cukup jika hanya diam.
Mereka merasa mengeluarkan ide-ide yang ada dalam pikirannya, informasi yang awalnya diserap lalu ia muntahkan kembali sebagai informasi untuk orang lain lewat tulisannya.
Informasi yang sudah diolah—yang bisa jadi dalam bentuk ‘framing’, dalam artian ia adalah informasi yang sudah berbingkai. Atau isi kepala yang ia dapat selama hidupnya untuk dikeluarkan.
Lalu, apakah penulis itu punya peran untuk kemajuan daerah?
Penggerak Demokrasi Informasi
Sebagai sebuah produsen ide dan informasi, kontribusi penulis tergantung pada sebanyak apakah tulisannya dan seberapa menarik tulisannya untuk dibaca orang. Lalu, sejauh mana tulisannya mempengaruhi pikiran orang lain.
Kata ‘mempengaruhi’ di sini bisa diartikan dua hal. Pertama, isi tulisannya tajam dan dalam, kritis dan menggugah, lalu orang yang membacanya mendapatkan pemahaman baru. Kedua, tulisan yang menimbulkan banyak diskusi dan melahirkan perbincangan yang membuat orang banyak memikirkan suatu hal, lalu melahirkan dialektika kesadaran.
Masalahnya adalah: seberapa banyak orang yang menulis dan seberapa banyak yang membacanya? Ini tergantung banyak hal. Bahkan di era milenial, hal ini tergantung apa medianya. Media cetak sudah banyak ditinggalkan. Koran sudah banyak yang tidak baca. Buku? Bisa jadi buku juga demikian.
Buku cetak mungkin sebagian sudah disuguhkan dalam versi online atau PDF. Meskipun jumlah buku PDF yang saya miliki di laptop saya tetap tak sebanyak jumlah judul buku yang ada di delapan lemari atau rak buku saya di rumah.
Apalagi di perpustakaan daerah yang jumlahnya semakin banyak dan lemarinya bagus-bagus, pun tempatnya juga bersih yang membuat pengunjung menjadi nyaman.
Saya sendiri lebih nyaman membaca buku cetak daripada buku pdf. Saya lihat, perpustakaan daerah seperti Perpustakaan Daerah Trenggalek juga semakin ramai.
Tiap saya ke sana, yang biasanya minimal seminggu sekali, pasti ada aja anak muda atau remaja, yang sedang duduk di meja sambil membaca buku—atau yang sedang mencari-cari buku yang tertata di rak-rak. Juga selalu ada anak-anak kecil yang didampingi orangtuanya di tempat buku anak-anak di pojok selatan-barat ruangan baca. Ada yang membaca atau melihat gambar-gambar, ada juga yang bermain.
Jadi, ternyata orang yang membaca buku cetak juga masih ada. Tentu hal ini bisa dilihat dari data peminjaman buku itu di perpustakaan.
Kenapa masih ada orang suka membaca buku cetak? Saya kira, sensasi membaca buku cetak lebih “berasa” dibanding membaca buku pdf atau membaca tulisan online. Bahkan ada beberapa Negara yang mengembalikan tradisi membaca buku cetak—salah satunya melihat sisi negatif budaya online.
Di daerah saya, Trenggalek, penulis buku yang kemudian dicetak jumlahnya lumayan. Ada yang dicetak oleh penerbit ‘major’—dalam artian mereka adalah penulis professional yang menulis naskah buku lalu naskahnya diterbitkan penerbit komersil yang membuat penulisnya mendapatkan duit (dari royalty atau “beli putus”).
Saya adalah salah satunya. Beberapa buku beberapa tahun lalu masih menyisakan royalty untuk saya hingga sekarang, yang hasilnya bisa saya pakai untuk bertahan hidup (‘slow living’).
Ada juga buku karya penulis Trenggalek yang dicetak secara ‘indie’. Dalam hal ini penulis mencetak buku (membukukan tulisannya) bukan untuk dijual dalam rangka mencari pendapatan apalagi keuntungan.
Tapi hanya untuk sekadar eksis atau agar karya bisa terbukukan. Bahkan para penulis yang karyanya dibukukan membiayai karyanya secara patungan. Artinya mengeluarkan duit sendiri untuk menerbitkan karyanya. Di antaranya adalah guru atau dosen yang ingin mendapat “portofolio” yang bisa memperlancar kariernya dan mendapatkan tunjangan sertifikasi.
Sementara itu para penulis yang menerbitkan karyanya di media online juga tak kalah eksis. Jumlah media online yang kian menjamur memungkinkan para penulis memuat karyanya secara online. Yang saya maksud di sini adalah tulisan yang berupa ‘news’—baik ‘straight news’ atau liputan jurnalistik—ataupun opini atau artikel di media online.
Penulis berita disebut jurnalis (wartawan). Sedangkan penulis opini atau esai ada yang penulis lepas yang tak terikat dengan media. Seperti saya dengan tulisan-tulisan saya di media ini dan beberapa media lainnya.
Intinya, para penulis daerah ini, eksis dengan perannya menyebarkan informasi dan edukasi lewat tulisan. Mereka menjadi pilar utama demokrasi informasi dengan menjalankan hak-hak informasi mereka—terutama hak untuk menyebarkan informasi, ide, gagasan—baik yang analitis dan yang kritis.
Banyak tulisan-tulisan yang kritis yang saya jumpai. Ini menarik karena dalam demokrasi kritik merupakan hal yang baik—termasuk sebagai kontrol kebijakan, khususnya tulisan-tulisan yang menyoroti kebijakan publik. Dus, di sini, peran penulis bisa dikatakan sebagai kontrol sosial.
Penulis dan Ekonomi Daerah
Kira-kira peran apa lagi yang dimainkan penulis? Kalau misalnya ada peran ekonomi, apakah kira-kira ada dan tidakkah berlebihan jika keberadaan penulis bisa berperan dalam ekonomi?
Ya tidak berlebihan. Tapi memang tidak mungkin penulis akan menjadi penggerak ekonomi yang menentukan. Ia hanya bermain dalam remahan-remahan ekonomi. Ia bisa di sektor formal, tapi kebanyakan informal. Tentunya, sebagai warga Negara mereka membayar pajak.
Setidaknya setiap warga Negara pasti menjadi bagian dari kehidupan ekonomi. Dan yang terpenting adalah jika keberadaannya sebagai agregat ekonomi, bukan sebagai parasit tetapi punya kontribusi bagi warga lain.
Kalau ada kasus wartawan ditangkap tangan memeras orang di dinas, sementara ia jarang menulis sama sekali, tentu ini bisa disebut sebagai parasit. Saya jadi ingat nasehat orangtua: Setidaknya kalau tak bisa jadi obat, jangan jadi penyakit!
Menariknya, di daerah seperti Trenggalek yang merupakan kota kecil ini, para jurnalis menghasilkan ekonominya dari pekerjaannya sebagai penulis. Ini saja sudah jelas perannya. Dari penghasilannya, mereka membayar pajak penghasilan.
Mereka mendapatkan gaji atau honor dari dari perusahaan media baik yang berkantor pusat di luar kota dan dalam kota (kabupaten). Mereka membawa uang dari luar ke Trenggalek. Juga dari iklan-iklan produk yang dimuat di medianya. Peran mereka adalah membantu mempromosikan produk-produk, termasuk produk lokal.
Yang paling menarik adalah ketika penulis/jurnalis lokal mendapatkan uang dari luar daerah, lalu pendapatannya digunakan untuk membeli (konsumsi) barang-barang kebutuhan di Trenggalek di kampungnya. Berarti, mereka membawa uang dari luar untuk menambah peredaran uang di Trenggalek. Tentu ini lebih ‘nasionalistik’ [sich!] daripada yang dilakukan oleh pemerintah daerah ketika uangnya dibelanjakan di luar Trenggalek (pengadaan barang dan jasa dari luar kabupaten).
Dalam hal ini, ‘government spending’ tidak bermanfaat untuk menyemarakkan ekonomi di dalam daerah, tapi memberi rejeki pada orang di luar daerah yang tentunya uangnya dibelanjakan di luar.
Sedangkan para penulis dan jurnalis Trenggalek yang menerima gaji atau honor dari luar Trenggalek, uangnya dibelanjakan di Trenggalek. Beda lagi dengan ketika tak jarang pejabat Trenggalek yang sering plesir ke luar daerah dan membelanjakan uangnya di luar daerah. Belum lagi kalau ada dinas yang suka membuat acara pemerintah daerah di luar daerahnya.
Penulis yang mendapatkan royalti tiap tiga bulan dari penerbit di beberapa kota (Jakarta, Yogya, Bandung) lalu menggunakan uang hasil jerih payah memproduksi tulisan itu dengan membelanjakannya di warung tetangga, tentu lebih baik daripada menghambur-hamburkan uang di luar daerahnya. Belum lagi kontribusinya yang membayar pajak untuk Negara.
Juga tumbuhnya perusahaan percetakan lokal yang sudah bisa mencetak buku karya lokal. Dengan munculnya para penulis yang ingin menghasilkan karyanya berupa buku, ternyata nyetaknya juga di perusahaan lokal. Hal ini bisa menghidupkan usaha lokal yang membuat usaha-usaha tersebut eksis dan menyerap tenaga kerja.
Kepuasan menerbitkan karya berupa buku, memang kadang tak bisa tergantikan dibanding memosting artikel atau tulisan panjang di status facebook atau di website (media online). Kebutuhan para penulis dan munculnya para penulis indie itulah yang membuat usaha percetakan juga mendapatkan rejekinya.
Apresiasi terhadap peran penulis ini ada kalanya diapresiasi oleh Negara, termasuk pemerintah daerah. Dulu, sebagaimana di ceritakan seorang sastrawan Ngawi, pemerintah daerah Ngawi memberikan insentif bagi penulis.
Misalnya, ketika tulisan penulis Ngawi dimuat di media nasional, maka pemerintah Ngawi akan memberi insentif beerupa uang tambahan. Ini seperti yang dulu dilakukan oleh Kampus UMM: Jika ada mahasisiswa atau dosen yang tulisanya di muat di media massa, maka waktu itu untuk mahasiswa akan diberi uang Rp75.000. Saya sendiri kurang tahu apakah kebijakan semacam itu masih berlaku sekarang.
Sebenarnya memang akan lebih baik jika Negara memahami peran para penulis, termasuk Negara dalam konteks pemerintah daerah. Di Trenggalek, dengan tindakan dinas perpustakaan daerah yang membeli buku para penulis Trenggalek, hal ini sudah lumayan bagus. Mungkin yang belum adalah memfasilitasi adanya pameran buku karya para penulis Trenggalek.
Produk literasi sendiri saat ini menghadapi tantangan budaya baca yang rendah. Orang tidak lagi tertarik menjadi penulis profesional, karena daya beli buku juga rendah. Tentu harus ada kolaborasi untuk memajukan baik budaya membaca, budaya menulis, dan budaya literasi secara umum.
Tugas pemerintah (Negara) untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa” sebagaimana amanat UUD 1945 menghadapi tantangan. Elemen-elemen yang paling strategis bagi pemajuan budaya cerdas adalah para pekerja budaya literasi seperti para penulis. Kolaborasi harus dilakukan untuk meningkatkan budaya literasi. Butuh peningkatan kesadaran akan tantangan yang kian besar, serta upaya strategis secara bersama untuk menghadapinya.***
*) Nurani Soyomukti, penulis, ketua komunitas literasi Quantum Litera Center (QLC); saat ini nyantri di pasca-sarjana Akidah Filsafat Islam Universitas Islam Negeri Tulungagung.