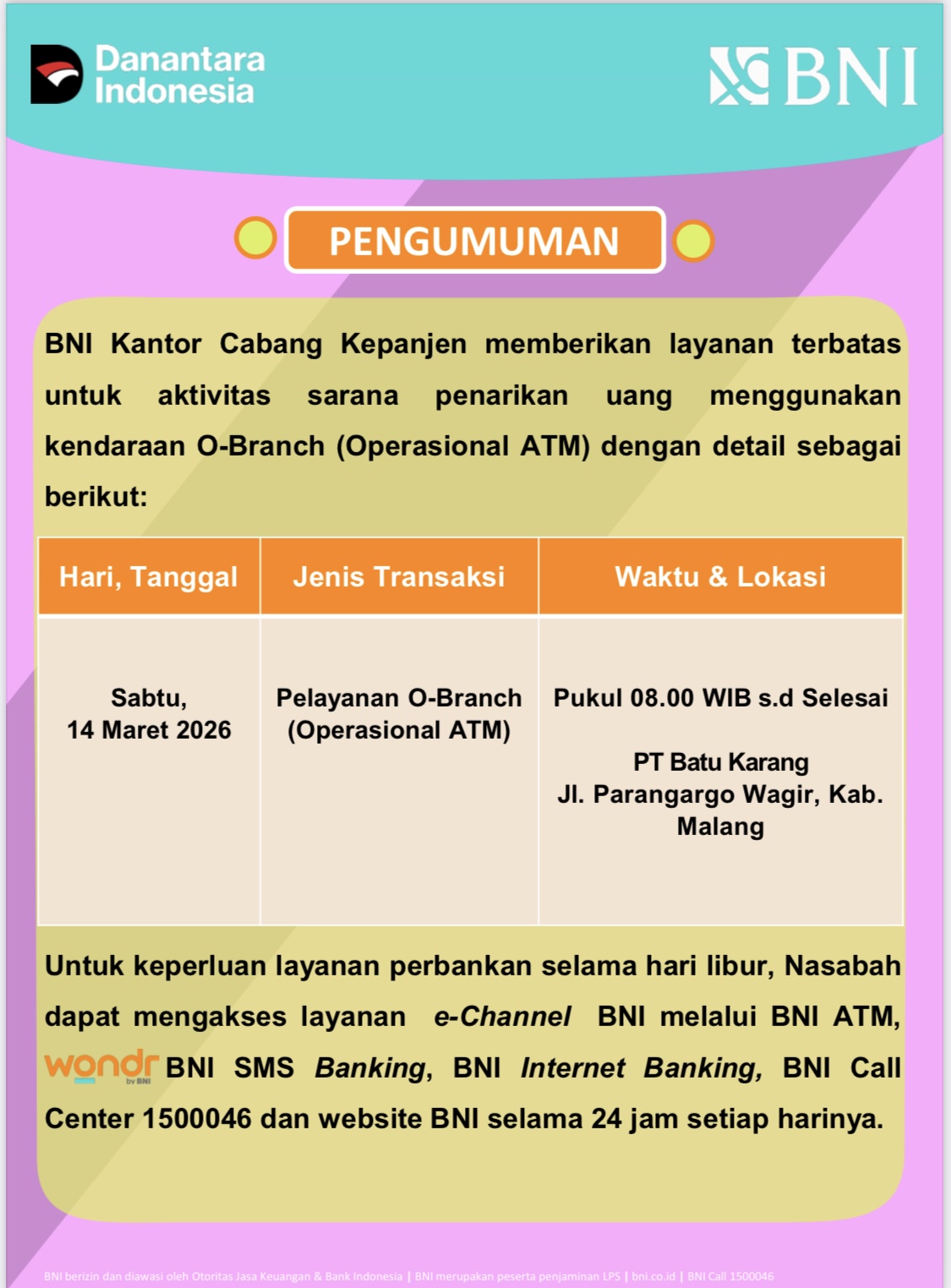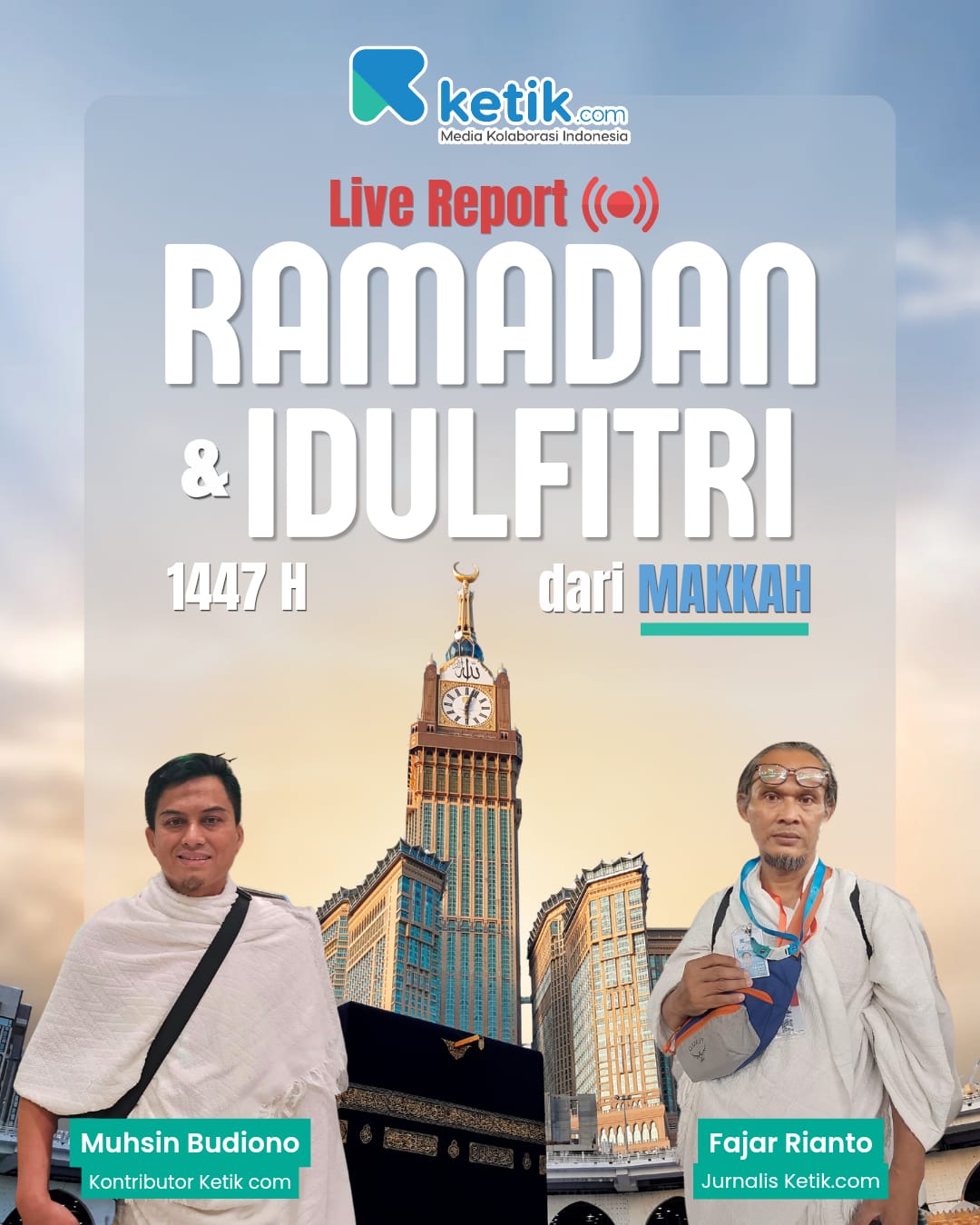KETIK, BLITAR – Malam itu, Senin 27 Oktober 20205, udara di Pasar Legi terasa lembab, seperti menahan napas menjelang hujan. Di sudut kedai kopi Selasar, meja-meja kayu dipenuhi cangkir beruap dan percakapan yang hangat.
Para aktivis, akademisi, dan jurnalis duduk bersisian, membahas makna Sumpah Pemuda dengan nada santai hingga seseorang datang dan mengubah segalanya.
Sekitar pukul delapan malam, Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin (Mas Ibin) melangkah masuk, disusul tiga puluh menit kemudian oleh Wakil Wali Kota Elim Tyu Samba (Mbak Elim).
Dua nama yang belakangan jadi buah bibir karena hubungan kerja yang dikabarkan renggang, kini duduk dalam satu ruang. Suasana seketika berubah. Kopi yang semula hangat terasa lebih panas.
Acara yang bertajuk Refleksi Sumpah Pemuda itu diinisiasi sejumlah tokoh aktivis Blitar. Ada Moh. Trijanto, aktivis antikorupsi yang dikenal lugas; Walid, akademisi UGM yang kerap bicara soal idealisme; dan Henni Indarriyanti, dosen sekaligus aktivis perempuan yang memandu jalannya diskusi.
Beberapa tokoh daerah turut hadir: Ketua LSM Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) Jaka Prasetya, Ketua PPI Kabupaten Blitar Mujianto, Ketua KPU Kota Blitar Rangga Bisma, Ketua IJTI Blitar Raya Robby Ridwan, dan Ketua SMSI Blitar Raya Prawoto Sadewo.
Malam itu, mereka tak hanya berbicara tentang sejarah pemuda 1928, tapi juga tentang kegelisahan Blitar hari ini.
Wali Kota Mas Ibin membuka sesi dengan paparan singkat soal makna Sumpah Pemuda: pentingnya kebersamaan dan nasionalisme di tengah perbedaan.
“Sumpah Pemuda adalah semangat untuk merajut persatuan, sebagaimana bangsa ini dibangun dari keberagaman,” ucapnya.
Namun, begitu sesi diskusi dimulai, arah pembicaraan segera bergeser. Aktivis Moh. Trijantomemantik debat dengan pernyataan yang tajam.
“Kegaduhan dan kondusifitas di Kota Blitar itu akibat kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Dan tanggung jawab tetap di tangan wali kota,” ujarnya lantang, disambut riuh tepuk tangan kecil dari beberapa peserta.
Wajah Mas Ibin begitu warga akrab menyapanya tampak menahan senyum. Ia membetulkan posisi duduk, mencoba menanggapi dengan tenang. Namun malam itu, forum tak memberi ruang luas bagi klarifikasi.
Giliran Prawoto Sadewo, Ketua SMSI Blitar Raya, angkat bicara. Ia dikenal ceplas-ceplos dan berani menyampaikan kritik terbuka.
“Kalau Kota Blitar ingin damai, Mas Ibin jangan mengkotak-kotakkan media. Ada yang disebut media Pemkot, media istana, dan lainnya. Itu memicu reaksi di kalangan pewarta,” katanya.
Nada suaranya tegas, tapi diselipi tawa kecil yang memecah ketegangan. Ia kemudian menambahkan dengan nada bergurau,
“Kalau Blitar ingin kondusif, ada lima kiat menyelesaikan perpecahan antara Wawali dan Mas Ibin. Tapi saya sebut dua saja, karena tiga sisanya mahal harganya," jelasnya.
Tawa pun pecah di antara peserta. Namun di balik lelucon itu, terselip sindiran serius.
“Kalau jadi wali kota itu susah, lepaskan ego politik sektoral. Walau dulu yang milih cuma sebagian, tapi sekarang saatnya merangkul semua warga. Jadilah bapaknya wong Blitar,” imbuhnya.
Suasana diskusi berubah menjadi debat konstruktif. Beberapa peserta mengangguk, sebagian lain memilih diam. Malam semakin larut, tapi api kecil perdebatan belum padam.
Ketika mikrofon berpindah ke Elim Tyu Samba, forum mendadak hening. Elim berbicara pelan, tapi setiap katanya terasa mengandung makna.
“Saya tidak ada masalah dengan Mas Ibin. Setiap pemimpin punya gaya sendiri. Tapi yang dibutuhkan adalah konsistensi antara ucapan dan tindakan,” ujarnya, menatap ke arah wali kota.
Tak ada suara tinggi, tak ada gestur keras. Tapi nada kalem itu justru menohok. Seolah menyiratkan lebih banyak dari yang diucapkan.
“Pengawasan terhadap program pemerintah itu kewajiban. Dan saya memahami, setiap kebijakan tentu punya risiko. Tapi kalau kita ingin maju, harus ada komunikasi dan keterbukaan,” tambahnya.
Beberapa peserta bertepuk tangan kecil, sementara Mas Ibin tersenyum kaku. Kopinya yang sudah dingin diaduk pelan.
Malam itu, diskusi refleksi Sumpah Pemuda menjelma menjadi ruang jujur bagi warga Blitar menumpahkan uneg-uneg. Tak sekadar nostalgia sejarah, tapi evaluasi terhadap kepemimpinan hari ini.
Di penghujung acara, moderator Henni Indarriyanti menutup dengan kalimat ringan namun menggigit.
“Refleksi ini bukan tentang siapa yang benar atau salah, tapi tentang siapa yang masih mau mendengar," ucapnya.
Lampu kedai redup, kursi-kursi mulai kosong. Tapi percakapan malam itu terus bergema tentang kota kecil yang sedang belajar menghidupkan kembali semangat Sumpah Pemuda: bersatu di tengah perbedaan, meski kadang harus melewati panasnya secangkir kopi. (*)